Ujian Nalar Demokrasi
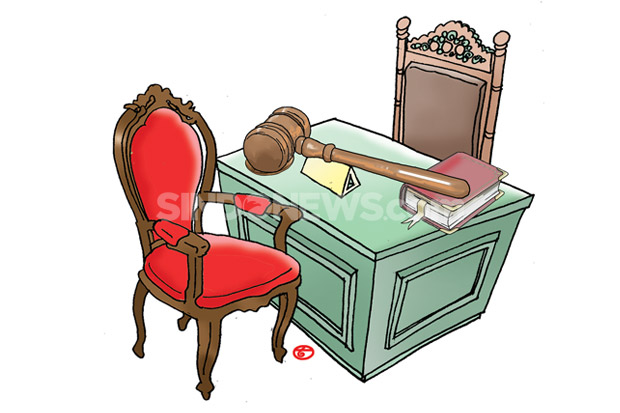
Ujian Nalar Demokrasi
A
A
A
Nasir Djamil
Anggota Komisi III DPR RI
KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 lalu menjadi batu uji nalar demokrasi sebagian rakyat Indonesia. Demokrasi yang memberikan jaminan kesetaraan bagi rakyat berupa hak memilih maupun hak dipilih ternyata sering kali tidak sejalan dengan pilar utama demokrasi, yaitu moral politik dan etika berbangsa dan bernegara.
Bahkan moral dan etika tersebut sebenarnya telah dinormakan dalam bentuk kaidah hukum yang artinya memiliki kekuatan hukum mengikat.
Uji nalar demokrasi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang yang telah dijadikan status tersangka atau terdakwa ternyata masih dipilih oleh sebagian besar rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pilkada DKI, yaitu salah satu calon yang merupakan petahana dan telah menjadi terdakwa memperoleh suara terbanyak walaupun harus ke putaran kedua karena belum memperoleh 50%+1.
Sebelum itu pun kita dapat melihat kontestasi pilkada serentak tahun 2015 yang di dalamnya ada empat kepala daerah mencalonkan diri (incumbent, petahana), yaitu Wali Kota Gunung Sitoli, Sumatra Utara, Lakhomizaro Zebua; Bupati Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira Tome; Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae; Bupati Maros, Sulawesi Selatan, Hatta Rahman, padahal keempatnya telah berstatus tersangka tetapi tetap terpilih.
Tentu keterpilihan tersebut adalah pilihan rakyat masing-masing. Namun keterpilihan itu menunjukkan sisi negatif dari demokrasi. Jimly Asshiddiqie (2005) menyebut demokrasi membawa cacat bawaan karena terlalu mengandalkan logika suara one man one vote.
Padahal mayoritas suara tersebut belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah, dalam kehidupan bernegara, demokrasi tidaklah cukup, melainkan membutuhkan juga pranata hukum dan etika sebagai penjaga suara keadilan tersebut.
Fenomena Calon Tersangka/Terdakwa
Ujian nalar demokrasi dimulai dari Putusan MK Nomor 42/PUU/XIII/2015 yang menyebut mantan terpidana boleh mencalonkan diri asalkan mengakui dan terbuka atas statusnya tersebut. Akibatnya UU Pilkada pun dipaksa berubah dan menyesuaikan beleid tersebut.
Putusan MK itu sebenarnya membawa petaka bagi nalar demokrasi Indonesia karena demokrasi kita semakin tidak bermoral. Akibatnya muncul sikap, jika terpidana saja boleh mencalonkan diri, mengapa tersangka atau terdakwa tidak boleh mencalonkan diri?
Logika ini di satu sisi betul, tetapi sesungguhnya telah meruntuhkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dan demokrasi.
Betul memang kita harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence alias prinsip praduga tak bersalah di mana seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
Namun ketika seseorang telah tersangkut sebuah kasus hukum dan kemudian penegak hukum memprosesnya, bahkan telah dilimpahkan ke pengadilan, nalar hukum kita tentu akan berbicara bahwa tidak mungkin penegak hukum tidak melandaskan proses hukum terhadap seseorang tersebut tanpa alat bukti yang kuat.
Karenanya kita mendapati sebuah aturan hukum yang bersendikan moral bahwa seorang pejabat publik yang telah diajukan ke pengadilan (alias menjadi terdakwa) harus diberhentikan sementara, sedangkan jika telah ada putusan pengadilan (alias menjadi terpidana) pejabat publik tersebut harus diberhentikan secara tetap.
Tujuannya selain agar pejabat tersebut dapat berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang dihadapi, juga bertujuan lebih tinggi, yaitu menjaga kepatutan dan kepantasan dalam kepemimpinan sebuah institusi.
Dalam berbagai kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita akan melihat kesepakatan moral bahwa seseorang yang ditersangkakan, apalagi diterdakwakan oleh KPK, harus mundur dari jabatannya. Institusi pemerintahan ataupun partai politik tempat asal pejabat tersebut pun berlomba-lomba untuk segera memberhentikan karena terdapat moral hukum soal kepantasan, semangat menghormati hukum, dan terutama semangat pemberantasan korupsi.
Hal yang aneh terjadi dalam kasus hukum lainnya yang ditangani kepolisian dan kejaksaan yang ternyata moral hukum soal kepantasan maupun semangat menghormati hukum tidak diperlakukan sama seperti halnya dalam kasus yang ditangani KPK.
Dan hari ini kita menyaksikan, tidak hanya sebagian rakyat Indonesia yang sedang mempertaruhkan nalar hukum dalam berdemokrasi, tetapi termasuk juga pemimpin di negeri ini yang tak juga memberhentikan pejabat yang telah dijadikan terdakwa tersebut.
Bahkan pengabaian beleid yang menyebut seseorang terdakwa harus diberhentikan sementara tersebut sama saja sedang mempertaruhkan proses hukum di pengadilan dengan titik tekannya pada kepolisian dan kejaksaan yang dianggap tidak cakap menghadirkan alat bukti yang kuat.
Demokrasi Kebablasan
Presiden Joko Widodo pada sebuah kesempatan menyebut demokrasi di Indonesia saat ini telah kebablasan. Pernyataan yang bisa jadi tepat dan benar. Sayangnya hal itu dipraktikkan sendiri oleh Presiden Indonesia ketujuh tersebut dalam bentuk tidak mematuhi aturan pemberhentian sementara kepala daerah yang menjadi terdakwa.
Karena itu semestinya kita bersama menggunakan penalaran terhadap permasalahan dalam dinamika politik pilkada supaya melahirkan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat. Penalaran sebagaimana dimaksud KBBI adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan empiris yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian, yang berdasarkan pengamatan sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi sejenis pula.
Berdasarkan hal tersebut, seyogianya nalar demokrasi kita dibangun tidak hanya berdasarkan nalar hukum semata, melainkan juga nalar moral dan etika.
Dengan demikian, menempatkan proses hukum sebagai bagian dari moral dan etika akan dapat mendorong kita untuk memiliki pandangan yang sama bahwa seseorang yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa semestinya tidak dijadikan sebagai pejabat yang mengurusi persoalan rakyat.
Bahkan semestinya siapa pun yang dijadikan tersangka atau terdakwa mengundurkan diri dari proses publik baik sebagai kontestan pemilihan umum maupun apalagi menjadi kepala daerah sebagaimana banyak dipraktikkan di negara demokrasi yang telah maju dengan dasar shame culture alias budaya malu. Hal ini tidak lain merupakan upaya agar demokrasi tidak kebablasan.
Anggota Komisi III DPR RI
KONTESTASI pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 15 Februari 2017 lalu menjadi batu uji nalar demokrasi sebagian rakyat Indonesia. Demokrasi yang memberikan jaminan kesetaraan bagi rakyat berupa hak memilih maupun hak dipilih ternyata sering kali tidak sejalan dengan pilar utama demokrasi, yaitu moral politik dan etika berbangsa dan bernegara.
Bahkan moral dan etika tersebut sebenarnya telah dinormakan dalam bentuk kaidah hukum yang artinya memiliki kekuatan hukum mengikat.
Uji nalar demokrasi yang dimaksud di sini adalah ketika seorang yang telah dijadikan status tersangka atau terdakwa ternyata masih dipilih oleh sebagian besar rakyat. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pilkada DKI, yaitu salah satu calon yang merupakan petahana dan telah menjadi terdakwa memperoleh suara terbanyak walaupun harus ke putaran kedua karena belum memperoleh 50%+1.
Sebelum itu pun kita dapat melihat kontestasi pilkada serentak tahun 2015 yang di dalamnya ada empat kepala daerah mencalonkan diri (incumbent, petahana), yaitu Wali Kota Gunung Sitoli, Sumatra Utara, Lakhomizaro Zebua; Bupati Sabu Raijua, NTT, Marthen Dira Tome; Bupati Ngada, NTT, Marianus Sae; Bupati Maros, Sulawesi Selatan, Hatta Rahman, padahal keempatnya telah berstatus tersangka tetapi tetap terpilih.
Tentu keterpilihan tersebut adalah pilihan rakyat masing-masing. Namun keterpilihan itu menunjukkan sisi negatif dari demokrasi. Jimly Asshiddiqie (2005) menyebut demokrasi membawa cacat bawaan karena terlalu mengandalkan logika suara one man one vote.
Padahal mayoritas suara tersebut belum tentu mencerminkan kebenaran dan keadilan. Karena itulah, dalam kehidupan bernegara, demokrasi tidaklah cukup, melainkan membutuhkan juga pranata hukum dan etika sebagai penjaga suara keadilan tersebut.
Fenomena Calon Tersangka/Terdakwa
Ujian nalar demokrasi dimulai dari Putusan MK Nomor 42/PUU/XIII/2015 yang menyebut mantan terpidana boleh mencalonkan diri asalkan mengakui dan terbuka atas statusnya tersebut. Akibatnya UU Pilkada pun dipaksa berubah dan menyesuaikan beleid tersebut.
Putusan MK itu sebenarnya membawa petaka bagi nalar demokrasi Indonesia karena demokrasi kita semakin tidak bermoral. Akibatnya muncul sikap, jika terpidana saja boleh mencalonkan diri, mengapa tersangka atau terdakwa tidak boleh mencalonkan diri?
Logika ini di satu sisi betul, tetapi sesungguhnya telah meruntuhkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam hukum dan demokrasi.
Betul memang kita harus menjunjung tinggi asas presumption of innocence alias prinsip praduga tak bersalah di mana seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incracht van gewisjde).
Namun ketika seseorang telah tersangkut sebuah kasus hukum dan kemudian penegak hukum memprosesnya, bahkan telah dilimpahkan ke pengadilan, nalar hukum kita tentu akan berbicara bahwa tidak mungkin penegak hukum tidak melandaskan proses hukum terhadap seseorang tersebut tanpa alat bukti yang kuat.
Karenanya kita mendapati sebuah aturan hukum yang bersendikan moral bahwa seorang pejabat publik yang telah diajukan ke pengadilan (alias menjadi terdakwa) harus diberhentikan sementara, sedangkan jika telah ada putusan pengadilan (alias menjadi terpidana) pejabat publik tersebut harus diberhentikan secara tetap.
Tujuannya selain agar pejabat tersebut dapat berkonsentrasi terhadap kasus hukum yang dihadapi, juga bertujuan lebih tinggi, yaitu menjaga kepatutan dan kepantasan dalam kepemimpinan sebuah institusi.
Dalam berbagai kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kita akan melihat kesepakatan moral bahwa seseorang yang ditersangkakan, apalagi diterdakwakan oleh KPK, harus mundur dari jabatannya. Institusi pemerintahan ataupun partai politik tempat asal pejabat tersebut pun berlomba-lomba untuk segera memberhentikan karena terdapat moral hukum soal kepantasan, semangat menghormati hukum, dan terutama semangat pemberantasan korupsi.
Hal yang aneh terjadi dalam kasus hukum lainnya yang ditangani kepolisian dan kejaksaan yang ternyata moral hukum soal kepantasan maupun semangat menghormati hukum tidak diperlakukan sama seperti halnya dalam kasus yang ditangani KPK.
Dan hari ini kita menyaksikan, tidak hanya sebagian rakyat Indonesia yang sedang mempertaruhkan nalar hukum dalam berdemokrasi, tetapi termasuk juga pemimpin di negeri ini yang tak juga memberhentikan pejabat yang telah dijadikan terdakwa tersebut.
Bahkan pengabaian beleid yang menyebut seseorang terdakwa harus diberhentikan sementara tersebut sama saja sedang mempertaruhkan proses hukum di pengadilan dengan titik tekannya pada kepolisian dan kejaksaan yang dianggap tidak cakap menghadirkan alat bukti yang kuat.
Demokrasi Kebablasan
Presiden Joko Widodo pada sebuah kesempatan menyebut demokrasi di Indonesia saat ini telah kebablasan. Pernyataan yang bisa jadi tepat dan benar. Sayangnya hal itu dipraktikkan sendiri oleh Presiden Indonesia ketujuh tersebut dalam bentuk tidak mematuhi aturan pemberhentian sementara kepala daerah yang menjadi terdakwa.
Karena itu semestinya kita bersama menggunakan penalaran terhadap permasalahan dalam dinamika politik pilkada supaya melahirkan demokrasi Indonesia yang lebih bermartabat. Penalaran sebagaimana dimaksud KBBI adalah proses berpikir yang bertolak dari pengamatan empiris yang menghasilkan sejumlah konsep dan pengertian, yang berdasarkan pengamatan sejenis juga akan terbentuk proposisi-proposisi sejenis pula.
Berdasarkan hal tersebut, seyogianya nalar demokrasi kita dibangun tidak hanya berdasarkan nalar hukum semata, melainkan juga nalar moral dan etika.
Dengan demikian, menempatkan proses hukum sebagai bagian dari moral dan etika akan dapat mendorong kita untuk memiliki pandangan yang sama bahwa seseorang yang dijadikan tersangka ataupun terdakwa semestinya tidak dijadikan sebagai pejabat yang mengurusi persoalan rakyat.
Bahkan semestinya siapa pun yang dijadikan tersangka atau terdakwa mengundurkan diri dari proses publik baik sebagai kontestan pemilihan umum maupun apalagi menjadi kepala daerah sebagaimana banyak dipraktikkan di negara demokrasi yang telah maju dengan dasar shame culture alias budaya malu. Hal ini tidak lain merupakan upaya agar demokrasi tidak kebablasan.
(poe)














