Memisahkan (Lagi) Pemilu Serentak
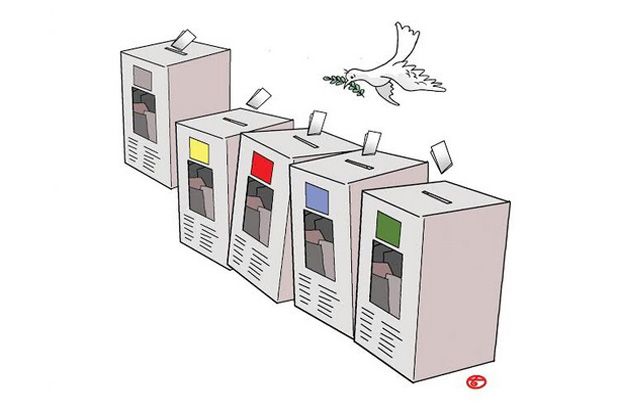
Memisahkan (Lagi) Pemilu Serentak
A
A
A
Idul Rishan
Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Wilayah DIY
Pengajar Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia
SALAH satu karakteristik penyelenggaraan pemilu di Indonesia ialah perubahan cetak biru pemilu yang bisa terjadi secara cepat. Hampir di setiap fase pemilu pascatransisi politik, kita melahirkan undang-undang yang berbeda serta tawaran konsep yang berbeda. Setelah melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 17 April lalu, tentu ada banyak catatan dan kelemahan yang perlu dijadikan bahan evaluasi.
Mungkin yang menjadi salah satu sorotan ialah faktor daya tahan fisik sumber daya manusia dalam mengawal logistik pemilu. Akibat kuantitas pekerjaan yang meningkat, banyak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta kepolisian yang meninggal dan sakit ketika melaksanakan tugas.
Melihat fenomena ini, pembentuk hukum nasional kembali melempar isu untuk memisahkan dua tahap pemilu serentak. Pertama , rezim pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Kedua , rezim pemilu daerah yang terdiri dari pemilihan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hemat penulis, gagasan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan tidak menuntut kemungkinan, gagasan ini hanya menjadi "pepesan kosong " di ruang publik. Ada begitu banyak tantangan, termasuk memperhatikan beberapa norma konstitusi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada.
(In) Konsistensi Konsep
Jika melihat praktik demokrasi di Amerika Serikat (AS), konsep pemilu pada dasarnya didesain untuk bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perangkat peraturan perundang-undangan dibentuk dan digunakan untuk melewati setiap fase pemilu. Sebagai contoh, dalam desain pemilihan presiden di AS, keterpilihan capres ditentukan dengan yang namanya electoral collage.
Konsep ini menawarkan bahwa keterpilihan capres tidak hanya bersandar pada popular vote, tetapi juga dipengaruhi oleh suara para elector yang tersebar di beberapa negara bagian. Meskipun menuai banyak kritik, Amerika tetap konsisten menggunakan sistem ini, dan terus berupaya mengendalikan ekses yang muncul dari penerapan electoral collage.
Pemerintah AS berpendapat bahwa, ekses yang muncul dari konsep electoral collage tidak membawa penyakit kronis bagi kualitas demokrasi di AS. (Bernard Grofman: Thinking About the Political Impacts of the Electoral College :2005). Kondisi demikian tentu berbeda dengan praktik demokrasi di Indonesia. Kita cenderung memaksakan cara dan pendekatan institusionalisasi secara instan. Bermain dengan konsep, tetapi di saat yang sama cenderung meninggalkan konsep yang telah dibangun.
Lima tahun yang lalu (2014), kita membangun konsep dan melaksanakan pemilu secara bertahap (staggerd election). Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam membangun stabilitas pemerintahan, elektabilitas partai dibangun terlebih dahulu untuk mengusung calon presiden guna berkompetisi di pilpres.
Merasa tidak begitu puas dengan model staggerd election, kita menggagas pemilu serentak (concurrent election) sebagai konsep yang dicita-citakan pada lima tahun setelahnya (2019). Demi memuluskan cita-cita concurrent election, kita memohon pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka jalan demi mendapatkan legitimasi sesuai dengan kehendak konstitusi.
Bahwa pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD, ialah pelaksanaan pemilu secara serentak untuk pileg dan pilpres pada waktu dan hari yang sama. Setelah merealisasikan harapan itu di Pemilu 2019, lantas mengapa pemerintah membangun gagasan baru untuk memisahkan lagi tahapan pemilu yang sudah serentak? Desain concurrent election tampak begitu ringkih, seolah tak mampu mengikuti perkembangan dan realitas di masyarakat.
Kalkulasi Manfaat
Sebenarnya harus diakui bahwa gagasan memisahkan rezim pemilu memang merupakan ide yang menarik. Dengan memisahkan dua rezim pemilu nasional dan pemilu daerah, secara tidak langsung tampak akan menutupi beberapa kelemahan yang ditimbulkan melalui pemilu serentak. Pertama, beban kerja penyelenggara pemilu tentu akan berkurang secara signifikan sebab, pemilu dilakukan melalui dua tahapan.
Kedua, pendidikan politik melalui kampanye jauh lebih efisien karena masyarakat bisa memisahkan secara langsung yang mana isu daerah dan yang mana isu nasional. Termasuk di dalamnya membuka rasionalitas pemilih karena jumlah calon yang akan dipilih akan menjadi lebih ramping. Ketiga , pemisahan rezim pemilu juga akan berpengaruh pada rasionalisasi mata anggaran. Skema pembiayaan pemilu nasional akan dibebankan pada APBN, sedangkan skema pembiayaan pemilu daerah akan dibebankan pada APBD.
Namun sekali lagi, beberapa identifikasi dari sejumlah manfaat di atas ialah hanya sebuah kalkulasi sederhana; sedangkan dalam praktiknya, membangun sebuah cetak biru guna memisahkan rezim pemilu nasional dan daerah bukanlah hal yang sederhana. Perdebatan politik hukum tentu menjadi sangat tajam, sebab dalam menyusun perubahan undang-undang, kita tidak hanya berbicara soal premis mayor ataupun premis minor. Di sana ada sejumlah perdebatan kepentingan golongan yang harus diakomodasi dalam proses legislasi.
Memetakan Tantangan
Terlepas dari itu semua, hal yang paling mendasar untuk dipetakan ialah apakah konstitusi menghendaki adanya pemisahan rezim pemilu serentak? Konstruksi penormaan di dalam UUD, sudah membatasi tawaran konsep tersebut. Pasal 22E ayat (2) UUD menegaskan bahwa, pemilihan anggota DPRD merupakan rezim pemilihan umum. Sementara di dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) bukan termasuk di dalam rezim pemilu, melainkan rezim pemerintah daerah.
Bahkan sebagai bentuk interpretasi dari masing-masing Pasal a quo, pada tahun 2015 MK sudah memberikan garis demarkasi bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim nonpemilu. kemudian untuk penyelenggaraannya, pemilu dilaksanakan secara serentak di waktu dan di hari yang sama. (Putusan MK No 14/PUU-XI/2013).
Melihat bentangan norma di atas, ada baiknya pemerintah konsisten dengan pilihan konsep yang telah disepakati baik di dalam UUD maupun melalui interpretasi MK. Evaluasi beberapa kelemahan pascapemilu serentak memang penting, tetapi jangan melempar gagasan untuk melakukan perubahan konsep secara mendasar. Terkecuali, pemerintah berani untuk mendetakkan kembali lonceng amendemen UUD.
Pengurus Asosiasi Pengajar HTN-HAN Wilayah DIY
Pengajar Hukum Konstitusi, Universitas Islam Indonesia
SALAH satu karakteristik penyelenggaraan pemilu di Indonesia ialah perubahan cetak biru pemilu yang bisa terjadi secara cepat. Hampir di setiap fase pemilu pascatransisi politik, kita melahirkan undang-undang yang berbeda serta tawaran konsep yang berbeda. Setelah melaksanakan penyelenggaraan pemilu secara serentak pada 17 April lalu, tentu ada banyak catatan dan kelemahan yang perlu dijadikan bahan evaluasi.
Mungkin yang menjadi salah satu sorotan ialah faktor daya tahan fisik sumber daya manusia dalam mengawal logistik pemilu. Akibat kuantitas pekerjaan yang meningkat, banyak anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) serta kepolisian yang meninggal dan sakit ketika melaksanakan tugas.
Melihat fenomena ini, pembentuk hukum nasional kembali melempar isu untuk memisahkan dua tahap pemilu serentak. Pertama , rezim pemilu nasional yang terdiri dari pemilihan presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI). Kedua , rezim pemilu daerah yang terdiri dari pemilihan kepala daerah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hemat penulis, gagasan ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Bahkan tidak menuntut kemungkinan, gagasan ini hanya menjadi "pepesan kosong " di ruang publik. Ada begitu banyak tantangan, termasuk memperhatikan beberapa norma konstitusi yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu dan pilkada.
(In) Konsistensi Konsep
Jika melihat praktik demokrasi di Amerika Serikat (AS), konsep pemilu pada dasarnya didesain untuk bertahan dalam jangka waktu yang relatif panjang. Perangkat peraturan perundang-undangan dibentuk dan digunakan untuk melewati setiap fase pemilu. Sebagai contoh, dalam desain pemilihan presiden di AS, keterpilihan capres ditentukan dengan yang namanya electoral collage.
Konsep ini menawarkan bahwa keterpilihan capres tidak hanya bersandar pada popular vote, tetapi juga dipengaruhi oleh suara para elector yang tersebar di beberapa negara bagian. Meskipun menuai banyak kritik, Amerika tetap konsisten menggunakan sistem ini, dan terus berupaya mengendalikan ekses yang muncul dari penerapan electoral collage.
Pemerintah AS berpendapat bahwa, ekses yang muncul dari konsep electoral collage tidak membawa penyakit kronis bagi kualitas demokrasi di AS. (Bernard Grofman: Thinking About the Political Impacts of the Electoral College :2005). Kondisi demikian tentu berbeda dengan praktik demokrasi di Indonesia. Kita cenderung memaksakan cara dan pendekatan institusionalisasi secara instan. Bermain dengan konsep, tetapi di saat yang sama cenderung meninggalkan konsep yang telah dibangun.
Lima tahun yang lalu (2014), kita membangun konsep dan melaksanakan pemilu secara bertahap (staggerd election). Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara terpisah. Dalam membangun stabilitas pemerintahan, elektabilitas partai dibangun terlebih dahulu untuk mengusung calon presiden guna berkompetisi di pilpres.
Merasa tidak begitu puas dengan model staggerd election, kita menggagas pemilu serentak (concurrent election) sebagai konsep yang dicita-citakan pada lima tahun setelahnya (2019). Demi memuluskan cita-cita concurrent election, kita memohon pada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membuka jalan demi mendapatkan legitimasi sesuai dengan kehendak konstitusi.
Bahwa pelaksanaan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E ayat (2) UUD, ialah pelaksanaan pemilu secara serentak untuk pileg dan pilpres pada waktu dan hari yang sama. Setelah merealisasikan harapan itu di Pemilu 2019, lantas mengapa pemerintah membangun gagasan baru untuk memisahkan lagi tahapan pemilu yang sudah serentak? Desain concurrent election tampak begitu ringkih, seolah tak mampu mengikuti perkembangan dan realitas di masyarakat.
Kalkulasi Manfaat
Sebenarnya harus diakui bahwa gagasan memisahkan rezim pemilu memang merupakan ide yang menarik. Dengan memisahkan dua rezim pemilu nasional dan pemilu daerah, secara tidak langsung tampak akan menutupi beberapa kelemahan yang ditimbulkan melalui pemilu serentak. Pertama, beban kerja penyelenggara pemilu tentu akan berkurang secara signifikan sebab, pemilu dilakukan melalui dua tahapan.
Kedua, pendidikan politik melalui kampanye jauh lebih efisien karena masyarakat bisa memisahkan secara langsung yang mana isu daerah dan yang mana isu nasional. Termasuk di dalamnya membuka rasionalitas pemilih karena jumlah calon yang akan dipilih akan menjadi lebih ramping. Ketiga , pemisahan rezim pemilu juga akan berpengaruh pada rasionalisasi mata anggaran. Skema pembiayaan pemilu nasional akan dibebankan pada APBN, sedangkan skema pembiayaan pemilu daerah akan dibebankan pada APBD.
Namun sekali lagi, beberapa identifikasi dari sejumlah manfaat di atas ialah hanya sebuah kalkulasi sederhana; sedangkan dalam praktiknya, membangun sebuah cetak biru guna memisahkan rezim pemilu nasional dan daerah bukanlah hal yang sederhana. Perdebatan politik hukum tentu menjadi sangat tajam, sebab dalam menyusun perubahan undang-undang, kita tidak hanya berbicara soal premis mayor ataupun premis minor. Di sana ada sejumlah perdebatan kepentingan golongan yang harus diakomodasi dalam proses legislasi.
Memetakan Tantangan
Terlepas dari itu semua, hal yang paling mendasar untuk dipetakan ialah apakah konstitusi menghendaki adanya pemisahan rezim pemilu serentak? Konstruksi penormaan di dalam UUD, sudah membatasi tawaran konsep tersebut. Pasal 22E ayat (2) UUD menegaskan bahwa, pemilihan anggota DPRD merupakan rezim pemilihan umum. Sementara di dalam pemilihan kepala daerah yang diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) bukan termasuk di dalam rezim pemilu, melainkan rezim pemerintah daerah.
Bahkan sebagai bentuk interpretasi dari masing-masing Pasal a quo, pada tahun 2015 MK sudah memberikan garis demarkasi bahwa pemilihan kepala daerah merupakan rezim nonpemilu. kemudian untuk penyelenggaraannya, pemilu dilaksanakan secara serentak di waktu dan di hari yang sama. (Putusan MK No 14/PUU-XI/2013).
Melihat bentangan norma di atas, ada baiknya pemerintah konsisten dengan pilihan konsep yang telah disepakati baik di dalam UUD maupun melalui interpretasi MK. Evaluasi beberapa kelemahan pascapemilu serentak memang penting, tetapi jangan melempar gagasan untuk melakukan perubahan konsep secara mendasar. Terkecuali, pemerintah berani untuk mendetakkan kembali lonceng amendemen UUD.
(maf)














