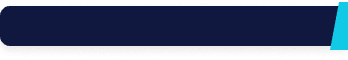Anatomi trias corruptica

Anatomi trias corruptica
A
A
A
TIGA pilar kuasa negara di negeri ini yang dalam khazanah teori negara dinisbatkan sebagai trias politica, menjelang Pemilu 2014 tak pernah lengang dari kegaduhan yang bersumber dari terungkapnya berbagai kasus korupsi politik.
Tak satu pun dari tiga pilar kuasa negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bersih dari kumuhnya praktik-praktik kleptokrasi maupun kleptopolitik. Ketika jerat korupsi politik merambah pilar legislatif dan eksekutif tak pernah sekalipun muncul konsiderasi “ihwal kegentingan yang memaksa” yang bisa melahirkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Hal yang berbeda dengan tafsir eksekutif (baca: Presiden) pada saat korupsi politik dengan modus yang nyaris serupa dengan yang pernah terjadi pada pilar-pilar legislatif dan eksekutif terungkap di lingkungan yudikatif (baca: MK) yang mendorong lahirnya Perppu No 1 Tahun 2013 sebagai hasil tafsir sepihak situasi “darurat negara” terhadap kasus korupsi politik yang menimpa (ketua) Mahkamah Konstitusi.
Hal itu justru membenarkan tesis filosofis bahwa ada politik adalah ada yang hibrida, pada saat politik berkelindan dengan entitas-entitas nonpolitik seperti citra, kepentingan subjektif, komoditas, dan hiburan. Deleuze dan Guattari mengungkapkan bahwa garis- garis imanen dalam perbatasan politik dan nonpolitik sebagai suatu rizhome yaitu garisgaris yang tak pernah berhenti mencari hubungan atau tali temali dengan yang lain.
Terdapat kegalauan ontologis dalam dunia politik di negeri ini pada saat para aktor telah mereproduksi dirinya menjadi citra para aktor. Demikian juga ideologi yang bercampuraduk dengan domain citra dan kepentingan subjektif aktor politik telah mereproduksi diri menjadi suatu imagologi.
Arsitektur politik dan institusi-institusi politik yang dibangun dalam kondisi perpolitikan dan interaksi antaraktor yang kini menjadi sebuah “checks and balances” yang timpang telah menjadikan kuasa-kuasa negara di negeri kegaduhan ini telah bergerak diantara pendulum ada dan (ti)ada (being and nothingness). Kondisi vakum kekuasaan semacam itu telah membuka peluang bagi perebutan kuasa kepentingan subjektif yang mengudeta kuasa trias politica.
Situasi semacam itu dengan kasatmata menggambarkan bahwa arsitektur politik dan kuasa konstitusional dibangun di dataran garis rhizome yang mengosongkan kebenaran dan melucuti transendentalitas serta tanggung jawab. Pada saat itulah sebenarnya rakyat yang oleh konstitusi ditahtakan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi telah diturunkan paksa dari tahtanya justru di era seremonialitas demokrasi langsung.
Relativitas garis batas antara yang politik dan nonpolitik telah melahirkan kuasa nirakuntabilitas. Kehadiran perppu tentang MK yang dipicu oleh keroposnya moralitas dan integritas lembaga pelindung konstitusi itu kini telah membuka arena baru transaksi kepentingan di wilayah yudikatif. Pendulum checks and balances yang selama ini direproduksi sebagai pendulum transaksi kepentingan telah menjadikan negeri ini kian kumuh dengan politik kedustaan dan anomali kuasa.
Graham Maddox (1985) dalam bukunya, Australian Democracy: In Theory and Practice,mengkritik ontologi demokrasi langsung melalui analogi pergeseran sistem demos di Athena yang kemudian beralih pada kuasa-kuasa elite dalam ecclesia. Kondisi pada masa itulah yang kini digambarkan oleh relasi destruktif antarkuasa negara di negeri ini. Akibat itu, Perppu No 1 Tahun 2013 hanya menegaskan situasi ketimpangan dalam sistem checks and balances diantara pilar-pilar kuasa negara di negeri ini.
Agar pedang dewi keadilan bisa berayun menegakkan keadilan, harus diawali dengan kehadiran etika politik. Etika politik tak hanya berkutat pada perilaku para politisi, tapi juga berkelindan dengan praktik institusi-institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi.
Dari dalam diri sang pelaku/politisi harus lahir keutamaan yang merupakan faktor stabilisasi tindakan dan akan berpengaruh terhadap efektivitas praktik- praktik penegakan hukum, peran institusi-institusi penegak hukum maupun institusiinstitusi politik. Gagalnya institusi-institusi hukum, politik, maupun ekonomi melaksanakan peran-peran sesuai mandatnya karena absennya etika (pejabat) politik.
Kuasa selalu membutuhkan dana untuk menopangnya. Itulah yang selama ini telah menjadikan negeri ini melaksanakan demokrasi yang mengalami defisit integritas dan akuntabilitas, menegakkan hukum minus keadilan, dan sejenisnya. Anthony Giddens menyatakan bahwa kejahatan struktural selalu dimulai dari kejahatan moral di ranah privat individu maupun kolektif.
Guna memutus mata rantai kejahatan struktural, perlu dimulai dari kesadaran individual maupun kolektif dari para pejabat politik untuk menegakkan etika (pejabat) politik. Tangan-tangan kotor para koruptor, spekulan politik, dan politik kronisme telah meminjam partai, negara, dan institusi untuk memberikan ruang representasi bagi syahwat berkuasa yang berujung pada pendangkalan politik.
Lenyapnya batas kuasa negara dengan kepentingan, kroni, partai, dan sejenisnya pada hakikatnya merupakan apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai ”kekerasan simbol” yang kian menjadikan negara— meminjam istilah Sartre— antara ada dan tiada (being and nothingness). Irasionalitas politik di negeri ini telah menggiring terjadi ironi dan absurditas perpolitikan. Kontingensi kebenaran yang dito pengikuasa negara dan diberi baju hukum tak urung hanya memunculkan imagologi politik dalam seremoni demokrasi.
Seharusnya diperlukan refleksi mendasar terhadap jejak epistemologis kebenaran politik dalam bernegara yang pada masa lalu dipraktikkan oleh para pendiri negara dan diwasiatkan dalam pembukaan UUD Negara 1945.
DR W RIAWAN TJANDRA SH M HUM
Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Visiting Associate pada Flinders Law School, Adelaide, South Australia
Tak satu pun dari tiga pilar kuasa negara legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang bersih dari kumuhnya praktik-praktik kleptokrasi maupun kleptopolitik. Ketika jerat korupsi politik merambah pilar legislatif dan eksekutif tak pernah sekalipun muncul konsiderasi “ihwal kegentingan yang memaksa” yang bisa melahirkan sebuah peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu).
Hal yang berbeda dengan tafsir eksekutif (baca: Presiden) pada saat korupsi politik dengan modus yang nyaris serupa dengan yang pernah terjadi pada pilar-pilar legislatif dan eksekutif terungkap di lingkungan yudikatif (baca: MK) yang mendorong lahirnya Perppu No 1 Tahun 2013 sebagai hasil tafsir sepihak situasi “darurat negara” terhadap kasus korupsi politik yang menimpa (ketua) Mahkamah Konstitusi.
Hal itu justru membenarkan tesis filosofis bahwa ada politik adalah ada yang hibrida, pada saat politik berkelindan dengan entitas-entitas nonpolitik seperti citra, kepentingan subjektif, komoditas, dan hiburan. Deleuze dan Guattari mengungkapkan bahwa garis- garis imanen dalam perbatasan politik dan nonpolitik sebagai suatu rizhome yaitu garisgaris yang tak pernah berhenti mencari hubungan atau tali temali dengan yang lain.
Terdapat kegalauan ontologis dalam dunia politik di negeri ini pada saat para aktor telah mereproduksi dirinya menjadi citra para aktor. Demikian juga ideologi yang bercampuraduk dengan domain citra dan kepentingan subjektif aktor politik telah mereproduksi diri menjadi suatu imagologi.
Arsitektur politik dan institusi-institusi politik yang dibangun dalam kondisi perpolitikan dan interaksi antaraktor yang kini menjadi sebuah “checks and balances” yang timpang telah menjadikan kuasa-kuasa negara di negeri kegaduhan ini telah bergerak diantara pendulum ada dan (ti)ada (being and nothingness). Kondisi vakum kekuasaan semacam itu telah membuka peluang bagi perebutan kuasa kepentingan subjektif yang mengudeta kuasa trias politica.
Situasi semacam itu dengan kasatmata menggambarkan bahwa arsitektur politik dan kuasa konstitusional dibangun di dataran garis rhizome yang mengosongkan kebenaran dan melucuti transendentalitas serta tanggung jawab. Pada saat itulah sebenarnya rakyat yang oleh konstitusi ditahtakan sebagai pemegang kedaulatan tertinggi telah diturunkan paksa dari tahtanya justru di era seremonialitas demokrasi langsung.
Relativitas garis batas antara yang politik dan nonpolitik telah melahirkan kuasa nirakuntabilitas. Kehadiran perppu tentang MK yang dipicu oleh keroposnya moralitas dan integritas lembaga pelindung konstitusi itu kini telah membuka arena baru transaksi kepentingan di wilayah yudikatif. Pendulum checks and balances yang selama ini direproduksi sebagai pendulum transaksi kepentingan telah menjadikan negeri ini kian kumuh dengan politik kedustaan dan anomali kuasa.
Graham Maddox (1985) dalam bukunya, Australian Democracy: In Theory and Practice,mengkritik ontologi demokrasi langsung melalui analogi pergeseran sistem demos di Athena yang kemudian beralih pada kuasa-kuasa elite dalam ecclesia. Kondisi pada masa itulah yang kini digambarkan oleh relasi destruktif antarkuasa negara di negeri ini. Akibat itu, Perppu No 1 Tahun 2013 hanya menegaskan situasi ketimpangan dalam sistem checks and balances diantara pilar-pilar kuasa negara di negeri ini.
Agar pedang dewi keadilan bisa berayun menegakkan keadilan, harus diawali dengan kehadiran etika politik. Etika politik tak hanya berkutat pada perilaku para politisi, tapi juga berkelindan dengan praktik institusi-institusi sosial, hukum, komunitas, struktur-struktur sosial, politik, dan ekonomi.
Dari dalam diri sang pelaku/politisi harus lahir keutamaan yang merupakan faktor stabilisasi tindakan dan akan berpengaruh terhadap efektivitas praktik- praktik penegakan hukum, peran institusi-institusi penegak hukum maupun institusiinstitusi politik. Gagalnya institusi-institusi hukum, politik, maupun ekonomi melaksanakan peran-peran sesuai mandatnya karena absennya etika (pejabat) politik.
Kuasa selalu membutuhkan dana untuk menopangnya. Itulah yang selama ini telah menjadikan negeri ini melaksanakan demokrasi yang mengalami defisit integritas dan akuntabilitas, menegakkan hukum minus keadilan, dan sejenisnya. Anthony Giddens menyatakan bahwa kejahatan struktural selalu dimulai dari kejahatan moral di ranah privat individu maupun kolektif.
Guna memutus mata rantai kejahatan struktural, perlu dimulai dari kesadaran individual maupun kolektif dari para pejabat politik untuk menegakkan etika (pejabat) politik. Tangan-tangan kotor para koruptor, spekulan politik, dan politik kronisme telah meminjam partai, negara, dan institusi untuk memberikan ruang representasi bagi syahwat berkuasa yang berujung pada pendangkalan politik.
Lenyapnya batas kuasa negara dengan kepentingan, kroni, partai, dan sejenisnya pada hakikatnya merupakan apa yang oleh Bourdieu disebut sebagai ”kekerasan simbol” yang kian menjadikan negara— meminjam istilah Sartre— antara ada dan tiada (being and nothingness). Irasionalitas politik di negeri ini telah menggiring terjadi ironi dan absurditas perpolitikan. Kontingensi kebenaran yang dito pengikuasa negara dan diberi baju hukum tak urung hanya memunculkan imagologi politik dalam seremoni demokrasi.
Seharusnya diperlukan refleksi mendasar terhadap jejak epistemologis kebenaran politik dalam bernegara yang pada masa lalu dipraktikkan oleh para pendiri negara dan diwasiatkan dalam pembukaan UUD Negara 1945.
DR W RIAWAN TJANDRA SH M HUM
Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Visiting Associate pada Flinders Law School, Adelaide, South Australia
(nfl)