Sisi Gelap Modernisasi Nelayan
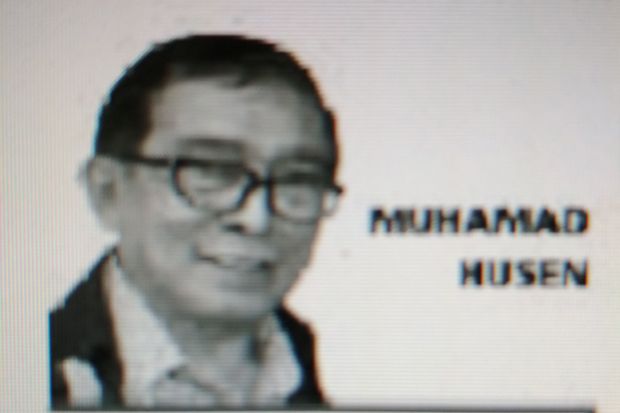
Sisi Gelap Modernisasi Nelayan
A
A
A
Muhamad Husen
Pengurus DPD HNSI Jabar dan Pengurus Masyarakat Akuakultur Indonesia
PERINGATAN Hari Nelayan Indonesia, 6 April, berlangsung senyap. Tidak ada gempita, kemeriahan di sejumlah wilayah, gaung Hari Nelayan nyaris tak terdengar. Membahas kampanye partai dan pemilu tampaknya lebih menarik ketimbang isu-isu nelayan. Padahal untuk menggali potensi perikanan yang demikian besar, dibutuhkan sosok nelayan modern.
Posisi nelayan di Tanah Air saat ini memang belum bisa dikatakan modern. Meskipun dikatakan primitif juga tentu tidak. Untuk mencapai modern pun belum memungkinkan. Roda kehidupan nelayan berjalan seperti biasa, melanjutkan hidup di tengah kesesakan pendapatan dan impitan kebutuhan hidup. Nasibnya tetap memprihatinkan.
Mengapa nelayan belum modern? Sebagian besar jawabannya akan merujuk pada terbatasnya armada dan teknologi penangkapan serta adanya hambatan kultural dan struktural, termasuk berbagai kendala lain yang selalu menghadang. Kalaupun mereka menikmati kemajuan, posisinya selalu tertera pada urutan paling belakang. Kehidupan nelayan tetap saja merupakan sosok ketertinggalan, padahal para pemegang kebijakan di negeri ini sudah sering bongkar pasang berikut program memodernisasi nelayan menjadi salah satu pencanangan kerjanya.
Realita modernisasi masih memiliki sisi gelap, mereka yang bertarung hidup di tengah ganasnya lautan, ibarat pahlawan yang kalah perang. Hasil tangkapan cenderung menurun karena kalahnya daya jangkau menembus laut dalam, mengingat kapal yang dipakai berukuran kecil. Akibatnya, pendapatan nelayan minim. Jika patah semangat, sebagian dari mereka akan menempuh jalan pintas dengan cara berpindah pekerjaan. Sebagian bisa berhasil, tetapi tidak sedikit pula gagal karena tidak memiliki keterampilan khusus. Tidak mudahnya meraih tambahan modal, apalagi tingkat edukasi mereka yang rendah sehingga keterbelakangan selalu menyelimutinya.
Mengalami Penurunan
Gaung yales veva yaya mahe serta bait-bait lagu “nenek moyangku orang pelaut”, semakin kental dikenal dan mudah dihafal di kalangan anak-anak sekolah. Semboyan yang mencerminkan kejayaan nenek moyang kita sejak zaman Sriwijaya dan masih tertanam di benak para pelaut Indonesia sampai sekarang. Makna isinya baru terasa menggema pada sebagian kecil dari penguasaan laut secara menyeluruh, yaitu dalam dunia pelayaran dan penjelajahan laut-laut Nusantara. Namun, pada bidang-bidang lain, khususnya pada pemanfaatan sumber daya hayati yang secara ekologis dapat terlestarikan, kajian ekonomisnya menguntungkan dan analisis ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, semboyan heroik itu belum terpatri secara utuh dalam sanubari para petinggi negeri ini.
Secara kasatmata bangsa Indonesia umumnya mengetahui bahwa sekitar tiga per empat wilayahnya berupa laut. Memiliki luas 5,8 juta kilometer persegi yang menghubungkan lebih dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 95.200 km (terpanjang kedua di dunia). Daerah pesisir dan lautannya mengandung potensi ekonomi kelautan luar biasa, diperkirakan mencapai USD1,3 miliar per tahun. Konon dari perikanan tangkap bernilai USD15,1 juta, budi daya laut USD46,7 juta, budi daya tambak USD10 juta, dan bioteknologi kelautan USD4 juta. Sumber daya ikan laut diperkirakan sebanyak 12,5 juta ton/tahun. Pada 2017 produksinya baru 7,67 juta ton.
Di balik fakta di atas, selalu muncul pertanyaan klise dan menggelitik, mengapa kekayaan laut sedemikian besar itu belum bisa membuat bangsa kita menjadi lebih maju dan makmur. Apalagi untuk memodernkan nelayan, padahal merekalah selama ini turut menggali potensi kelautan tersebut. Saat ini kontribusi sektor kelautan Indonesia sekitar 22% dari produk domestik bruto (PDB), tergolong kecil dibandingkan dengan negara APEC lainnya, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Bahkan tingkat pendapatan nelayan masih berkisar sekitar Rp300.000 per bulan. Sementara kerugian negara akibat pencurian ikan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) diperkirakan rata-rata Rp30 triliun per tahun.
Runyamnya regulasi perikanan tangkap, adanya dugaan tentang sumber daya ikan di beberapa wilayah perairan sudah mengalami degradasi, dan sering kurang bersahabatnya cuaca buruk tidak menentu, telah menambah deretan panjang penyebab nasib nelayan selama ini. Ujung-ujungnya, mereka terpuruk di ladang sendiri. Tidak mengherankan apabila jumlah nelayan di negara kita mengalami penurunan, jika pada 2003 tercatat 3,85 juta nelayan, maka pada 2007 berkurang menjadi 2,66 juta. Pada 2016 diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87% dari jumlah tenaga kerja Indonesia).
Minimnya akses sarana produksi membuat nelayan belum mampu memanfaatkan dan mengelola kekayaan laut secara optimal. Di sejumlah sentra produksi perikanan, akses bahan bakar minyak sulit diperoleh. Nelayan terpaksa membeli solar eceran di warung dengan harga lebih mahal ketimbang membeli di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Kesulitan lain adalah akses permodalan untuk melaut. Sulitnya akses perbankan mengakibatkan nelayan terjerat utang permodalan dengan tengkulak.
Model perikanan skala menengah ke bawah dengan sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik menghasilkan hubungan patronase yang kuat. Artinya, segala sesuatu kendala pengusaha ditanggung pula pekerjanya. Kendala berlanjut hingga hilir, yakni mata rantai perdagangan yang dikuasai tengkulak. Akibatnya, nelayan nyaris tak punya posisi tawar.
Tidak Ada Apa-apanya
Manakala menelaah volume serta nilai produk perikanan Indonesia, tentu kita berpendapat ternyata kemampuan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara lain dalam mengelola kekayaan lautnya. Korea Selatan yang hanya memiliki garis pantai tak lebih dari 2.713 kilometer mampu menyumbang 37% bagi PDB-nya. Jepang dengan garis pantai 34.386 kilometer, sektor kelautannya mampu menyumbang 54%. Tetangga kita, Thailand, yang garis pantainya saja 2.600 kilometer juga dapat mengekspor produk perikanan jauh lebih besar dari Indonesia.
Sementara Cina, luas wilayah perairannya 503.209 km persegi (8,81% luas perairan Indonesia) dengan panjang garis pantai 32.000 km, sepuluh tahun lalu kontribusi sektor kelautannya terhadap PDB mencapai 48,4%, keberpihakan pemerintahnya terhadap sektor perikanan terbukti mulai dari pembangunan rumah susun nelayan yang layak termasuk berbagai insentif usaha untuk menumbuhkan investasi.
Negara Islandia dan Norwegia telah membuktikan pula bahwa laut dapat menjadi tumpuan penghidupan ekonomi. Di Islandia, 65% PDB berasal dari sektor perikanan dengan pendapatan per kapita rakyatnya USD26.000, sedangkan Norwegia memberikan kontribusi 25% untuk ekspor ikan salmon saja senilai USD2 miliar per tahun. Adapun pendapatan per kapitanya mencapai USD30.000.
Mencermati kisah sukses negara lain berikut sederet persoalan yang dihadapi nelayan, saatnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan peringatan Hari Nelayan tahun ini sebagai momentum membangkitkan dan menyejahterakan nelayan sesuai Nawacita. Ambisi menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya bisa tercapai jika nelayan modern bisa diwujudkan.
Pengurus DPD HNSI Jabar dan Pengurus Masyarakat Akuakultur Indonesia
PERINGATAN Hari Nelayan Indonesia, 6 April, berlangsung senyap. Tidak ada gempita, kemeriahan di sejumlah wilayah, gaung Hari Nelayan nyaris tak terdengar. Membahas kampanye partai dan pemilu tampaknya lebih menarik ketimbang isu-isu nelayan. Padahal untuk menggali potensi perikanan yang demikian besar, dibutuhkan sosok nelayan modern.
Posisi nelayan di Tanah Air saat ini memang belum bisa dikatakan modern. Meskipun dikatakan primitif juga tentu tidak. Untuk mencapai modern pun belum memungkinkan. Roda kehidupan nelayan berjalan seperti biasa, melanjutkan hidup di tengah kesesakan pendapatan dan impitan kebutuhan hidup. Nasibnya tetap memprihatinkan.
Mengapa nelayan belum modern? Sebagian besar jawabannya akan merujuk pada terbatasnya armada dan teknologi penangkapan serta adanya hambatan kultural dan struktural, termasuk berbagai kendala lain yang selalu menghadang. Kalaupun mereka menikmati kemajuan, posisinya selalu tertera pada urutan paling belakang. Kehidupan nelayan tetap saja merupakan sosok ketertinggalan, padahal para pemegang kebijakan di negeri ini sudah sering bongkar pasang berikut program memodernisasi nelayan menjadi salah satu pencanangan kerjanya.
Realita modernisasi masih memiliki sisi gelap, mereka yang bertarung hidup di tengah ganasnya lautan, ibarat pahlawan yang kalah perang. Hasil tangkapan cenderung menurun karena kalahnya daya jangkau menembus laut dalam, mengingat kapal yang dipakai berukuran kecil. Akibatnya, pendapatan nelayan minim. Jika patah semangat, sebagian dari mereka akan menempuh jalan pintas dengan cara berpindah pekerjaan. Sebagian bisa berhasil, tetapi tidak sedikit pula gagal karena tidak memiliki keterampilan khusus. Tidak mudahnya meraih tambahan modal, apalagi tingkat edukasi mereka yang rendah sehingga keterbelakangan selalu menyelimutinya.
Mengalami Penurunan
Gaung yales veva yaya mahe serta bait-bait lagu “nenek moyangku orang pelaut”, semakin kental dikenal dan mudah dihafal di kalangan anak-anak sekolah. Semboyan yang mencerminkan kejayaan nenek moyang kita sejak zaman Sriwijaya dan masih tertanam di benak para pelaut Indonesia sampai sekarang. Makna isinya baru terasa menggema pada sebagian kecil dari penguasaan laut secara menyeluruh, yaitu dalam dunia pelayaran dan penjelajahan laut-laut Nusantara. Namun, pada bidang-bidang lain, khususnya pada pemanfaatan sumber daya hayati yang secara ekologis dapat terlestarikan, kajian ekonomisnya menguntungkan dan analisis ilmiah bisa dipertanggungjawabkan, semboyan heroik itu belum terpatri secara utuh dalam sanubari para petinggi negeri ini.
Secara kasatmata bangsa Indonesia umumnya mengetahui bahwa sekitar tiga per empat wilayahnya berupa laut. Memiliki luas 5,8 juta kilometer persegi yang menghubungkan lebih dari 17.504 pulau dengan panjang garis pantai 95.200 km (terpanjang kedua di dunia). Daerah pesisir dan lautannya mengandung potensi ekonomi kelautan luar biasa, diperkirakan mencapai USD1,3 miliar per tahun. Konon dari perikanan tangkap bernilai USD15,1 juta, budi daya laut USD46,7 juta, budi daya tambak USD10 juta, dan bioteknologi kelautan USD4 juta. Sumber daya ikan laut diperkirakan sebanyak 12,5 juta ton/tahun. Pada 2017 produksinya baru 7,67 juta ton.
Di balik fakta di atas, selalu muncul pertanyaan klise dan menggelitik, mengapa kekayaan laut sedemikian besar itu belum bisa membuat bangsa kita menjadi lebih maju dan makmur. Apalagi untuk memodernkan nelayan, padahal merekalah selama ini turut menggali potensi kelautan tersebut. Saat ini kontribusi sektor kelautan Indonesia sekitar 22% dari produk domestik bruto (PDB), tergolong kecil dibandingkan dengan negara APEC lainnya, seperti Vietnam, Korea, dan Jepang. Bahkan tingkat pendapatan nelayan masih berkisar sekitar Rp300.000 per bulan. Sementara kerugian negara akibat pencurian ikan menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) diperkirakan rata-rata Rp30 triliun per tahun.
Runyamnya regulasi perikanan tangkap, adanya dugaan tentang sumber daya ikan di beberapa wilayah perairan sudah mengalami degradasi, dan sering kurang bersahabatnya cuaca buruk tidak menentu, telah menambah deretan panjang penyebab nasib nelayan selama ini. Ujung-ujungnya, mereka terpuruk di ladang sendiri. Tidak mengherankan apabila jumlah nelayan di negara kita mengalami penurunan, jika pada 2003 tercatat 3,85 juta nelayan, maka pada 2007 berkurang menjadi 2,66 juta. Pada 2016 diperkirakan sebanyak 2,17 juta (hanya 0,87% dari jumlah tenaga kerja Indonesia).
Minimnya akses sarana produksi membuat nelayan belum mampu memanfaatkan dan mengelola kekayaan laut secara optimal. Di sejumlah sentra produksi perikanan, akses bahan bakar minyak sulit diperoleh. Nelayan terpaksa membeli solar eceran di warung dengan harga lebih mahal ketimbang membeli di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Kesulitan lain adalah akses permodalan untuk melaut. Sulitnya akses perbankan mengakibatkan nelayan terjerat utang permodalan dengan tengkulak.
Model perikanan skala menengah ke bawah dengan sistem bagi hasil nelayan dengan pemilik menghasilkan hubungan patronase yang kuat. Artinya, segala sesuatu kendala pengusaha ditanggung pula pekerjanya. Kendala berlanjut hingga hilir, yakni mata rantai perdagangan yang dikuasai tengkulak. Akibatnya, nelayan nyaris tak punya posisi tawar.
Tidak Ada Apa-apanya
Manakala menelaah volume serta nilai produk perikanan Indonesia, tentu kita berpendapat ternyata kemampuan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan negara lain dalam mengelola kekayaan lautnya. Korea Selatan yang hanya memiliki garis pantai tak lebih dari 2.713 kilometer mampu menyumbang 37% bagi PDB-nya. Jepang dengan garis pantai 34.386 kilometer, sektor kelautannya mampu menyumbang 54%. Tetangga kita, Thailand, yang garis pantainya saja 2.600 kilometer juga dapat mengekspor produk perikanan jauh lebih besar dari Indonesia.
Sementara Cina, luas wilayah perairannya 503.209 km persegi (8,81% luas perairan Indonesia) dengan panjang garis pantai 32.000 km, sepuluh tahun lalu kontribusi sektor kelautannya terhadap PDB mencapai 48,4%, keberpihakan pemerintahnya terhadap sektor perikanan terbukti mulai dari pembangunan rumah susun nelayan yang layak termasuk berbagai insentif usaha untuk menumbuhkan investasi.
Negara Islandia dan Norwegia telah membuktikan pula bahwa laut dapat menjadi tumpuan penghidupan ekonomi. Di Islandia, 65% PDB berasal dari sektor perikanan dengan pendapatan per kapita rakyatnya USD26.000, sedangkan Norwegia memberikan kontribusi 25% untuk ekspor ikan salmon saja senilai USD2 miliar per tahun. Adapun pendapatan per kapitanya mencapai USD30.000.
Mencermati kisah sukses negara lain berikut sederet persoalan yang dihadapi nelayan, saatnya Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan peringatan Hari Nelayan tahun ini sebagai momentum membangkitkan dan menyejahterakan nelayan sesuai Nawacita. Ambisi menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia hanya bisa tercapai jika nelayan modern bisa diwujudkan.
(pur)














