Najis Politik
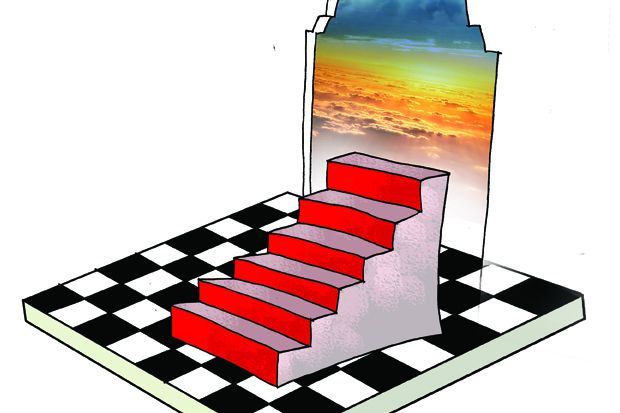
Najis Politik
A
A
A
Teuku Kemal Fasya
Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh dan Mantan Sekretaris Timsel Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Aceh Regional 3
BEBERAPA waktu belakangan, Badan Pengawas Pemilu RI sedang mengupayakan pembentukan perangkat pengawas pemilu, baik provinsi dan kabupaten/kota hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pembentukan lembaga pengawas ini menyambut Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.
Di Aceh sendiri, proses seleksi panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota se-Aceh oleh tim seleksi independen telah dilaksanakan pada akhir Juli lalu. Tim seleksi di tiga regional di Aceh telah memberikan enam nama calon komisioner per kabupaten/kota yang akan kembali dipilih tiga orang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi.
Kemungkinan pada akhir Agustus, publik akan mengetahui hasilnya. Penulis kebetulan menjadi tim seleksi untuk regional 3 Aceh yang membawahi tujuh kabupaten/kota. Namun, ada kisah tertinggal yang penting dibagi.
Kisah itu terkait jawaban sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Penulis bertanya tentang apa yang dianggap aib bagi komisioner panwaslu. Apakah mereka akan malu dituduh mendukung salah seorang peserta pemilu partai politik, mengorupsi dana penyelenggara pemilu, atau berselingkuh.
Meskipun sebagian sempat ragu-ragu menjawab, semua menganggap selingkuhlah paling memalukan. Alasannya pun hampir identik. Tuduhan selingkuh dianggap langsung menempel meskipun tidak dilakukan. Padahal logika dari jawaban ini bisa juga merujuk pada dua aib lainnya.
Moral Publik
Semuanya memang aib yang harus dijauhi. Namun, jika konsep moral publik dikedepankan dan menjadi bagian secara internal diyakini, dua masalah lain harusnya lebih memalukan. Bayangkan, sebagai pengawas yang harusnya adil sejak dalam pikiran--mengutip kata-kata dalam novel Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia--membela peserta pemilu atau partai pemilu bagi penyelenggara adalah aib yang tidak kecil.
Munculnya kesadaran bahwa hal itu tidak aib dan melecehkan lembaga penyelenggara pemilu karena penyakit ini sudah dianggap biasa. Jika kembali kilas balik perjalanan kepemiluan (baik pilkada atau pileg), terlihat ada saja penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu calon sehingga banyak dari mereka menghadapi sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Penulis sempat melihat gestur seorang komisioner penyelenggara yang terpukul karena salah seorang peserta pemilihan kalah dalam pilkada. Keterikatannya pada partai politik pengusung peserta itu masih melekat kuat dalam dirinya, meskipun ia telah menjadi "wasit" dan "hakim garis" di kepemiluan. Padahal kata-kata Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat ketiga, penting dicamkan, "kesetiaanku kepada partai akan luruh tatkala aku menjadi presiden. "
Karenanya, kasus-kasus pemihakan politik bukan saja menjadi dosa dalam konteks moral publik penyelenggara kepemiluan, tapi bisa juga membuat karier sang komisioner bisa cepat mati. Menjadi penyelenggara pemilu, di samping karier publik, juga mengasah kepekaan atas sikap imparsialitas.
Kesadaran Koruptif
Hal lain seharusnya menjadi aib paling besar adalah korupsi. Namun, tidak ada satu pun peserta bisa menjawab dengan sigap, kecuali jawaban protokoler yang normatif. Antikorupsi belum menjadi ruh dalam memahami integritas politik.
Korupsi masih terserak, terbang-terbang, dan dikumpulkan begitu saja. Dengan kesadaran (palsu) masih ada pertanyaan, kenapa tidak harus korupsi? Dengan sikap naif orang lain akan menganggap bahwa ketika peluang dan kewenangan itu ada dan kita tidak melakukan korupsi, maka kita adalah manusia ganjil, terasing, atau mengalami gangguan neurosis. Di kelembagaan agama pun korupsi melumut tanpa ada yang sungguh-sungguh ingin membersihkannya.
Perihal masalah ini pernah disampaikan Daniel Dhakiadae, pemikir etika politik. Menurutnya korupsi belum masuk dalam sumsum teologi arus utama. Agama sendiri masih berbeda ijtihad tentang korupsi sehingga ada pernyataan bahwa hal itu tidak bisa disamakan dengan kejahatan pencurian atau perampokan. Meskipun dampak korupsi jauh lebih besar dibandingkan kejahatan jinayah itu.
Menurut Dhakidae, korupsi terjadi dengan kesadaran yang melekat pada diri sang pelakunya, yaitu kewenangan (authority) dan kuasa (power). Kewenangan menyebabkan pelaku korupsi menganggapnya diskresi atas kebijakan.
Adapun relasi kuasa dalam praktiknya menurut perspektif Foucaultian bisa menjadi basis kebenaran, bahkan modul pengetahuan bagi koruptor. Maka tak heran banyak koruptor dan mantan narapidana korupsi memiliki nama harum di masyarakat berkat citra kesalehan dan kedermawanannya.
Dalam Islam ada konsep risywah (suap: bribery) yang dalam sebuah hadis disebutkan, baik penyuap atau yang disuap masuk neraka. Namun, di kalangan Kerajaan Arab Saudi, mereka terbiasa menerima pemberian dari perusahaan migas yang bekerja di negaranya. Bagi mereka anggaran yang tidak diaudit perusahaan migas itu atau off budget halal semata. Bukan risywah .
Menurut Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) pemberian seperti itu dianggap gratifikasi atau penyuapan. Sejak disahkan 31 Oktober 2003, konvensi itu telah diratifikasi di banyak negara. Indonesia secara regulasi cukup maju dalam melawan tindakan korupsi. Hanya sedikit negara yang belum meratifikasi Konvensi Anti-Korupsi. Rata-rata adalah negara antidemokrasi dan gagal, seperti Somalia, Korea Utara, Chad, dan Suriah. Sejak awal reformasi Indonesia telah membuat pelbagai undang-undang tentang antikorupsi. Paling fenomenal tentu UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Menjijikkan
Meskipun masih tertatih-tatih, kita musti menjadikan korupsi masuk sebagai kejahatan paling menjijikkan. Bisa jadi pandangan ini dianggap sebuah kesombongan dibandingkan dengan sikap realistis terhadap konteks sosiologis. Namun, bagi aktivis antikorupsi dan pemerintahan yang bersih sikap itu adalah idealisme yang harus diperjuangkan sepanjang hayat.
Sebagai timsel (tim seleksi), penulis menyadari ruang korupsi juga terbuka lebar. Bisa dari pilihan ngopi bareng hingga silaturahim menjadi ruang yang bisa membintikkan korupsi. Bintik-bintik itu akan semakin terbuka ketika kita bersikap "ramah" kepada peserta calon sehingga aneka "wujud basa-basi" dan "tanda persahabatan" bisa menjadi modus korupsi yang semakin konkret.
Dalam level agak kasar bisa saja terjadi seperti yang dilakukan Akil Mochtar, Rudi Rudiantara, Irman Gusman, atau Patrialis Akbar, yang membuka ruang untuk menentukan "pemberian" secara pasti, bisa jadi tujuannya bukan karena kebutuhan mendesak, tapi agar hidup semakin bergaya.
Padahal jika kita tekun memahami arti kata korupsi secara genealogis bahasa Latin, yaitu corruptio, artinya sesuatu yang busuk, mengotori, dan menggoyahkan jiwa, maka tindakan korup bukanlah sebuah "diskresi" yang mudah dilupakan. Banyak kita lihat koruptor beribadah cukup taat dan bersikap ramah kepada publik.
Penulis sendiri membuat batasan cukup tegas ketika menjadi timsel, baik melalui media sosial ataupun melalui percakapan di WhatsApp dan SMS untuk tidak memberikan apa pun. Karena momen pemberian itu bukan seperti makna hadiah yang dianjurkan Nabi Muhammad untuk mengakrabkan hubungan, tapi bisa menajiskan rezeki. Korupsi itu seperti narkoba. Ia berdampak adiktif sehingga membuat kita semakin ingin menambah dosis demi ketenangan. Pada akhirnya akan terasa ada yang hampa ketika itu tidak dilakukan.
Belajar dari kasus mantan ketua MK itu, tindakan suap membawanya kepada efek domino kejahatan, seperti membela yang bayar berpengaruh terhadap hadirnya pemimpin lokal bobrok dan selingkuh dengan perempuan lain karena uang memang mudah didapatkan. Uang haram akan kembali ke muara yang haram. Jika dipraktikkan di praktik kekuasaan, ia akan melahirkan najis politik. Itulah yang menyebabkan banyak orang idealis malas mendekati politik.
Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh dan Mantan Sekretaris Timsel Seleksi Panwaslu Kabupaten/Kota se-Aceh Regional 3
BEBERAPA waktu belakangan, Badan Pengawas Pemilu RI sedang mengupayakan pembentukan perangkat pengawas pemilu, baik provinsi dan kabupaten/kota hampir di seluruh daerah di Indonesia. Pembentukan lembaga pengawas ini menyambut Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.
Di Aceh sendiri, proses seleksi panitia pengawas pemilu (panwaslu) kabupaten/kota se-Aceh oleh tim seleksi independen telah dilaksanakan pada akhir Juli lalu. Tim seleksi di tiga regional di Aceh telah memberikan enam nama calon komisioner per kabupaten/kota yang akan kembali dipilih tiga orang oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi.
Kemungkinan pada akhir Agustus, publik akan mengetahui hasilnya. Penulis kebetulan menjadi tim seleksi untuk regional 3 Aceh yang membawahi tujuh kabupaten/kota. Namun, ada kisah tertinggal yang penting dibagi.
Kisah itu terkait jawaban sebuah pertanyaan yang mungkin tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Penulis bertanya tentang apa yang dianggap aib bagi komisioner panwaslu. Apakah mereka akan malu dituduh mendukung salah seorang peserta pemilu partai politik, mengorupsi dana penyelenggara pemilu, atau berselingkuh.
Meskipun sebagian sempat ragu-ragu menjawab, semua menganggap selingkuhlah paling memalukan. Alasannya pun hampir identik. Tuduhan selingkuh dianggap langsung menempel meskipun tidak dilakukan. Padahal logika dari jawaban ini bisa juga merujuk pada dua aib lainnya.
Moral Publik
Semuanya memang aib yang harus dijauhi. Namun, jika konsep moral publik dikedepankan dan menjadi bagian secara internal diyakini, dua masalah lain harusnya lebih memalukan. Bayangkan, sebagai pengawas yang harusnya adil sejak dalam pikiran--mengutip kata-kata dalam novel Pramoedya Ananta Toer, Bumi Manusia--membela peserta pemilu atau partai pemilu bagi penyelenggara adalah aib yang tidak kecil.
Munculnya kesadaran bahwa hal itu tidak aib dan melecehkan lembaga penyelenggara pemilu karena penyakit ini sudah dianggap biasa. Jika kembali kilas balik perjalanan kepemiluan (baik pilkada atau pileg), terlihat ada saja penyelenggara pemilu berpihak kepada salah satu calon sehingga banyak dari mereka menghadapi sidang etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Penulis sempat melihat gestur seorang komisioner penyelenggara yang terpukul karena salah seorang peserta pemilihan kalah dalam pilkada. Keterikatannya pada partai politik pengusung peserta itu masih melekat kuat dalam dirinya, meskipun ia telah menjadi "wasit" dan "hakim garis" di kepemiluan. Padahal kata-kata Thomas Jefferson, mantan Presiden Amerika Serikat ketiga, penting dicamkan, "kesetiaanku kepada partai akan luruh tatkala aku menjadi presiden. "
Karenanya, kasus-kasus pemihakan politik bukan saja menjadi dosa dalam konteks moral publik penyelenggara kepemiluan, tapi bisa juga membuat karier sang komisioner bisa cepat mati. Menjadi penyelenggara pemilu, di samping karier publik, juga mengasah kepekaan atas sikap imparsialitas.
Kesadaran Koruptif
Hal lain seharusnya menjadi aib paling besar adalah korupsi. Namun, tidak ada satu pun peserta bisa menjawab dengan sigap, kecuali jawaban protokoler yang normatif. Antikorupsi belum menjadi ruh dalam memahami integritas politik.
Korupsi masih terserak, terbang-terbang, dan dikumpulkan begitu saja. Dengan kesadaran (palsu) masih ada pertanyaan, kenapa tidak harus korupsi? Dengan sikap naif orang lain akan menganggap bahwa ketika peluang dan kewenangan itu ada dan kita tidak melakukan korupsi, maka kita adalah manusia ganjil, terasing, atau mengalami gangguan neurosis. Di kelembagaan agama pun korupsi melumut tanpa ada yang sungguh-sungguh ingin membersihkannya.
Perihal masalah ini pernah disampaikan Daniel Dhakiadae, pemikir etika politik. Menurutnya korupsi belum masuk dalam sumsum teologi arus utama. Agama sendiri masih berbeda ijtihad tentang korupsi sehingga ada pernyataan bahwa hal itu tidak bisa disamakan dengan kejahatan pencurian atau perampokan. Meskipun dampak korupsi jauh lebih besar dibandingkan kejahatan jinayah itu.
Menurut Dhakidae, korupsi terjadi dengan kesadaran yang melekat pada diri sang pelakunya, yaitu kewenangan (authority) dan kuasa (power). Kewenangan menyebabkan pelaku korupsi menganggapnya diskresi atas kebijakan.
Adapun relasi kuasa dalam praktiknya menurut perspektif Foucaultian bisa menjadi basis kebenaran, bahkan modul pengetahuan bagi koruptor. Maka tak heran banyak koruptor dan mantan narapidana korupsi memiliki nama harum di masyarakat berkat citra kesalehan dan kedermawanannya.
Dalam Islam ada konsep risywah (suap: bribery) yang dalam sebuah hadis disebutkan, baik penyuap atau yang disuap masuk neraka. Namun, di kalangan Kerajaan Arab Saudi, mereka terbiasa menerima pemberian dari perusahaan migas yang bekerja di negaranya. Bagi mereka anggaran yang tidak diaudit perusahaan migas itu atau off budget halal semata. Bukan risywah .
Menurut Konvensi PBB tentang Anti Korupsi (United Nations Convention against Corruption/UNCAC) pemberian seperti itu dianggap gratifikasi atau penyuapan. Sejak disahkan 31 Oktober 2003, konvensi itu telah diratifikasi di banyak negara. Indonesia secara regulasi cukup maju dalam melawan tindakan korupsi. Hanya sedikit negara yang belum meratifikasi Konvensi Anti-Korupsi. Rata-rata adalah negara antidemokrasi dan gagal, seperti Somalia, Korea Utara, Chad, dan Suriah. Sejak awal reformasi Indonesia telah membuat pelbagai undang-undang tentang antikorupsi. Paling fenomenal tentu UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Menjijikkan
Meskipun masih tertatih-tatih, kita musti menjadikan korupsi masuk sebagai kejahatan paling menjijikkan. Bisa jadi pandangan ini dianggap sebuah kesombongan dibandingkan dengan sikap realistis terhadap konteks sosiologis. Namun, bagi aktivis antikorupsi dan pemerintahan yang bersih sikap itu adalah idealisme yang harus diperjuangkan sepanjang hayat.
Sebagai timsel (tim seleksi), penulis menyadari ruang korupsi juga terbuka lebar. Bisa dari pilihan ngopi bareng hingga silaturahim menjadi ruang yang bisa membintikkan korupsi. Bintik-bintik itu akan semakin terbuka ketika kita bersikap "ramah" kepada peserta calon sehingga aneka "wujud basa-basi" dan "tanda persahabatan" bisa menjadi modus korupsi yang semakin konkret.
Dalam level agak kasar bisa saja terjadi seperti yang dilakukan Akil Mochtar, Rudi Rudiantara, Irman Gusman, atau Patrialis Akbar, yang membuka ruang untuk menentukan "pemberian" secara pasti, bisa jadi tujuannya bukan karena kebutuhan mendesak, tapi agar hidup semakin bergaya.
Padahal jika kita tekun memahami arti kata korupsi secara genealogis bahasa Latin, yaitu corruptio, artinya sesuatu yang busuk, mengotori, dan menggoyahkan jiwa, maka tindakan korup bukanlah sebuah "diskresi" yang mudah dilupakan. Banyak kita lihat koruptor beribadah cukup taat dan bersikap ramah kepada publik.
Penulis sendiri membuat batasan cukup tegas ketika menjadi timsel, baik melalui media sosial ataupun melalui percakapan di WhatsApp dan SMS untuk tidak memberikan apa pun. Karena momen pemberian itu bukan seperti makna hadiah yang dianjurkan Nabi Muhammad untuk mengakrabkan hubungan, tapi bisa menajiskan rezeki. Korupsi itu seperti narkoba. Ia berdampak adiktif sehingga membuat kita semakin ingin menambah dosis demi ketenangan. Pada akhirnya akan terasa ada yang hampa ketika itu tidak dilakukan.
Belajar dari kasus mantan ketua MK itu, tindakan suap membawanya kepada efek domino kejahatan, seperti membela yang bayar berpengaruh terhadap hadirnya pemimpin lokal bobrok dan selingkuh dengan perempuan lain karena uang memang mudah didapatkan. Uang haram akan kembali ke muara yang haram. Jika dipraktikkan di praktik kekuasaan, ia akan melahirkan najis politik. Itulah yang menyebabkan banyak orang idealis malas mendekati politik.
(whb)














