Status Dualisme Pimpinan DPD
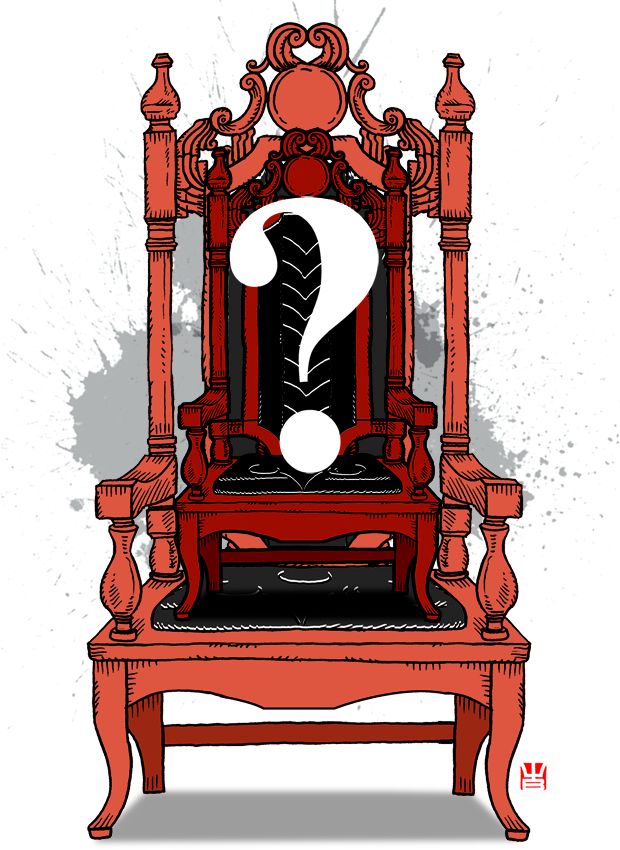
Status Dualisme Pimpinan DPD
A
A
A
FERI Amsari
Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 11 April lalu berlangsung ricuh. Status pimpinan DPD ilegal yang melekat pada kubu Oesman Sapta Odang (OSO) diduga sebagai pemicu.
Kepemimpinan OSO dianggap ilegal karena proses pemilihannya bertentangan dengan hukum. Proses pemilihan OSO itu memang alot dan di luar logika hukum yang wajar. Selain tidak memenuhi kuorum sidang, pemilihan OSO bertentangan dengan substansi putusan Mahkamah Agung (MA).
Menariknya, meskipun proses pemilihan bertentangan dengan putusan MA, wakil ketua MA memilih tetap memandu sumpah OSO selaku pimpinan DPD. Proses pemanduan itu sendiri bertentangan dengan ketentuan Pasal 260 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur bahwa penuntun sumpah hanya dapat dilakukan oleh ketua MA.
Langkah MA tetap melanjutkan penuntunan sumpah merupakan hal yang paling krusial dari upaya pengambilalihan pimpinan DPD secara ilegal tersebut.
Dengan terlaksana proses sumpah yang bertentangan dengan UU MD3 dan putusan MA itu, kepemimpinan OSO terkesan sah. Sebaliknya, status pimpinan DPD yang konstitusional dianggap telah berakhir. Apalagi, pimpinan DPD di bawah kendali M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad terpecah karena M Saleh memilih untuk menyerahkan ”kursinya” kepada OSO.
Di sisi lain, pimpinan DPD versi OSO berpendapat bahwa putusan MA itu tetap dijalankan dengan cara sinkronisasi melalui pembentukan peraturan DPD yang baru. Pembentukan peraturan baru tersebut bertujuan untuk melegalkan status pimpinan DPD versi OSO untuk menjabat hingga Pemilu 2019. Jika disimak putusan MA, cara berpikir pimpinan DPD versi OSO terkesan dipaksakan.
Dalam amar putusan MA secara eksplisit disebutkan MA mengabulkan seluruh pokok permohonan pemohon. Maknanya, MA menghendaki bahwa pimpinan DPD dengan komposisi M Saleh, GKR Hemar, dan Farouk Muhammad memimpin hingga 2019.
Dengan kondisi demikian, timbul pertanyaan ketatanegaraan. Pertama, bagaimanakah kekuatan putusan MA terkait pimpinan DPD? Kedua, apakah konsekuensi yang ditimbulkan dari pengabaian putusan MA tersebut?
Drama yang Hampir Sempurna
Selain melibatkan MA dalam sengkarut perebutan kursi pimpinan DPD, unsur kesekretariatan jenderal DPD juga terlibat dalam ”kudeta” kepemimpinan tersebut.
Asumsi itu berdasarkan sikap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD yang mengabaikan perintah GKR Hemas untuk membacakan putusan MA dalam paripurna 4 April lalu.
Apa yang menyebabkan sekjen memilih mengabaikan perintah pimpinan DPD satu-satunya ketika itu?
Sikap keberpihakan sekjen DPD kian kentara dengan menutup akses yang menjadi hak pimpinan DPD GKR Hemas dan Farouk Muhammad serta anggota DPD lainnya dari kubu yang sama. Sikap sekjen DPD itu tidak tepat karena hanya mengakomodasi salah satu pihak yang bertikai.
Jika asumsi keterlibatan kesekretariatan jenderal itu benar, sidang paripurna 4 April adalah drama politik yang hampir sempurna. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kudeta kursi pimpinan DPD telah dirancang dengan sangat matang.
Setidaknya terdapat tiga langkah yang dilakukan untuk merebut pimpinan DPD yang sah.
Pertama, pelaku kudeta memulai dengan menguasai mayoritas anggota DPD. Beralihnya visi politik sebagian besar anggota DPD menjadi anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dapat dipahami sebagai langkah menguasai lembaga parlemen yang mewakili aspirasi kedaerahan tersebut. Dengan dikuasainya DPD, proses ”meributkan” status pimpinan DPD yang sah mudah dilakukan.
Kedua, menguasai proses administrasi kelembagaan. Dengan menguasai kesekretariatan jenderal, proses persidangan, surat-menyurat, korespondensi dengan lembaga negara lain, jadwal kegiatan anggota, semua dapat dikendalikan sesuai kepentingan.
Tanpa proses administrasi kesekretariatan, upaya perebutan pimpinan akan sulit dilakukan. Itu sebabnya sebagian besar anggota DPD mengeluh tentang sikap keberpihakan kesekretariatan jenderal DPD pada kubu tertentu. Namun, hal itu sekaligus menunjukkan upaya kudeta dirancang matang.
Ketiga, proses penuntunan sumpah adalah puncak kudeta. Tanpa proses sumpah, kepemimpinan versi OSO tidak akan punya nilai dan mudah diabaikan.
Sumpah akan memberikan kesan telah legalnya proses peralihan kepemimpinan. Itu sebabnya, meskipun nyata-nyata berseberangan dengan putusan MA dan Pasal 260 UU MD3, proses penuntunan sumpah harus dipaksakan terjadi agar upaya pengambilalihan kursi pimpinan DPD terkesan sah.
Dengan tiga langkah itu, upaya kudeta terhadap pimpinan DPD yang sesuai putusan MA telah terjadi. Meskipun publik merasakan ada yang janggal dari pelantikan pimpinan DPD versi OSO, politik tidak mengakomodasi ”nurani publik”.
Satu-satunya cara melawan kekuatan politik yang demikian besar adalah menempuh jalur hukum. Misalnya, menggugat surat keputusan pelantikan pimpinan DPD versi OSO dan memberhentikan unsur kesekretariatan jenderal yang berpihak pada kubu tertentu.
Sifat Putusan MA
Beberapa ahli menyatakan pelantikan pimpinan DPD versi OSO dapat dianggap sah karena daya laku putusan MA tidak serta-merta. Butuh proses administrasi untuk mencabut Peraturan DPD Nomor 1/2016 dan Nomor 1/ 2017 tentang Tata Tertib. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materi yang menyatakan, jika pejabat tata usaha negara tidak memenuhi kewajibannya untuk mencabut putusan MA itu, dalam 90 hari peraturan itu tidak memiliki kekuatan hukum dengan sendirinya.
Menurut para ahli, karena peraturan itu belum dicabut, masa jabatan pimpinan DPD versi GKR Hemas dan Farouk Muhammad telah berakhir. Argumentasi ahli itu tidak jeli sebab dalam sidang paripurna 4 April putusan MA telah dibacakan dan pimpinan sidang (selaku pejabat tata usaha negara) telah mencabut dua peraturan tata tertib tersebut.
Tindakan pencabutan peraturan itu telah sesuai Pasal 6 ayat (2) Perma Hak Uji Materiil. Itu sebabnya, argumentasi yang menyatakan bahwa putusan MA tidak segera berlaku adalah argumentasi yang tidak cermat dan memahami apa yang terjadi di DPD.
Dengan berlaku putusan MA dan terjadi kealpaan prosesi sumpah pimpinan DPD yang bertentangan dengan putusan MA, status dualisme pimpinan DPD dapat dijawab secara hukum.
Pertama, pimpinan DPD yang sah adalah yang sesuai dengan putusan MA, yaitu sebagaimana yang dimohonkan dalam pokok-pokok permohonan uji materiil yang diajukan ke MA.
Kedua, prosesi sumpah pimpinan DPD kubu OSO tidak sah disebabkan bertentangan dengan Pasal 260 UU MD3 dan putusan MA. Konsekuensinya, kepemimpinan tersebut harus dianggap batal demi hukum.
Ketiga, secara hukum pimpinan DPD yang sah dan sesuai putusan MA berhak menjalankan fungsi ketatanegaraannya. Karena tidak memiliki kekuatan hukum, pilihan pihak-pihak yang mengudeta pimpinan DPD yang sah adalah dengan mengabaikan kebenaran yuridis putusan MA.
Itu sebabnya, penguasaan simbol-simbol politik pimpinan DPD merupakan bentuk praktik berpolitik yang sangat buruk karena telah mengabaikan putusan lembaga hukum tertinggi dan harus dihormati seluruh pihak.
Membiarkan pimpinan DPD yang sesuai dengan putusan MA tersingkir dengan kekuatan politik sama saja mengabaikan proses penegakan hukum yang sah.
Meskipun secara politik pimpinan DPD versi OSO sangat kuat, seluruh tindakannya adalah perbuatan melawan hukum.
Dosen Hukum Tata Negara dan Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PusaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)
SIDANG Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 11 April lalu berlangsung ricuh. Status pimpinan DPD ilegal yang melekat pada kubu Oesman Sapta Odang (OSO) diduga sebagai pemicu.
Kepemimpinan OSO dianggap ilegal karena proses pemilihannya bertentangan dengan hukum. Proses pemilihan OSO itu memang alot dan di luar logika hukum yang wajar. Selain tidak memenuhi kuorum sidang, pemilihan OSO bertentangan dengan substansi putusan Mahkamah Agung (MA).
Menariknya, meskipun proses pemilihan bertentangan dengan putusan MA, wakil ketua MA memilih tetap memandu sumpah OSO selaku pimpinan DPD. Proses pemanduan itu sendiri bertentangan dengan ketentuan Pasal 260 UU Nomor 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) yang mengatur bahwa penuntun sumpah hanya dapat dilakukan oleh ketua MA.
Langkah MA tetap melanjutkan penuntunan sumpah merupakan hal yang paling krusial dari upaya pengambilalihan pimpinan DPD secara ilegal tersebut.
Dengan terlaksana proses sumpah yang bertentangan dengan UU MD3 dan putusan MA itu, kepemimpinan OSO terkesan sah. Sebaliknya, status pimpinan DPD yang konstitusional dianggap telah berakhir. Apalagi, pimpinan DPD di bawah kendali M Saleh, GKR Hemas, dan Farouk Muhammad terpecah karena M Saleh memilih untuk menyerahkan ”kursinya” kepada OSO.
Di sisi lain, pimpinan DPD versi OSO berpendapat bahwa putusan MA itu tetap dijalankan dengan cara sinkronisasi melalui pembentukan peraturan DPD yang baru. Pembentukan peraturan baru tersebut bertujuan untuk melegalkan status pimpinan DPD versi OSO untuk menjabat hingga Pemilu 2019. Jika disimak putusan MA, cara berpikir pimpinan DPD versi OSO terkesan dipaksakan.
Dalam amar putusan MA secara eksplisit disebutkan MA mengabulkan seluruh pokok permohonan pemohon. Maknanya, MA menghendaki bahwa pimpinan DPD dengan komposisi M Saleh, GKR Hemar, dan Farouk Muhammad memimpin hingga 2019.
Dengan kondisi demikian, timbul pertanyaan ketatanegaraan. Pertama, bagaimanakah kekuatan putusan MA terkait pimpinan DPD? Kedua, apakah konsekuensi yang ditimbulkan dari pengabaian putusan MA tersebut?
Drama yang Hampir Sempurna
Selain melibatkan MA dalam sengkarut perebutan kursi pimpinan DPD, unsur kesekretariatan jenderal DPD juga terlibat dalam ”kudeta” kepemimpinan tersebut.
Asumsi itu berdasarkan sikap Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD yang mengabaikan perintah GKR Hemas untuk membacakan putusan MA dalam paripurna 4 April lalu.
Apa yang menyebabkan sekjen memilih mengabaikan perintah pimpinan DPD satu-satunya ketika itu?
Sikap keberpihakan sekjen DPD kian kentara dengan menutup akses yang menjadi hak pimpinan DPD GKR Hemas dan Farouk Muhammad serta anggota DPD lainnya dari kubu yang sama. Sikap sekjen DPD itu tidak tepat karena hanya mengakomodasi salah satu pihak yang bertikai.
Jika asumsi keterlibatan kesekretariatan jenderal itu benar, sidang paripurna 4 April adalah drama politik yang hampir sempurna. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kudeta kursi pimpinan DPD telah dirancang dengan sangat matang.
Setidaknya terdapat tiga langkah yang dilakukan untuk merebut pimpinan DPD yang sah.
Pertama, pelaku kudeta memulai dengan menguasai mayoritas anggota DPD. Beralihnya visi politik sebagian besar anggota DPD menjadi anggota Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dapat dipahami sebagai langkah menguasai lembaga parlemen yang mewakili aspirasi kedaerahan tersebut. Dengan dikuasainya DPD, proses ”meributkan” status pimpinan DPD yang sah mudah dilakukan.
Kedua, menguasai proses administrasi kelembagaan. Dengan menguasai kesekretariatan jenderal, proses persidangan, surat-menyurat, korespondensi dengan lembaga negara lain, jadwal kegiatan anggota, semua dapat dikendalikan sesuai kepentingan.
Tanpa proses administrasi kesekretariatan, upaya perebutan pimpinan akan sulit dilakukan. Itu sebabnya sebagian besar anggota DPD mengeluh tentang sikap keberpihakan kesekretariatan jenderal DPD pada kubu tertentu. Namun, hal itu sekaligus menunjukkan upaya kudeta dirancang matang.
Ketiga, proses penuntunan sumpah adalah puncak kudeta. Tanpa proses sumpah, kepemimpinan versi OSO tidak akan punya nilai dan mudah diabaikan.
Sumpah akan memberikan kesan telah legalnya proses peralihan kepemimpinan. Itu sebabnya, meskipun nyata-nyata berseberangan dengan putusan MA dan Pasal 260 UU MD3, proses penuntunan sumpah harus dipaksakan terjadi agar upaya pengambilalihan kursi pimpinan DPD terkesan sah.
Dengan tiga langkah itu, upaya kudeta terhadap pimpinan DPD yang sesuai putusan MA telah terjadi. Meskipun publik merasakan ada yang janggal dari pelantikan pimpinan DPD versi OSO, politik tidak mengakomodasi ”nurani publik”.
Satu-satunya cara melawan kekuatan politik yang demikian besar adalah menempuh jalur hukum. Misalnya, menggugat surat keputusan pelantikan pimpinan DPD versi OSO dan memberhentikan unsur kesekretariatan jenderal yang berpihak pada kubu tertentu.
Sifat Putusan MA
Beberapa ahli menyatakan pelantikan pimpinan DPD versi OSO dapat dianggap sah karena daya laku putusan MA tidak serta-merta. Butuh proses administrasi untuk mencabut Peraturan DPD Nomor 1/2016 dan Nomor 1/ 2017 tentang Tata Tertib. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan MA Nomor 1/2011 tentang Hak Uji Materi yang menyatakan, jika pejabat tata usaha negara tidak memenuhi kewajibannya untuk mencabut putusan MA itu, dalam 90 hari peraturan itu tidak memiliki kekuatan hukum dengan sendirinya.
Menurut para ahli, karena peraturan itu belum dicabut, masa jabatan pimpinan DPD versi GKR Hemas dan Farouk Muhammad telah berakhir. Argumentasi ahli itu tidak jeli sebab dalam sidang paripurna 4 April putusan MA telah dibacakan dan pimpinan sidang (selaku pejabat tata usaha negara) telah mencabut dua peraturan tata tertib tersebut.
Tindakan pencabutan peraturan itu telah sesuai Pasal 6 ayat (2) Perma Hak Uji Materiil. Itu sebabnya, argumentasi yang menyatakan bahwa putusan MA tidak segera berlaku adalah argumentasi yang tidak cermat dan memahami apa yang terjadi di DPD.
Dengan berlaku putusan MA dan terjadi kealpaan prosesi sumpah pimpinan DPD yang bertentangan dengan putusan MA, status dualisme pimpinan DPD dapat dijawab secara hukum.
Pertama, pimpinan DPD yang sah adalah yang sesuai dengan putusan MA, yaitu sebagaimana yang dimohonkan dalam pokok-pokok permohonan uji materiil yang diajukan ke MA.
Kedua, prosesi sumpah pimpinan DPD kubu OSO tidak sah disebabkan bertentangan dengan Pasal 260 UU MD3 dan putusan MA. Konsekuensinya, kepemimpinan tersebut harus dianggap batal demi hukum.
Ketiga, secara hukum pimpinan DPD yang sah dan sesuai putusan MA berhak menjalankan fungsi ketatanegaraannya. Karena tidak memiliki kekuatan hukum, pilihan pihak-pihak yang mengudeta pimpinan DPD yang sah adalah dengan mengabaikan kebenaran yuridis putusan MA.
Itu sebabnya, penguasaan simbol-simbol politik pimpinan DPD merupakan bentuk praktik berpolitik yang sangat buruk karena telah mengabaikan putusan lembaga hukum tertinggi dan harus dihormati seluruh pihak.
Membiarkan pimpinan DPD yang sesuai dengan putusan MA tersingkir dengan kekuatan politik sama saja mengabaikan proses penegakan hukum yang sah.
Meskipun secara politik pimpinan DPD versi OSO sangat kuat, seluruh tindakannya adalah perbuatan melawan hukum.
(dam)














