Menuju Masyarakat Literat
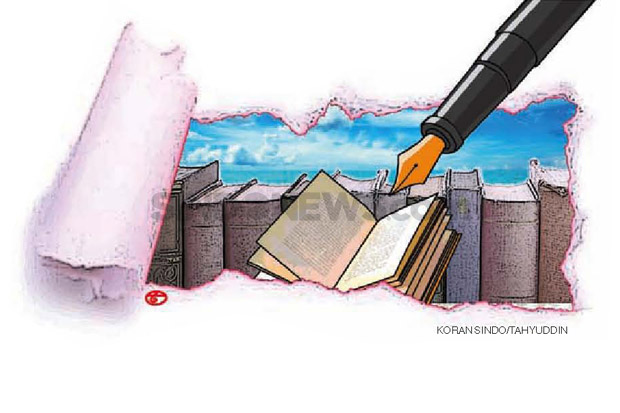
Menuju Masyarakat Literat
A
A
A
Deddy Kristian Aritonang
Kolumnis Lepas, Guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan, dan Dosen PTS
SETIAP kali penelitian tentang budaya literasi dibuat oleh berbagai lembaga internasional, Indonesia selalu masuk kategori negara dengan minat baca rendah.
UNESCO pada 2012 mengonfirmasi bahwa indeks minat baca masyarakat kita hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 penduduk Indonesia, hanya satu orang yang gemar membaca. Tiga tahun kemudian, hasil penelitian PISA (Programme for International Student Assessment) yang dirilis oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan Indonesia ada di peringkat 62 dari 70 negara. Lalu pada 2016, Central Connecticut State University ( CCSU) dalam laporan yang berjudul "The World’s Most Literate Nation" lagi-lagi menempatkan Indonesia hanya di posisi ke-60 dari 61 negara peserta atau satu tingkat lebih baik dari Botswana, negara di Afrika bagian selatan.
Bangsa yang Malas Membaca?
Rendahnya pencapaian-pencapaian itu sering diasosiasikan dengan "penyakit" malas membaca yang diidap oleh kebanyakan masyarakat kita. Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat 90% penduduk berusia 10 tahun ke atas ternyata lebih suka menonton televisi ketimbang membaca buku.
Keadaan ini semakin diperparah dengan data statistik yang menunjukkan bahwa buku-buku yang dibaca orang Indonesia rata-rata per tahun hanya tiga judul. Jumlah itu kalah jauh bila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, atau Jerman yang penduduknya mampu melahap 20 sampai 30 buku dalam kurun waktu satu tahun.
Lalu, benarkah sifat malas membaca merupakan akar permasalahannya? Sejujurnya, saya bukan bermaksud untuk meragukan kredibilitas lembaga-lembaga tadi. Hanya, jika melihat kenyataan di lapangan, boleh jadi akar permasalahannya bukan terletak pada sifat malas atau kurangnya minat membaca.
Pertama, coba kita lihat fenomena bazar buku terbesar di dunia, Big Bad Wolf (BBW), yang pernah digelar di kota-kota besar di Indonesia. Dari awal kemunculannya, BBW selalu dibanjiri masyarakat. Tren penjualan buku-buku mereka juga selalu konsisten melampaui target di setiap tahun penyelenggaraan. Padahal, selain didominasi buku-buku dengan pengantar bahasa Inggris, harga buku-buku di BBW juga tidak bisa dikategorikan sangat murah kendati sudah diberikan potongan harga.
Kedua, para pegiat literasi ketika mengampanyekan budaya membaca dan mendistribusikan buku-buku ke banyak daerah terpencil di Tanah Air, justru sering mendapati respons sangat positif dan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat. Nirwan Ahmad Arsuka, inisiator Pustaka Bergerak, berpendapat bahwa hasil temuan UNESCO, PISA, CCSU, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya justru kerap memicu timbulnya kesimpulan yang salah soal minat baca bangsa kita.
Itulah yang terjadi saban hari—stigma orang Indonesia malas membaca semakin lama semakin melekat. Ironisnya, pandangan itu diterima begitu saja dan malah diamini oleh sebagian besar masyarakat kita. Maka tidak heran bila setiap kali hendak mencari solusi terhadap persoalan literasi, tuduhan malas membaca cepat-cepat mengisi ruang dalam pola pikir kita.
Pada akhirnya, kita terjebak oleh ulah kita sendiri. Memecahkan masalah literasi kita simplifikasi secara parsial, yakni sebatas mengubah sifat malas membaca. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan asumsi yang kita bangun sendiri bahwa mengubah sifat, apalagi yang sudah begitu melekat, merupakan pekerjaan sangat sulit. Dan karena justifikasi soal sifat malas membaca itu pula, yang kemudian membuat kita abai atau kurang memberi perhatian lebih pada isu-isu lain yang barangkali menjadi faktor-faktor utama penyebab rendahnya budaya literasi kita dari tahun ke tahun.
Berbenah
Kunci untuk menjadi sebuah negara maju dengan kualitas sumber daya manusia mumpuni tidak bisa dipisahkan dari kemampuan membaca para penduduknya (baca: masyarakat literat). Tanggung jawab itu tidak bisa serta-merta dipikul oleh satu pihak saja. Harus ada keterlibatan dan saling dukung di antara elemen-elemen terkait.
Menumbuhkan minta baca harus dilakukan sejak dini. Dengan demikian, keluarga mengemban konsekuensi logis sebagai fondasi awal untuk mewujudkan cita-cita itu. Kita beruntung karena negeri ini kaya akan dongeng dan cerita rakyat. Jika dahulu orang tua suka melantunkan cerita pengantar tidur pada anak, kebiasaan itu sudah bisa dimodifikasi. Orang tua harus mulai membudayakan membacakan cerita kepada anak-anak sehingga kita tidak cuma menjadi bangsa penganut tradisi lisan (oral tradition) .
Selain dijadikan sebagai budaya, membaca juga semestinya dipandang sebagai kebutuhan. Untuk itu, panutan merupakan unsur penting. Sayangnya, kebanyakan orang tua belum menunjukkan teladan membaca dan terkesan menyerahkan urusan literasi kepada sekolah.
Menyuruh anak rajin membaca, sementara orang tua sendiri tidak memiliki animo membaca, adalah bentuk pola asuh yang salah kaprah. Harus disadari betul bahwa anak-anak sejatinya merupakan peniru ulung (children are great immitators). Jika sejak kecil anak-anak sudah terekspos oleh rutinitas membaca yang ditunjukkan ayah dan ibu secara konsisten, niscaya mereka akan mengikuti kebiasaan itu.
Sekolah juga demikian. Guru tidak cukup hanya mengimbau murid-murid agar giat membaca, tapi juga harus menjadi pembaca aktif. Sayangnya, guru-guru sekarang terlalu disibukkan dengan urusan tugas administrasi sekolah dan seabrek tuntutan kurikulum yang membuat mereka kurang atau tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk membaca. Kondisi ini harus dibenahi agar menggiatkan literasi tidak terkesan hanya sebatas jargon semata khususnya di mata para peserta didik.
Secara khusus, mata pelajaran Bahasa Indonesia harus berada di garda terdepan. Selama ini, pembelajaran Bahasa Indonesia cenderung berorientasi pada ujian sehingga metode mengajar lebih berfokus pada kiat-kiat menjawab soal ketimbang membaca dan mengulas karya-karya sastra.
Terkait dengan hal ini, Johannes Sumardinata dalam bukunya yang berjudul Guru Gokil Murid Unyu , memaparkan fakta yang cukup memprihatinkan. Dari sekian banyak guru Bahasa Indonesia, tidak sampai 0,5% yang pernah membaca Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Meski sempat dilarang di masa pemerintahan Orde Baru, Tetralogi Buru beberapa kali mengantarkan sang penulis sebagai nominator peraih Nobel Prize. Intinya, sekolah adalah agen perubahan (agent of change).
Berikutnya, mewujudkan masyarakat literat harus diinisiasi oleh prinsip menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Di negara-negara maju, bukan pemandangan aneh apabila penduduknya banyak ditemukan menyempatkan diri membaca di ruang-ruang publik seperti ketika berada di bus, kereta api, ruang tunggu.
Masyarakat kita pun seharusnya bisa demikian. Dewasa ini kita terlalu dibombardir oleh rutinitas menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Sudah saatnya kebiasaan kontraproduktif itu direduksi perlahan-lahan dan dialihkan pada kegiatan membaca buku.
Memang, kita tidak bisa serta-merta memaksakan diri dengan target muluk-muluk. Seperti kata Riduan Situmorang, gerakan literasi tidak seperti memakan cabai: di situ makan, di situ terasa pedasnya. Artinya, ia bukan hal yang instan. Prinsip satu buku satu bulan bisa menjadi target awal yang harus dicapai mengingat membaca harus dilakukan secara tuntas.
Ketika anak-anak, orang tua, guru-guru, dan masyarakat luas sudah memiliki komitmen yang kuat untuk membumikan minat baca, maka ekosistem yang sudah terbentuk ini harus mendapat sokongan kuat dari pemerintah.
Pemerintah semestinya menjamin ketersediaan akses buku-buku bacaan yang bermutu dan terjangkau. Menambah jumlah perpustakaan umum sehingga bisa menjangkau ke daerah pelosok-pelosok adalah salah satu solusinya. Sejauh ini perpustakaan umum hanya bisa dinikmati penduduk yang berdomisili di wilayah kabupaten dan kota.
Selain itu, pemerintah punya tanggung jawab besar merawat industri perbukuan. Memang tidak bisa dimungkiri apabila sesuatu sudah masuk ranah perindustrian, kalkulasinya selalu antara untung dan rugi yang disertai dengan mekanisme pajak. Besarnya pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan untuk penulis dari hasil royalti penjualan buku selama ini, dianggap begitu mencekik sehingga banyak penulis yang mengurungkan niatnya untuk berkarya.
Bahkan, sekelas Tere Liye pun sampai harus memutus kontrak dengan dua penerbit besar, Gramedia Pustaka Utama dan Republika, pada 2017 silam sebagai bentuk protesnya. Bagaimanapun, penulis tetaplah manusia yang butuh bertahan hidup. Permasalahan ini harus direspons serius oleh pemerintah mengingat produksi buku kita berdasarkan International Standard Book Number (ISBN) pada 2016 hanya sekitar 64.000 per tahun. Bandingkan dengan China yang mampu memproduksi sebanyak 440.000 setiap tahun. Jika terus-menerus dibiarkan, sulit rasanya untuk mengharapkan peningkatan jumlah buku-buku secara signifikan.
Terakhir, pemerintah juga harus menggandeng relawan-relawan literasi yang sudah berjuang keras "menjemput bola" dengan menjadi perpustakaan bergerak dari satu desa ke desa lainnya dan menawarkan buku kepada masyarakat secara cuma-cuma. Mereka adalah pahlawan literasi karena dengan kehadiran mereka penduduk di daerah tertinggal mulai bisa menikmati buku. Salam literasi!
Kolumnis Lepas, Guru SMP/SMA Sutomo 2 Medan, dan Dosen PTS
SETIAP kali penelitian tentang budaya literasi dibuat oleh berbagai lembaga internasional, Indonesia selalu masuk kategori negara dengan minat baca rendah.
UNESCO pada 2012 mengonfirmasi bahwa indeks minat baca masyarakat kita hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 penduduk Indonesia, hanya satu orang yang gemar membaca. Tiga tahun kemudian, hasil penelitian PISA (Programme for International Student Assessment) yang dirilis oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan Indonesia ada di peringkat 62 dari 70 negara. Lalu pada 2016, Central Connecticut State University ( CCSU) dalam laporan yang berjudul "The World’s Most Literate Nation" lagi-lagi menempatkan Indonesia hanya di posisi ke-60 dari 61 negara peserta atau satu tingkat lebih baik dari Botswana, negara di Afrika bagian selatan.
Bangsa yang Malas Membaca?
Rendahnya pencapaian-pencapaian itu sering diasosiasikan dengan "penyakit" malas membaca yang diidap oleh kebanyakan masyarakat kita. Kantor Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mencatat 90% penduduk berusia 10 tahun ke atas ternyata lebih suka menonton televisi ketimbang membaca buku.
Keadaan ini semakin diperparah dengan data statistik yang menunjukkan bahwa buku-buku yang dibaca orang Indonesia rata-rata per tahun hanya tiga judul. Jumlah itu kalah jauh bila dibandingkan dengan negara-negara maju seperti Finlandia, Jepang, atau Jerman yang penduduknya mampu melahap 20 sampai 30 buku dalam kurun waktu satu tahun.
Lalu, benarkah sifat malas membaca merupakan akar permasalahannya? Sejujurnya, saya bukan bermaksud untuk meragukan kredibilitas lembaga-lembaga tadi. Hanya, jika melihat kenyataan di lapangan, boleh jadi akar permasalahannya bukan terletak pada sifat malas atau kurangnya minat membaca.
Pertama, coba kita lihat fenomena bazar buku terbesar di dunia, Big Bad Wolf (BBW), yang pernah digelar di kota-kota besar di Indonesia. Dari awal kemunculannya, BBW selalu dibanjiri masyarakat. Tren penjualan buku-buku mereka juga selalu konsisten melampaui target di setiap tahun penyelenggaraan. Padahal, selain didominasi buku-buku dengan pengantar bahasa Inggris, harga buku-buku di BBW juga tidak bisa dikategorikan sangat murah kendati sudah diberikan potongan harga.
Kedua, para pegiat literasi ketika mengampanyekan budaya membaca dan mendistribusikan buku-buku ke banyak daerah terpencil di Tanah Air, justru sering mendapati respons sangat positif dan antusiasme yang begitu tinggi dari masyarakat. Nirwan Ahmad Arsuka, inisiator Pustaka Bergerak, berpendapat bahwa hasil temuan UNESCO, PISA, CCSU, dan lembaga-lembaga sejenis lainnya justru kerap memicu timbulnya kesimpulan yang salah soal minat baca bangsa kita.
Itulah yang terjadi saban hari—stigma orang Indonesia malas membaca semakin lama semakin melekat. Ironisnya, pandangan itu diterima begitu saja dan malah diamini oleh sebagian besar masyarakat kita. Maka tidak heran bila setiap kali hendak mencari solusi terhadap persoalan literasi, tuduhan malas membaca cepat-cepat mengisi ruang dalam pola pikir kita.
Pada akhirnya, kita terjebak oleh ulah kita sendiri. Memecahkan masalah literasi kita simplifikasi secara parsial, yakni sebatas mengubah sifat malas membaca. Situasi ini menjadi semakin rumit dengan asumsi yang kita bangun sendiri bahwa mengubah sifat, apalagi yang sudah begitu melekat, merupakan pekerjaan sangat sulit. Dan karena justifikasi soal sifat malas membaca itu pula, yang kemudian membuat kita abai atau kurang memberi perhatian lebih pada isu-isu lain yang barangkali menjadi faktor-faktor utama penyebab rendahnya budaya literasi kita dari tahun ke tahun.
Berbenah
Kunci untuk menjadi sebuah negara maju dengan kualitas sumber daya manusia mumpuni tidak bisa dipisahkan dari kemampuan membaca para penduduknya (baca: masyarakat literat). Tanggung jawab itu tidak bisa serta-merta dipikul oleh satu pihak saja. Harus ada keterlibatan dan saling dukung di antara elemen-elemen terkait.
Menumbuhkan minta baca harus dilakukan sejak dini. Dengan demikian, keluarga mengemban konsekuensi logis sebagai fondasi awal untuk mewujudkan cita-cita itu. Kita beruntung karena negeri ini kaya akan dongeng dan cerita rakyat. Jika dahulu orang tua suka melantunkan cerita pengantar tidur pada anak, kebiasaan itu sudah bisa dimodifikasi. Orang tua harus mulai membudayakan membacakan cerita kepada anak-anak sehingga kita tidak cuma menjadi bangsa penganut tradisi lisan (oral tradition) .
Selain dijadikan sebagai budaya, membaca juga semestinya dipandang sebagai kebutuhan. Untuk itu, panutan merupakan unsur penting. Sayangnya, kebanyakan orang tua belum menunjukkan teladan membaca dan terkesan menyerahkan urusan literasi kepada sekolah.
Menyuruh anak rajin membaca, sementara orang tua sendiri tidak memiliki animo membaca, adalah bentuk pola asuh yang salah kaprah. Harus disadari betul bahwa anak-anak sejatinya merupakan peniru ulung (children are great immitators). Jika sejak kecil anak-anak sudah terekspos oleh rutinitas membaca yang ditunjukkan ayah dan ibu secara konsisten, niscaya mereka akan mengikuti kebiasaan itu.
Sekolah juga demikian. Guru tidak cukup hanya mengimbau murid-murid agar giat membaca, tapi juga harus menjadi pembaca aktif. Sayangnya, guru-guru sekarang terlalu disibukkan dengan urusan tugas administrasi sekolah dan seabrek tuntutan kurikulum yang membuat mereka kurang atau tidak lagi memiliki waktu yang cukup untuk membaca. Kondisi ini harus dibenahi agar menggiatkan literasi tidak terkesan hanya sebatas jargon semata khususnya di mata para peserta didik.
Secara khusus, mata pelajaran Bahasa Indonesia harus berada di garda terdepan. Selama ini, pembelajaran Bahasa Indonesia cenderung berorientasi pada ujian sehingga metode mengajar lebih berfokus pada kiat-kiat menjawab soal ketimbang membaca dan mengulas karya-karya sastra.
Terkait dengan hal ini, Johannes Sumardinata dalam bukunya yang berjudul Guru Gokil Murid Unyu , memaparkan fakta yang cukup memprihatinkan. Dari sekian banyak guru Bahasa Indonesia, tidak sampai 0,5% yang pernah membaca Tetralogi Buru karya Pramoedya Ananta Toer. Meski sempat dilarang di masa pemerintahan Orde Baru, Tetralogi Buru beberapa kali mengantarkan sang penulis sebagai nominator peraih Nobel Prize. Intinya, sekolah adalah agen perubahan (agent of change).
Berikutnya, mewujudkan masyarakat literat harus diinisiasi oleh prinsip menjadikan membaca sebagai kebiasaan. Di negara-negara maju, bukan pemandangan aneh apabila penduduknya banyak ditemukan menyempatkan diri membaca di ruang-ruang publik seperti ketika berada di bus, kereta api, ruang tunggu.
Masyarakat kita pun seharusnya bisa demikian. Dewasa ini kita terlalu dibombardir oleh rutinitas menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial. Sudah saatnya kebiasaan kontraproduktif itu direduksi perlahan-lahan dan dialihkan pada kegiatan membaca buku.
Memang, kita tidak bisa serta-merta memaksakan diri dengan target muluk-muluk. Seperti kata Riduan Situmorang, gerakan literasi tidak seperti memakan cabai: di situ makan, di situ terasa pedasnya. Artinya, ia bukan hal yang instan. Prinsip satu buku satu bulan bisa menjadi target awal yang harus dicapai mengingat membaca harus dilakukan secara tuntas.
Ketika anak-anak, orang tua, guru-guru, dan masyarakat luas sudah memiliki komitmen yang kuat untuk membumikan minat baca, maka ekosistem yang sudah terbentuk ini harus mendapat sokongan kuat dari pemerintah.
Pemerintah semestinya menjamin ketersediaan akses buku-buku bacaan yang bermutu dan terjangkau. Menambah jumlah perpustakaan umum sehingga bisa menjangkau ke daerah pelosok-pelosok adalah salah satu solusinya. Sejauh ini perpustakaan umum hanya bisa dinikmati penduduk yang berdomisili di wilayah kabupaten dan kota.
Selain itu, pemerintah punya tanggung jawab besar merawat industri perbukuan. Memang tidak bisa dimungkiri apabila sesuatu sudah masuk ranah perindustrian, kalkulasinya selalu antara untung dan rugi yang disertai dengan mekanisme pajak. Besarnya pajak penghasilan (PPh) yang dikenakan untuk penulis dari hasil royalti penjualan buku selama ini, dianggap begitu mencekik sehingga banyak penulis yang mengurungkan niatnya untuk berkarya.
Bahkan, sekelas Tere Liye pun sampai harus memutus kontrak dengan dua penerbit besar, Gramedia Pustaka Utama dan Republika, pada 2017 silam sebagai bentuk protesnya. Bagaimanapun, penulis tetaplah manusia yang butuh bertahan hidup. Permasalahan ini harus direspons serius oleh pemerintah mengingat produksi buku kita berdasarkan International Standard Book Number (ISBN) pada 2016 hanya sekitar 64.000 per tahun. Bandingkan dengan China yang mampu memproduksi sebanyak 440.000 setiap tahun. Jika terus-menerus dibiarkan, sulit rasanya untuk mengharapkan peningkatan jumlah buku-buku secara signifikan.
Terakhir, pemerintah juga harus menggandeng relawan-relawan literasi yang sudah berjuang keras "menjemput bola" dengan menjadi perpustakaan bergerak dari satu desa ke desa lainnya dan menawarkan buku kepada masyarakat secara cuma-cuma. Mereka adalah pahlawan literasi karena dengan kehadiran mereka penduduk di daerah tertinggal mulai bisa menikmati buku. Salam literasi!
(wib)














