Simulakra Bahasa
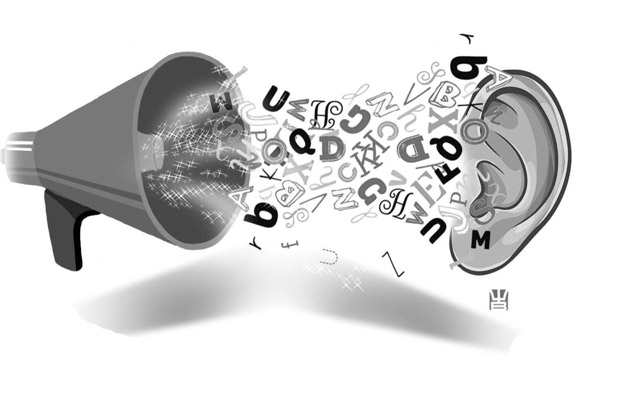
Simulakra Bahasa
A
A
A
Joko Santoso
Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
BAHASA dapat digunakan untuk berkata benar (kebenaran) sekaligus berkata bohong (kebohongan). Selain secara fungsional menjadi standar komunikasi, bahasa juga tak ubahnya menjadi sebuah wadah, media, atau "tempurung" bagi kepentingan menyampaikan kebenaran sekaligus kebohongan. Dua hal terakhir ini bukannya tidak terendus teknologi. Bahkan, ide mendeteksi kebohongan sudah dimulai oleh James McKenzie pada 1902 dan disempurnakan oleh mahasiswa kedokteran Universitas California bernama John Larson pada 1921 dengan sebuah mesin poligraf.
Apakah dengan demikian, untuk alasan kedua hal itu (kebenaran dan kebohongan), bahasa sebagai media sudah gagal objektif? Jika yang dimaksud adalah bahasa tulis dengan sistemnya, bisa jadi tidak gagal secara formal. Namun, berbeda halnya dengan bahasa lisan yang memungkinkan lebih besar terjadinya duplikasi, imitasi, dan konotasi-konotasi sesuai kondisi penuturnya. Walaupun di era internet sekarang, bahasa tulis dan lisan sudah tidak berjarak. Keduanya hadir dalam ruang yang sama.
Arena Politik dan Konotasi Siber
Sering dibicarakan para ahli bahwa bahasa dalam arena politik terbukti tidak bebas nilai. Bahasa menghamba pada kepentingan-kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Jika salah satu nilai atau kepentingan itu adalah denotasi-denotasi (upaya kebenaran), bahasa dalam arena politik berusaha sebaik mungkin menjauhi denotasi itu dan sebanyak-banyaknya menampung konotasi-konotasi (upaya kebohongan). Konotasi tersebut meruang dalam jaring-jaring siber. Atau, katakanlah sebagai konotasi siber. Konotasi yang menyebar dalam bahasa dan ruang siber (internet dan multimedia).
Dengan kata lain, dalam arena politik denotasi tidaklah penting lagi. Sebab, ada hal yang lebih penting, yaitu upaya membuat bahasa "terpisah" dari maknanya dan "terpisah" pula dari denotasinya. Artinya, tidak penting lagi apakah kata-kata yang diucapkan atau dituliskan seharusnya bermakna sesuai kebenaran maknanya. Arena ini memungkinkan keberjarakan atau alienasi makna yang bahkan bisa berlawanan atau bertolak belakang sama sekali.
Simulakra: Reduplikasi Konotasi
Kalau denotasi atau makna sebenarnya sudah tidak lagi penting maka yang diproduksi adalah konotasi yang bahkan tidak ada referen atau dasarnya. Konotasi ini tidak perlu sama sekali acuan kebenaran dalam logika wajar manusia. Misalnya, dalam kamus disepakati: "Pencuri adalah orang yang mencuri", maka arena politik tidak harus berdasar pada hal itu. Arena ini bisa saja membuat: "Pencuri adalah orang yang tidak pernah mencuri", atau "Pencuri adalah orang baik dan suci".
Kalaupun ada acuan penggunaan bahasa dalam arena politik maka acuannya bukan makna sebenarnya (denotasi), tetapi makna yang lain (konotasi). Tradisi berpolitik serupa itu, yang memungkinkan sebuah transformasi radikal terhadap penggunaan bahasa, mendorong lahirnya konotasi-konotasi (kebohongan) baru. Acuannya bukan lagi kebenaran, melainkan kebohongan. Oleh karena kebohongan adalah acuan utamanya, maka produksinya adalah kebohongan yang lain pula. Akhirnya, sirkulasi bahasa adalah keruwetan komunikasi yang berisi tumpang tindihnya kebohongan. Reproduksi dan reduplikasi konotasi atau kebohongan pada gilirannya akan terus berlanjut.
Saya prihatin jika apa yang saya tuliskan tersebut memang benar adanya. Bayangkan jika bahasa memang digunakan hanya untuk reproduksi kebohongan. Bertubi-tubi bahasa digunakan hanya untuk memenangkan tender politik maupun tender kepentingan. Masih mending jika "lidah" atau media boleh disalahkan sebagai lidah tak bertulang . Artinya, antara pikiran dan nurani (sumber kebenaran) dengan lidah sedang tidak nyambung saja. Hal itu masih bisa dibenahi, diklarifikasi, diluruskan. Namun, saya tidak bisa membayangkan jika pikiran dan nurani tidak lagi menyimpan memori kebenaran, melainkan kebohongan-kebohongan yang terus-menerus direproduksi dan direduplikasi. Apakah masih mungkin menyalahkan lidah?
Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
BAHASA dapat digunakan untuk berkata benar (kebenaran) sekaligus berkata bohong (kebohongan). Selain secara fungsional menjadi standar komunikasi, bahasa juga tak ubahnya menjadi sebuah wadah, media, atau "tempurung" bagi kepentingan menyampaikan kebenaran sekaligus kebohongan. Dua hal terakhir ini bukannya tidak terendus teknologi. Bahkan, ide mendeteksi kebohongan sudah dimulai oleh James McKenzie pada 1902 dan disempurnakan oleh mahasiswa kedokteran Universitas California bernama John Larson pada 1921 dengan sebuah mesin poligraf.
Apakah dengan demikian, untuk alasan kedua hal itu (kebenaran dan kebohongan), bahasa sebagai media sudah gagal objektif? Jika yang dimaksud adalah bahasa tulis dengan sistemnya, bisa jadi tidak gagal secara formal. Namun, berbeda halnya dengan bahasa lisan yang memungkinkan lebih besar terjadinya duplikasi, imitasi, dan konotasi-konotasi sesuai kondisi penuturnya. Walaupun di era internet sekarang, bahasa tulis dan lisan sudah tidak berjarak. Keduanya hadir dalam ruang yang sama.
Arena Politik dan Konotasi Siber
Sering dibicarakan para ahli bahwa bahasa dalam arena politik terbukti tidak bebas nilai. Bahasa menghamba pada kepentingan-kepentingan seseorang atau golongan tertentu. Jika salah satu nilai atau kepentingan itu adalah denotasi-denotasi (upaya kebenaran), bahasa dalam arena politik berusaha sebaik mungkin menjauhi denotasi itu dan sebanyak-banyaknya menampung konotasi-konotasi (upaya kebohongan). Konotasi tersebut meruang dalam jaring-jaring siber. Atau, katakanlah sebagai konotasi siber. Konotasi yang menyebar dalam bahasa dan ruang siber (internet dan multimedia).
Dengan kata lain, dalam arena politik denotasi tidaklah penting lagi. Sebab, ada hal yang lebih penting, yaitu upaya membuat bahasa "terpisah" dari maknanya dan "terpisah" pula dari denotasinya. Artinya, tidak penting lagi apakah kata-kata yang diucapkan atau dituliskan seharusnya bermakna sesuai kebenaran maknanya. Arena ini memungkinkan keberjarakan atau alienasi makna yang bahkan bisa berlawanan atau bertolak belakang sama sekali.
Simulakra: Reduplikasi Konotasi
Kalau denotasi atau makna sebenarnya sudah tidak lagi penting maka yang diproduksi adalah konotasi yang bahkan tidak ada referen atau dasarnya. Konotasi ini tidak perlu sama sekali acuan kebenaran dalam logika wajar manusia. Misalnya, dalam kamus disepakati: "Pencuri adalah orang yang mencuri", maka arena politik tidak harus berdasar pada hal itu. Arena ini bisa saja membuat: "Pencuri adalah orang yang tidak pernah mencuri", atau "Pencuri adalah orang baik dan suci".
Kalaupun ada acuan penggunaan bahasa dalam arena politik maka acuannya bukan makna sebenarnya (denotasi), tetapi makna yang lain (konotasi). Tradisi berpolitik serupa itu, yang memungkinkan sebuah transformasi radikal terhadap penggunaan bahasa, mendorong lahirnya konotasi-konotasi (kebohongan) baru. Acuannya bukan lagi kebenaran, melainkan kebohongan. Oleh karena kebohongan adalah acuan utamanya, maka produksinya adalah kebohongan yang lain pula. Akhirnya, sirkulasi bahasa adalah keruwetan komunikasi yang berisi tumpang tindihnya kebohongan. Reproduksi dan reduplikasi konotasi atau kebohongan pada gilirannya akan terus berlanjut.
Saya prihatin jika apa yang saya tuliskan tersebut memang benar adanya. Bayangkan jika bahasa memang digunakan hanya untuk reproduksi kebohongan. Bertubi-tubi bahasa digunakan hanya untuk memenangkan tender politik maupun tender kepentingan. Masih mending jika "lidah" atau media boleh disalahkan sebagai lidah tak bertulang . Artinya, antara pikiran dan nurani (sumber kebenaran) dengan lidah sedang tidak nyambung saja. Hal itu masih bisa dibenahi, diklarifikasi, diluruskan. Namun, saya tidak bisa membayangkan jika pikiran dan nurani tidak lagi menyimpan memori kebenaran, melainkan kebohongan-kebohongan yang terus-menerus direproduksi dan direduplikasi. Apakah masih mungkin menyalahkan lidah?
(thm)














