Setelah Perda Agama
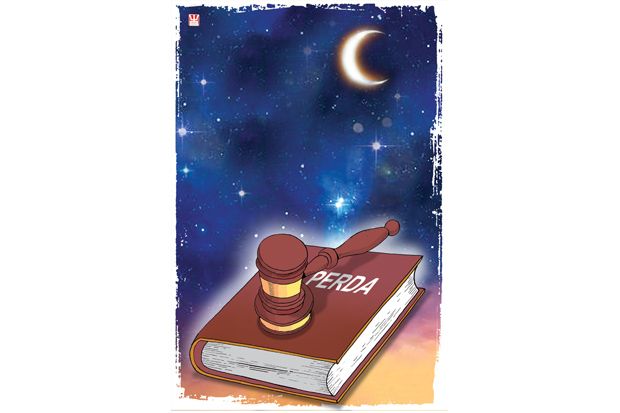
Setelah Perda Agama
A
A
A
Dimas Firdausy Hunafa
Mahasiswa Magister Hukum UII Yogyakarta, Peneliti Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Yogyakarta
BEBERAPA waktu lalu, publik digegerkan dengan sikap politik salah satu partai yang menolak peraturan daerah berbasis agama (perda syariah dan Injil). Hal tersebut disampaikan ketua umumnya yang menyatakan bahwa negara Indonesia kini tidak lagi memerlukan perda berbasis agama. Alasannya adalah relevansi perda berbasis agama berpotensi pada diskriminasi terhadap warga negara.
Mengenai polemik perda syariah sebenarnya pernah mencuat sejak diberlakukan di beberapa daerah sebagai dampak dari adanya otonomi daerah. Berbeda dalam kasus ini, tidak hanya dalam konteks perda syariah, namun yang menjadi sorotan adalah konteks pernyataannya lebih luas karena menyangkut agama lain. Alhasil, pernyataan itu dinarasikan sebagian pihak sebagai penistaan agama yang berpotensi membahayakan akal sehat publik. Sikap politik dalam memandang hukum ini menimbulkan narasi patut diluruskan.
Persoalan ini setidaknya menimbulkan dua hal, pertama, publik terganggu pada satu pertanyaan besar tentang arti “apa itu hukum” dan kedua, publik juga menanyakan mengenai “untuk apa sebenarnya hukum itu dibuat”. Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengurai dua masalah di atas dalam beberapa catatan.
Hukum Tidak Bebas Nilai
Untuk memahami hukum tidak bebas nilai setidaknya dijabarkan dalam dua argumentasi. Pertama, nilai adalah rohnya hukum. Dalam tataran filsafat hukum, dikenal tingkatan hukum, yakni nilai, asas, norma, dan undang-undang (Despan Heryansyah, 2018). Bisa diartikan nilai merupakan tingkatan tertinggi sebelum diturunkan menjadi undang-undang (produk hukum).Nilai tidak dapat dipisahkan karena menjadi formula paling awal dalam proses pembentukan produk hukum di Indonesia. Tugas filsafat hukum dalam proses pembentukan produk hukum mempunyai andil tersendiri, salah satunya ialah meleburkan nilai ke dalam produk hukum. (baca: undang-undang).
Berangkat dari uraian di atas, proses pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan (dalam kasus ini adalah perda) tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai yang seharusnya terkandung di dalamnya. Terlebih dalam iklim Indonesia yang sangat majemuk, hukum harus menjangkau masyarakat dalam berbagai lini, bahkan sangat sensitif sekalipun termasuk agama.Jadi, jika agama dilepaskan dalam kandungan hukum, hal itu sangat fatal. Sebab seperti apa yang sudah kita ketahui bersama, ajaran agama ialah ajaran tentang kebaikan dan semua agama memiliki nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Agama menjadi dasar filosofis pembentukan produk hukum. Karena agama tidak terbatas pada aturan dasar keimanan seseorang, namun mencakup hubungan antarindividu dalam kerukunan.
Kedua, efektivitas dan kedayagunaan produk hukum bisa dilihat ketika produk hukum itu diterima oleh publik. Di sinilah nilai agama ditekankan. Agama tidak hanya memberikan nilai kebenaran subyektif, tapi juga nilai kebenaran universal, dan nilai kebenaran universal agama itulah digali dan melebur dalam suatu produk hukum. Seperti apa yang kita ketahui, semua agama memiliki nilai kebenaran universal tersebut. Kesimpulannya adalah agama merupakan modal awal dalam pembentukan suatu produk hukum.
Lain hal dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, haji, zakat atau undang-undang sejenis, tidak bisa dikatakan jika undang-undang itu murni produk hukum syariah atau agama tertentu. Alasannya norma tersebut bersifat publik karena mengatur tentang aturan teknis untuk dapat menjalankan ibadah bagi suatu agama tertentu. Jika hukum sudah masuk dalam ranah publik, pengaturannya sudah menjadi suatu kebutuhan (walau di dalamnya tidak terlepas nilai).
Sebagai catatan, bagi negara Indonesia hukum diartikan sebagai tujuan substantif masyarakat, dan hukum adalah representasi nilai- nilai. Nilai tersebut termasuk nilai agama yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Artinya, hukum dibuat atas dasar kultur sosial masyarakat yang bisa kita lihat berlakunya agama sebagai pandangan hidup bernegara bagi setiap pemeluknya.Untuk itu, proses pembentukan produk hukum harus menggali nilai-nilai agama. Kebaikan dan kebenaran nilai agama itulah salah satu formula yang tidak dapat dilepaskan. Karena pada dasarnya, ketika suatu rancangan undang-undang disahkan menjadi norma, itulah hukum positif, bukan lagi hukum syariah atau hukum agama tertentu. Dengan begitu yang terefleksi dalam produk hukum ialah substansi nilai kebaikan dan kebenaran universal agama, bukan semata-mata terletak pada label (agama)-nya saja.
MA dan Kewenangan Menilai
Persoalan di atas seharusnya sudah selesai jika melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015. Pada dasarnya, putusan tersebut menguji berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah. Kini melalui putusan itu, MK menegaskan yang berwenang menilai, menguji, dan membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik itu perda, peraturan pemerintah, dan produk hukum sejenis ialah Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tidak lagi di tangan Mendagri.
Artinya, jika dikaitkan dengan konteks ini, kekhawatiran tentang produk hukum yang mendiskriminasi warga negara sebenarnya sudah teratasi karena dapat diuji oleh MA. Namun yang menjadi persoalan lebih lanjut ialah, kesungguhan MA dalam memberikan putusan yang tidak hanya prosedural, namun lebih bermakna substansial itulah yang sebenarnya perlu kita kawal. Untuk itu, publik dituntut untuk turun tangan di setiap proses pembentukan, pengundangan sampai dengan penilaian suatu produk hukum peraturan perundang-undangan di semua tingkat.
Mahasiswa Magister Hukum UII Yogyakarta, Peneliti Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (LKBHMI) Cabang Yogyakarta
BEBERAPA waktu lalu, publik digegerkan dengan sikap politik salah satu partai yang menolak peraturan daerah berbasis agama (perda syariah dan Injil). Hal tersebut disampaikan ketua umumnya yang menyatakan bahwa negara Indonesia kini tidak lagi memerlukan perda berbasis agama. Alasannya adalah relevansi perda berbasis agama berpotensi pada diskriminasi terhadap warga negara.
Mengenai polemik perda syariah sebenarnya pernah mencuat sejak diberlakukan di beberapa daerah sebagai dampak dari adanya otonomi daerah. Berbeda dalam kasus ini, tidak hanya dalam konteks perda syariah, namun yang menjadi sorotan adalah konteks pernyataannya lebih luas karena menyangkut agama lain. Alhasil, pernyataan itu dinarasikan sebagian pihak sebagai penistaan agama yang berpotensi membahayakan akal sehat publik. Sikap politik dalam memandang hukum ini menimbulkan narasi patut diluruskan.
Persoalan ini setidaknya menimbulkan dua hal, pertama, publik terganggu pada satu pertanyaan besar tentang arti “apa itu hukum” dan kedua, publik juga menanyakan mengenai “untuk apa sebenarnya hukum itu dibuat”. Melalui tulisan ini, penulis mencoba mengurai dua masalah di atas dalam beberapa catatan.
Hukum Tidak Bebas Nilai
Untuk memahami hukum tidak bebas nilai setidaknya dijabarkan dalam dua argumentasi. Pertama, nilai adalah rohnya hukum. Dalam tataran filsafat hukum, dikenal tingkatan hukum, yakni nilai, asas, norma, dan undang-undang (Despan Heryansyah, 2018). Bisa diartikan nilai merupakan tingkatan tertinggi sebelum diturunkan menjadi undang-undang (produk hukum).Nilai tidak dapat dipisahkan karena menjadi formula paling awal dalam proses pembentukan produk hukum di Indonesia. Tugas filsafat hukum dalam proses pembentukan produk hukum mempunyai andil tersendiri, salah satunya ialah meleburkan nilai ke dalam produk hukum. (baca: undang-undang).
Berangkat dari uraian di atas, proses pembentukan produk hukum peraturan perundang-undangan (dalam kasus ini adalah perda) tidak bisa dilepaskan dengan nilai-nilai yang seharusnya terkandung di dalamnya. Terlebih dalam iklim Indonesia yang sangat majemuk, hukum harus menjangkau masyarakat dalam berbagai lini, bahkan sangat sensitif sekalipun termasuk agama.Jadi, jika agama dilepaskan dalam kandungan hukum, hal itu sangat fatal. Sebab seperti apa yang sudah kita ketahui bersama, ajaran agama ialah ajaran tentang kebaikan dan semua agama memiliki nilai-nilai kebaikan itu sendiri. Agama menjadi dasar filosofis pembentukan produk hukum. Karena agama tidak terbatas pada aturan dasar keimanan seseorang, namun mencakup hubungan antarindividu dalam kerukunan.
Kedua, efektivitas dan kedayagunaan produk hukum bisa dilihat ketika produk hukum itu diterima oleh publik. Di sinilah nilai agama ditekankan. Agama tidak hanya memberikan nilai kebenaran subyektif, tapi juga nilai kebenaran universal, dan nilai kebenaran universal agama itulah digali dan melebur dalam suatu produk hukum. Seperti apa yang kita ketahui, semua agama memiliki nilai kebenaran universal tersebut. Kesimpulannya adalah agama merupakan modal awal dalam pembentukan suatu produk hukum.
Lain hal dengan undang-undang yang mengatur tentang perkawinan, haji, zakat atau undang-undang sejenis, tidak bisa dikatakan jika undang-undang itu murni produk hukum syariah atau agama tertentu. Alasannya norma tersebut bersifat publik karena mengatur tentang aturan teknis untuk dapat menjalankan ibadah bagi suatu agama tertentu. Jika hukum sudah masuk dalam ranah publik, pengaturannya sudah menjadi suatu kebutuhan (walau di dalamnya tidak terlepas nilai).
Sebagai catatan, bagi negara Indonesia hukum diartikan sebagai tujuan substantif masyarakat, dan hukum adalah representasi nilai- nilai. Nilai tersebut termasuk nilai agama yang sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Artinya, hukum dibuat atas dasar kultur sosial masyarakat yang bisa kita lihat berlakunya agama sebagai pandangan hidup bernegara bagi setiap pemeluknya.Untuk itu, proses pembentukan produk hukum harus menggali nilai-nilai agama. Kebaikan dan kebenaran nilai agama itulah salah satu formula yang tidak dapat dilepaskan. Karena pada dasarnya, ketika suatu rancangan undang-undang disahkan menjadi norma, itulah hukum positif, bukan lagi hukum syariah atau hukum agama tertentu. Dengan begitu yang terefleksi dalam produk hukum ialah substansi nilai kebaikan dan kebenaran universal agama, bukan semata-mata terletak pada label (agama)-nya saja.
MA dan Kewenangan Menilai
Persoalan di atas seharusnya sudah selesai jika melihat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 137/PUU-XIII/2015. Pada dasarnya, putusan tersebut menguji berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah. Kini melalui putusan itu, MK menegaskan yang berwenang menilai, menguji, dan membatalkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik itu perda, peraturan pemerintah, dan produk hukum sejenis ialah Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman tidak lagi di tangan Mendagri.
Artinya, jika dikaitkan dengan konteks ini, kekhawatiran tentang produk hukum yang mendiskriminasi warga negara sebenarnya sudah teratasi karena dapat diuji oleh MA. Namun yang menjadi persoalan lebih lanjut ialah, kesungguhan MA dalam memberikan putusan yang tidak hanya prosedural, namun lebih bermakna substansial itulah yang sebenarnya perlu kita kawal. Untuk itu, publik dituntut untuk turun tangan di setiap proses pembentukan, pengundangan sampai dengan penilaian suatu produk hukum peraturan perundang-undangan di semua tingkat.
(whb)














