Pilkada dan Ketimpangan
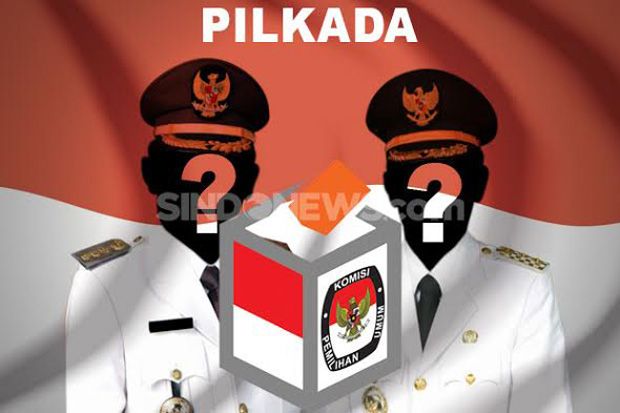
Pilkada dan Ketimpangan
A
A
A
Dr Edy Purwo Saputro
Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo
PILKADA serentak telah sukses dilaksanakan dan pemenang versi hitung cepat atau quick count sudah bisa terbaca. Sekarang tinggal menunggu verifikasi hitung manual versi KPUD. Para pemenang pilkada tidak bisa terlena dan harus langsung tancap gas karena ada target pemenangan Pilpres 2019, termasuk juga tantangan Pilkada Serentak 2024.
Meski demikian, tantangan utama yang harus dihadapi yaitu mereduksi ketimpangan. Model kebijakan era Jokowi melalui pembangunan infrastruktur sejatinya untuk mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Persoalan ketimpangan tidak hanya terkait besaran nominal dan sebaran yang terjadi, tapi juga kian maraknya migrasi.
Indikator ketimpangan mengacu BPS yakni jika angkanya lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan tinggi, antara 0,4-0,5 terjadi ketimpangan sedang, dan jika kurang dari 0,4, berarti ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Mengacu World Happiness Report 2018 Indonesia ada di urutan ke-62 dengan indeks gini 0,395 dan versi BPS per September 2017 indeks gini Indonesia mencapai 0,391.
Problem ketimpangan tidak terlepas dari kemiskinan, sementara kemiskinan juga terkait dengan ancaman sosial termasuk fakta pengangguran. Fakta ini menegaskan tantangan pemenang pilkada serentak tidak terlepas dari persoalan ketimpangan yang ternyata kini masih parah.
Di satu sisi hal ini memicu heterogenitas yang rentan riak konflik termasuk juga ancaman SARA meski di sisi lain ketimpangan memicu migrasi yang menjadikan perkotaan dan daerah penyangga sebagai tujuan. Dampak situasi ini adalah kemiskinan.
Terkait ini jumlah penduduk miskin di Jakarta per Maret 2017 yaitu 389,69 ribu orang (3,77%) dibanding per September 2016 yaitu 385,84 ribu orang atau 3,75% atau meningkat 3,85 ribu orang. Problem sosial ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah bagi pemenang pilkada serentak untuk penataan ke depan.
Serius
Problem kompleks pembangunan yang memicu ketimpangan sebenarnya juga direduksi dengan otonomi daerah (otda) meski 16 tahun otda ternyata justru kian banyak pemekaran daerah yang kemudian memicu berbagai problem baru, termasuk tingginya migrasi dan korupsi. Persoalan utama migrasi yaitu mencari kehidupan yang lebih baik dan perkotaan masih diyakini memberikan perbaikan kehidupan.
Asumsi ini mengebiri otda yang diharapkan memacu ekonomi daerah. Otda tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan dan ini terlihat dari banyak daerah tertinggal, kemiskinan, dan ketimpangan. Ironisnya di wilayah Indonesia timur masih ada 105 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.
Jadi, fakta ketimpangan di Jakarta bukanlah persoalan baru meski tantangan dan faktor pemicunya cenderung kompleks sehingga identifikasi dan pemetaan dari kasus ini menjadi relevan untuk dilakukan, setidaknya bisa untuk mereduksi dampak negatif dari ketimpangan, termasuk misalnya ancaman sosial dan kriminal dari ketimpangan yang terjadi di perkotaan. Fakta ini menjadi tantangan bagi pemenang pilkada serentak.
Fakta sebaran daerah tertinggal menjadi ancaman serius terhadap ketimpangan dan migrasi. Karena itu, ego pemekaran daerah sudah selayaknya dihentikan dan perlu ada kaji ulang terhadap otda itu sendiri, termasuk juga kaji ulang terhadap daerah pemekaran yang sudah ada, terutama untuk mereduksi kemiskinan di daerah pemekaran.
Tingkat kemiskinan dan perubahannya bervariasi menurut provinsi dan variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarprovinsi dalam banyak hal yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi dan sifatnya (apakah padat karya atau padat modal), infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan implementasi program-program antikemiskinan dari pemerintah.
Sebaran investasi ternyata juga belum mampu mendukung peningkatan taraf kesejahteraan. Ironisnya, di era otda justru banyak kasus OTT melibatkan kepala daerah, baik suap atau korupsi sehingga ini menjadi tantangan. Pemenang pilkada serentak diharapkan jangan menambah daftar koruptor kepala daerah, termasuk dalih balik modal karena mahalnya ongkos demokrasi di republik ini.
Esensi potret daerah tertinggal dan migrasi tidak bisa lepas dari dampak kesenjangan. Persoalan tentang kesenjangan memang menjadi ancaman pembangunan dan Indonesia sebagai negara kepulauan tampaknya juga tidak bisa menghindar dari hal ini. Terlepas dari pro-kontra, ketimpangan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan kesejahteraan - perkembangan ekonomi antarwilayah.
Realita menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya 5,2% dan di Papua 38,7%. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia misalnya pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antarwilayah, di mana penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah 9,7 tahun dan penduduk di daerah tertinggal rata-rata bersekolah selama 5,8 tahun.
Konsekuensi hal ini, maka 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah per Maret 2017 yaitu Jakarta (3,77%), Bali (4,25%), Kalimantan Selatan (4,73%), Kepulauan Bangka Belitung (5,2%), Kalimantan Tengah (5,37%), Banten (5,49%), Kepulauan Riau (6,06%), Kalimantan Timur (6,19%), Maluku Utara (6,35%), dan Sumatera Barat (6,87%).
Kumuh
Fakta ketimpangan antarwilayah juga ditandai rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi-sosial, terutama di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan, serta daerah tertinggal.
Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan (misalnya area Jabodetabek dan daerah penyangga) juga ditunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dari perkotaan, dan tingginya ketergantungan perdesaan terhadap perkotaan.
Ini disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan pemasaran hasil produksi di perdesaan. Fakta ketimpangan ini memicu migrasi. Di sisi lain, ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah tujuan migrasi, juga memicu ancaman kerawanan sosial di daerah perkotaan dan tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan.
Jadi wajar jika di Jakarta masih banyak kawasan kumuh dan karenanya pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta bertekad menjadikan Jakarta bebas kawasan kumuh pada 2019. Ironisnya, pendatang melalui arus balik Lebaran ini justru semakin meningkat dan tentu rawan memicu kekumuhan baru.
Sinergi program tersebut dilakukan dengan model 100-10-100 yang dicanangkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan program pengembang permukiman secara berkelanjutan, yaitu melalui komitmen pencapaian 100% akses air minum, mereduksi kawasan kumuh 10%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat.
Data Kempupera menyatakan bahwa di Indonesia ada 37.407 hektare kawasan kumuh dan tersebar di mayoritas perkotaan, akses pelayanan air minum baru 67,7%, dan akses pelayanan sanitasi baru 59,7%. Pencapaian program itu pada dasarnya adalah sasaran dari Millennium Development Goals (MDGs) sampai 2020. Pencapaian ini tentu sangat berat karena data BPS DKI Jakarta menegaskan jumlah kawasan kumuh mencapai 309 RW kumuh dengan lokasi Jakarta Utara menjadi kawasan terkumuh.
Dosen Pascasarjana di Universitas Muhammadiyah Solo
PILKADA serentak telah sukses dilaksanakan dan pemenang versi hitung cepat atau quick count sudah bisa terbaca. Sekarang tinggal menunggu verifikasi hitung manual versi KPUD. Para pemenang pilkada tidak bisa terlena dan harus langsung tancap gas karena ada target pemenangan Pilpres 2019, termasuk juga tantangan Pilkada Serentak 2024.
Meski demikian, tantangan utama yang harus dihadapi yaitu mereduksi ketimpangan. Model kebijakan era Jokowi melalui pembangunan infrastruktur sejatinya untuk mereduksi kemiskinan dan ketimpangan. Persoalan ketimpangan tidak hanya terkait besaran nominal dan sebaran yang terjadi, tapi juga kian maraknya migrasi.
Indikator ketimpangan mengacu BPS yakni jika angkanya lebih dari 0,5, maka terjadi ketimpangan tinggi, antara 0,4-0,5 terjadi ketimpangan sedang, dan jika kurang dari 0,4, berarti ketimpangan distribusi pendapatan rendah. Mengacu World Happiness Report 2018 Indonesia ada di urutan ke-62 dengan indeks gini 0,395 dan versi BPS per September 2017 indeks gini Indonesia mencapai 0,391.
Problem ketimpangan tidak terlepas dari kemiskinan, sementara kemiskinan juga terkait dengan ancaman sosial termasuk fakta pengangguran. Fakta ini menegaskan tantangan pemenang pilkada serentak tidak terlepas dari persoalan ketimpangan yang ternyata kini masih parah.
Di satu sisi hal ini memicu heterogenitas yang rentan riak konflik termasuk juga ancaman SARA meski di sisi lain ketimpangan memicu migrasi yang menjadikan perkotaan dan daerah penyangga sebagai tujuan. Dampak situasi ini adalah kemiskinan.
Terkait ini jumlah penduduk miskin di Jakarta per Maret 2017 yaitu 389,69 ribu orang (3,77%) dibanding per September 2016 yaitu 385,84 ribu orang atau 3,75% atau meningkat 3,85 ribu orang. Problem sosial ini menjadi pekerjaan rumah (PR) yang tidak mudah bagi pemenang pilkada serentak untuk penataan ke depan.
Serius
Problem kompleks pembangunan yang memicu ketimpangan sebenarnya juga direduksi dengan otonomi daerah (otda) meski 16 tahun otda ternyata justru kian banyak pemekaran daerah yang kemudian memicu berbagai problem baru, termasuk tingginya migrasi dan korupsi. Persoalan utama migrasi yaitu mencari kehidupan yang lebih baik dan perkotaan masih diyakini memberikan perbaikan kehidupan.
Asumsi ini mengebiri otda yang diharapkan memacu ekonomi daerah. Otda tidak berpengaruh signifikan bagi kesejahteraan dan ini terlihat dari banyak daerah tertinggal, kemiskinan, dan ketimpangan. Ironisnya di wilayah Indonesia timur masih ada 105 kabupaten yang termasuk daerah tertinggal.
Jadi, fakta ketimpangan di Jakarta bukanlah persoalan baru meski tantangan dan faktor pemicunya cenderung kompleks sehingga identifikasi dan pemetaan dari kasus ini menjadi relevan untuk dilakukan, setidaknya bisa untuk mereduksi dampak negatif dari ketimpangan, termasuk misalnya ancaman sosial dan kriminal dari ketimpangan yang terjadi di perkotaan. Fakta ini menjadi tantangan bagi pemenang pilkada serentak.
Fakta sebaran daerah tertinggal menjadi ancaman serius terhadap ketimpangan dan migrasi. Karena itu, ego pemekaran daerah sudah selayaknya dihentikan dan perlu ada kaji ulang terhadap otda itu sendiri, termasuk juga kaji ulang terhadap daerah pemekaran yang sudah ada, terutama untuk mereduksi kemiskinan di daerah pemekaran.
Tingkat kemiskinan dan perubahannya bervariasi menurut provinsi dan variasi ini disebabkan oleh perbedaan antarprovinsi dalam banyak hal yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan seperti pertumbuhan ekonomi dan sifatnya (apakah padat karya atau padat modal), infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, khususnya dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan implementasi program-program antikemiskinan dari pemerintah.
Sebaran investasi ternyata juga belum mampu mendukung peningkatan taraf kesejahteraan. Ironisnya, di era otda justru banyak kasus OTT melibatkan kepala daerah, baik suap atau korupsi sehingga ini menjadi tantangan. Pemenang pilkada serentak diharapkan jangan menambah daftar koruptor kepala daerah, termasuk dalih balik modal karena mahalnya ongkos demokrasi di republik ini.
Esensi potret daerah tertinggal dan migrasi tidak bisa lepas dari dampak kesenjangan. Persoalan tentang kesenjangan memang menjadi ancaman pembangunan dan Indonesia sebagai negara kepulauan tampaknya juga tidak bisa menghindar dari hal ini. Terlepas dari pro-kontra, ketimpangan antarwilayah dapat dilihat dari perbedaan kesejahteraan - perkembangan ekonomi antarwilayah.
Realita menunjukkan bahwa angka kemiskinan di DKI Jakarta hanya 5,2% dan di Papua 38,7%. Ketimpangan pelayanan sosial dasar yang tersedia misalnya pendidikan, kesehatan, dan air bersih juga terjadi antarwilayah, di mana penduduk di Jakarta rata-rata bersekolah 9,7 tahun dan penduduk di daerah tertinggal rata-rata bersekolah selama 5,8 tahun.
Konsekuensi hal ini, maka 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah per Maret 2017 yaitu Jakarta (3,77%), Bali (4,25%), Kalimantan Selatan (4,73%), Kepulauan Bangka Belitung (5,2%), Kalimantan Tengah (5,37%), Banten (5,49%), Kepulauan Riau (6,06%), Kalimantan Timur (6,19%), Maluku Utara (6,35%), dan Sumatera Barat (6,87%).
Kumuh
Fakta ketimpangan antarwilayah juga ditandai rendahnya aksesibilitas pelayanan sarana dan prasarana ekonomi-sosial, terutama di perdesaan, daerah terpencil, perbatasan, serta daerah tertinggal.
Ketimpangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan (misalnya area Jabodetabek dan daerah penyangga) juga ditunjukkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa, tertinggalnya pembangunan kawasan perdesaan dari perkotaan, dan tingginya ketergantungan perdesaan terhadap perkotaan.
Ini disebabkan minimnya akses pada permodalan, lapangan kerja, informasi, teknologi, dan pemasaran hasil produksi di perdesaan. Fakta ketimpangan ini memicu migrasi. Di sisi lain, ini juga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin di daerah tujuan migrasi, juga memicu ancaman kerawanan sosial di daerah perkotaan dan tumbuhnya kawasan kumuh di perkotaan.
Jadi wajar jika di Jakarta masih banyak kawasan kumuh dan karenanya pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta bertekad menjadikan Jakarta bebas kawasan kumuh pada 2019. Ironisnya, pendatang melalui arus balik Lebaran ini justru semakin meningkat dan tentu rawan memicu kekumuhan baru.
Sinergi program tersebut dilakukan dengan model 100-10-100 yang dicanangkan oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (Kempupera) dengan program pengembang permukiman secara berkelanjutan, yaitu melalui komitmen pencapaian 100% akses air minum, mereduksi kawasan kumuh 10%, dan 100% akses sanitasi untuk masyarakat.
Data Kempupera menyatakan bahwa di Indonesia ada 37.407 hektare kawasan kumuh dan tersebar di mayoritas perkotaan, akses pelayanan air minum baru 67,7%, dan akses pelayanan sanitasi baru 59,7%. Pencapaian program itu pada dasarnya adalah sasaran dari Millennium Development Goals (MDGs) sampai 2020. Pencapaian ini tentu sangat berat karena data BPS DKI Jakarta menegaskan jumlah kawasan kumuh mencapai 309 RW kumuh dengan lokasi Jakarta Utara menjadi kawasan terkumuh.
(maf)














