Perguruan Tinggi Menyambut Era Disrupsi
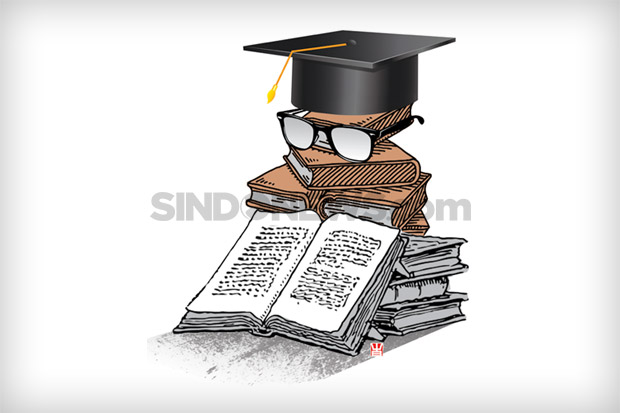
Perguruan Tinggi Menyambut Era Disrupsi
A
A
A
Fathur Rokhman
Rektor Universitas Negeri Semarang
Perubahan besar dan mendasar terjadi hampir di setiap bidang kehidupan. Kini cara manusia hidup dan menikmati kehidupan sama sekali berbeda dengan era-era sebelumnya. Perubahan itu memberi peluang sekaligus tantangan kepada setiap institusi negara, termasuk perguruan tinggi.
Oleh sejumlah ahli manajemen, perubahan besar dan mendasar itu disebut sebagai disrupsi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan pada era itu lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan menggantinya dengan ekosistem baru yang sama sekali berbeda.
Institusi bisnis adalah "korban" yang terdampak paling cepat. Puluhan perusahaan besar yang mapan tumbang dalam waktu singkat akibat muncul pesaing baru tak teramalkan sebelumnya. Inovasi berkesinambungan tak cukup membuatnya selamat dari ledakkan perubahan yang masif dan di luar dugaan itu.
Lembaga pemerintah seperti perguruan tinggi memang belum terkena dampak secara besar-besaran. Namun, pelan tapi pasti, disrupsi juga mengancam eksistensi lembaga pemerintah. Bahkan, dalam bentuk paling ekstrem, disrupsi juga akan mengancam eksistensi negara. Karena itu, pepatah lama "berubah atau punah" benar-benar menemukan tajinya.
Dua Kendala
Dorongan agar perguruan tinggi berubah secara radikal sebenarnya telah muncul dari berbagai kalangan. Hampir setiap datang ke perguruan tinggi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar perguruan tinggi membuka program studi baru yang spesifik. Dia pernah mengusulkan program studi media sosial (medsos), toko online, bahkan meme. Meski kerap disampaikan dengan gaya guyon, gagasan Presiden sebenarnya berangkat dari refleksi akademik yang mendalam. Dengan cara itu dia sedang mendorong perguruan tinggi lebih adaptif dalam merespons perubahan. Bagi Presiden, perubahan dunia tak cukup lagi dihadapi dengan inovasi yang bertahap, tetapi harus dengan perubahan lebih radikal.
Secara praktis, gagasan Presiden sangat relevan dengan kondisi masyarakat dunia saat ini. Lembaga riset internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada Maret 2017 lalu sudah memprediksi disrupsi akan membuat 30% pekerjaan di Inggris hilang, sementara di Amerika Serikat mencapai 38%, di Jerman 35%, dan Jepang 21%. Meski belum diteliti secara khusus, Indonesia juga mengalami kekhawatiran sama. Berbagai profesi akan kehilangan relevansinya karena perubahan masyarakat yang begitu cepat.
Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klauss Schwab memberi gambaran lebih konkret. Perubahan yang muncul pada Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya kecerdasan buatan, penerapan teknologi nano di berbagai bidang, dan rekayasa genetis. Ketika tiga teknologi itu berhasil diaplikasikan, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Adapun ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi tidak lagi berguna karena kehilangan relevansinya.
Harari (2016) menyebutkan era kecerdasan buatan tidak bisa dihindarkan. Era itu akan membawa manusia pada era penuh optimisme sekaligus penuh kekhawatiran. Optimisme muncul karena kecerdasan buatan akan membuat efisiensi pekerjaan bisa ditingkatkan berkali-kali lipat. Kekhawatiran muncul karena kecerdasan buatan juga berpotensi mengancam eksistensi manusia dan kemanusiaan yang selama ini telah mapan.
Teknologi nano juga akan segera mendapat ruang dalam berbagai moda produksi. Ketika teknologi ini sudah diterapkan, efektivitas produksi bisa ditingkatkan puluhan bahkan ratusan kali lipat. Pada saat itu, mekanika tradisional akan terasa sangat kuno, sebagaimana hari ini kita menilai kapak batu.
Rekayasa genetis barang kali akan jadi pertarungan penuh ketegangan karena diikuti sengketa sains dan etika. Ilmuwan akan memandang rekayasa genetis sebagai cara mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik. Adimanusia atau manusia super bisa diciptakan melalui rekayasa DNA. Tapi di sisi lain, agamawan akan merasa teknologi itu sudah keterlaluan dan melampaui "hak" manusia.
Perkembangan sains mengubah dunia dengan laju perubahan begitu kencang bagaikan banjir bandang. Idealnya, perguruan tinggi ada di dalam arus perubahan itu, menjadi pengendali arah dan kecepatan perubahan. Dengan modal sosial dan budaya yang dimilikinya, perguruan tinggi memberi komando kapan perubahan itu harus dipercepat, dihentikan, atau dialihkan arahnya.
Di Indonesia, agar kondisi ideal itu terwujud, perguruan tinggi harus menyelesaikan dua persoalan internal yang membelitnya. Pertama, sebagai “alat negara” perguruan tinggi cenderung terikat regulasi ketat yang disusun pemerintah. Hak dan kewajibannya dibatasi ketat sehingga kelincahannya dalam merespons setiap perubahan yang terjadi cenderung kurang. Untuk membuka atau menutup program studi, misalnya, perguruan tinggi harus melakukan kajian akademik dan memenuhi syarat administrasi yang tak sedikit jumlahnya.
Kedua, paradigma positivistik yang dianut perguruan tinggi di Indonesia lebih apresiatif terhadap status quo daripada perubahan. Positivisme mengasumsikan segala sesuatu bersifat pasti dan cenderung tetap. Bahkan dalam membaca perubahan, positivisme cenderung membacanya sebagai proses yang terprediksikan. Positivisme mengandalkan variabel-variabel tertentu yang tampak dan terukur untuk membaca perubahan superkompleks.
Sikap keilmuan itu cenderung kontradiktif dengan perubahan sebagai realitas. Dalam praktiknya, jumlah variabel bisa tidak terbatas dengan peran dan pola relasi yang terus berubah. Ketika ilmuwan mengasumsikan variabel tertentu lebih berperan, di lapangan kondisi sudah berubah. Paradigma demikian membuat perguruan tinggi harus diakui terkungkung oleh pagar yang dibuatnya sendiri.
Kepercayaan Diri
Dalam beberapa dekade terakhir, memang berkembang paradigma baru yang berusaha mengevaluasi rezim pasti positivisme. Posmodernisme lebih apresiatif terhadap perubahan karena menerima ketidakpastian, subjektivitas, dan mengasumsikan segala sesuatu bersifat konstruktif. Namun, keberterimaan paradigma ini masih relatif terbatas, lazimnya baru dipakai dalam ilmu humaniora. Untuk itulah, ilmuwan-ilmuwan dengan mazhab ini harus lebih percaya diri berdiri di podium akademik dan mengambil alih laju perubahan.
Bangsa kita akan memasuki periode yang penuh optimisme pada satu atau dua dasawarsa ke depan. Bonus demografi semakin terasa dampaknya, antara lain dengan semakin banyaknya tawaran model bisnis baru. Generasi Y telah menawarkan gaya hidup yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z mulai merangsek naik membawa cara hidup yang berbeda lagi.
Jika ingin tetap mempertahankan peran sosialnya, perguruan tinggi harus lebih peka terhadap perubahan yang dibawa generasi Y dan Z itu. Mau tidak mau kekakuan birokrasi harus ditinggalkan, lebih terbuka terhadap gagasan baru, dan lebih reflektif terhadap dirinya. Meskipun terasa berat di awal, saya yakin perguruan tinggi Indonesia akan bisa melakukannya.
Rektor Universitas Negeri Semarang
Perubahan besar dan mendasar terjadi hampir di setiap bidang kehidupan. Kini cara manusia hidup dan menikmati kehidupan sama sekali berbeda dengan era-era sebelumnya. Perubahan itu memberi peluang sekaligus tantangan kepada setiap institusi negara, termasuk perguruan tinggi.
Oleh sejumlah ahli manajemen, perubahan besar dan mendasar itu disebut sebagai disrupsi. Dalam era disrupsi, perubahan tidak terjadi bertahap seperti orang meniti tangga. Perubahan pada era itu lebih menyerupai ledakan gunung berapi yang meluluhlantakkan ekosistem lama dan menggantinya dengan ekosistem baru yang sama sekali berbeda.
Institusi bisnis adalah "korban" yang terdampak paling cepat. Puluhan perusahaan besar yang mapan tumbang dalam waktu singkat akibat muncul pesaing baru tak teramalkan sebelumnya. Inovasi berkesinambungan tak cukup membuatnya selamat dari ledakkan perubahan yang masif dan di luar dugaan itu.
Lembaga pemerintah seperti perguruan tinggi memang belum terkena dampak secara besar-besaran. Namun, pelan tapi pasti, disrupsi juga mengancam eksistensi lembaga pemerintah. Bahkan, dalam bentuk paling ekstrem, disrupsi juga akan mengancam eksistensi negara. Karena itu, pepatah lama "berubah atau punah" benar-benar menemukan tajinya.
Dua Kendala
Dorongan agar perguruan tinggi berubah secara radikal sebenarnya telah muncul dari berbagai kalangan. Hampir setiap datang ke perguruan tinggi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar perguruan tinggi membuka program studi baru yang spesifik. Dia pernah mengusulkan program studi media sosial (medsos), toko online, bahkan meme. Meski kerap disampaikan dengan gaya guyon, gagasan Presiden sebenarnya berangkat dari refleksi akademik yang mendalam. Dengan cara itu dia sedang mendorong perguruan tinggi lebih adaptif dalam merespons perubahan. Bagi Presiden, perubahan dunia tak cukup lagi dihadapi dengan inovasi yang bertahap, tetapi harus dengan perubahan lebih radikal.
Secara praktis, gagasan Presiden sangat relevan dengan kondisi masyarakat dunia saat ini. Lembaga riset internasional Pricewaterhouse Coopers (PwC) pada Maret 2017 lalu sudah memprediksi disrupsi akan membuat 30% pekerjaan di Inggris hilang, sementara di Amerika Serikat mencapai 38%, di Jerman 35%, dan Jepang 21%. Meski belum diteliti secara khusus, Indonesia juga mengalami kekhawatiran sama. Berbagai profesi akan kehilangan relevansinya karena perubahan masyarakat yang begitu cepat.
Ketua Eksekutif Forum Ekonomi Dunia Klauss Schwab memberi gambaran lebih konkret. Perubahan yang muncul pada Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya kecerdasan buatan, penerapan teknologi nano di berbagai bidang, dan rekayasa genetis. Ketika tiga teknologi itu berhasil diaplikasikan, jutaan orang akan kehilangan pekerjaan. Adapun ilmu pengetahuan yang diperoleh di perguruan tinggi tidak lagi berguna karena kehilangan relevansinya.
Harari (2016) menyebutkan era kecerdasan buatan tidak bisa dihindarkan. Era itu akan membawa manusia pada era penuh optimisme sekaligus penuh kekhawatiran. Optimisme muncul karena kecerdasan buatan akan membuat efisiensi pekerjaan bisa ditingkatkan berkali-kali lipat. Kekhawatiran muncul karena kecerdasan buatan juga berpotensi mengancam eksistensi manusia dan kemanusiaan yang selama ini telah mapan.
Teknologi nano juga akan segera mendapat ruang dalam berbagai moda produksi. Ketika teknologi ini sudah diterapkan, efektivitas produksi bisa ditingkatkan puluhan bahkan ratusan kali lipat. Pada saat itu, mekanika tradisional akan terasa sangat kuno, sebagaimana hari ini kita menilai kapak batu.
Rekayasa genetis barang kali akan jadi pertarungan penuh ketegangan karena diikuti sengketa sains dan etika. Ilmuwan akan memandang rekayasa genetis sebagai cara mewujudkan kehidupan manusia yang lebih baik. Adimanusia atau manusia super bisa diciptakan melalui rekayasa DNA. Tapi di sisi lain, agamawan akan merasa teknologi itu sudah keterlaluan dan melampaui "hak" manusia.
Perkembangan sains mengubah dunia dengan laju perubahan begitu kencang bagaikan banjir bandang. Idealnya, perguruan tinggi ada di dalam arus perubahan itu, menjadi pengendali arah dan kecepatan perubahan. Dengan modal sosial dan budaya yang dimilikinya, perguruan tinggi memberi komando kapan perubahan itu harus dipercepat, dihentikan, atau dialihkan arahnya.
Di Indonesia, agar kondisi ideal itu terwujud, perguruan tinggi harus menyelesaikan dua persoalan internal yang membelitnya. Pertama, sebagai “alat negara” perguruan tinggi cenderung terikat regulasi ketat yang disusun pemerintah. Hak dan kewajibannya dibatasi ketat sehingga kelincahannya dalam merespons setiap perubahan yang terjadi cenderung kurang. Untuk membuka atau menutup program studi, misalnya, perguruan tinggi harus melakukan kajian akademik dan memenuhi syarat administrasi yang tak sedikit jumlahnya.
Kedua, paradigma positivistik yang dianut perguruan tinggi di Indonesia lebih apresiatif terhadap status quo daripada perubahan. Positivisme mengasumsikan segala sesuatu bersifat pasti dan cenderung tetap. Bahkan dalam membaca perubahan, positivisme cenderung membacanya sebagai proses yang terprediksikan. Positivisme mengandalkan variabel-variabel tertentu yang tampak dan terukur untuk membaca perubahan superkompleks.
Sikap keilmuan itu cenderung kontradiktif dengan perubahan sebagai realitas. Dalam praktiknya, jumlah variabel bisa tidak terbatas dengan peran dan pola relasi yang terus berubah. Ketika ilmuwan mengasumsikan variabel tertentu lebih berperan, di lapangan kondisi sudah berubah. Paradigma demikian membuat perguruan tinggi harus diakui terkungkung oleh pagar yang dibuatnya sendiri.
Kepercayaan Diri
Dalam beberapa dekade terakhir, memang berkembang paradigma baru yang berusaha mengevaluasi rezim pasti positivisme. Posmodernisme lebih apresiatif terhadap perubahan karena menerima ketidakpastian, subjektivitas, dan mengasumsikan segala sesuatu bersifat konstruktif. Namun, keberterimaan paradigma ini masih relatif terbatas, lazimnya baru dipakai dalam ilmu humaniora. Untuk itulah, ilmuwan-ilmuwan dengan mazhab ini harus lebih percaya diri berdiri di podium akademik dan mengambil alih laju perubahan.
Bangsa kita akan memasuki periode yang penuh optimisme pada satu atau dua dasawarsa ke depan. Bonus demografi semakin terasa dampaknya, antara lain dengan semakin banyaknya tawaran model bisnis baru. Generasi Y telah menawarkan gaya hidup yang sama sekali berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi Z mulai merangsek naik membawa cara hidup yang berbeda lagi.
Jika ingin tetap mempertahankan peran sosialnya, perguruan tinggi harus lebih peka terhadap perubahan yang dibawa generasi Y dan Z itu. Mau tidak mau kekakuan birokrasi harus ditinggalkan, lebih terbuka terhadap gagasan baru, dan lebih reflektif terhadap dirinya. Meskipun terasa berat di awal, saya yakin perguruan tinggi Indonesia akan bisa melakukannya.
(zik)














