Menyegarkan Kembali Habibienomics
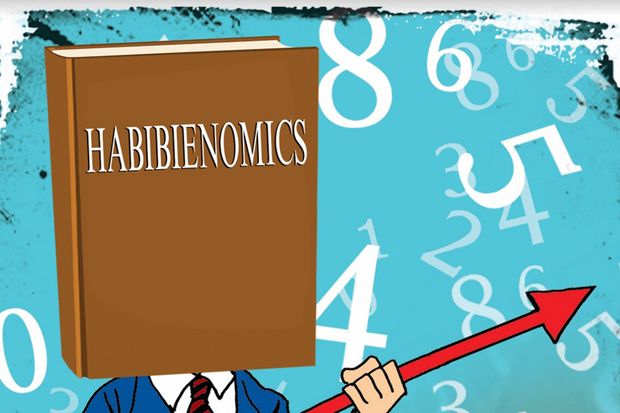
Menyegarkan Kembali Habibienomics
A
A
A
Mukhaer Pakkanna
Peneliti CIDES dan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta
SALAH satu legacy pemikiran Presiden RI ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), yakni berkaitan konsep ekonomi. Kendati almarhum seorang teknolog, terutama di bidang dirgantara berkelas dunia, gagasan ekonomi yang disampaikannya pada dekade 1990-an telah menyentakkan para ahli dan pengambil kebijakan ekonomi nasional. Bahkan, jauh sebelumnya, pada dekade 1970-an, BJ Habibie yang didaulat sebagai menteri riset dan teknologi RI oleh Presiden Soeharto, telah memperlihatkan corak pemikiran ekonominya yang khas.
Bahkan, pada zaman Orde Baru (Orba), gagasan ekonomi BJ Habibie menjadi arus utama (mainstream) wacana pembangunan ekonomi, selain sebelumnya sudah eksis gagasan ekonom brilian, Widjojo Nitisastro. Tidak heran, dua gagasan itu dikelola dengan baik oleh Presiden Soeharto hingga beliau mengundurkan diri pada 1998.
Pada era Orba, kedua orang kepercayaan Presiden Soeharto ini dikutubkan dalam kategorisasi mazhab Widjojonomics dan Habibienomics. Pendekatan dua strategi ini terlihat pada pertentangannya dalam memanfaatkan antara keunggulan komparatif yang mengandalkan sumber daya alam (SDA) lawan keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia (SDM).
Dua mazhab pemikiran ini digunakan oleh Presiden Soeharto dalam menangani problema ekonomi, dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, terutama konteks penanganan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.
Perdebatan Mazhab
Kendati telah lama menjadi wacana dan perdebatan publik di era 1990-an, ada baiknya kita mengingatkan kembali konsep Habibienomics, sebagai apresiasi kita kepada almarhum. Dalam tulisan Kwik Kian Gie, pada sebuah media yang terbit di Jakarta, 4 Maret 1993, istilah Habibienomics untuk pertama kali ditampilkan.
Kwik menciptakan istilah ini berdasarkan isi pidato BJ Habibie yang dibacakan dalam sebuah pertemuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta. Inti Habibienomics adalah "Perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, tetapi harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif bisa dicari melalui pengejaran teknologi tinggi”.
Sejatinya, Kwik bukanlah orang pertama yang menanggapi pemikiran BJ Habibie. Sebelumnya, pada medio ‘80-an, Soemitro Djojohadikusumo pernah mengulas pemikiran BJ Habibie dalam makalah berjudul "Industrialisasi dalam Pembangunan Ekonomi" yang disampaikan sebagai ceramah Pembukaan Simposium "Industrialisasi di Indonesia: Prospek dan Masalahnya" dalam peringatan 35 tahun Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Dalam makalah Soemitro tidak disebut secara eksplisit istilah Habibienomics. Bahkan, Sumitro secara moderat menyampaikan bahwa dua pemikiran itu (Widjojo dan BJ Habibie) seolah-olah ada, di mana yang satu merupakan alternatif bagi yang lain. Sumitro menganjurkan agar masing-masing tidak menjadikan pemikiran mereka sebagai dogma. Karena pemikiran atau konsep itu perlu pengkajian lebih lanjut, baik secara akademis maupun melalui pengalaman empiris dalam pelaksanaan kebijaksanaan (Rahardjo, 1996).
Sebenarnya, kata Sumitro, tidak adil jika dikatakan bahwa Widjojonomics itu intinya, hanya kebijakan yang mendasarkan diri pada prinsip keuntungan komparatif. Kebijakan ekonomi yang dikembangkan kelompok Widjojo sebenarnya jauh lebih luas dan dapat disimpulkan dalam doktrin Trilogi Pembangunan yang menekankan pada pengendalian kebijakan ekonomi makro dalam upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
Pada kebijakan sektoral, misalnya pembangunan pertanian, industri dan perdagangan harus diperhitungkan dan dikontrol berdasarkan kerangka dan keseimbangan ekonomi makro yang dinamis, khususnya dengan melihat kepada indikator ekonomi fundamental.
Dalam catatan Dawam Rahardjo (1996), reaksi terhadap Widjojonomics baru muncul pada 1978. Pandangan yang timbul cukup beragam. Pada 1974 timbul protes terhadap dominasi penanaman modal asing, khususnya Jepang, yang dinilai memarjinalisasikan industri kecil di berbagai sentra produksi. Protes itu bahkan berkembang menjadi aksi sosial yang menimbulkan peristiwa Malari di Jakarta.
Pada pertengahan dasawarsa 1970-an, tulis Rahardjo (1994), timbul minat di kalangan perguruan tinggi dan LSM untuk menyelidiki masalah dampak pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi terhadap timbulnya kemiskinan.
Bahkan, sesungguhnya sejak awal dasawarsa itu dalam lingkup Dunia Ketiga telah terdengar gugatan Mahbub al Haq dalam bukunya The Poverty Curtain (1976), terhadap strategi pembangunan yang menghasilkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dan dia mencoba menarik perhatian orang untuk menengok strategi pembangunan RRC yang memerangi kemiskinan secara langsung (direct attack on poverty).
Kegagalan, baik pada strategi berdasarkan prinsip keuntungan komparatif maupun strategi pendalaman industri merangsang pencarian alternatif baru. Acuannya adalah masalah kebergantungan teknologi yang menjadi sumber kemacetan pembangunan dalam jangka panjang. Dalam konteks inilah, gagasan BJ Habibie memperoleh justifikasi empirik.
Mengenang Habibienomics
Dalam makalahnya yang berjudul "Pembangunan Berorientasi Nilai Tambah" (1990), BJ Habibie berujar: "Keberhasilan pembangunan negara-negara berkembang dalam tiga dekade terakhir ternyata tidak menyurutkan ketergantungannya pada negara-negara maju. Lemahnya infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi serta rendahnya kapabilitas sumber daya manusia negara-negara tersebut dipandang sebagai penyebab utama rendahnya daya saing mereka di pasar global".
Masalah ketergantungan teknologi menyebabkan negara-negara sedang berkembang makin tertinggal dalam perkembangan ekonomi dan makin tergantung, sehingga makin merugikan negara-negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan negara-negara maju, mendorong BJ Habibie untuk mencari alternatif ketiga.
Alternatif ketiga BJ Habibie, memberi jalan keluar dengan konsep strategi lompatan. Asumsinya adalah bahwa negara-negara sedang berkembang tidak bakal mampu mengejar perkembangan teknologi, jika berkembang menurut garis linier. Untuk mengejarnya harus diciptakan garis perkembangan eksponensial, dengan melakukan apa yang disebut BJ Habibie sebagai "accelerated evolution" atau evolusi yang dipercepat.
Evolusi yang dipercepat tersebut tidak sama dengan "lompatan katak" (leap frogging) sebab lompatan katak bersifat acak dan tak dapat diperkirakan, sedangkan evolusi yang dipercepat tidak acak karena gerakannya dikendalikan dan diperkirakan. Hal ini berarti mengurangi risiko dan biaya transformasi yang tinggi.
Dalam mengemukakan alternatifnya tersebut, BJ Habibie melontarkan kritik terhadap konsep strategi konvensional, khususnya yang mendasarkan diri pada prinsip keuntungan komparatif saja. Strategi ini menurut BJ Habibie hanya berpedoman pada tolok ukur pendapatan nasional atau produksi nasional. Indikator itu sebenarnya tidak ditolaknya, tetapi dia mengusulkan indikator lain.
Untuk bisa menilai kemampuan membangun suatu bangsa, dia menambahkan bahwa indikator lain dalam suatu kesatuan ekonomi makro, yaitu indikator "Produktivitas Prestasi Nasional" (PPN) dan indikator "Pertumbuhan Produktivitas Prestasi Nasional". Indikator satu dalam dua itu merupakan perpaduan dari produktivitas tenaga kerja (labour productivity) dan produktivitas modal (capital productivity) dalam bentuk prasarana, sarana, dan mesin.
Itulah rumusan mazhab Habibienomics tentang strategi pembangunan yang mengandalkan kepada kualitas SDM. Berdasarkan kapabilitas SDM dapat dioptimalisasikan pemanfaatan sumber daya sumber daya lainnya. Persoalannya kemudian, bisa kita menjalankan strategi tersebut? Dalam konteks inilah, jargon Peringatan Kemerdekaan ke 74, yakni SDM Unggul, Indonesia Maju memiliki kompatibilitas dengan mazhab Habibienomics.
Peneliti CIDES dan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta
SALAH satu legacy pemikiran Presiden RI ke-3, Bacharuddin Jusuf Habibie (BJ Habibie), yakni berkaitan konsep ekonomi. Kendati almarhum seorang teknolog, terutama di bidang dirgantara berkelas dunia, gagasan ekonomi yang disampaikannya pada dekade 1990-an telah menyentakkan para ahli dan pengambil kebijakan ekonomi nasional. Bahkan, jauh sebelumnya, pada dekade 1970-an, BJ Habibie yang didaulat sebagai menteri riset dan teknologi RI oleh Presiden Soeharto, telah memperlihatkan corak pemikiran ekonominya yang khas.
Bahkan, pada zaman Orde Baru (Orba), gagasan ekonomi BJ Habibie menjadi arus utama (mainstream) wacana pembangunan ekonomi, selain sebelumnya sudah eksis gagasan ekonom brilian, Widjojo Nitisastro. Tidak heran, dua gagasan itu dikelola dengan baik oleh Presiden Soeharto hingga beliau mengundurkan diri pada 1998.
Pada era Orba, kedua orang kepercayaan Presiden Soeharto ini dikutubkan dalam kategorisasi mazhab Widjojonomics dan Habibienomics. Pendekatan dua strategi ini terlihat pada pertentangannya dalam memanfaatkan antara keunggulan komparatif yang mengandalkan sumber daya alam (SDA) lawan keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia (SDM).
Dua mazhab pemikiran ini digunakan oleh Presiden Soeharto dalam menangani problema ekonomi, dalam memacu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, terutama konteks penanganan ketimpangan dan kesenjangan ekonomi.
Perdebatan Mazhab
Kendati telah lama menjadi wacana dan perdebatan publik di era 1990-an, ada baiknya kita mengingatkan kembali konsep Habibienomics, sebagai apresiasi kita kepada almarhum. Dalam tulisan Kwik Kian Gie, pada sebuah media yang terbit di Jakarta, 4 Maret 1993, istilah Habibienomics untuk pertama kali ditampilkan.
Kwik menciptakan istilah ini berdasarkan isi pidato BJ Habibie yang dibacakan dalam sebuah pertemuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di Jakarta. Inti Habibienomics adalah "Perekonomian harus dikembangkan melalui perebutan teknologi canggih untuk mengejar ketertinggalan dari negara maju. Indonesia tidak boleh menjadi negara yang hanya bisa memproduksi barang yang memiliki keunggulan komparatif, tetapi harus memiliki keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif bisa dicari melalui pengejaran teknologi tinggi”.
Sejatinya, Kwik bukanlah orang pertama yang menanggapi pemikiran BJ Habibie. Sebelumnya, pada medio ‘80-an, Soemitro Djojohadikusumo pernah mengulas pemikiran BJ Habibie dalam makalah berjudul "Industrialisasi dalam Pembangunan Ekonomi" yang disampaikan sebagai ceramah Pembukaan Simposium "Industrialisasi di Indonesia: Prospek dan Masalahnya" dalam peringatan 35 tahun Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
Dalam makalah Soemitro tidak disebut secara eksplisit istilah Habibienomics. Bahkan, Sumitro secara moderat menyampaikan bahwa dua pemikiran itu (Widjojo dan BJ Habibie) seolah-olah ada, di mana yang satu merupakan alternatif bagi yang lain. Sumitro menganjurkan agar masing-masing tidak menjadikan pemikiran mereka sebagai dogma. Karena pemikiran atau konsep itu perlu pengkajian lebih lanjut, baik secara akademis maupun melalui pengalaman empiris dalam pelaksanaan kebijaksanaan (Rahardjo, 1996).
Sebenarnya, kata Sumitro, tidak adil jika dikatakan bahwa Widjojonomics itu intinya, hanya kebijakan yang mendasarkan diri pada prinsip keuntungan komparatif. Kebijakan ekonomi yang dikembangkan kelompok Widjojo sebenarnya jauh lebih luas dan dapat disimpulkan dalam doktrin Trilogi Pembangunan yang menekankan pada pengendalian kebijakan ekonomi makro dalam upaya-upaya untuk menciptakan stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan.
Pada kebijakan sektoral, misalnya pembangunan pertanian, industri dan perdagangan harus diperhitungkan dan dikontrol berdasarkan kerangka dan keseimbangan ekonomi makro yang dinamis, khususnya dengan melihat kepada indikator ekonomi fundamental.
Dalam catatan Dawam Rahardjo (1996), reaksi terhadap Widjojonomics baru muncul pada 1978. Pandangan yang timbul cukup beragam. Pada 1974 timbul protes terhadap dominasi penanaman modal asing, khususnya Jepang, yang dinilai memarjinalisasikan industri kecil di berbagai sentra produksi. Protes itu bahkan berkembang menjadi aksi sosial yang menimbulkan peristiwa Malari di Jakarta.
Pada pertengahan dasawarsa 1970-an, tulis Rahardjo (1994), timbul minat di kalangan perguruan tinggi dan LSM untuk menyelidiki masalah dampak pembangunan yang berorientasi kepada pertumbuhan ekonomi terhadap timbulnya kemiskinan.
Bahkan, sesungguhnya sejak awal dasawarsa itu dalam lingkup Dunia Ketiga telah terdengar gugatan Mahbub al Haq dalam bukunya The Poverty Curtain (1976), terhadap strategi pembangunan yang menghasilkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, dan dia mencoba menarik perhatian orang untuk menengok strategi pembangunan RRC yang memerangi kemiskinan secara langsung (direct attack on poverty).
Kegagalan, baik pada strategi berdasarkan prinsip keuntungan komparatif maupun strategi pendalaman industri merangsang pencarian alternatif baru. Acuannya adalah masalah kebergantungan teknologi yang menjadi sumber kemacetan pembangunan dalam jangka panjang. Dalam konteks inilah, gagasan BJ Habibie memperoleh justifikasi empirik.
Mengenang Habibienomics
Dalam makalahnya yang berjudul "Pembangunan Berorientasi Nilai Tambah" (1990), BJ Habibie berujar: "Keberhasilan pembangunan negara-negara berkembang dalam tiga dekade terakhir ternyata tidak menyurutkan ketergantungannya pada negara-negara maju. Lemahnya infrastruktur ilmu pengetahuan dan teknologi serta rendahnya kapabilitas sumber daya manusia negara-negara tersebut dipandang sebagai penyebab utama rendahnya daya saing mereka di pasar global".
Masalah ketergantungan teknologi menyebabkan negara-negara sedang berkembang makin tertinggal dalam perkembangan ekonomi dan makin tergantung, sehingga makin merugikan negara-negara sedang berkembang dalam hubungannya dengan negara-negara maju, mendorong BJ Habibie untuk mencari alternatif ketiga.
Alternatif ketiga BJ Habibie, memberi jalan keluar dengan konsep strategi lompatan. Asumsinya adalah bahwa negara-negara sedang berkembang tidak bakal mampu mengejar perkembangan teknologi, jika berkembang menurut garis linier. Untuk mengejarnya harus diciptakan garis perkembangan eksponensial, dengan melakukan apa yang disebut BJ Habibie sebagai "accelerated evolution" atau evolusi yang dipercepat.
Evolusi yang dipercepat tersebut tidak sama dengan "lompatan katak" (leap frogging) sebab lompatan katak bersifat acak dan tak dapat diperkirakan, sedangkan evolusi yang dipercepat tidak acak karena gerakannya dikendalikan dan diperkirakan. Hal ini berarti mengurangi risiko dan biaya transformasi yang tinggi.
Dalam mengemukakan alternatifnya tersebut, BJ Habibie melontarkan kritik terhadap konsep strategi konvensional, khususnya yang mendasarkan diri pada prinsip keuntungan komparatif saja. Strategi ini menurut BJ Habibie hanya berpedoman pada tolok ukur pendapatan nasional atau produksi nasional. Indikator itu sebenarnya tidak ditolaknya, tetapi dia mengusulkan indikator lain.
Untuk bisa menilai kemampuan membangun suatu bangsa, dia menambahkan bahwa indikator lain dalam suatu kesatuan ekonomi makro, yaitu indikator "Produktivitas Prestasi Nasional" (PPN) dan indikator "Pertumbuhan Produktivitas Prestasi Nasional". Indikator satu dalam dua itu merupakan perpaduan dari produktivitas tenaga kerja (labour productivity) dan produktivitas modal (capital productivity) dalam bentuk prasarana, sarana, dan mesin.
Itulah rumusan mazhab Habibienomics tentang strategi pembangunan yang mengandalkan kepada kualitas SDM. Berdasarkan kapabilitas SDM dapat dioptimalisasikan pemanfaatan sumber daya sumber daya lainnya. Persoalannya kemudian, bisa kita menjalankan strategi tersebut? Dalam konteks inilah, jargon Peringatan Kemerdekaan ke 74, yakni SDM Unggul, Indonesia Maju memiliki kompatibilitas dengan mazhab Habibienomics.
(maf)














