Rezim Gender Muhammadiyah: Mispersepsi atau Fakta?
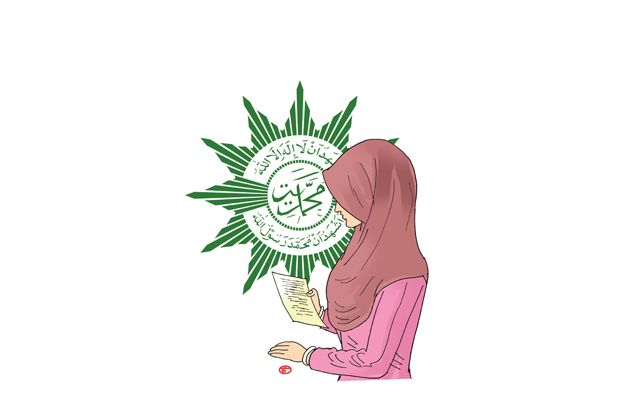
Rezim Gender Muhammadiyah: Mispersepsi atau Fakta?
A
A
A
Faisal Ismail
Guru Besar Pascasarjana FIAI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
SAYA sangat senang mendapat hadiah buku berjudul ”Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi” (2015) dari Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin MA. Siti Ruhaini Dzuhayatin (SRD) adalah sarjana lulusan terbaik Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga dan dosen pascasarjana di almamaternya. Ia pernah menjabat sebagai direktur Pusat Studi Wanita dan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama UIN Sunan Kalijaga.
Di level internasional, ia pernah mengikuti Training Mekanisme HAM Internasional di Gedung PBB (New York, Amerika Serikat) dan menjabat sebagai ketua Komisi HAM Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (berpusat di Jeddah, Arab Saudi). Masih banyak lagi prestasi akademik dan jabatan publik penting yang (pernah) ia sandang. Pada 2010, SRD mendapat penghargaan sebagai dosen terbaik dan produktif dari Menteri Agama RI. Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai staf khusus presiden bidang isu keagamaan internasional.
SRD mempunyai otoritas keilmuan membahas isu gender. Karya ilmiahnya ”Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi” merefleksikan perhatiannya terhadap studi ini. Setelah membaca buku tersebut, timbul pertanyaan: “Rezim Gender Muhammadiyah” itu fakta atau mispersepsi? Inilah poin penting yang menjadi catatan kritis-apreasiatif dalam tulisan ini. Sebagai titik tolak, perlu dikemukan pengertian “rezim” dan “gender.”
Menurut The Random House Dictionary of the English Language (Random House, New York, 1987, hlm. 1623), arti “regime” (rezim) adalah (1)a mode or system of rule or government; (2) a ruling or prevailing system; (3) a government in power; (4) the period during which a particular government or ruling system is in power. Artinya (1) tatanan atau sistem pemerintahan; (2) sistem pemerintahan yang berlaku; (3) pemerintah yang sedang berkuasa; (4) periode di mana pemerintah atau sistem pemerintahan sedang berkuasa. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami kata “rezim” biasanya dipakai dalam konteks sistem pemerintahan.
Dalam kamus yang sama, kata “gender” antara lain diartikan perbedaan “sex.” Menurut kamus ini, “gender gap” adalah the differences between women and men, especially as reflected in social, political, intellectual, cultural, or economic attainments or attitudes (perbedaan antara wanita dan pria, khususnya seperti terefleksikan dalam pencapaian atau sikap sosial, politik, intelektual, dan kultural). Melalui bukunya “Rezim Gender Muhammadiyah,” SRD mengkritik Muhammadiyah sebagai rezim sosial yang melaksanakan sistem dan tata kelola organisasinya dengan menerapkan kebijakan dan tindakan diskriminasi gender.
Dalam pembacaan saya atas buku tersebut, kaum pria lebih diutamakan dan ditempatkan pada posisi penting di jabatan struktural, sedang kaum wanita di-exlude dan disubordinasikan. Dengan demikian, Muhammadiyah bertindak sebagai “rezim gender” dengan menyubordinasikan perempuan. Kira-kira demikian pola pemikiran dan jalan pikiran SRD yang saya tangkap dalam bukunya.
Kasus yang Diangkat
Salah satu kasus yang diangkat oleh SRD dalam bukunya adalah tentang gagalnya perempuan menjadi anggota pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah gara-gara cara berpakaian. Merujuk pernyataan Abdurrahman (bukan nama sebenarnya), SRD menuturkan: “Rame sekali ketika akan memilih anggota pengurus Majelis Tarjih, terutama anggota yang perempuan.Banyak nama yang didaftar tetapi hanya satu akhirnya yang memenuhi kriteria. Konon Anda (penyusun, Siti Ruhaini Dzuhayatin) didrop karena ada yang melihat kerudungnya masih suka melorot dan pake celana jeans. Ada juga seorang calon perempuan yang didrop karena ketahuan pake daster di jalan dekat rumahnya, ya yang begitu-begitu jadi masalah.”
Menurut saya, kasus ini bukan semata-mata merupakan persoalan diskriminasi gender (bukan karena kedua calon itu berjenis kelamin perempuan), tetapi lebih merupakan tampilan “dress code” yang seharusnya dilakukan oleh kedua calon perempuan yang didrop itu. Seandainya SRD dan calon perempuan lain yang didrop itu berpakaian dan memakai busana seperti yang dikehendaki Majelis Tarjih, mereka berdua atau salah satu dari keduanya akan lolos menjadi anggota pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Selanjutnya, SRD dalam bukunya mengemukakan indikasi lain ketidakadilan gender di tubuh Muhammadiyah. Pada 2005, Ulfah terpilih sebagai ketua umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, tetapi kemudian ia mengundurkan diri karena ada “keberatan” dari PW Muhammadiyah dan PW Aisiyah setempat. Ulfah menuturkan pengunduran dirinya: “Aku memang terpilih secara aklamasi dalam pemilihan langsung, tetapi karena ada ‘semacam’ keberatan dari beberapa ayahanda (Pengurus PW Muhammadiyah) dan ibunda (Pengurus PW Aisiyah) meskipun tidak secara resmi, artinya hanya pendapat individu-individu.
Kata mereka ‘masih lebih baik laki-laki yang kurang mampu ketimbang seorang perempuan yang mampu.’ Sebenarnya teman-teman mendorong saya untuk bertahan tetapi saya pilih mundur daripada nanti menjadi masalah. Sayangnya aku bukan orang yang kuat, jadi aku mundur.”
Bisa jadi kultur masyarakat setempat (Sulawesi Selatan) pada 2005 belum sepenuhnya dapat menerima perempuan menjadi ketua umum IPM. Tampaknya sistem nilai sosial budaya masih menjadi bahan pertimbangan bagi perempuan untuk menduduki posisi puncak di IPM Sulsel saat itu. Situasi ini tentu akan berubah sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat.
Lagi pula, kasus lokal Ulfah yang mengundurkan diri menyusul dirinya terpilih sebagai ketua umum IPM Sulawesi Selatan itu tidak seharusnya “digeneralisasi” begitu saja oleh SRD dan dijadikan “kritik” empuk terhadap Muhammadiyah sebagai rezim gender. Menurut saya, kasus lokal Ulfah di Sulawesi Selatan tidak mewakili visi keagamaan dan pandangan gender yang dianut oleh Muhammadiyah.
Sebagai outsider, saya secara jelas melihat Muhammadiyah menganut pandangan sensitivitas gender. Sekarang ini, ketua umum PP Muhammadiyah dan ketua umum PP Aisiyah dijabat oleh pasangan suami-istri. Sangat terasa ada keserasian, keharmonisan, dan kesetaraan gender. Ketua Umum PP Muhammadiyah dijabat oleh Dr Haedar Nashir (suami) dan ketua umum PP Aisiyah dimotori oleh Dra Siti Noordjannah Djohantini, MM, MSi.
Muhammadiyah, sebagai organisasi muslim modernis, hadir secara fungsional dan berperan penting dalam menyosialisasi dan mengedukasi sensitivitas gender dalam kehidupan umat dan bangsa. Menurut saya, kritik terhadap Muhammadiyah sebagai rezim gender lebih merupakan mispersepsi, bukan fakta.
Guru Besar Pascasarjana FIAI
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta
SAYA sangat senang mendapat hadiah buku berjudul ”Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi” (2015) dari Dr Siti Ruhaini Dzuhayatin MA. Siti Ruhaini Dzuhayatin (SRD) adalah sarjana lulusan terbaik Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga dan dosen pascasarjana di almamaternya. Ia pernah menjabat sebagai direktur Pusat Studi Wanita dan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan kerja sama UIN Sunan Kalijaga.
Di level internasional, ia pernah mengikuti Training Mekanisme HAM Internasional di Gedung PBB (New York, Amerika Serikat) dan menjabat sebagai ketua Komisi HAM Organisasi Kerja Sama Islam/OKI (berpusat di Jeddah, Arab Saudi). Masih banyak lagi prestasi akademik dan jabatan publik penting yang (pernah) ia sandang. Pada 2010, SRD mendapat penghargaan sebagai dosen terbaik dan produktif dari Menteri Agama RI. Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai staf khusus presiden bidang isu keagamaan internasional.
SRD mempunyai otoritas keilmuan membahas isu gender. Karya ilmiahnya ”Rezim Gender Muhammadiyah: Kontestasi Gender, Identitas, dan Eksistensi” merefleksikan perhatiannya terhadap studi ini. Setelah membaca buku tersebut, timbul pertanyaan: “Rezim Gender Muhammadiyah” itu fakta atau mispersepsi? Inilah poin penting yang menjadi catatan kritis-apreasiatif dalam tulisan ini. Sebagai titik tolak, perlu dikemukan pengertian “rezim” dan “gender.”
Menurut The Random House Dictionary of the English Language (Random House, New York, 1987, hlm. 1623), arti “regime” (rezim) adalah (1)a mode or system of rule or government; (2) a ruling or prevailing system; (3) a government in power; (4) the period during which a particular government or ruling system is in power. Artinya (1) tatanan atau sistem pemerintahan; (2) sistem pemerintahan yang berlaku; (3) pemerintah yang sedang berkuasa; (4) periode di mana pemerintah atau sistem pemerintahan sedang berkuasa. Berdasarkan pengertian ini, dapat dipahami kata “rezim” biasanya dipakai dalam konteks sistem pemerintahan.
Dalam kamus yang sama, kata “gender” antara lain diartikan perbedaan “sex.” Menurut kamus ini, “gender gap” adalah the differences between women and men, especially as reflected in social, political, intellectual, cultural, or economic attainments or attitudes (perbedaan antara wanita dan pria, khususnya seperti terefleksikan dalam pencapaian atau sikap sosial, politik, intelektual, dan kultural). Melalui bukunya “Rezim Gender Muhammadiyah,” SRD mengkritik Muhammadiyah sebagai rezim sosial yang melaksanakan sistem dan tata kelola organisasinya dengan menerapkan kebijakan dan tindakan diskriminasi gender.
Dalam pembacaan saya atas buku tersebut, kaum pria lebih diutamakan dan ditempatkan pada posisi penting di jabatan struktural, sedang kaum wanita di-exlude dan disubordinasikan. Dengan demikian, Muhammadiyah bertindak sebagai “rezim gender” dengan menyubordinasikan perempuan. Kira-kira demikian pola pemikiran dan jalan pikiran SRD yang saya tangkap dalam bukunya.
Kasus yang Diangkat
Salah satu kasus yang diangkat oleh SRD dalam bukunya adalah tentang gagalnya perempuan menjadi anggota pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah gara-gara cara berpakaian. Merujuk pernyataan Abdurrahman (bukan nama sebenarnya), SRD menuturkan: “Rame sekali ketika akan memilih anggota pengurus Majelis Tarjih, terutama anggota yang perempuan.Banyak nama yang didaftar tetapi hanya satu akhirnya yang memenuhi kriteria. Konon Anda (penyusun, Siti Ruhaini Dzuhayatin) didrop karena ada yang melihat kerudungnya masih suka melorot dan pake celana jeans. Ada juga seorang calon perempuan yang didrop karena ketahuan pake daster di jalan dekat rumahnya, ya yang begitu-begitu jadi masalah.”
Menurut saya, kasus ini bukan semata-mata merupakan persoalan diskriminasi gender (bukan karena kedua calon itu berjenis kelamin perempuan), tetapi lebih merupakan tampilan “dress code” yang seharusnya dilakukan oleh kedua calon perempuan yang didrop itu. Seandainya SRD dan calon perempuan lain yang didrop itu berpakaian dan memakai busana seperti yang dikehendaki Majelis Tarjih, mereka berdua atau salah satu dari keduanya akan lolos menjadi anggota pengurus Majelis Tarjih Muhammadiyah.
Selanjutnya, SRD dalam bukunya mengemukakan indikasi lain ketidakadilan gender di tubuh Muhammadiyah. Pada 2005, Ulfah terpilih sebagai ketua umum Ikatan Pemuda Muhammadiyah Sulawesi Selatan, tetapi kemudian ia mengundurkan diri karena ada “keberatan” dari PW Muhammadiyah dan PW Aisiyah setempat. Ulfah menuturkan pengunduran dirinya: “Aku memang terpilih secara aklamasi dalam pemilihan langsung, tetapi karena ada ‘semacam’ keberatan dari beberapa ayahanda (Pengurus PW Muhammadiyah) dan ibunda (Pengurus PW Aisiyah) meskipun tidak secara resmi, artinya hanya pendapat individu-individu.
Kata mereka ‘masih lebih baik laki-laki yang kurang mampu ketimbang seorang perempuan yang mampu.’ Sebenarnya teman-teman mendorong saya untuk bertahan tetapi saya pilih mundur daripada nanti menjadi masalah. Sayangnya aku bukan orang yang kuat, jadi aku mundur.”
Bisa jadi kultur masyarakat setempat (Sulawesi Selatan) pada 2005 belum sepenuhnya dapat menerima perempuan menjadi ketua umum IPM. Tampaknya sistem nilai sosial budaya masih menjadi bahan pertimbangan bagi perempuan untuk menduduki posisi puncak di IPM Sulsel saat itu. Situasi ini tentu akan berubah sejalan dengan dinamika perkembangan masyarakat.
Lagi pula, kasus lokal Ulfah yang mengundurkan diri menyusul dirinya terpilih sebagai ketua umum IPM Sulawesi Selatan itu tidak seharusnya “digeneralisasi” begitu saja oleh SRD dan dijadikan “kritik” empuk terhadap Muhammadiyah sebagai rezim gender. Menurut saya, kasus lokal Ulfah di Sulawesi Selatan tidak mewakili visi keagamaan dan pandangan gender yang dianut oleh Muhammadiyah.
Sebagai outsider, saya secara jelas melihat Muhammadiyah menganut pandangan sensitivitas gender. Sekarang ini, ketua umum PP Muhammadiyah dan ketua umum PP Aisiyah dijabat oleh pasangan suami-istri. Sangat terasa ada keserasian, keharmonisan, dan kesetaraan gender. Ketua Umum PP Muhammadiyah dijabat oleh Dr Haedar Nashir (suami) dan ketua umum PP Aisiyah dimotori oleh Dra Siti Noordjannah Djohantini, MM, MSi.
Muhammadiyah, sebagai organisasi muslim modernis, hadir secara fungsional dan berperan penting dalam menyosialisasi dan mengedukasi sensitivitas gender dalam kehidupan umat dan bangsa. Menurut saya, kritik terhadap Muhammadiyah sebagai rezim gender lebih merupakan mispersepsi, bukan fakta.
(whb)














