Narasi Ke(tidak)adilan Gender
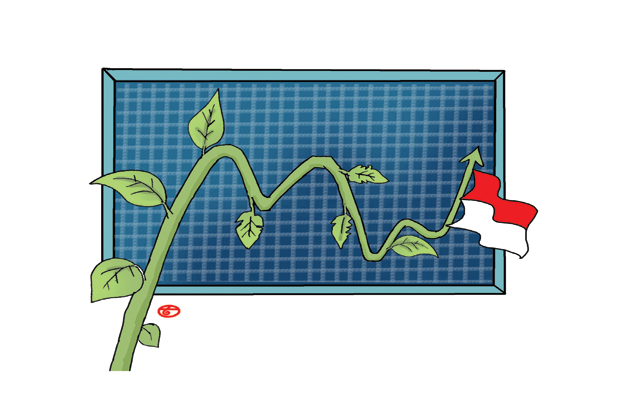
Narasi Ke(tidak)adilan Gender
A
A
A
Rio Christiawan
Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya
“…Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja, wanita dijajah pria sejak dulu…”
SAYA mengawali artikel ini dengan potongan lagu yang menggambarkan narasi penegakan hukum di Indonesia yang masih bias gender sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Sejak dari zaman kasus yang dikenal dengan kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970; korban perkosaan yang justru dijadikan tersangka pemberian keterangan palsu.
Perkembangan terbaru Mahkamah Agung (MA) baru saja menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda Rp500 juta rupiah kepada seorang guru honorer perempuan di Mataram, NTB karena melanggar UU ITE. Ihwal diseretnya guru honorer perempuan ini ke meja hijau adalah ketika guru honorer tersebut merekam pembicaraan mesum kepala sekolah selaku atasannya. Justru ketika guru honorer tersebut ingin membongkar perilaku atasannya tersebut dia diadili di meja hijau.
Bukan kali ini saja peradilan Indonesia meletakkan korban sebagai tersangka, belum lama ini menjadi isu nasional dan menjadi headline di media masa internasional ketika pengadilan negeri Muara Bulian menjatuhkan pidana penjara kepada seorang anak perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi di awal kehamilannya karena diperkosa kakak kandungnya. Praktik-praktik peradilan bias gender masih sering terjadi, sehingga korban yang semestinya mendapat perlindungan hukum justru dihukum dengan alasan unsur yang didakwakan jaksa telah terbukti. Ini merupakan contoh positivisme hukum yang sempit pada praktik peradilan di Indonesia dan pada akhirnya selalu menempatkan perempuan sebagai korban.
Dalam konteks peradilan yang berkeadilan gender, kini peradilan sebagai tempat mencari keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan yang disebabkan oleh bias gender. Betapa melukai perasaan keadilan masyarakat ketika kepala sekolah sebagai pimpinan institusi pendidikan yang khawatir percakapan mesumnya terbongkar justru diposisikan sebagai korban. Ironisnya lagi anak buah perempuannya yang merekam percakapan tersebut karena tidak nyaman dan merasa terlecehkan dengan sikap kepala sekolah justru diposisikan sebagai pelaku kejahatan.
Fenomena di atas justru mengukuhkan pentingnya mengintrodusir model pendekatan feminisme jurisprudence dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebenarnya MA telah memiliki pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Perma tersebut lahir sebagai bentuk konkret pelaksanaan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, namun pada faktanya praktik peradilan di Indonesia di segala level masih belum menunjukkan sensitivitas gender dalam mewujudkan keadilan. Dengan melihat pada banyaknya fenomena bias gender dalam praktik peradilan maka Komnas Perempuan perlu mengawal konsistensi pendekatan feminisme jurisprudence pada praktik penegakan hukum di pengadilan.
Legisme Tanpa Makna
Ciri dari sistem peradilan yang dibangun zaman kolonial Belanda adalah menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku hingga saat ini meninggalkan jejak legisme yang kuat. Meuwissen (1967), menyebutkan bahwa aliran legisme (positivis) menganggap semua hukum ada dalam undang-undang sehingga tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan.
Gustaf Radbruch (1981), menyebut sebaik-baiknya peradilan tidak akan bermakna jika tidak mampu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga keputusan hakim harus berorientasi pada keseimbangan ketiganya, peraturan perundangan hanya berlaku sebagai pedoman saja. Urgensi inisiasi feminisme jurisprudence dalam praktik peradilan di Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan kodrati pada perempuan dalam konteks penegakan hukum.
Mengacu pada putusan MA Nomor 1604 K/Pdt/2004, MA merumuskan paradigma feminisme jurisprudence sebagai paradigma yang memandang kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat kodrati dan hak-hak natural yang timbul olehnya, artinya keadilan kodrati berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat naturalnya. Timbangan keadilan kodrati itulah yang dinamakan sensitivitas gender.
Sebagai contoh pada kasus-kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan pada bagian awal artikel ini jika hakim yang memutus perkara ini mengunakan timbangan sensitivitas gender maka terdakwa seharusnya diposisikan sebagai korban dalam perspektif keadilan kodrati model feminisme jurisprudence.
Kini setelah banyaknya persoalan yang menempatkan wanita sebagai pelaku meskipun seharusnya diposisikan sebagai korban, MA seharusnya meninggalkan model penegakan hukum legisme buta. Sebagaimana dinyatakan oleh mantan hakim dan guru besar ilmu hukum Soedikno Mertokusumo (2000), bahwa pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum (judge made law).
Artinya hakim dapat mengabaikan peraturan perundangan berdasarkan keyakinannya untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Maka tolok ukur dari baik atau buruknya putusan pengadilan adalah makna putusan pengadilan itu bagi pencari keadilan. Maka kini pertanyaan reflektifnya adalah apa makna dan manfaat putusan pengadilan yang menghukum guru honorer perempuan maupun anak perempuan di bawah umur yang seharusnya diposisikan sebagai korban.Putusan putusan tersebut justru sulit diterima dalam logika akal sehat dan hati nurani.
Sensitifitas Gender
Penegakan hukum berprespektif gender adalah dalam mengadili suatu perkara hakim harus melihat kronologis perkara secara utuh pada posisi masing-masing sehingga dapat merumuskan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Salah konstruksi korban sebagai pelaku dan sebaliknya pada perkara yang melibatkan perempuan dan laki-laki merupakan bukti bahwa peradilan di Indonesia belum menggunakan tolak ukur sensitifitas gender.
MA harus berani melakukan koreksi atas putusan jajarannya demi mewujudkan keadilan dan membersihkan lembaga peradilan dari praktek bias gender pada penegakan hukum. Model penegakan hukum feminisme jurisprudence adalah melepaskan perempuan pada posisinya sebagai subordinasi laki-laki. Kini banyak putusan-putusan lembaga peradilan yang justru melanggengkan status quo subordinasi laki-laki atas perempuan.
Dengan posisi perempuan tidak dibawah subordinasi laki-laki maka hukum akan secara lebih jernih dapat menilai posisi perempuan dan laki-laki, karena penegakan hukum berbasis sensitifitas gender meletakkan baik laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum sehingga memiliki nilai yang sama untuk dilindungi, dalam kondisi demikian akan terwujud equality before the law.
Para penegak hukum dan MA sebagai benteng peradilan dan muara dari segala penegakan hukum harus meninggalkan paradigma yang meletakkan perempuan sebagai objek. Dalam melakukan penegakan hukumharus ditinggalkan patron patriarki peninggalan zaman kolonial yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pada akhirnya hukum tanpa logika sama artinya dengan menggunakan kekuasaan secara buta dan menimbulkan kesewenang-wenangan, maka MA harus segera mengoreksi putusan-putusan yang bias gender.
MA dan institusi terkait harus menghindarkan kesewenang-wenangan dengan menempatkan pelaku sebagai korban dan korban sebagai pelaku. Bangsa Indonesia sudah harus mengakhiri penegakan hukum tanpa logika karena pada akhirnya sebenarnya semangat penegakan hukum adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
Kriminolog dan Dosen Hukum Universitas Prasetiya Mulya
“…Ditakdirkan bahwa pria berkuasa, adapun wanita lemah lembut manja, wanita dijajah pria sejak dulu…”
SAYA mengawali artikel ini dengan potongan lagu yang menggambarkan narasi penegakan hukum di Indonesia yang masih bias gender sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Sejak dari zaman kasus yang dikenal dengan kasus Sum Kuning di Yogyakarta pada 1970; korban perkosaan yang justru dijadikan tersangka pemberian keterangan palsu.
Perkembangan terbaru Mahkamah Agung (MA) baru saja menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda Rp500 juta rupiah kepada seorang guru honorer perempuan di Mataram, NTB karena melanggar UU ITE. Ihwal diseretnya guru honorer perempuan ini ke meja hijau adalah ketika guru honorer tersebut merekam pembicaraan mesum kepala sekolah selaku atasannya. Justru ketika guru honorer tersebut ingin membongkar perilaku atasannya tersebut dia diadili di meja hijau.
Bukan kali ini saja peradilan Indonesia meletakkan korban sebagai tersangka, belum lama ini menjadi isu nasional dan menjadi headline di media masa internasional ketika pengadilan negeri Muara Bulian menjatuhkan pidana penjara kepada seorang anak perempuan di bawah umur yang melakukan aborsi di awal kehamilannya karena diperkosa kakak kandungnya. Praktik-praktik peradilan bias gender masih sering terjadi, sehingga korban yang semestinya mendapat perlindungan hukum justru dihukum dengan alasan unsur yang didakwakan jaksa telah terbukti. Ini merupakan contoh positivisme hukum yang sempit pada praktik peradilan di Indonesia dan pada akhirnya selalu menempatkan perempuan sebagai korban.
Dalam konteks peradilan yang berkeadilan gender, kini peradilan sebagai tempat mencari keadilan justru menjadi sumber ketidakadilan yang disebabkan oleh bias gender. Betapa melukai perasaan keadilan masyarakat ketika kepala sekolah sebagai pimpinan institusi pendidikan yang khawatir percakapan mesumnya terbongkar justru diposisikan sebagai korban. Ironisnya lagi anak buah perempuannya yang merekam percakapan tersebut karena tidak nyaman dan merasa terlecehkan dengan sikap kepala sekolah justru diposisikan sebagai pelaku kejahatan.
Fenomena di atas justru mengukuhkan pentingnya mengintrodusir model pendekatan feminisme jurisprudence dalam praktik peradilan di Indonesia. Sebenarnya MA telah memiliki pedoman melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum.
Perma tersebut lahir sebagai bentuk konkret pelaksanaan Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita, namun pada faktanya praktik peradilan di Indonesia di segala level masih belum menunjukkan sensitivitas gender dalam mewujudkan keadilan. Dengan melihat pada banyaknya fenomena bias gender dalam praktik peradilan maka Komnas Perempuan perlu mengawal konsistensi pendekatan feminisme jurisprudence pada praktik penegakan hukum di pengadilan.
Legisme Tanpa Makna
Ciri dari sistem peradilan yang dibangun zaman kolonial Belanda adalah menempatkan hakim sebagai corong undang-undang. Sistem hukum Eropa Kontinental (Civil Law) yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku hingga saat ini meninggalkan jejak legisme yang kuat. Meuwissen (1967), menyebutkan bahwa aliran legisme (positivis) menganggap semua hukum ada dalam undang-undang sehingga tidak ada hukum di luar peraturan perundang-undangan.
Gustaf Radbruch (1981), menyebut sebaik-baiknya peradilan tidak akan bermakna jika tidak mampu mewujudkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga keputusan hakim harus berorientasi pada keseimbangan ketiganya, peraturan perundangan hanya berlaku sebagai pedoman saja. Urgensi inisiasi feminisme jurisprudence dalam praktik peradilan di Indonesia adalah untuk mewujudkan keadilan kodrati pada perempuan dalam konteks penegakan hukum.
Mengacu pada putusan MA Nomor 1604 K/Pdt/2004, MA merumuskan paradigma feminisme jurisprudence sebagai paradigma yang memandang kesetaraan hukum antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat kodrati dan hak-hak natural yang timbul olehnya, artinya keadilan kodrati berbeda antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat naturalnya. Timbangan keadilan kodrati itulah yang dinamakan sensitivitas gender.
Sebagai contoh pada kasus-kasus yang terjadi sebagaimana diuraikan pada bagian awal artikel ini jika hakim yang memutus perkara ini mengunakan timbangan sensitivitas gender maka terdakwa seharusnya diposisikan sebagai korban dalam perspektif keadilan kodrati model feminisme jurisprudence.
Kini setelah banyaknya persoalan yang menempatkan wanita sebagai pelaku meskipun seharusnya diposisikan sebagai korban, MA seharusnya meninggalkan model penegakan hukum legisme buta. Sebagaimana dinyatakan oleh mantan hakim dan guru besar ilmu hukum Soedikno Mertokusumo (2000), bahwa pekerjaan hakim adalah menciptakan hukum (judge made law).
Artinya hakim dapat mengabaikan peraturan perundangan berdasarkan keyakinannya untuk memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat. Maka tolok ukur dari baik atau buruknya putusan pengadilan adalah makna putusan pengadilan itu bagi pencari keadilan. Maka kini pertanyaan reflektifnya adalah apa makna dan manfaat putusan pengadilan yang menghukum guru honorer perempuan maupun anak perempuan di bawah umur yang seharusnya diposisikan sebagai korban.Putusan putusan tersebut justru sulit diterima dalam logika akal sehat dan hati nurani.
Sensitifitas Gender
Penegakan hukum berprespektif gender adalah dalam mengadili suatu perkara hakim harus melihat kronologis perkara secara utuh pada posisi masing-masing sehingga dapat merumuskan putusan yang memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum. Salah konstruksi korban sebagai pelaku dan sebaliknya pada perkara yang melibatkan perempuan dan laki-laki merupakan bukti bahwa peradilan di Indonesia belum menggunakan tolak ukur sensitifitas gender.
MA harus berani melakukan koreksi atas putusan jajarannya demi mewujudkan keadilan dan membersihkan lembaga peradilan dari praktek bias gender pada penegakan hukum. Model penegakan hukum feminisme jurisprudence adalah melepaskan perempuan pada posisinya sebagai subordinasi laki-laki. Kini banyak putusan-putusan lembaga peradilan yang justru melanggengkan status quo subordinasi laki-laki atas perempuan.
Dengan posisi perempuan tidak dibawah subordinasi laki-laki maka hukum akan secara lebih jernih dapat menilai posisi perempuan dan laki-laki, karena penegakan hukum berbasis sensitifitas gender meletakkan baik laki-laki dan perempuan sebagai subjek hukum sehingga memiliki nilai yang sama untuk dilindungi, dalam kondisi demikian akan terwujud equality before the law.
Para penegak hukum dan MA sebagai benteng peradilan dan muara dari segala penegakan hukum harus meninggalkan paradigma yang meletakkan perempuan sebagai objek. Dalam melakukan penegakan hukumharus ditinggalkan patron patriarki peninggalan zaman kolonial yang menempatkan perempuan sebagai subordinasi laki-laki. Pada akhirnya hukum tanpa logika sama artinya dengan menggunakan kekuasaan secara buta dan menimbulkan kesewenang-wenangan, maka MA harus segera mengoreksi putusan-putusan yang bias gender.
MA dan institusi terkait harus menghindarkan kesewenang-wenangan dengan menempatkan pelaku sebagai korban dan korban sebagai pelaku. Bangsa Indonesia sudah harus mengakhiri penegakan hukum tanpa logika karena pada akhirnya sebenarnya semangat penegakan hukum adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
(thm)














