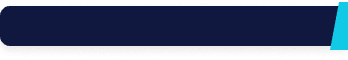Keselamatan Kerja di Sektor Konstruksi: Tantangan dan Perspektif Indonesia dan Inggris
loading...

Faktor di balik terjadinya kecelakaan kerja cukup beragam, mulai dari kurangnya tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam mematuhi standar K3 hingga kurangnya ketersediaan tenaga ahli muda yang ada di lapangan. FOTO ILUSTRASI/DOK.SINDOnews
A
A
A
M Zaky Ardian, Ikhtiar A Hidayat, M Rifli Mubarak
Engineer di Mabey Hire (UK), Corporate Secretary di PT Hutama Karya Infrastruktur, Government Relation and Legal Compliance di CNGR
KECELAKAAN kerja yang terjadi pada 24 Desember 2023 silam yang beroperasi di kawasan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), dipicu oleh ledakan tungku. Insiden tersebut bermula pada saat pekerja melakukan perbaikan dan pemasangan pelat pada bagian tungku. Mengoperasikan alat berat dan proses peleburan (smelting) memiliki risiko besar yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itu, pekerja smelter harus menjalani pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Persoalan K3 terjadi berulang kali, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Sesuai rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Sulawesi Tengah terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perusahaan juga wajib memiliki sistem pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur.
Menyoroti kasus kecelakaan kerja fatal (fatal injuries), sektor konstruksi merupakan penyumbang terbesar terhadap angka kecelakaan kerja di Indonesia. Pada awal Januari 2023, dilaporkan terdapat 264.334 kasus kecelakaan kerja menurut Liputan6.com, bahkan menurut data dari International Labour Organization (ILO), setidaknya 60.000 kecelakaan fatal terjadi setiap tahunnya. Ironisnya, seringkali kecelakaan tersebut masih dinilai sebagai bagian dari 'tumbal proyek” yang tak terhindarkan. Padahal, sebenarnya kecelakaan kerja yang sering terjadi di sektor konstruksi memiliki alasan logis dan penyebab yang dapat diidentifikasi.
Faktor di balik terjadinya kecelakaan kerja cukup beragam, mulai dari kurangnya tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga kurangnya ketersediaan tenaga ahli muda yang ada di lapangan. Sebab berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), banyaknya tenaga kerja ahli konstruksi per tahun 2023 berdasarkan kualifikasi hanya terdiri dari 53,36 muda, 68,65 madya, dan 9,31 utama dari total 131,32. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan K3 sebagai prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan K3 sebagai prinsip dan hak dasar di tempat kerja (occupational safety and health as fundamental principles and right at work). "Kondisi kerja yang selamat dan sehat adalah fundamental bagi pekerjaan yang layak (decent work)".
Aturan di Inggris mengamanatkan bahwa setiap temporary works (bangunan sementara) harus direncanakan, dipasang, dan dipelihara agar dapat menahan beban yang dikenakan padanya dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal. Di Inggris, 45 dari 135 pekerja konstruksi tewas akibat fatal injuries dan 29,62% akibat jatuh dari ketinggian yang berhubungan dengan perancah (scaffolding) sebagaimana pada data di bawah ini:
![Keselamatan Kerja di Sektor Konstruksi: Tantangan dan Perspektif Indonesia dan Inggris]()
Temporary works seperti perancah, penggalian, cofferdam dan caisson harus diperiksa secara berkala oleh orang yang berkompeten. Tidak ada persyaratan hukum khusus mengenai bagaimana pekerjaan sementara harus dikelola; setiap organisasi dapat memilih bagaimana mereka mengatur dan mengelola keselamatan di lokasi.
Desain dan pelaksanaan temporary works yang benar merupakan elemen penting dalam pencegahan dan mitigasi risiko dalam konstruksi. BS 5975: 2019 memberikan rekomendasi dan panduan mengenai pengendalian prosedural yang akan diterapkan pada semua aspek pekerjaan sementara di industri konstruksi dan pada desain, spesifikasi, konstruksi, penggunaan dan pembongkaran temporary works.
Sebagian besar perkembangan desain pekerjaan sementara terjadi di Inggris ketika Jembatan Barton, Jembatan Lodden pada tahun 1960an dan 1970an runtuh selama konstruksi dan pemerintah tergerak untuk menentukan apakah Inggris berada dalam kondisi yang sehat untuk mengelola bengunan sementara. Kegagalan besar yang berkait dengan temporary works di Inggris hampir menghilang sejak BS 5975 diterbitkan pada tahun 1982. Di Inggris, desain tiang penyangga sementara biasanya sesuai dengan ketentuan persyaratan BS 5975 kecuali penggunaan Eurocode 12811 dan EN 12812 ditetapkan sebagai persyaratan kontrak.
Temporary Works Forum (TWf) dibentuk pada tahun 2009 di Inggris sebagai lembaga independen dan nirlaba perusahaan yang beroperasi pada basis biaya terbatas. Panduan dan perangkat yang berguna serta dokumen panduan dihasilkan oleh TWf yang membahas masalah pekerjaan sementara dan penerapan Eurocodes untuk konstruksi yang lebih aman di Inggris. Prinsip-prinsip perangkat alat yang dihasilkan oleh TWf ini dapat diterapkan di seluruh dunia.
ILO mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat bervariasi tergantung pada kondisi di setiap negara, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Terutama di negara-negara berkembang, angka kematian dan cedera akibat kecelakaan kerja cenderung tinggi. Namun, ada beberapa negara industri yang berhasil menurunkan angka cedera serius yang mencerminkan keberhasilan dari upaya-upaya perbaikan dalam hal K3, seperti Negara Inggris atau United Kingdom (UK).
ILO menekankan pentingnya menerapkan budaya K3 sebagai strategi global untuk pengelolaan K3 di seluruh dunia. Dalam makalah yang berjudul "Creating A Safety Culture" yang disusun oleh Jane Ardern, disebutkan bahwa ada tiga faktor utama yang membentuk budaya K3, yaitu sikap, lingkungan, dan sistem. Faktor-faktor ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya K3 di tempat kerja serta mendorong implementasi praktik-praktik yang aman dan bertanggung jawab.
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Indonesia bersifat mandatory yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah, yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan konstruksi dengan elemen yang mesti diterapkan: Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, dan Penerapan.
Di Indonesia, terdapat beragam peraturan yang saling melengkapi satu sama lain dalam menciptakan ekosistem keselamatan kerja yang holistik. Dimulai dari Pengaturan Keselamatan Kerja di Bidang Konstruksi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Berbagai aturan tersebut melibatkan banyak elemen untuk bisa menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Seperti halnya pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan yang merupakan prinsip fundamental dalam membangun bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang mematuhi prinsip berkelanjutan, siklus hidup, dan sumber daya dengan tiga pilar utama: 1) Secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasa konstruksi; 2) Menjaga pelestarian lingkungan; dan 3) Mengurangi disparitas sosial masyarakat jasa konstruksi. Dengan adanya prinsip Konstruksi Berkelanjutan, penyelenggara jasa usaha tentunya memiliki kewajiban untuk membangun suatu bangunan dengan basis standar yang solid dan prinsip ini diimplementasikan melalui: 1) Perencanaan umum; 2) Pemrograman; 3) Pelaksanaan konsultasi konstruksi; dan 4) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa yang bersangkutan juga wajib melaksanakan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (“SMKK”) untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang berlaku dengan memastikan keselamatan aspek-aspek tertentu dimulai dari aspek keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan publik, hingga keselamatan lingkungan.
Dalam hal perlindungan pekerja/buruh khususnya mereka yang bekerja di ruang terbatas dari potensi bahaya, Indonesia juga telah mengatur hal tersebut melalui Peraturan No. 11 tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (“Permenaker 11/2023”). Ruang terbatas sendiri didefinisikan lokasi yang meliputi: 1) Tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tungku, silo, dan cerobong; 2) Jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa; 3) Sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya dengan kedalaman melebihi 1,5 meter; dan/atau 4) Ruang lain yang dikategorikan sebagai ruang terbatas oleh Pelaku Usaha.
Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerja, persyaratan K3 untuk ruang terbatas diterapkan berdasarkan enam bidang berikut: 1) Penetapan klasifikasi; 2) Pembatasan akses terhadap ruang terbatas; 3) Izin masuk; 4) Prosedur kerja aman; 5) Peralatan dan perlengkapan; dan 6) Personel K3. Dari upaya tersebut, diharapkan adanya ketentuan protektif bagi para pekerja agar dapat mengetahui tanda-tanda dan/atau limitasi dalam ruang bekerja untuk mencegah kemungkinan terburuk yakni kecelakaan saat bekerja.
Berkaca pada negara Inggris, hadirnya The Building Safety Act 2022 menjadi bentuk respons nyata terhadap tragedi Grenfell Tower tahun 2017 yang mana bertujuan dari untuk meningkatkan desain, konstruksi, dan manajemen gedung-gedung berisiko tinggi. Namun, hal yang menarik dari Inggris bahwa mereka juga menekankan pentingnya kesehatan mental untuk dimasukkan ke dalam bagian dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di jasa konstruksi. Health and Safety Executive (HSE) yang merupakan badan publik Inggris yang bertanggung jawab atas dorongan, regulasi, dan penegakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja menetapkan ketegasan untuk mengurangi penyakit terkait kerja, dengan fokus khusus pada kesehatan mental dan stres. Hal ini dijadikan sebagai pusat strategi sejak 2022-2023 di Inggris dan pengusaha memiliki kewajiban terhadap karyawan dan pekerja lainnya (termasuk kontraktor) untuk memastikan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja berdasarkan Health and Safety at Work etc. Act 1974. Hal tersebut tentunya dilandasi dengan statistik mengenai risiko kesehatan mental di tempat kerja dan dampaknya terhadap produktivitas pekerja yang dalam pencapaian tujuan perusahaan.
Dari perspektif sosial dan kesejahteraan, K3 di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan para pekerja serta masyarakat secara keseluruhan. Poin tersebut antara lain berpengaruh pada perlindungan terhadap tenaga kerja yang tercantum pada Undang-Undang No 14 tahun 1969. Lingkungan kerja yang aman dan sehat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan mengurangi risiko kecelakaan dapat berdampak positif pada pengurangan beban kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan kualitas hidup berpengaruh pada kesejahteraan individu di tingkat mikro dan berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat.
Peran Sertifikasi Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja. Para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mendapatkan manfaat diantaranya jaminan kejelasan besaran imbalan/gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan perlindungan hukum pada profesi. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar para pekerja tidak lantas puas setelah mendapatkan sertifikat.
Isu terkait SMK3 juga ditemukan bahwa hal yang menimbulkan potensi kecelakaan kerja bukan hanya semata-mata berasal dari kurang efektifnya sistem atau aturan yang diberlakukan, melainkan kesadaran dari pekerja itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut yakni dari sisi pekerja dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing pekerja tersebut yang lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan keselamatan saat bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian ini bahwa para pekerja lebih mementingkan bonus atau insentif sebagai output bekerja dan adanya rasa ketidaknyaman dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (“APD”) pada saat bekerja.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 di kalangan pekerja, menyediakan pelatihan yang memadai, serta memastikan ketersediaan peralatan keselamatan yang lengkap dan berkualitas adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan demikian, diharapkan tingkat kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan kesejahteraan pekerja dapat terjaga, sehingga produktivitas dan kualitas pekerjaan dapat meningkat secara signifikan. Terms like “sustainability” and “corporate social responsibility” are not new for now. They have been present for over two decades. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh semua pihak terkait.
2. Kemnaker. Profil K3 Nasional 2022.
3. Health and Safety Executive. UK Health and Safety Statistics - Fatal injuries in Great Britain.
4. The Law Society. Building Safety Act 2022 and residential conveyancing.
5. Osborne Clarke. Health and Safety Executive spotlights mental health risks to GB workforce.
6. Saragi, T. E., & Sinaga, R. E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan rumah susun lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan.
Engineer di Mabey Hire (UK), Corporate Secretary di PT Hutama Karya Infrastruktur, Government Relation and Legal Compliance di CNGR
KECELAKAAN kerja yang terjadi pada 24 Desember 2023 silam yang beroperasi di kawasan PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS), dipicu oleh ledakan tungku. Insiden tersebut bermula pada saat pekerja melakukan perbaikan dan pemasangan pelat pada bagian tungku. Mengoperasikan alat berat dan proses peleburan (smelting) memiliki risiko besar yang memerlukan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itu, pekerja smelter harus menjalani pelatihan keselamatan kerja sesuai dengan standar yang berlaku. Persoalan K3 terjadi berulang kali, bahkan mengakibatkan korban jiwa. Sesuai rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Sulawesi Tengah terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), perusahaan juga wajib memiliki sistem pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan secara teratur.
Menyoroti kasus kecelakaan kerja fatal (fatal injuries), sektor konstruksi merupakan penyumbang terbesar terhadap angka kecelakaan kerja di Indonesia. Pada awal Januari 2023, dilaporkan terdapat 264.334 kasus kecelakaan kerja menurut Liputan6.com, bahkan menurut data dari International Labour Organization (ILO), setidaknya 60.000 kecelakaan fatal terjadi setiap tahunnya. Ironisnya, seringkali kecelakaan tersebut masih dinilai sebagai bagian dari 'tumbal proyek” yang tak terhindarkan. Padahal, sebenarnya kecelakaan kerja yang sering terjadi di sektor konstruksi memiliki alasan logis dan penyebab yang dapat diidentifikasi.
Faktor di balik terjadinya kecelakaan kerja cukup beragam, mulai dari kurangnya tingkat kedisiplinan tenaga kerja dalam mematuhi standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) hingga kurangnya ketersediaan tenaga ahli muda yang ada di lapangan. Sebab berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), banyaknya tenaga kerja ahli konstruksi per tahun 2023 berdasarkan kualifikasi hanya terdiri dari 53,36 muda, 68,65 madya, dan 9,31 utama dari total 131,32. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan K3 sebagai prinsip dan hak dasar di tempat kerja. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk lebih memperhatikan K3 sebagai prinsip dan hak dasar di tempat kerja (occupational safety and health as fundamental principles and right at work). "Kondisi kerja yang selamat dan sehat adalah fundamental bagi pekerjaan yang layak (decent work)".
Aturan di Inggris mengamanatkan bahwa setiap temporary works (bangunan sementara) harus direncanakan, dipasang, dan dipelihara agar dapat menahan beban yang dikenakan padanya dan hanya dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal. Di Inggris, 45 dari 135 pekerja konstruksi tewas akibat fatal injuries dan 29,62% akibat jatuh dari ketinggian yang berhubungan dengan perancah (scaffolding) sebagaimana pada data di bawah ini:

Temporary works seperti perancah, penggalian, cofferdam dan caisson harus diperiksa secara berkala oleh orang yang berkompeten. Tidak ada persyaratan hukum khusus mengenai bagaimana pekerjaan sementara harus dikelola; setiap organisasi dapat memilih bagaimana mereka mengatur dan mengelola keselamatan di lokasi.
Desain dan pelaksanaan temporary works yang benar merupakan elemen penting dalam pencegahan dan mitigasi risiko dalam konstruksi. BS 5975: 2019 memberikan rekomendasi dan panduan mengenai pengendalian prosedural yang akan diterapkan pada semua aspek pekerjaan sementara di industri konstruksi dan pada desain, spesifikasi, konstruksi, penggunaan dan pembongkaran temporary works.
Sebagian besar perkembangan desain pekerjaan sementara terjadi di Inggris ketika Jembatan Barton, Jembatan Lodden pada tahun 1960an dan 1970an runtuh selama konstruksi dan pemerintah tergerak untuk menentukan apakah Inggris berada dalam kondisi yang sehat untuk mengelola bengunan sementara. Kegagalan besar yang berkait dengan temporary works di Inggris hampir menghilang sejak BS 5975 diterbitkan pada tahun 1982. Di Inggris, desain tiang penyangga sementara biasanya sesuai dengan ketentuan persyaratan BS 5975 kecuali penggunaan Eurocode 12811 dan EN 12812 ditetapkan sebagai persyaratan kontrak.
Temporary Works Forum (TWf) dibentuk pada tahun 2009 di Inggris sebagai lembaga independen dan nirlaba perusahaan yang beroperasi pada basis biaya terbatas. Panduan dan perangkat yang berguna serta dokumen panduan dihasilkan oleh TWf yang membahas masalah pekerjaan sementara dan penerapan Eurocodes untuk konstruksi yang lebih aman di Inggris. Prinsip-prinsip perangkat alat yang dihasilkan oleh TWf ini dapat diterapkan di seluruh dunia.
ILO mengemukakan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sangat bervariasi tergantung pada kondisi di setiap negara, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan sosial. Terutama di negara-negara berkembang, angka kematian dan cedera akibat kecelakaan kerja cenderung tinggi. Namun, ada beberapa negara industri yang berhasil menurunkan angka cedera serius yang mencerminkan keberhasilan dari upaya-upaya perbaikan dalam hal K3, seperti Negara Inggris atau United Kingdom (UK).
ILO menekankan pentingnya menerapkan budaya K3 sebagai strategi global untuk pengelolaan K3 di seluruh dunia. Dalam makalah yang berjudul "Creating A Safety Culture" yang disusun oleh Jane Ardern, disebutkan bahwa ada tiga faktor utama yang membentuk budaya K3, yaitu sikap, lingkungan, dan sistem. Faktor-faktor ini menjadi landasan penting dalam membangun kesadaran akan pentingnya K3 di tempat kerja serta mendorong implementasi praktik-praktik yang aman dan bertanggung jawab.
Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi di Indonesia bersifat mandatory yang telah diatur dalam kebijakan pemerintah, yakni Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) dalam Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2012 dalam rangka mengendalikan risiko keselamatan konstruksi dengan elemen yang mesti diterapkan: Komitmen dan Kebijakan, Perencanaan, dan Penerapan.
Di Indonesia, terdapat beragam peraturan yang saling melengkapi satu sama lain dalam menciptakan ekosistem keselamatan kerja yang holistik. Dimulai dari Pengaturan Keselamatan Kerja di Bidang Konstruksi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Berbagai aturan tersebut melibatkan banyak elemen untuk bisa menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat. Seperti halnya pelaksanaan Konstruksi Berkelanjutan yang merupakan prinsip fundamental dalam membangun bangunan gedung dan/atau bangunan sipil yang mematuhi prinsip berkelanjutan, siklus hidup, dan sumber daya dengan tiga pilar utama: 1) Secara ekonomi layak dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jasa konstruksi; 2) Menjaga pelestarian lingkungan; dan 3) Mengurangi disparitas sosial masyarakat jasa konstruksi. Dengan adanya prinsip Konstruksi Berkelanjutan, penyelenggara jasa usaha tentunya memiliki kewajiban untuk membangun suatu bangunan dengan basis standar yang solid dan prinsip ini diimplementasikan melalui: 1) Perencanaan umum; 2) Pemrograman; 3) Pelaksanaan konsultasi konstruksi; dan 4) Pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa yang bersangkutan juga wajib melaksanakan Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (“SMKK”) untuk memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang berlaku dengan memastikan keselamatan aspek-aspek tertentu dimulai dari aspek keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan publik, hingga keselamatan lingkungan.
Dalam hal perlindungan pekerja/buruh khususnya mereka yang bekerja di ruang terbatas dari potensi bahaya, Indonesia juga telah mengatur hal tersebut melalui Peraturan No. 11 tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas (“Permenaker 11/2023”). Ruang terbatas sendiri didefinisikan lokasi yang meliputi: 1) Tangki dan/atau bejana, pesawat uap, dapur/tungku, silo, dan cerobong; 2) Jaringan perpipaan, terowongan, dan konstruksi bawah tanah lainnya yang serupa; 3) Sumur atau lubang yang memiliki bukaan di bagian atasnya dengan kedalaman melebihi 1,5 meter; dan/atau 4) Ruang lain yang dikategorikan sebagai ruang terbatas oleh Pelaku Usaha.
Untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerja, persyaratan K3 untuk ruang terbatas diterapkan berdasarkan enam bidang berikut: 1) Penetapan klasifikasi; 2) Pembatasan akses terhadap ruang terbatas; 3) Izin masuk; 4) Prosedur kerja aman; 5) Peralatan dan perlengkapan; dan 6) Personel K3. Dari upaya tersebut, diharapkan adanya ketentuan protektif bagi para pekerja agar dapat mengetahui tanda-tanda dan/atau limitasi dalam ruang bekerja untuk mencegah kemungkinan terburuk yakni kecelakaan saat bekerja.
Berkaca pada negara Inggris, hadirnya The Building Safety Act 2022 menjadi bentuk respons nyata terhadap tragedi Grenfell Tower tahun 2017 yang mana bertujuan dari untuk meningkatkan desain, konstruksi, dan manajemen gedung-gedung berisiko tinggi. Namun, hal yang menarik dari Inggris bahwa mereka juga menekankan pentingnya kesehatan mental untuk dimasukkan ke dalam bagian dari sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di jasa konstruksi. Health and Safety Executive (HSE) yang merupakan badan publik Inggris yang bertanggung jawab atas dorongan, regulasi, dan penegakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan di tempat kerja menetapkan ketegasan untuk mengurangi penyakit terkait kerja, dengan fokus khusus pada kesehatan mental dan stres. Hal ini dijadikan sebagai pusat strategi sejak 2022-2023 di Inggris dan pengusaha memiliki kewajiban terhadap karyawan dan pekerja lainnya (termasuk kontraktor) untuk memastikan, kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja berdasarkan Health and Safety at Work etc. Act 1974. Hal tersebut tentunya dilandasi dengan statistik mengenai risiko kesehatan mental di tempat kerja dan dampaknya terhadap produktivitas pekerja yang dalam pencapaian tujuan perusahaan.
Dari perspektif sosial dan kesejahteraan, K3 di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan para pekerja serta masyarakat secara keseluruhan. Poin tersebut antara lain berpengaruh pada perlindungan terhadap tenaga kerja yang tercantum pada Undang-Undang No 14 tahun 1969. Lingkungan kerja yang aman dan sehat berkontribusi pada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan mengurangi risiko kecelakaan dapat berdampak positif pada pengurangan beban kesehatan dan kesejahteraan. Selain itu, peningkatan kualitas hidup berpengaruh pada kesejahteraan individu di tingkat mikro dan berdampak signifikan pada ekonomi masyarakat.
Peran Sertifikasi Tenaga Kerja terhadap Kesejahteraan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mewajibkan setiap tenaga kerja konstruksi memiliki sertifikat kompetensi kerja. Para pengguna jasa dan/atau penyedia jasa juga wajib mempekerjakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat mendapatkan manfaat diantaranya jaminan kejelasan besaran imbalan/gaji sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah dan memberikan perlindungan hukum pada profesi. Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar para pekerja tidak lantas puas setelah mendapatkan sertifikat.
Isu terkait SMK3 juga ditemukan bahwa hal yang menimbulkan potensi kecelakaan kerja bukan hanya semata-mata berasal dari kurang efektifnya sistem atau aturan yang diberlakukan, melainkan kesadaran dari pekerja itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan program tersebut yakni dari sisi pekerja dikarenakan kurangnya kesadaran dari masing-masing pekerja tersebut yang lebih mengutamakan kebutuhan pokok dibandingkan keselamatan saat bekerja. Hal ini dapat dibuktikan dari penelitian ini bahwa para pekerja lebih mementingkan bonus atau insentif sebagai output bekerja dan adanya rasa ketidaknyaman dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (“APD”) pada saat bekerja.
Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek konstruksi. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 di kalangan pekerja, menyediakan pelatihan yang memadai, serta memastikan ketersediaan peralatan keselamatan yang lengkap dan berkualitas adalah langkah-langkah yang tidak bisa ditawar lagi. Dengan demikian, diharapkan tingkat kecelakaan kerja dapat diminimalisir dan kesejahteraan pekerja dapat terjaga, sehingga produktivitas dan kualitas pekerjaan dapat meningkat secara signifikan. Terms like “sustainability” and “corporate social responsibility” are not new for now. They have been present for over two decades. Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan saja, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang harus didukung oleh semua pihak terkait.
Referensi:
1. ISO Standards: ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, ISO 37001:20162. Kemnaker. Profil K3 Nasional 2022.
3. Health and Safety Executive. UK Health and Safety Statistics - Fatal injuries in Great Britain.
4. The Law Society. Building Safety Act 2022 and residential conveyancing.
5. Osborne Clarke. Health and Safety Executive spotlights mental health risks to GB workforce.
6. Saragi, T. E., & Sinaga, R. E. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek pembangunan rumah susun lanjutan Provinsi Sumatera Utara I Medan.
(abd)