Merancang Hukum Penghinaan
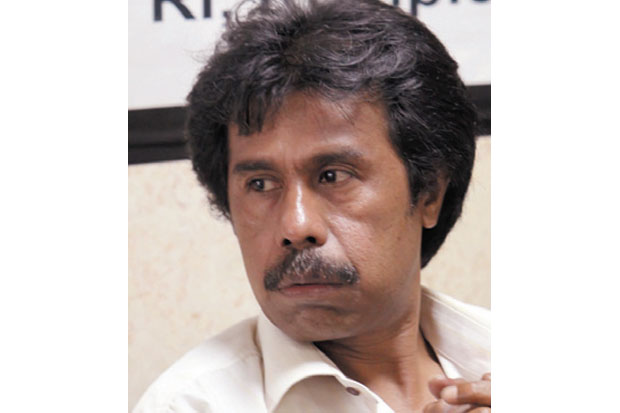
Merancang Hukum Penghinaan
A
A
A
Margarito Kamis
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
DPR baru saja mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, perubahan ini menyisakan soal. Secepat kilat, soal itu menjadi panorama sosio-politico legal bermakna jamak. Polemik atas perubahan UU tersebut muncul akibat ada keraguan terhadap pembentuknya. Masalah tabiat politik, kompetensi teknis, kompetensi kognitif interes pembentuknya menjadi kata yang berserakan di mana-mana setiap kali soal ini diperbincangkan.
Polemik itu tampak beralasan karena sebelumnya panorama sosio-politico legal telah lebih dulu tersentak dengan gagasan penghinaan terhadap presiden. Gagasan ini termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Walau diperlukan, rumus tentang penghinaan yang sedang dirancang itu mengandung bahaya. Kata-katanya tak memiliki batas, tak bertepi, dan amat jauh dari kelayakan teknis hukum. Pemaknaan epistemologis dan ontologis atas konsep presiden yang dirangkai dengan kata penghinaan menjadi menghina presiden, terlepas dari kata presiden ditulis dengan huruf kapital atau biasa, juga tetap bermasalah.
Beradab
Menghiasi panorama sosio-politico legal dengan ragam kalimat, betapa hukum memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan politis, tanpa memperlihatkan abstraksi filosofis atas konsep-konsep di dalamnya, tak bermakna apa pun, selain sekadar menyatakannya. Ini laksana butiran hujan membasahi pasir. Dimensi itu, terutama filosofis dan sosiologis, mengharuskan pembentuk hukum menenggelamkan diri ke dalam khasanah asal-usul, pertumbuhan, dan penerimaan sukarela atas hal yang diatur itu, sebagai hal logis secara alamiah, bukan artifisial.
Manusia secara alamiah terkodratkan sebagai makhluk mulia, sama dan sederajat sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wata’ala, harus diterima apa adanya. Titik. Kategori-kategori manusia sebagaimana dipraktikkan Romawi kuno dikenal dengan patriarch dan plebs atau di Prancis sebelum revolusi berdarahnya 1789, bangsawan, pemuka agama, dan orang kebanyakan, three general estate, menurut Andrew Hussey, dalam kenyataannya memuakkan. Muak karena konsep-konsep itu membelakangi, mengingkari, mencampakkan esensi kodrati manusia.
Pesona kemuliaan dan kesamaan derajat secara alamiah itu demikian menawan. Pesona itu meluluhlantakkan eksistensi kekaisaran, kerajaan, dan akhirnya menghasilkan republik. Raja berganti raja dan kaisar berganti kaisar yang menahbiskan sendiri diri mereka sebagai orang istimewa di antara orang kebanyakan, yang satu dan lainnya dalam masyarakat itu tidak setara, akhirnya tenggelam.
Republik pun muncul dan mekar sebagai sebuah konsep pemerintahan. Setelah mengubur premis ketidaksamaan derajat, menggantikannya dengan kesamaan derajat, republik kala itu meniscayakan pemimpin, konsul tidak lagi istimewa, tidak lagi berada di atas hukum, dan harus dipilih. Masa jabatannya, dalam istilah konstitusionalisme modern, kala itu juga dibatasi. Keistimewaan kaisar dan raja pun akhirnya sirna bersamaan dengan kenaikan sinar kesamaan derajat ke langit republik.
Louise XVI di Prancis yang menitahkan dirinya adalah negara, sekaligus sebagai wakil Tuhan di muka bumi, setelah jauh sebelumnya konsep republik menggema dan memukau kaum plebs di Romawi kuno, terbukti tak lebih tangguh dari debu. Usaha itu patah, hancur, menghilang di Prancis setelah perlawanan berdarah, revolusi kaum ketiga –rakyat jelata- di Prancis 1789, yang mengimpikan republik. Roberspier, pemimpin kasta ketiga sesudah revolusi itu, yang mengonsolidasi tatanan kesetaraan, dengan membunuh ribuan orang, berakhir malang dan menyedihkan.
Republik menyinari nalarnya dengan hanya manusia, bukan lembaga hasil kreasi manusia, yang memiliki kemuliaan. Manusialah yang mulia secara kodrati. Kemuliaan kodrati itulah dasar keadilan republik. Hanya manusialah yang memiliki atribut rasa, moral, harga diri, dan lainnya sebagai sesuatu yang immanent, dalam kadar kodrat sebagai manusia.
Di titik inilah gagasan penghinaan yang hendak diatur dalam KUHP baru menemukan nalar filosofisnya. Hinaan jelas memukul esensi kodrati manusia. Tak boleh ditoleransi. Mengaturnya dalam hukum karena hukum dalam sifatnya sedari mula didedikasikan kepada manusia untuk memastikan kodratnya sebagai manusia terjaga tak bisa tak melarang penghinaan. Hukum karena itu pula sama sekali tidak bisa dirancang berdasarkan gagasan utilitarian Jeremy Bentham. Ini lantaran kegunaan dalam gagasan Jeremy Bentham menyemburkan nalar penyingkiran; menyingkirkan satu kelompok demi menghidupi kelompok lain. Itu tak beradab.
Harus Jelas
Raja, konsul, begitu sejarahnya, sama dengan kaisar, senatum, perdana menteri, juga presiden tak memiliki sifat kodrati. Semuanya adalah hasil kreasi manusia. Khusus konsep presiden sebagai jabatan, setidaknya sebagai institusi, bukan sebagai orang, terlihat pada gagasan sejumlah peserta pembahasan konstitusi Amerika, yang dikutip Carol Berkin. Mereka antara lain William Pierce, James Wilson, dan Edmund Randolph. William Pierce dari Connecticut misalnya menyatakan, executive was “nothing more than an institution for carrying the will of the legislature in to effect.”
Presiden jelas adalah nama jabatan, nama lembaga, bukan orang, apalagi nama orang. Jabatan dan lembaga apa pun namanya tak punya rasa, moralitas, dan harga diri. Semua atribut terakhir ini milik manusia, pemangku jabatan itu, yang pada waktunya akan berlalu meninggalkan jabatan itu. Di titik inilah terlihat kerancuan nalar rancangan pasal “penghinaan presiden” dan “dewan.” Nalar rancangan ini adalah personalisasi jabatan dengan pemangku jabatan, orang. Memersonalisasi jabatan dengan pemangku jabatan sungguh terlalu dekat dengan tabiat feodalisme abad kegelapan.
Mempertahankan makna literal “penghinaan” dalam rancangan KUHP sekarang sama dengan memberi senjata terkokang kepada pemangku jabatan atau fungsionaris lembaga menembak sesuka-sukanya siapa pun yang membicarakan, mendiskusikan inkompetensi lembaga itu. Perkaranya bukan tak bisa melarang dan memidana orang “menghina”, tetapi “apa itu penghinaan.” Memastikan ketepatan makna “penghinaan” adalah hal imperatif yang dinantikan, sangat, oleh ilmu perancang undang-undang.
Ketepatan makna literal bernilai sebagai “depersonalisasi norma.” Depersonalisasi norma dalam ilmu hukum merupakan cara objektifikasi norma; semua orang memiliki patokan yang sama dalam mengenali, mendefinisikan dan menafsir norma itu. Praktis objektifikasi norma berfungsi sebagai benteng tafsir sewenang-wenang, sesuai selera. Ini imperatif sifatnya.
Cara itu membantu kebebasan berbicara berada dalam track peradaban. Sejenak saja sekalipun, kebebasan berbicara tak terlintas dalam jagat republik sebagai moralitas yang membenarkan penghinaan kepada sesama umat manusia. Tidak. Republik dan demokrasi berkilau karena kehebatannya menempatkan harkat dan martabat manusia di jantungnya. Menghina orang dalam republik sama nilainya dengan merendahkan dirinya sendiri, melumpuhkan demokrasi, sekaligus menghadirkan moralitas anarki. Ini busuk sebusuk hukum digunakan sesuai selera.
John Peter Zenger, penerbit surat kabar New York pada 1734, mencetak artikel yang mengecam sangat keras pemerintah kerajaan dikoloni, Amerika, dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, dengan enteng, tulis John W John, Zenger membela diri. Zenger di pengadilan itu mengatakan ia punya hak menerbitkan kritik terhadap pejabat publik, bahkan kritik yang dianggap pejabat tersebut sebagai cemoohan, sepanjang kritik itu benar. Argumen ini diterima juri, dan Zenger dibebaskan. Sesudah merdeka, James Thomson Callender, seorang wartawan dituduh melanggar Sedition Act 1789. Callender menyebarkan pamflet yang berisi tulisan John Adams sebagai pria tua bangka dan di tangannya berlumuran darah. Ia dihukum. Tetapi, kelak dibebaskan Thomas Jefferson, presiden sesudah John Adam, pada 1801.
Merancang hukum yang buruk, karena kata-katanya elastis, bermakna ganda, tak berpijak pada penalaran yang logis, tak tersemangati nilai-nilai intrinsik kemanusiaan, tak mencakup konsekuensi-konsekuensi tak dikehendaki - unintended consequences- sama buruknya dengan menegakkan hukum sesuai selera. Membentengi kemanusiaan dengan hukum yang literalnya elastis sama dengan mencampakkan kemanusiaan. Laranglah penghinaan, tetapi definisikan dan rumuskan sejelas-jelasnya jenis kata dan tindakan yang tercakup dalam konsep penghinaan itu. Semoga.
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate
DPR baru saja mengesahkan perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Namun, perubahan ini menyisakan soal. Secepat kilat, soal itu menjadi panorama sosio-politico legal bermakna jamak. Polemik atas perubahan UU tersebut muncul akibat ada keraguan terhadap pembentuknya. Masalah tabiat politik, kompetensi teknis, kompetensi kognitif interes pembentuknya menjadi kata yang berserakan di mana-mana setiap kali soal ini diperbincangkan.
Polemik itu tampak beralasan karena sebelumnya panorama sosio-politico legal telah lebih dulu tersentak dengan gagasan penghinaan terhadap presiden. Gagasan ini termuat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Walau diperlukan, rumus tentang penghinaan yang sedang dirancang itu mengandung bahaya. Kata-katanya tak memiliki batas, tak bertepi, dan amat jauh dari kelayakan teknis hukum. Pemaknaan epistemologis dan ontologis atas konsep presiden yang dirangkai dengan kata penghinaan menjadi menghina presiden, terlepas dari kata presiden ditulis dengan huruf kapital atau biasa, juga tetap bermasalah.
Beradab
Menghiasi panorama sosio-politico legal dengan ragam kalimat, betapa hukum memiliki dimensi filosofis, yuridis, dan politis, tanpa memperlihatkan abstraksi filosofis atas konsep-konsep di dalamnya, tak bermakna apa pun, selain sekadar menyatakannya. Ini laksana butiran hujan membasahi pasir. Dimensi itu, terutama filosofis dan sosiologis, mengharuskan pembentuk hukum menenggelamkan diri ke dalam khasanah asal-usul, pertumbuhan, dan penerimaan sukarela atas hal yang diatur itu, sebagai hal logis secara alamiah, bukan artifisial.
Manusia secara alamiah terkodratkan sebagai makhluk mulia, sama dan sederajat sebagai ciptaan Allah Subhanahu Wata’ala, harus diterima apa adanya. Titik. Kategori-kategori manusia sebagaimana dipraktikkan Romawi kuno dikenal dengan patriarch dan plebs atau di Prancis sebelum revolusi berdarahnya 1789, bangsawan, pemuka agama, dan orang kebanyakan, three general estate, menurut Andrew Hussey, dalam kenyataannya memuakkan. Muak karena konsep-konsep itu membelakangi, mengingkari, mencampakkan esensi kodrati manusia.
Pesona kemuliaan dan kesamaan derajat secara alamiah itu demikian menawan. Pesona itu meluluhlantakkan eksistensi kekaisaran, kerajaan, dan akhirnya menghasilkan republik. Raja berganti raja dan kaisar berganti kaisar yang menahbiskan sendiri diri mereka sebagai orang istimewa di antara orang kebanyakan, yang satu dan lainnya dalam masyarakat itu tidak setara, akhirnya tenggelam.
Republik pun muncul dan mekar sebagai sebuah konsep pemerintahan. Setelah mengubur premis ketidaksamaan derajat, menggantikannya dengan kesamaan derajat, republik kala itu meniscayakan pemimpin, konsul tidak lagi istimewa, tidak lagi berada di atas hukum, dan harus dipilih. Masa jabatannya, dalam istilah konstitusionalisme modern, kala itu juga dibatasi. Keistimewaan kaisar dan raja pun akhirnya sirna bersamaan dengan kenaikan sinar kesamaan derajat ke langit republik.
Louise XVI di Prancis yang menitahkan dirinya adalah negara, sekaligus sebagai wakil Tuhan di muka bumi, setelah jauh sebelumnya konsep republik menggema dan memukau kaum plebs di Romawi kuno, terbukti tak lebih tangguh dari debu. Usaha itu patah, hancur, menghilang di Prancis setelah perlawanan berdarah, revolusi kaum ketiga –rakyat jelata- di Prancis 1789, yang mengimpikan republik. Roberspier, pemimpin kasta ketiga sesudah revolusi itu, yang mengonsolidasi tatanan kesetaraan, dengan membunuh ribuan orang, berakhir malang dan menyedihkan.
Republik menyinari nalarnya dengan hanya manusia, bukan lembaga hasil kreasi manusia, yang memiliki kemuliaan. Manusialah yang mulia secara kodrati. Kemuliaan kodrati itulah dasar keadilan republik. Hanya manusialah yang memiliki atribut rasa, moral, harga diri, dan lainnya sebagai sesuatu yang immanent, dalam kadar kodrat sebagai manusia.
Di titik inilah gagasan penghinaan yang hendak diatur dalam KUHP baru menemukan nalar filosofisnya. Hinaan jelas memukul esensi kodrati manusia. Tak boleh ditoleransi. Mengaturnya dalam hukum karena hukum dalam sifatnya sedari mula didedikasikan kepada manusia untuk memastikan kodratnya sebagai manusia terjaga tak bisa tak melarang penghinaan. Hukum karena itu pula sama sekali tidak bisa dirancang berdasarkan gagasan utilitarian Jeremy Bentham. Ini lantaran kegunaan dalam gagasan Jeremy Bentham menyemburkan nalar penyingkiran; menyingkirkan satu kelompok demi menghidupi kelompok lain. Itu tak beradab.
Harus Jelas
Raja, konsul, begitu sejarahnya, sama dengan kaisar, senatum, perdana menteri, juga presiden tak memiliki sifat kodrati. Semuanya adalah hasil kreasi manusia. Khusus konsep presiden sebagai jabatan, setidaknya sebagai institusi, bukan sebagai orang, terlihat pada gagasan sejumlah peserta pembahasan konstitusi Amerika, yang dikutip Carol Berkin. Mereka antara lain William Pierce, James Wilson, dan Edmund Randolph. William Pierce dari Connecticut misalnya menyatakan, executive was “nothing more than an institution for carrying the will of the legislature in to effect.”
Presiden jelas adalah nama jabatan, nama lembaga, bukan orang, apalagi nama orang. Jabatan dan lembaga apa pun namanya tak punya rasa, moralitas, dan harga diri. Semua atribut terakhir ini milik manusia, pemangku jabatan itu, yang pada waktunya akan berlalu meninggalkan jabatan itu. Di titik inilah terlihat kerancuan nalar rancangan pasal “penghinaan presiden” dan “dewan.” Nalar rancangan ini adalah personalisasi jabatan dengan pemangku jabatan, orang. Memersonalisasi jabatan dengan pemangku jabatan sungguh terlalu dekat dengan tabiat feodalisme abad kegelapan.
Mempertahankan makna literal “penghinaan” dalam rancangan KUHP sekarang sama dengan memberi senjata terkokang kepada pemangku jabatan atau fungsionaris lembaga menembak sesuka-sukanya siapa pun yang membicarakan, mendiskusikan inkompetensi lembaga itu. Perkaranya bukan tak bisa melarang dan memidana orang “menghina”, tetapi “apa itu penghinaan.” Memastikan ketepatan makna “penghinaan” adalah hal imperatif yang dinantikan, sangat, oleh ilmu perancang undang-undang.
Ketepatan makna literal bernilai sebagai “depersonalisasi norma.” Depersonalisasi norma dalam ilmu hukum merupakan cara objektifikasi norma; semua orang memiliki patokan yang sama dalam mengenali, mendefinisikan dan menafsir norma itu. Praktis objektifikasi norma berfungsi sebagai benteng tafsir sewenang-wenang, sesuai selera. Ini imperatif sifatnya.
Cara itu membantu kebebasan berbicara berada dalam track peradaban. Sejenak saja sekalipun, kebebasan berbicara tak terlintas dalam jagat republik sebagai moralitas yang membenarkan penghinaan kepada sesama umat manusia. Tidak. Republik dan demokrasi berkilau karena kehebatannya menempatkan harkat dan martabat manusia di jantungnya. Menghina orang dalam republik sama nilainya dengan merendahkan dirinya sendiri, melumpuhkan demokrasi, sekaligus menghadirkan moralitas anarki. Ini busuk sebusuk hukum digunakan sesuai selera.
John Peter Zenger, penerbit surat kabar New York pada 1734, mencetak artikel yang mengecam sangat keras pemerintah kerajaan dikoloni, Amerika, dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, dengan enteng, tulis John W John, Zenger membela diri. Zenger di pengadilan itu mengatakan ia punya hak menerbitkan kritik terhadap pejabat publik, bahkan kritik yang dianggap pejabat tersebut sebagai cemoohan, sepanjang kritik itu benar. Argumen ini diterima juri, dan Zenger dibebaskan. Sesudah merdeka, James Thomson Callender, seorang wartawan dituduh melanggar Sedition Act 1789. Callender menyebarkan pamflet yang berisi tulisan John Adams sebagai pria tua bangka dan di tangannya berlumuran darah. Ia dihukum. Tetapi, kelak dibebaskan Thomas Jefferson, presiden sesudah John Adam, pada 1801.
Merancang hukum yang buruk, karena kata-katanya elastis, bermakna ganda, tak berpijak pada penalaran yang logis, tak tersemangati nilai-nilai intrinsik kemanusiaan, tak mencakup konsekuensi-konsekuensi tak dikehendaki - unintended consequences- sama buruknya dengan menegakkan hukum sesuai selera. Membentengi kemanusiaan dengan hukum yang literalnya elastis sama dengan mencampakkan kemanusiaan. Laranglah penghinaan, tetapi definisikan dan rumuskan sejelas-jelasnya jenis kata dan tindakan yang tercakup dalam konsep penghinaan itu. Semoga.
(pur)














