Urgensitas Mewujudkan Asuransi Bencana
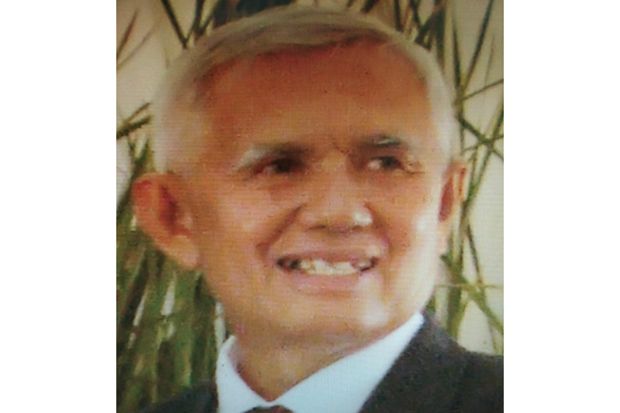
Urgensitas Mewujudkan Asuransi Bencana
A
A
A
Abraham Fanggidae
Mantan PNS Kementerian Sosial
DUNIA bisnis perasuransian di Indonesia kini mendapat sorotan negatif sebagian publik dikarenakan sengkarut dua perusahaan asuransi "pelat merah". Kerugian berinvestasi diperkirakan mencapai belasan triliunan rupiah baik pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asabri (Persero). Perlu penanganan cepat agar permasalahan pada dua perusahaan asuransi pelat merah tersebut terselesaikan. Solusi cepat diperlukan lantaran bisnis asuransi dibutuhkan, terutama untuk pembiayaan kerugian pemerintah, swasta, dan warga yang merupakan penyintas bencana alam.
Tanpa asuransi bencana, beban yang dipikul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) teramat berat, mengingat dampak bencana alam sering meluluhlantakkan sarana dan prasarana publik yang nilai rupiahnya pada umumnya tinggi/mahal. Lembaga swasta, juga mayoritas warga penyintas, pun menderita kerugian material akibat bencana alam.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konser amal dari puluhan musisi Maluku untuk Maluku bertajuk "Hela Basudara: Baku Bantu Untuk Maluku" di MBLOC, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019) memaparkan bahwa pemerintah memberi alokasi APBN untuk membantu bencana dengan cara membuat skema asuransi. Artinya, di semua daerah di Indonesia dibuat skema pooling risiko sehingga apabila ada bencana di satu tempat bisa langsung memicu penggunaan dananya.
Sebagai contoh, sekitar 2013 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menyiapkan polis dengan uang pertanggungan sebesar Rp10 triliun dengan premi tahunan sebesar Rp500 miliar. Logika mengatakan, bencana alam berimbas pada risiko fiskal, maka asuransi bencana merupakan solusi terbaik. Apalagi, pembiayaan menanggulangi bencana pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dana sangat besar. Sumber utama pendanaan untuk dua kegiatan penting dalam manajemen bencana adalah APBN dengan dua konsekuensi saling mengait.
Pertama , membiayai rehabilitasi dan konstruksi dengan keuangan negara memberatkan APBN. Kedua , APBN yang terbatas akan tertekan sehingga pembiayaan tersendat, rehabilitasi dan rekonstruksi dipastikan terhambat. Metode "klasik" ini masih berlangsung hingga detik ini. Operasional penanggulangan bencana dari pemerintah masih berkutat kuat pada metode di atas.
Sebagai contoh gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat pada 2009. Sumatera Barat memerlukan dana Rp6,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, alokasi pembiayaan pemerintah sebesar Rp4 triliun selama tiga tahun. Dengan jumlah dana tersebut pun belum seluruh penyintas terjangkau pembiayaan.
Indonesia negeri "berbakat" bencana alam. BNPB menampilkan Peta Indeks Rawan Bencana (PIRB). Data PIRB menyatakan, 175 kabupaten merupakan daerah rawan bencana tinggi, 150 kabupaten masuk kategori rawan bencana sedang, dan 95 kabupaten dikualifikasi merupakan daerah rawan bencana rendah. Dari PIRB, telah teridentifikasi dan dipetakan 150 kabupaten merupakan daerah rawan tsunami.Peta dan data penting kebencanaan seperti ini menjadi indikasi yang membawa konsekuensi, memudahkan mengetahui wilayah rawan bencana, tapi dengan konsekuensi keharusan pemerintah, lembaga swasta, dan warga menyiapkan budget penanggulangan yang siap digunakan kapan pun apabila bencana mengguncangkan wilayah tertentu.
Keterbatasan APBN
Membiayai penanggulangan bencana terbesar hanya bersumber dari APBN. Bantuan luar negeri tak bisa dipungkiri memang ada. Tapi, apakah negara harus bergantung pada bantuan negara sahabat sebagai pendonor untuk menanggulangi bencana? Padahal, negara harus hadir untuk melayani publik melalui fasilitas publik yang tersedia. Pelayanan publik tidak boleh terganggu dengan alasan sarana dan prasarana untuk itu masih rusak atau hancur.
Pun kegiatan dari berbagai lembaga swasta, warga/perorangan sebagai penyintas bencana harus terus berlangsung. Mau tidak mau dua segmen dalam masyarakat ini pun harus merogoh kantong, mengeluarkan biaya ekstra lembaga/organisasi. Konsekuensinya, bagi lembaga swasta mungkin berbentuk mencari utang, pengetatan anggaran, pemutusan hubungan kerja. Sedangkan bagi penyintas atau warga untuk memperbaiki rumah rusak, maka harus menarik tabungan, bahkan berutang.
Bencana bisa memiskinkan warga bukan isapan jempol, tapi keniscayaan. Warga sedikit tertolong jika memperoleh bantuan dana pemerintah untuk rehabilitasi rumah. Tapi, harus diingat, dan biasa dalam praktik, santunan uang pemerintah bagi penyintas perorangan/pribadi/masyarakat sekadar meringankan lembaga dan warga penyintas. Indeks bantuan pun biasanya "pukul rata", tidak berdasarkan kalkulasi riil. Semua itu, sekali lagi, keterbatasan kemampuan pemerintah.
Sudah saatnya pemerintah mereduksi pembiayaan penanggulangan bencana melalui APBN juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Asuransi bencana merupakan alternatif terbaik. Kanada, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara maju di Eropa Barat menggunakan asuransi bencana sebagai solusi pembiayaan penanggulangan bencana. Asuransi bencana diperlukan lantaran nilai ekonomis pembiayaan rehabilitasi dan konstruksi baru untuk fasilitas publik berbiaya tinggi.
Tahun 2018 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sebuah acara telah menyambut baik wacana asuransi bencana alam. Menurut JK, Indonesia bagaikan "supermarket " bencana. Semua jenis bencana seringkali terjadi di negeri tercinta ini sehingga asuransi bencana bisa memperkecil risiko kerugian negara. Persoalannya, belum tersurat satu pun aturan hukum/legalitas hukum bagaimana aset negara yang terdampak bencana dapat diasuransikan. Tugas pemerintah dan DPR RI menghadirkan produk hukum terkait asuransi bencana.
Padahal, risiko bencana adalah bagaimana mengelola manajemen bencana dan bagaimana risiko fiskal dari bencana. Pemerintah tidak ingin penanganan bencana sebagai beban APBN. Juga tidak ingin secara terus-menerus mengharapkan bantuan luar negeri untuk penanganan/penanggulangan bencana.
Hingga kini pemerintah melalui menteri keuangan sebagai bendahara negara menyediakan dana cadangan bencana rata-rata berkisar Rp3,1 triliun hingga Rp4 triliun, bahkan lebih setiap tahun. Namun, dana triliunan seringkali kurang mencukupi. Kerugian akibat gempa dan tsunami Aceh pada 2004 mencapai Rp51,4 triliun (USD3,5 miliar). Pemerintah membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk pemulihan Aceh dan Nias seperti kondisi sebelum bencana.
Kementerian Keuangan telah berinisiatif menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dalam rangka mewujudkan bangsa dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana dan terjaminnya keberlangsungan berbagai program pembangunan. Kerangka strategi pemerintah. PARB ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terencana, tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, yang dikelola dengan transparan untuk melindungi keuangan negara.
Urgensitas pemerintah memiliki asuransi bencana tidak bisa ditawar lagi. Sebagian warga yang tinggal pada 175 kabupaten rawan bencana alam dan tsunami pada kualifikasi tinggi (data dari PIRB) mayoritas tidak mampu secara finansial. Mayoritas warga belum/tidak mampu memiliki polis asuransi bencana untuk melindungi aset/harta warga. Membayar BPJS saja, mayoritas peserta BPJS kelas III berbeban berat. Perintah konstitusi negara berkewajiban melindungi dan menyejahterakan segenap warga negara.
Mantan PNS Kementerian Sosial
DUNIA bisnis perasuransian di Indonesia kini mendapat sorotan negatif sebagian publik dikarenakan sengkarut dua perusahaan asuransi "pelat merah". Kerugian berinvestasi diperkirakan mencapai belasan triliunan rupiah baik pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) maupun PT Asabri (Persero). Perlu penanganan cepat agar permasalahan pada dua perusahaan asuransi pelat merah tersebut terselesaikan. Solusi cepat diperlukan lantaran bisnis asuransi dibutuhkan, terutama untuk pembiayaan kerugian pemerintah, swasta, dan warga yang merupakan penyintas bencana alam.
Tanpa asuransi bencana, beban yang dipikul Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) teramat berat, mengingat dampak bencana alam sering meluluhlantakkan sarana dan prasarana publik yang nilai rupiahnya pada umumnya tinggi/mahal. Lembaga swasta, juga mayoritas warga penyintas, pun menderita kerugian material akibat bencana alam.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada konser amal dari puluhan musisi Maluku untuk Maluku bertajuk "Hela Basudara: Baku Bantu Untuk Maluku" di MBLOC, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2019) memaparkan bahwa pemerintah memberi alokasi APBN untuk membantu bencana dengan cara membuat skema asuransi. Artinya, di semua daerah di Indonesia dibuat skema pooling risiko sehingga apabila ada bencana di satu tempat bisa langsung memicu penggunaan dananya.
Sebagai contoh, sekitar 2013 Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pernah menyiapkan polis dengan uang pertanggungan sebesar Rp10 triliun dengan premi tahunan sebesar Rp500 miliar. Logika mengatakan, bencana alam berimbas pada risiko fiskal, maka asuransi bencana merupakan solusi terbaik. Apalagi, pembiayaan menanggulangi bencana pada tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi memerlukan dana sangat besar. Sumber utama pendanaan untuk dua kegiatan penting dalam manajemen bencana adalah APBN dengan dua konsekuensi saling mengait.
Pertama , membiayai rehabilitasi dan konstruksi dengan keuangan negara memberatkan APBN. Kedua , APBN yang terbatas akan tertekan sehingga pembiayaan tersendat, rehabilitasi dan rekonstruksi dipastikan terhambat. Metode "klasik" ini masih berlangsung hingga detik ini. Operasional penanggulangan bencana dari pemerintah masih berkutat kuat pada metode di atas.
Sebagai contoh gempa bumi dan tsunami di Sumatera Barat pada 2009. Sumatera Barat memerlukan dana Rp6,4 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, alokasi pembiayaan pemerintah sebesar Rp4 triliun selama tiga tahun. Dengan jumlah dana tersebut pun belum seluruh penyintas terjangkau pembiayaan.
Indonesia negeri "berbakat" bencana alam. BNPB menampilkan Peta Indeks Rawan Bencana (PIRB). Data PIRB menyatakan, 175 kabupaten merupakan daerah rawan bencana tinggi, 150 kabupaten masuk kategori rawan bencana sedang, dan 95 kabupaten dikualifikasi merupakan daerah rawan bencana rendah. Dari PIRB, telah teridentifikasi dan dipetakan 150 kabupaten merupakan daerah rawan tsunami.Peta dan data penting kebencanaan seperti ini menjadi indikasi yang membawa konsekuensi, memudahkan mengetahui wilayah rawan bencana, tapi dengan konsekuensi keharusan pemerintah, lembaga swasta, dan warga menyiapkan budget penanggulangan yang siap digunakan kapan pun apabila bencana mengguncangkan wilayah tertentu.
Keterbatasan APBN
Membiayai penanggulangan bencana terbesar hanya bersumber dari APBN. Bantuan luar negeri tak bisa dipungkiri memang ada. Tapi, apakah negara harus bergantung pada bantuan negara sahabat sebagai pendonor untuk menanggulangi bencana? Padahal, negara harus hadir untuk melayani publik melalui fasilitas publik yang tersedia. Pelayanan publik tidak boleh terganggu dengan alasan sarana dan prasarana untuk itu masih rusak atau hancur.
Pun kegiatan dari berbagai lembaga swasta, warga/perorangan sebagai penyintas bencana harus terus berlangsung. Mau tidak mau dua segmen dalam masyarakat ini pun harus merogoh kantong, mengeluarkan biaya ekstra lembaga/organisasi. Konsekuensinya, bagi lembaga swasta mungkin berbentuk mencari utang, pengetatan anggaran, pemutusan hubungan kerja. Sedangkan bagi penyintas atau warga untuk memperbaiki rumah rusak, maka harus menarik tabungan, bahkan berutang.
Bencana bisa memiskinkan warga bukan isapan jempol, tapi keniscayaan. Warga sedikit tertolong jika memperoleh bantuan dana pemerintah untuk rehabilitasi rumah. Tapi, harus diingat, dan biasa dalam praktik, santunan uang pemerintah bagi penyintas perorangan/pribadi/masyarakat sekadar meringankan lembaga dan warga penyintas. Indeks bantuan pun biasanya "pukul rata", tidak berdasarkan kalkulasi riil. Semua itu, sekali lagi, keterbatasan kemampuan pemerintah.
Sudah saatnya pemerintah mereduksi pembiayaan penanggulangan bencana melalui APBN juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Asuransi bencana merupakan alternatif terbaik. Kanada, Jepang, Amerika Serikat, dan sejumlah negara maju di Eropa Barat menggunakan asuransi bencana sebagai solusi pembiayaan penanggulangan bencana. Asuransi bencana diperlukan lantaran nilai ekonomis pembiayaan rehabilitasi dan konstruksi baru untuk fasilitas publik berbiaya tinggi.
Tahun 2018 Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam sebuah acara telah menyambut baik wacana asuransi bencana alam. Menurut JK, Indonesia bagaikan "supermarket " bencana. Semua jenis bencana seringkali terjadi di negeri tercinta ini sehingga asuransi bencana bisa memperkecil risiko kerugian negara. Persoalannya, belum tersurat satu pun aturan hukum/legalitas hukum bagaimana aset negara yang terdampak bencana dapat diasuransikan. Tugas pemerintah dan DPR RI menghadirkan produk hukum terkait asuransi bencana.
Padahal, risiko bencana adalah bagaimana mengelola manajemen bencana dan bagaimana risiko fiskal dari bencana. Pemerintah tidak ingin penanganan bencana sebagai beban APBN. Juga tidak ingin secara terus-menerus mengharapkan bantuan luar negeri untuk penanganan/penanggulangan bencana.
Hingga kini pemerintah melalui menteri keuangan sebagai bendahara negara menyediakan dana cadangan bencana rata-rata berkisar Rp3,1 triliun hingga Rp4 triliun, bahkan lebih setiap tahun. Namun, dana triliunan seringkali kurang mencukupi. Kerugian akibat gempa dan tsunami Aceh pada 2004 mencapai Rp51,4 triliun (USD3,5 miliar). Pemerintah membutuhkan waktu lebih dari lima tahun untuk pemulihan Aceh dan Nias seperti kondisi sebelum bencana.
Kementerian Keuangan telah berinisiatif menyusun Strategi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB) atau Disaster Risk Financing and Insurance (DRFI) dalam rangka mewujudkan bangsa dan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana dan terjaminnya keberlangsungan berbagai program pembangunan. Kerangka strategi pemerintah. PARB ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan yang besar, terencana, tepat waktu dan sasaran, berkelanjutan, yang dikelola dengan transparan untuk melindungi keuangan negara.
Urgensitas pemerintah memiliki asuransi bencana tidak bisa ditawar lagi. Sebagian warga yang tinggal pada 175 kabupaten rawan bencana alam dan tsunami pada kualifikasi tinggi (data dari PIRB) mayoritas tidak mampu secara finansial. Mayoritas warga belum/tidak mampu memiliki polis asuransi bencana untuk melindungi aset/harta warga. Membayar BPJS saja, mayoritas peserta BPJS kelas III berbeban berat. Perintah konstitusi negara berkewajiban melindungi dan menyejahterakan segenap warga negara.
(pur)














