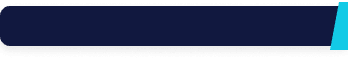Quo Vadis RKUHP Indonesia

Quo Vadis RKUHP Indonesia
A
A
A
Hariman Satria Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari
HARAPAN bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh anggota DPR RI periode 2014-2019, menguap begitu saja setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar membatalkan pembahasan tingkat akhir di DPR. Sikap Presiden Jokowi yang demikian, tersulut oleh tekanan publik yang beranggapan, bahwa terdapat sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Kini nasib RKUHP berada di tangan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Saya berpandangan bahwa, beberapa pasal yang dianggap bermasalah mesti dikaji dan dianalisis kembali termasuk memperbaiki redaksinya. Mesti dilakukan pula penjaringan pendapat dengan beberapa kelompok masyarakat sipil. Selain itu, mesti menggelar pula diskusi dengan beberapa lembaga negara sebagai pengguna RKUHP, misalnya KPK, BNN, BNPT dan Komnas HAM. Harapannya bisa menghasilkan rumusan KUHP yang jelas, kompak dan terpadu. Frasa quo vadis berasal dari bahasa latin yang berarti "mau dibawa ke mana", sehingga arti harfiah tulisan ini adalah mau dibawa kemana RKUHP?
Dua Buku
Sejak UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan, tidak terasa negeri ini telah menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI) produk kolonial Belanda—sekitar 73 tahun. Sebagai negara yang berdaulat, ini bisa dikatakan sebagai ironi, sebab hukum pidana kita belum benar-benar merdeka. Masih dipengaruhi oleh norma, doktrin dan asas hukum pidana Belanda.
Dalam KUHP terdiri atas tiga buku: Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Sedangkan dalam RKUHP hanya mengenal dua buku yakni Buku I tentang Asas-Asas Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Mengapa hanya menggunakan dua buku?
Menurut sejarahnya, ketika pertama kali RKUHP di rumuskan, Prof J.E. Sahetapy ditugaskan oleh Prof Sudarto (Penyusun pertama kali RKUHP), untuk berangkat ke Belanda guna berkonsultasi dengan Nico Keijzer (Hoge Raad Belanda) dan Schaffmeister, seorang pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Leiden. Ketika itu, yang menjadi fokus pembahasan adalah sistematika RKUHP Indonesia.
Sahetapy menyampaikan, bahwa RKUHP Indonesia nantinya terdiri atas dua buku yakni asas-asas umum pada buku I dan tindak pidana pada buku II. Konsep ini ditentang oleh Keijzer dan Schaffmeister sebab di Belanda saja, masih menggunakan tiga buku sebagaimana halnya KUHP Indonesia. Singkatnya, perdebatan tersebut, "dimenangkan" oleh Sahetapy. Sehingga RKUHP Indonesia sejak saat itu hanya terdiri atas dua buku hingga saat ini.
Mengenai kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, sesungguhnya memang kurang relevan. Apalagi tidak ada definisi dan kriteria yang jelas dan konsisten yang bersifat kualitatif untuk dapat membedakan keduanya. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, tidak jarang tindak pidana administratif yang sebenarnya merupakan pelanggaran, justru dipidana berat sebagaimana halnya kejahatan, seperti ketentuan dalam tindak pidana lingkungan hidup.
Pada saat ini, ada pergeseran paradigma pembentuk undang-undang ketika melihat kejahatan dan pelanggaran. Misalnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalamnya mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian pelanggaran berat HAM. Disini terlihat jelas, istilah kejahatan bercampur aduk dengan pelanggaran, kemudian pelanggaran malah disebut sebagai kejahatan. Maka wajar adanya, jika dalam RKUHP sebagai ius constituendum tidak mengenal lagi pembedaan kejahatan dan pelanggaran. Pada titik inilah saya sependapat dengan penyusun RKUHP yang hanya mengenal dua buku.
Mengurai Beberapa Masalah
Di tengah khalayak, beredar belasan pasal yang dianggap kontroversial dan dikhawatirkan dapat menimbulkan overcriminalization. Bertalian dengan itu, saya akan mengomentari tiga pasal yakni terkait dengan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, mengenai gelandangan , serta pengaturan delik korupsi.
Mengenai delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden. Pada awalnya diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP. Pasal-pasal a quo secara teori sering disebut sebagai haatzai artikelen atau pasal penebar kebencian. Menurut sejarahnya, pasal-pasal a quo dirumuskan oleh pemerintah kolonial Belanda guna melindungi kehormatan dan martabat Ratu Belanda dari rongrongan dan penghinaan oleh sejumlah orang di negara jajahan atau dalam negara Belanda. Meskipun demikian, Pasal 134, 136 bis dan Pasal 137 KUHP tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 013-002/PUU-IV/2006.
Apabila diperhatikan, ada perbedaan corak delik antara Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang telah dibatalkan oleh MK dengan Pasal 238 jo 239 RKUHP. Perbedaan elementernya adalah jika dalam KUHP dikualifikasi sebagai delik biasa maka dalam RKUHP diidentifikasi sebagai delik aduan. Artinya, pelaku hanya dapat diproses jika presiden/wakil presiden atau kuasanya mengadu secara resmi kepada aparat penegak hukum. Meskipun begitu, pelaku tidak dapat dipidana jika yang dinyatakan atau disebarnya depan umum merupakan suatu kebenaran, pembelaan diri atau demi kepentingan umum.
Selain itu, secara politis-sosiologis harus dakui bahwa pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden sesungguhnya sangat penting bertalian dengan wibawa dan martabat pemerintah. Presiden dan wakil presiden adalah simbol negara sehingga rasanya kurang logis jika tidak ada pengaturan yang bertujuan melindungi harkat dan martabatnya. Atas dasar itulah, di negara lain pun diatur pula hal yang sama.
Kemudian mengenai gelandangan dalam Pasal 432 RKUHP. Ketentuan semacam ini sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 505 KUHP. Pendeknya, ketentuan mengenai gelandangan bukanlah hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Saya termasuk yang berpendapat bahwa pengaturan gelandangan dalam RKUHP jauh lebih halus dan jelas ketimbang rumusan dalam KUHP. Misalnya menyangkut strafsoort (jenis pidana). RKUHP menggunakan pidana denda sehingga menjadi lebih manusiawi ketimbang pidana badan seperti dalam KUHP. Hakim bahkan bisa memberi sanksi tindakan berupa pelatihan kerja [Pasal 114 ayat (1) huruf a RKUHP]. Hal ini menjadi penegasan bahwa pemidanaan dalam RKUHP tidak bertujuan merendahkan martabat manusia [Pasal 58 ayat (2) RKUHP].
Isu terkahir yang ingin saya ulas adalah delik korupsi dalam RKUHP. Mengenai hal ini dapat ditemui pada Pasal 653-656 di bawah Bab XXXVII dengan judul tindak pidana khusus. Jan Remmelink (2003:47) menyatakan, untuk menafsirkan suatu peraturan ada postulat yang berbunyi rubrica est lex atau bagian peraturan yang menentukan. Delik korupsi berada di bawah bab delik khusus sehingga ia merupakan lex specilalis dari peraturan umum.
Masalahnya adalah di saat bersamaan ada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU anti korupsi). Peraturan ini adalah ketentuan khusus dari KUHP. Artinya, jika nanti RKUHP disahkan, akan ada dua aturan khusus tentang korupsi. Peraturan mana yang akan diberlakukan?
Dalam Pasal 14 UU anti korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, jika nanti RKUHP disahkan maka mengenai tindak pidana korupsi masih diberlakukan UU anti korupsi.
Hal ini sejalan dengan prinsip lex specilis sistematis artinya pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Prinsip hukum ini memperkokoh keberadaan UU anti korupsi yang telah ada sebelum RKUHP.
Hal yang menarik adalah mengenai perbedaan ancaman pidana. Misalnya, korupsi yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam UU anti korupsi diancam pidana penjara minimal 4 tahun sedangkan dalam RKUHP, minimal 2 tahun. Hakim bisa saja memilih RKUHP dengan alasan merujuk pada asas lex favor reo artinya jika ada perubahan undang-undang maka dikenakan peraturan yang paling meringkan bagi terdakwa.
Akhirnya mesti dikatakan bahwa agar tidak multitafsir, ada baiknya dalam RKUHP ditetapkan suatu klausul pasal yang menekankan bahwa terhadap tindak pidana korupsi maka diberlakukan UU anti korupsi kecuali perbuatan dan ancaman pidananya sama dengan RKUHP maka hakim dapat memilih salah satunya. Ketentuan ini menjadi sabuk pengaman ketika nanti RKUHP diberlakukan.
HARAPAN bahwa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akan disahkan oleh anggota DPR RI periode 2014-2019, menguap begitu saja setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar membatalkan pembahasan tingkat akhir di DPR. Sikap Presiden Jokowi yang demikian, tersulut oleh tekanan publik yang beranggapan, bahwa terdapat sejumlah pasal kontroversial dalam RKUHP yang berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari. Kini nasib RKUHP berada di tangan anggota DPR RI periode 2019-2024.
Saya berpandangan bahwa, beberapa pasal yang dianggap bermasalah mesti dikaji dan dianalisis kembali termasuk memperbaiki redaksinya. Mesti dilakukan pula penjaringan pendapat dengan beberapa kelompok masyarakat sipil. Selain itu, mesti menggelar pula diskusi dengan beberapa lembaga negara sebagai pengguna RKUHP, misalnya KPK, BNN, BNPT dan Komnas HAM. Harapannya bisa menghasilkan rumusan KUHP yang jelas, kompak dan terpadu. Frasa quo vadis berasal dari bahasa latin yang berarti "mau dibawa ke mana", sehingga arti harfiah tulisan ini adalah mau dibawa kemana RKUHP?
Dua Buku
Sejak UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) diberlakukan, tidak terasa negeri ini telah menggunakan Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie (WvSNI) produk kolonial Belanda—sekitar 73 tahun. Sebagai negara yang berdaulat, ini bisa dikatakan sebagai ironi, sebab hukum pidana kita belum benar-benar merdeka. Masih dipengaruhi oleh norma, doktrin dan asas hukum pidana Belanda.
Dalam KUHP terdiri atas tiga buku: Buku I tentang Ketentuan Umum, Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran. Sedangkan dalam RKUHP hanya mengenal dua buku yakni Buku I tentang Asas-Asas Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Mengapa hanya menggunakan dua buku?
Menurut sejarahnya, ketika pertama kali RKUHP di rumuskan, Prof J.E. Sahetapy ditugaskan oleh Prof Sudarto (Penyusun pertama kali RKUHP), untuk berangkat ke Belanda guna berkonsultasi dengan Nico Keijzer (Hoge Raad Belanda) dan Schaffmeister, seorang pakar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Leiden. Ketika itu, yang menjadi fokus pembahasan adalah sistematika RKUHP Indonesia.
Sahetapy menyampaikan, bahwa RKUHP Indonesia nantinya terdiri atas dua buku yakni asas-asas umum pada buku I dan tindak pidana pada buku II. Konsep ini ditentang oleh Keijzer dan Schaffmeister sebab di Belanda saja, masih menggunakan tiga buku sebagaimana halnya KUHP Indonesia. Singkatnya, perdebatan tersebut, "dimenangkan" oleh Sahetapy. Sehingga RKUHP Indonesia sejak saat itu hanya terdiri atas dua buku hingga saat ini.
Mengenai kejahatan dan pelanggaran dalam KUHP, sesungguhnya memang kurang relevan. Apalagi tidak ada definisi dan kriteria yang jelas dan konsisten yang bersifat kualitatif untuk dapat membedakan keduanya. Dalam perundang-undangan di luar KUHP, tidak jarang tindak pidana administratif yang sebenarnya merupakan pelanggaran, justru dipidana berat sebagaimana halnya kejahatan, seperti ketentuan dalam tindak pidana lingkungan hidup.
Pada saat ini, ada pergeseran paradigma pembentuk undang-undang ketika melihat kejahatan dan pelanggaran. Misalnya UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Di dalamnya mengatur kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai bagian pelanggaran berat HAM. Disini terlihat jelas, istilah kejahatan bercampur aduk dengan pelanggaran, kemudian pelanggaran malah disebut sebagai kejahatan. Maka wajar adanya, jika dalam RKUHP sebagai ius constituendum tidak mengenal lagi pembedaan kejahatan dan pelanggaran. Pada titik inilah saya sependapat dengan penyusun RKUHP yang hanya mengenal dua buku.
Mengurai Beberapa Masalah
Di tengah khalayak, beredar belasan pasal yang dianggap kontroversial dan dikhawatirkan dapat menimbulkan overcriminalization. Bertalian dengan itu, saya akan mengomentari tiga pasal yakni terkait dengan penghinaan terhadap presiden/wakil presiden, mengenai gelandangan , serta pengaturan delik korupsi.
Mengenai delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden. Pada awalnya diatur dalam Pasal 134, Pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP. Pasal-pasal a quo secara teori sering disebut sebagai haatzai artikelen atau pasal penebar kebencian. Menurut sejarahnya, pasal-pasal a quo dirumuskan oleh pemerintah kolonial Belanda guna melindungi kehormatan dan martabat Ratu Belanda dari rongrongan dan penghinaan oleh sejumlah orang di negara jajahan atau dalam negara Belanda. Meskipun demikian, Pasal 134, 136 bis dan Pasal 137 KUHP tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan Nomor 013-002/PUU-IV/2006.
Apabila diperhatikan, ada perbedaan corak delik antara Pasal 134, 136 bis, dan Pasal 137 KUHP yang telah dibatalkan oleh MK dengan Pasal 238 jo 239 RKUHP. Perbedaan elementernya adalah jika dalam KUHP dikualifikasi sebagai delik biasa maka dalam RKUHP diidentifikasi sebagai delik aduan. Artinya, pelaku hanya dapat diproses jika presiden/wakil presiden atau kuasanya mengadu secara resmi kepada aparat penegak hukum. Meskipun begitu, pelaku tidak dapat dipidana jika yang dinyatakan atau disebarnya depan umum merupakan suatu kebenaran, pembelaan diri atau demi kepentingan umum.
Selain itu, secara politis-sosiologis harus dakui bahwa pasal penghinaan terhadap presiden/wakil presiden sesungguhnya sangat penting bertalian dengan wibawa dan martabat pemerintah. Presiden dan wakil presiden adalah simbol negara sehingga rasanya kurang logis jika tidak ada pengaturan yang bertujuan melindungi harkat dan martabatnya. Atas dasar itulah, di negara lain pun diatur pula hal yang sama.
Kemudian mengenai gelandangan dalam Pasal 432 RKUHP. Ketentuan semacam ini sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 505 KUHP. Pendeknya, ketentuan mengenai gelandangan bukanlah hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Saya termasuk yang berpendapat bahwa pengaturan gelandangan dalam RKUHP jauh lebih halus dan jelas ketimbang rumusan dalam KUHP. Misalnya menyangkut strafsoort (jenis pidana). RKUHP menggunakan pidana denda sehingga menjadi lebih manusiawi ketimbang pidana badan seperti dalam KUHP. Hakim bahkan bisa memberi sanksi tindakan berupa pelatihan kerja [Pasal 114 ayat (1) huruf a RKUHP]. Hal ini menjadi penegasan bahwa pemidanaan dalam RKUHP tidak bertujuan merendahkan martabat manusia [Pasal 58 ayat (2) RKUHP].
Isu terkahir yang ingin saya ulas adalah delik korupsi dalam RKUHP. Mengenai hal ini dapat ditemui pada Pasal 653-656 di bawah Bab XXXVII dengan judul tindak pidana khusus. Jan Remmelink (2003:47) menyatakan, untuk menafsirkan suatu peraturan ada postulat yang berbunyi rubrica est lex atau bagian peraturan yang menentukan. Delik korupsi berada di bawah bab delik khusus sehingga ia merupakan lex specilalis dari peraturan umum.
Masalahnya adalah di saat bersamaan ada UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU anti korupsi). Peraturan ini adalah ketentuan khusus dari KUHP. Artinya, jika nanti RKUHP disahkan, akan ada dua aturan khusus tentang korupsi. Peraturan mana yang akan diberlakukan?
Dalam Pasal 14 UU anti korupsi disebutkan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Dengan demikian, jika nanti RKUHP disahkan maka mengenai tindak pidana korupsi masih diberlakukan UU anti korupsi.
Hal ini sejalan dengan prinsip lex specilis sistematis artinya pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu yang bersifat khusus atau ia akan bersifat khusus dari khusus yang telah ada. Prinsip hukum ini memperkokoh keberadaan UU anti korupsi yang telah ada sebelum RKUHP.
Hal yang menarik adalah mengenai perbedaan ancaman pidana. Misalnya, korupsi yang dilakukan secara melawan hukum. Dalam UU anti korupsi diancam pidana penjara minimal 4 tahun sedangkan dalam RKUHP, minimal 2 tahun. Hakim bisa saja memilih RKUHP dengan alasan merujuk pada asas lex favor reo artinya jika ada perubahan undang-undang maka dikenakan peraturan yang paling meringkan bagi terdakwa.
Akhirnya mesti dikatakan bahwa agar tidak multitafsir, ada baiknya dalam RKUHP ditetapkan suatu klausul pasal yang menekankan bahwa terhadap tindak pidana korupsi maka diberlakukan UU anti korupsi kecuali perbuatan dan ancaman pidananya sama dengan RKUHP maka hakim dapat memilih salah satunya. Ketentuan ini menjadi sabuk pengaman ketika nanti RKUHP diberlakukan.
(kri)