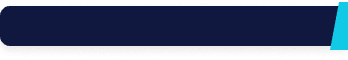Melanjutkan Poros Maritim Dunia

Melanjutkan Poros Maritim Dunia
A
A
A
Muhamad Karim
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim,
Dosen Universitas Trilogi Jakarta
LAPORAN OECD 2016 memproyeksikan bahwa ekonomi maritim dunia akan berkembang dua kali lipat (USD 3 triliun) pada 2030. Proyeksi ini menggembirakan bagi bangsa Indonesia untuk memosisikannya sebagai penghela perekonomian nasional. Tahun 2010 saja kontribusinya terhadap ekonomi dunia sebesar USD1,5 triliun.
Secara ekonomi politik, Indonesia sejak 2014 telah mendeklarasikan dirinya sebagai poros maritim dunia (PMD). Agendanya: (i) revitalisasi budaya maritim Indonesia; (ii) menjaga sumber daya laut dan kedaulatan pangan laut yang memosisikan nelayan sebagai pilar utamanya; (iii) pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim lewat tol laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (iv) diplomasi maritim terkait penanganan pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; dan (v) pembangunan kekuatan maritim untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.
Namun, pascaempat tahun PMD, hasilnya terkesan jalan di tempat. Meskipun dunia internasional mengapresiasi Indonesia dalam soal kemaritiman khususnya pemberantasan kejahatan perikanan. Selain itu, Indonesia pada 2018 didapuk sebagai tuan rumah konferensi kelautan dunia di Bali. Topik yang dibahas: perlindungan kawasan perlindungan laut, perubahan iklim, perikanan berkelanjutan, pencemaran laut, ekonomi biru berkelanjutan, dan keamanan maritim. Sayangnya, satu agenda luput dalam perhelatan tersebut, yaitu soal nelayan. Apalagi dikaitkan dengan soal PMD, Indonesia belum berhasil memosisikan kemaritiman sebagai kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi sekaligus pusat gravitasi ekonomi maritim dunia.
Gravitasi Ekonomi Maritim
Memosisikan Indonesia sebagai PMD sejatinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun Indonesia posisi geografinya strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sayangnya, Indonesia dengan PMD-nya belum mampu mendayagunakan secara optimal posisi geopolitik dan geoekonomi yang strategis tersebut.
Pertama, Indonesia memiliki jalur pelayaran internasional yang diakui dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982), yaitu alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. Jalur ALKI I melewati Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Jalur ALKI II melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur ALKI III melewati Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Keberadaan ALKI secara geopolitik bernilai vital karena menghubungkan jalur pelayaran internasional yang melayani Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, hingga Timur Tengah, yang juga beririsan dengan jalur sutra maritimnya Tiongkok.
Kedua, Indonesia belum menjadi pusat gravitasi ekonomi maritim dunia yang dibangun berbasiskan kekuatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, termasuk artifisial (digitalisasi). Jika melongok di abad 15–18, Nusantara menjadi pusat gravitasi ekonomi maritim dunia karena adanya perebutan sumber daya rempah-rempah. Kuat pengaruh gravitasi ekonomi itu karena pesatnya aktivitas pelayaran, kepelabuhanan, serta kota-kota pantai menjadi pusat perdagangan internasional maupun interseluler yang dukung sumber daya rempah-rempah dan perkebunan.
Pertanyaannya, apakah “basis kekuataan sumber daya alam” yang mendukung PMD hingga dapat memosisikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi maritim dunia? Apakah masih rempah-rempah ataukah komoditas pertanian, perkebunan, dan pertambangan lepas pantai?
Ketiga, PMD belum mampu mendayagunakan potensi ekonomi selat strategis yang menjadi jalur pelayaran internasional yang juga masuk jalur ALKI. Selat Malaka, Selat Makassar, dan Selat Lombok merupakan jalur pelayaran internasional yang dilewati kapal tonase besar setiap harinya. Halim (2014) mengutip Cleary dan Chuan (2000) mencatat bahwa diperkirakan (i) 200 kapal per hari dan 150 tanker setiap melayari perairan Selat Malaka; (ii) sekitar 72% kapal tanker dunia melayari Selat Malaka, sedangkan Selat Makasar dan Selat Lombok hanya 28%; dan (3) setiap tahunnya perputaran uang dari bisnis pelayaran di selat mencapai USD84–250 miliar.
Setiap tahun jumlah kapal yang melayari selat ini mencapai 60.000 unit mengangkut beragam kargo berupa minyak mentah hingga produk jadi dari seluruh dunia. Angkanya tiga kali lipat ketimbang jumlah kapal yang melayari Terusan Panama dan dua kali di Terusan Suez. Begitu vital dan strategisnya posisi Selat Malaka hingga negara-negara besar semacam Amerika Serikat, Jepang, India, dan China mengalokasikan anggaran kekuatan militer untuk melindungi kepentingan ekonominya.
IHS Jane's Defence (2013) mencatat Amerika Serikat mengalokasikan USD656,21 miliar, China USD126,29 miliar, Jepang USD65,67 miliar, dan India USD44,55 miliar pada 2012 (baca: Halim). Bedanya dengan China, ia lewat jalur sutra maritimnya yang melewati Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa. China mengalokasikan anggaran infrastruktur hingga USD8 triliun. Sekarang saja, Tiongkok mulai membangun terusan Kra di Thailand yang menghubungkan Laut Andaman dan Laut China Selatan yang secara geoekonomi dan geopolitik makin menguatkan hegemoninya di kawasan Asia Tenggara.
Keempat, mendayagunakan ekonomi teluk. Teluk merupakan suatu kawasan perairan semi-tertutup yang menjorok ke daratan dan menjadi pusat perkembangan kota-kota pantai dan kepelabuhanan dengan beragam aktivitas. Contohnya, Teluk Jakarta, Teluk Balikpapan, Teluk Tomini, Teluk Cendrawasih, Teluk Ambon, Teluk Semangka, Teluk Bayur, dan Teluk Palu. Selama ini Indonesia belum mendayagunakan secara optimal potensi ekonomi teluk sebagai pusat gravitasi ekonomi maritim berbasis wilayah (kabupaten/kota maupun provinsi).
Agenda ke Depan
Jika membaca ulang agenda PMD tahun 2014, terdapat beberapa isu pokok kurang optimal dalam pengembangannya, yaitu budaya maritim, keselamatan pelayaran, dan nasib nelayan. Kurun waktu 2014–2018 kerap kali terjadi kecelakaan pelayaran, pengembangan budaya maritim lewat pendidikan masih relatif kurang, soal kesejahteraan nelayan, hingga pencemaran plastik.
Membaca visi-misi pasangan calon presiden 2019–2024, ada kesan mereduksi visi PMD. Karena itu, penulis mengusulkan, pertama, melanjutkan visi PMD dan mempertajam program aksinya sehingga Indonesia bisa berkontribusi bagi ekonomi maritim hingga tahun 2030. Indonesia mesti mampu mendayagunakan dan mengapitalisiasi potensi ekonomi ALKI, selat, dan teluk untuk mewujudkan gravitasi ekonomi maritim berbasis sumber daya alam.
Kedua, menginternalisasikan budaya maritim dalam sistem pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nanti manusia Indonesia mampu mentranformasikan nilai-nilai, budaya, dan paradigma kemaritiman dalam politik, kepemimpinan, dan budaya kerja. Pasalnya, ciri khas budaya maritim ialah terbuka, outward looking, social enterpreneurship, berani mengambil risiko, dan menghargai kemajemukan.
Ketiga, membangun institusi pendidikan berbasis kemaritiman setidaknya di tiga wilayah yang berada di ALKI, selat strategis, dan teluk. Umpamanya, di Sulawesi Utara atau Maluku yang dekat dengan ALKI III serta Teluk Tomini dan Teluk Ambon.
Keempat, mengalokasikan politik anggaran kemaritiman berbasiskan daerah kepulauan dan pesisir dengan program pembangunan jelas dan terukur, terutama di wilayah jalur ALKI, selat strategis, dan teluk dengan kekhasannya.
Kelima, menambah dan memperbaiki tata kelola armada pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat (PELRA) agar menjangkau dan melayari wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil, sungai, dan danau. Tujuannya agar distribusi barang, jasa, dan mobilitas manusia lebih lancar serta terjamin keselamatannya. Sebagai negara kepulauan, pengembangan transportasi laut jadi prasyarat utama.
Keenam, pemerintah mesti memberlakukan disinsetif bagi pencemar di laut dari bahan plastik. Selain itu, pemerintah juga mendorong lembaga riset nasional dan universitas untuk mengembangkan teknologi bioremediasi penghancur sampah plastik. Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang telah menemukan bakteri penghasil enzim yang menghancurkan dan mencerna plastik jenis polyethylene terephthalate (PET) seperti botol plastik.
Ketujuh, memperkuat sistem keamanan dan pertahanan nasional di wilayah laut berbasiskan AKLI, selat, dan teluk strategis, untuk mendukung stabilisasi berkembangnya gravitasi ekonomi maritim. Ketujuh agenda di ataslah mesti dilakukan untuk melanjutkan visi PMD. Semoga!
Direktur Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim,
Dosen Universitas Trilogi Jakarta
LAPORAN OECD 2016 memproyeksikan bahwa ekonomi maritim dunia akan berkembang dua kali lipat (USD 3 triliun) pada 2030. Proyeksi ini menggembirakan bagi bangsa Indonesia untuk memosisikannya sebagai penghela perekonomian nasional. Tahun 2010 saja kontribusinya terhadap ekonomi dunia sebesar USD1,5 triliun.
Secara ekonomi politik, Indonesia sejak 2014 telah mendeklarasikan dirinya sebagai poros maritim dunia (PMD). Agendanya: (i) revitalisasi budaya maritim Indonesia; (ii) menjaga sumber daya laut dan kedaulatan pangan laut yang memosisikan nelayan sebagai pilar utamanya; (iii) pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim lewat tol laut, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim; (iv) diplomasi maritim terkait penanganan pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut; dan (v) pembangunan kekuatan maritim untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran.
Namun, pascaempat tahun PMD, hasilnya terkesan jalan di tempat. Meskipun dunia internasional mengapresiasi Indonesia dalam soal kemaritiman khususnya pemberantasan kejahatan perikanan. Selain itu, Indonesia pada 2018 didapuk sebagai tuan rumah konferensi kelautan dunia di Bali. Topik yang dibahas: perlindungan kawasan perlindungan laut, perubahan iklim, perikanan berkelanjutan, pencemaran laut, ekonomi biru berkelanjutan, dan keamanan maritim. Sayangnya, satu agenda luput dalam perhelatan tersebut, yaitu soal nelayan. Apalagi dikaitkan dengan soal PMD, Indonesia belum berhasil memosisikan kemaritiman sebagai kekuatan baru dalam pembangunan ekonomi sekaligus pusat gravitasi ekonomi maritim dunia.
Gravitasi Ekonomi Maritim
Memosisikan Indonesia sebagai PMD sejatinya tak semudah membalikkan telapak tangan. Meskipun Indonesia posisi geografinya strategis yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sayangnya, Indonesia dengan PMD-nya belum mampu mendayagunakan secara optimal posisi geopolitik dan geoekonomi yang strategis tersebut.
Pertama, Indonesia memiliki jalur pelayaran internasional yang diakui dalam hukum laut internasional (UNCLOS 1982), yaitu alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III. Jalur ALKI I melewati Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda. Jalur ALKI II melewati Laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores, dan Selat Lombok. Jalur ALKI III melewati Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, dan Laut Sawu. Keberadaan ALKI secara geopolitik bernilai vital karena menghubungkan jalur pelayaran internasional yang melayani Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika, hingga Timur Tengah, yang juga beririsan dengan jalur sutra maritimnya Tiongkok.
Kedua, Indonesia belum menjadi pusat gravitasi ekonomi maritim dunia yang dibangun berbasiskan kekuatan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), ilmu pengetahuan dan teknologi tinggi, termasuk artifisial (digitalisasi). Jika melongok di abad 15–18, Nusantara menjadi pusat gravitasi ekonomi maritim dunia karena adanya perebutan sumber daya rempah-rempah. Kuat pengaruh gravitasi ekonomi itu karena pesatnya aktivitas pelayaran, kepelabuhanan, serta kota-kota pantai menjadi pusat perdagangan internasional maupun interseluler yang dukung sumber daya rempah-rempah dan perkebunan.
Pertanyaannya, apakah “basis kekuataan sumber daya alam” yang mendukung PMD hingga dapat memosisikan Indonesia sebagai pusat gravitasi ekonomi maritim dunia? Apakah masih rempah-rempah ataukah komoditas pertanian, perkebunan, dan pertambangan lepas pantai?
Ketiga, PMD belum mampu mendayagunakan potensi ekonomi selat strategis yang menjadi jalur pelayaran internasional yang juga masuk jalur ALKI. Selat Malaka, Selat Makassar, dan Selat Lombok merupakan jalur pelayaran internasional yang dilewati kapal tonase besar setiap harinya. Halim (2014) mengutip Cleary dan Chuan (2000) mencatat bahwa diperkirakan (i) 200 kapal per hari dan 150 tanker setiap melayari perairan Selat Malaka; (ii) sekitar 72% kapal tanker dunia melayari Selat Malaka, sedangkan Selat Makasar dan Selat Lombok hanya 28%; dan (3) setiap tahunnya perputaran uang dari bisnis pelayaran di selat mencapai USD84–250 miliar.
Setiap tahun jumlah kapal yang melayari selat ini mencapai 60.000 unit mengangkut beragam kargo berupa minyak mentah hingga produk jadi dari seluruh dunia. Angkanya tiga kali lipat ketimbang jumlah kapal yang melayari Terusan Panama dan dua kali di Terusan Suez. Begitu vital dan strategisnya posisi Selat Malaka hingga negara-negara besar semacam Amerika Serikat, Jepang, India, dan China mengalokasikan anggaran kekuatan militer untuk melindungi kepentingan ekonominya.
IHS Jane's Defence (2013) mencatat Amerika Serikat mengalokasikan USD656,21 miliar, China USD126,29 miliar, Jepang USD65,67 miliar, dan India USD44,55 miliar pada 2012 (baca: Halim). Bedanya dengan China, ia lewat jalur sutra maritimnya yang melewati Asia Tenggara, Afrika, Timur Tengah, hingga Eropa. China mengalokasikan anggaran infrastruktur hingga USD8 triliun. Sekarang saja, Tiongkok mulai membangun terusan Kra di Thailand yang menghubungkan Laut Andaman dan Laut China Selatan yang secara geoekonomi dan geopolitik makin menguatkan hegemoninya di kawasan Asia Tenggara.
Keempat, mendayagunakan ekonomi teluk. Teluk merupakan suatu kawasan perairan semi-tertutup yang menjorok ke daratan dan menjadi pusat perkembangan kota-kota pantai dan kepelabuhanan dengan beragam aktivitas. Contohnya, Teluk Jakarta, Teluk Balikpapan, Teluk Tomini, Teluk Cendrawasih, Teluk Ambon, Teluk Semangka, Teluk Bayur, dan Teluk Palu. Selama ini Indonesia belum mendayagunakan secara optimal potensi ekonomi teluk sebagai pusat gravitasi ekonomi maritim berbasis wilayah (kabupaten/kota maupun provinsi).
Agenda ke Depan
Jika membaca ulang agenda PMD tahun 2014, terdapat beberapa isu pokok kurang optimal dalam pengembangannya, yaitu budaya maritim, keselamatan pelayaran, dan nasib nelayan. Kurun waktu 2014–2018 kerap kali terjadi kecelakaan pelayaran, pengembangan budaya maritim lewat pendidikan masih relatif kurang, soal kesejahteraan nelayan, hingga pencemaran plastik.
Membaca visi-misi pasangan calon presiden 2019–2024, ada kesan mereduksi visi PMD. Karena itu, penulis mengusulkan, pertama, melanjutkan visi PMD dan mempertajam program aksinya sehingga Indonesia bisa berkontribusi bagi ekonomi maritim hingga tahun 2030. Indonesia mesti mampu mendayagunakan dan mengapitalisiasi potensi ekonomi ALKI, selat, dan teluk untuk mewujudkan gravitasi ekonomi maritim berbasis sumber daya alam.
Kedua, menginternalisasikan budaya maritim dalam sistem pendidikan nasional mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Nanti manusia Indonesia mampu mentranformasikan nilai-nilai, budaya, dan paradigma kemaritiman dalam politik, kepemimpinan, dan budaya kerja. Pasalnya, ciri khas budaya maritim ialah terbuka, outward looking, social enterpreneurship, berani mengambil risiko, dan menghargai kemajemukan.
Ketiga, membangun institusi pendidikan berbasis kemaritiman setidaknya di tiga wilayah yang berada di ALKI, selat strategis, dan teluk. Umpamanya, di Sulawesi Utara atau Maluku yang dekat dengan ALKI III serta Teluk Tomini dan Teluk Ambon.
Keempat, mengalokasikan politik anggaran kemaritiman berbasiskan daerah kepulauan dan pesisir dengan program pembangunan jelas dan terukur, terutama di wilayah jalur ALKI, selat strategis, dan teluk dengan kekhasannya.
Kelima, menambah dan memperbaiki tata kelola armada pelayaran nasional maupun pelayaran rakyat (PELRA) agar menjangkau dan melayari wilayah perbatasan, pulau-pulau kecil, sungai, dan danau. Tujuannya agar distribusi barang, jasa, dan mobilitas manusia lebih lancar serta terjamin keselamatannya. Sebagai negara kepulauan, pengembangan transportasi laut jadi prasyarat utama.
Keenam, pemerintah mesti memberlakukan disinsetif bagi pencemar di laut dari bahan plastik. Selain itu, pemerintah juga mendorong lembaga riset nasional dan universitas untuk mengembangkan teknologi bioremediasi penghancur sampah plastik. Inggris, Amerika Serikat, dan Jepang telah menemukan bakteri penghasil enzim yang menghancurkan dan mencerna plastik jenis polyethylene terephthalate (PET) seperti botol plastik.
Ketujuh, memperkuat sistem keamanan dan pertahanan nasional di wilayah laut berbasiskan AKLI, selat, dan teluk strategis, untuk mendukung stabilisasi berkembangnya gravitasi ekonomi maritim. Ketujuh agenda di ataslah mesti dilakukan untuk melanjutkan visi PMD. Semoga!
(whb)