Ketika IAIN Masuk Politik
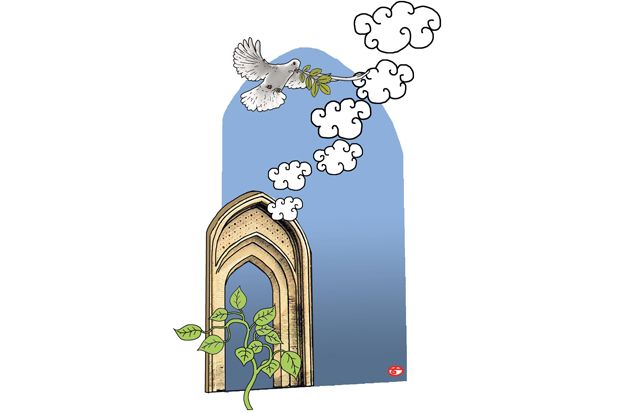
Ketika IAIN Masuk Politik
A
A
A
Akh. Muzakki
Sekretaris PW NU Jawa Timur
“MUNCUL lagi: IAIN, Ingkar Allah Ingkar Nabi!” Itulah seloroh seorang teman mengomentari fenomena terbaru dalam panggung Pilgub Jawa Timur. Tentu, nama IAIN sebenarnya adalah kependekan dari nomenklatur kelembagaan pendidikan tinggi Islam yang bernama Institut Agama Islam Negeri. Namun, nama itu ternyata kini lekat dengan fatwa politik dalam aksi dukung-mendukung paslon Pilgub.
Publik masih mengingat, makna pejoratif pernah mengemuka pada nama IAIN di awal tahun 2000-an. Lembaga pendidikan tinggi yang didirikan untuk mengemban tugas dakwah dan akademik pernah dibuat miring oleh pemaknaan negatif majalah Islam Suara Hidayatullah (edisi Agustus 2001) dan Sabili (edisi 30 Mei 2002). Kepanjangan IAIN diplesetkan menjadi Ingkar Allah Ingkar Nabi.
Internal akademisi IAIN pun terusik dengan suara nyinyir itu. Mereka justru membela diri dengan ilustrasi begini: Ittiba’ Allah Ittiba’ Nabi (artinya: Ikut Allah Ikut Nabi).Riuh sosial akademik pun tak terhindarkan. Mereka yang nyinyir terhadap lembaga IAIN menganggap lembaga pendidikan tinggi Islam itu telah kehilangan elan vitalnya sebagai lembaga dakwah akibat nalar kritis yang dikembangkan dan kemudian dianggap melintasi batas normatif agama. Mereka yang gerah dengan cap negatif itu memandang praktik nyinyir atas IAIN adalah bagian dari kepribadian yang terbelah dari praktik keberagamaan dan keilmuan Islam.
Nah, riuh soal “IAIN” pun kini mengemuka lagi. Bukan soal beda pendapat dalam mendialogkan antara nalar akademik dan nilai normatif Islam seperti terjadi pada era awal 2000-an yang lalu, melainkan akibat beda pilihan politik. Kepanjangan istilah dibuat tetap sama: Ingkar Allah Ingkar Nabi. Tapi modusnya beda.
Jika di awal abad 21 itu, pemlesetan istilah IAIN dilakukan untuk melabeli mereka yang dianggap terlalu liberal dalam paham dan praktik keagamaan, kini di musim bunga demokrasi bernama Pilgub pemlesetan itu dilakukan untuk mencap negatif mereka yang berbeda dalam aspirasi politik.
Alkisah, pada 3 Juni 2018 berkumpul sekitar 400 orang yang mengatasnamakan diri sebagai kyai. Tempatnya di sebuah pesantren di Pacet. Di momen itu, berkembang pemikiran yang lalu ditumpahkan ke dalam bentuk fatwa politik yang bernomor surat 1/SF-FA/6/2018. Bunyinya secara vulgar menyebut bahwa siapapun umat Islam yang tidak memilih pasangan calon tertentu dianggap sama dengan mengingkari Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW.
Dari sinilah muncul kembali istilah pejoratif “IAIN, Ingkar Allah Ingkar Nabi” dalam Pilgub. Sebetulnya fatwa “Ingkar Allah Ingkar Nabi” tersebut melengkapi fatwa politik sebelumnya yang menyebut fardlu ‘ain memilih paslon tertentu.
Riuh politik pun tak terhindarkan. Ruang publik dibikin haru biru oleh perdebatan sengit nan menghabiskan energi tentang fatwa politik itu. Ada yang mencoba bertahan dengan merasionalisasi fatwa politik tersebut. Ada yang menyayangkan munculnya fatwa itu. Ada pula yang mencibir mereka yang mengeluarkan fatwa itu sebagai kelompok yang secara serampangan telah melakukan politisasi agama.
Bahkan ada juga yang lebih dari itu semua: melaporkan mereka yang terlibat dalam pengeluaran fatwa politik itu ke kepolisian karena dianggap telah menebarkan kebencian dan penistaan atas paslon Pilgub tertentu akibat namanya disebut secara terang-terangan sebagai pihak yang “ditohok” dalam fatwa itu. Intinya, hiruk pikuk politik pun tak terhindarkan dengan impitan yang tampak kuat dengan urusan agama.
Pada titik ini, saya teringat dengan pengalaman saya mengajar mata kuliah Budaya dan Politik Indonesia sebagai rangkaian dari mata kuliah Indonesian Way di kampus almamater saya, Australian National University (ANU) pada 2004. Saat menjelaskan bagaimana agama di Indonesia begitu mengemuka dalam melatarbelakangi budaya politik, ada mahasiswa asli Australia yang bertanya kepada saya: “Zaki, kenapa sih di Indonesia agama begitu penting, bahkan dalam urusan politik kekuasaan pun agama dibawa-bawa?”
Mendapat pertanyaan mahasiswa saya yang kritis itu, saya bertanya balik: “Anda sendiri sebagai orang Australia bagaimana memandang agama dalam kehidupan Anda di Australia?” Jawaban mengejutkan keluar dari mahasiswa itu: “Bagi saya agama itu tidak penting. Sebab, saya ini sudah sangat bahagia hingga saat ini. Seluruh kehidupan saya sudah dijamin oleh negara. Lalu buat apa agama? Apa yang bisa diperbuat agama untuk saya?”
Saya tidak dalam kepentingan untuk membahas sekuler atau tidak jawaban mahasiswa saya yang orang Australia itu. Saya perlu melakukan refleksi atas jawaban dia tersebut untuk memahami mengapa selalu muncul gejala politisasi agama atau minimal memaksa regulasi agama masuk ke ranah politik di negeri-negeri seperti Indonesia.Dan jawaban mahasiswa saya tersebut penting untuk dijadikan sebagai pembanding semata agar agama mampu memberi manfaat besar bagi terciptanya ruang publik yang baik bagi kemaslahan bersama (common good), seperti yang dipertanyakan mahasiswa saya di atas, dan bukan keburukan bersama.
Penting dicatat, teori yang berkembang di dunia akademik internasional tidak selalu bisa dipraktikkan secara plug and play antara satu negara dengan lainnya. Selalu ada ruang yang menjadi titik pembeda akibat perbedaan basis sosiologis masyarakat.
Saat sejumlah riset menyebutkan Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, riset Saiful Mujani tentang religious democrats (2003) menjelaskan hal yang berbeda. Kearifan budaya lokal tertentu di Indonesia, seperti ritual tahlilan dan majelis taklim, membuat demokrasi dan agama memiliki nilai kompatibilitas yang cukup tinggi. Ritual-ritual itu menjadi modal sosial yang tinggi untuk memperkuat praktik-praktik partisipasi dalam demokratisasi di masyarakat.
Di tengah modal sosial dari keyakinan dan praktik agama yang tinggi di Indonesia di atas, rasanya semua, termasuk kaum agamawan, patut untuk bijak. Kepentingan penguatan partisipasi penganut agama dalam demokrasi tidak lalu direduksi sedemikian rupa hingga instrumen agama pun tercederai karenanya.
Fatwa adalah satu di antara instrumen agama yang tidak seharusnya diproduksi-diperlakukan sembarangan agar kebahagiaan hidup, seperti dalam jawaban mahasiswa saya di atas, tidak semu. Dan agama pun lalu memberi manfaat yang besar kepada ruang publik yang baik.
Sekretaris PW NU Jawa Timur
“MUNCUL lagi: IAIN, Ingkar Allah Ingkar Nabi!” Itulah seloroh seorang teman mengomentari fenomena terbaru dalam panggung Pilgub Jawa Timur. Tentu, nama IAIN sebenarnya adalah kependekan dari nomenklatur kelembagaan pendidikan tinggi Islam yang bernama Institut Agama Islam Negeri. Namun, nama itu ternyata kini lekat dengan fatwa politik dalam aksi dukung-mendukung paslon Pilgub.
Publik masih mengingat, makna pejoratif pernah mengemuka pada nama IAIN di awal tahun 2000-an. Lembaga pendidikan tinggi yang didirikan untuk mengemban tugas dakwah dan akademik pernah dibuat miring oleh pemaknaan negatif majalah Islam Suara Hidayatullah (edisi Agustus 2001) dan Sabili (edisi 30 Mei 2002). Kepanjangan IAIN diplesetkan menjadi Ingkar Allah Ingkar Nabi.
Internal akademisi IAIN pun terusik dengan suara nyinyir itu. Mereka justru membela diri dengan ilustrasi begini: Ittiba’ Allah Ittiba’ Nabi (artinya: Ikut Allah Ikut Nabi).Riuh sosial akademik pun tak terhindarkan. Mereka yang nyinyir terhadap lembaga IAIN menganggap lembaga pendidikan tinggi Islam itu telah kehilangan elan vitalnya sebagai lembaga dakwah akibat nalar kritis yang dikembangkan dan kemudian dianggap melintasi batas normatif agama. Mereka yang gerah dengan cap negatif itu memandang praktik nyinyir atas IAIN adalah bagian dari kepribadian yang terbelah dari praktik keberagamaan dan keilmuan Islam.
Nah, riuh soal “IAIN” pun kini mengemuka lagi. Bukan soal beda pendapat dalam mendialogkan antara nalar akademik dan nilai normatif Islam seperti terjadi pada era awal 2000-an yang lalu, melainkan akibat beda pilihan politik. Kepanjangan istilah dibuat tetap sama: Ingkar Allah Ingkar Nabi. Tapi modusnya beda.
Jika di awal abad 21 itu, pemlesetan istilah IAIN dilakukan untuk melabeli mereka yang dianggap terlalu liberal dalam paham dan praktik keagamaan, kini di musim bunga demokrasi bernama Pilgub pemlesetan itu dilakukan untuk mencap negatif mereka yang berbeda dalam aspirasi politik.
Alkisah, pada 3 Juni 2018 berkumpul sekitar 400 orang yang mengatasnamakan diri sebagai kyai. Tempatnya di sebuah pesantren di Pacet. Di momen itu, berkembang pemikiran yang lalu ditumpahkan ke dalam bentuk fatwa politik yang bernomor surat 1/SF-FA/6/2018. Bunyinya secara vulgar menyebut bahwa siapapun umat Islam yang tidak memilih pasangan calon tertentu dianggap sama dengan mengingkari Allah dan Rasul-Nya Muhammad SAW.
Dari sinilah muncul kembali istilah pejoratif “IAIN, Ingkar Allah Ingkar Nabi” dalam Pilgub. Sebetulnya fatwa “Ingkar Allah Ingkar Nabi” tersebut melengkapi fatwa politik sebelumnya yang menyebut fardlu ‘ain memilih paslon tertentu.
Riuh politik pun tak terhindarkan. Ruang publik dibikin haru biru oleh perdebatan sengit nan menghabiskan energi tentang fatwa politik itu. Ada yang mencoba bertahan dengan merasionalisasi fatwa politik tersebut. Ada yang menyayangkan munculnya fatwa itu. Ada pula yang mencibir mereka yang mengeluarkan fatwa itu sebagai kelompok yang secara serampangan telah melakukan politisasi agama.
Bahkan ada juga yang lebih dari itu semua: melaporkan mereka yang terlibat dalam pengeluaran fatwa politik itu ke kepolisian karena dianggap telah menebarkan kebencian dan penistaan atas paslon Pilgub tertentu akibat namanya disebut secara terang-terangan sebagai pihak yang “ditohok” dalam fatwa itu. Intinya, hiruk pikuk politik pun tak terhindarkan dengan impitan yang tampak kuat dengan urusan agama.
Pada titik ini, saya teringat dengan pengalaman saya mengajar mata kuliah Budaya dan Politik Indonesia sebagai rangkaian dari mata kuliah Indonesian Way di kampus almamater saya, Australian National University (ANU) pada 2004. Saat menjelaskan bagaimana agama di Indonesia begitu mengemuka dalam melatarbelakangi budaya politik, ada mahasiswa asli Australia yang bertanya kepada saya: “Zaki, kenapa sih di Indonesia agama begitu penting, bahkan dalam urusan politik kekuasaan pun agama dibawa-bawa?”
Mendapat pertanyaan mahasiswa saya yang kritis itu, saya bertanya balik: “Anda sendiri sebagai orang Australia bagaimana memandang agama dalam kehidupan Anda di Australia?” Jawaban mengejutkan keluar dari mahasiswa itu: “Bagi saya agama itu tidak penting. Sebab, saya ini sudah sangat bahagia hingga saat ini. Seluruh kehidupan saya sudah dijamin oleh negara. Lalu buat apa agama? Apa yang bisa diperbuat agama untuk saya?”
Saya tidak dalam kepentingan untuk membahas sekuler atau tidak jawaban mahasiswa saya yang orang Australia itu. Saya perlu melakukan refleksi atas jawaban dia tersebut untuk memahami mengapa selalu muncul gejala politisasi agama atau minimal memaksa regulasi agama masuk ke ranah politik di negeri-negeri seperti Indonesia.Dan jawaban mahasiswa saya tersebut penting untuk dijadikan sebagai pembanding semata agar agama mampu memberi manfaat besar bagi terciptanya ruang publik yang baik bagi kemaslahan bersama (common good), seperti yang dipertanyakan mahasiswa saya di atas, dan bukan keburukan bersama.
Penting dicatat, teori yang berkembang di dunia akademik internasional tidak selalu bisa dipraktikkan secara plug and play antara satu negara dengan lainnya. Selalu ada ruang yang menjadi titik pembeda akibat perbedaan basis sosiologis masyarakat.
Saat sejumlah riset menyebutkan Islam tidak kompatibel dengan demokrasi, riset Saiful Mujani tentang religious democrats (2003) menjelaskan hal yang berbeda. Kearifan budaya lokal tertentu di Indonesia, seperti ritual tahlilan dan majelis taklim, membuat demokrasi dan agama memiliki nilai kompatibilitas yang cukup tinggi. Ritual-ritual itu menjadi modal sosial yang tinggi untuk memperkuat praktik-praktik partisipasi dalam demokratisasi di masyarakat.
Di tengah modal sosial dari keyakinan dan praktik agama yang tinggi di Indonesia di atas, rasanya semua, termasuk kaum agamawan, patut untuk bijak. Kepentingan penguatan partisipasi penganut agama dalam demokrasi tidak lalu direduksi sedemikian rupa hingga instrumen agama pun tercederai karenanya.
Fatwa adalah satu di antara instrumen agama yang tidak seharusnya diproduksi-diperlakukan sembarangan agar kebahagiaan hidup, seperti dalam jawaban mahasiswa saya di atas, tidak semu. Dan agama pun lalu memberi manfaat yang besar kepada ruang publik yang baik.
(poe)














