Analogi, OTT, dan Fungsi KPK
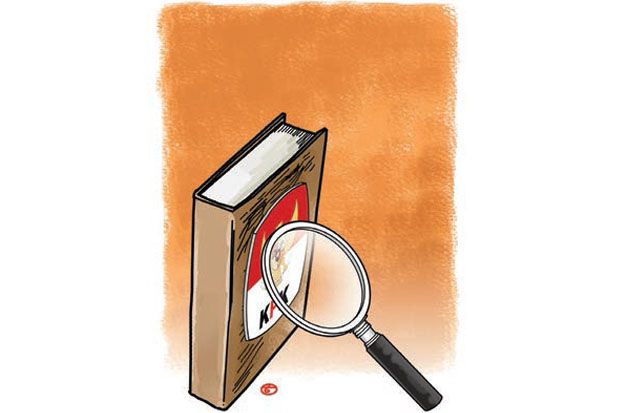
Analogi, OTT, dan Fungsi KPK
A
A
A
Romli Atmasasmita
Guru Besar Emeritus Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Expert UNODC untuk UNCAC 2003
ARTIKEL Prof Edward OS Hiariej (Prof Eddy) sebagai respons artikel saya di KORAN SINDO 5 Oktober 2017 mencantumkan empat variabel. Pertama, tertangkap tangan dibedakan dengan penjebakan. Kedua, percobaan dalam konteks hasil dari OTT. Ketiga, analogi merupakan cara yang bersangkutan membaca peristiwa hasil OTT. Keempat, dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.
Mengenai larangan analogi, saya tidak akan kupas lebih jauh karena dalam buku Prof Eddy sendiri sudah cukup jelas terdapat tiga golongan pendapat, dan pendapat yang menolak (Moeljatno, Simons, Van Hamel, Van Bemmelen, Van Hattum, dan Remmelink) lebih banyak dari yang menerima analogi (Rolling, Pompe, dan Jonkers), dan golongan yang tidak jelas (Hazewinkel Suringa dan Vos). Intinya tentang analogi jika dalam penerapan hukum (undang-undang) dilarang, sedangkan dalam penjelasan undang-undang boleh saja.
Namun, fokus diskusi saya dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK 2002 bukan penjelasan ketentuan UU KPK terkait pelaksanaan OTT dalam konteks penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KPK. Prof Eddy menyatakan dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hlm 120): Pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya diperbolehkan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Ketiga, dalam konteks penegakan hukum, analogi untuk menjelaskan undang-undang ataupun menimbulkan perbuatan pidana, baru diperbolehkan.
Prof Eddy sendiri tidak berpendapat atau tidak mempunyai pendapat sendiri tentang analogi; apakah menerima atau menolak. OTT sebagai bagian pelaksanaan penyelidikan-jelas merupakan penerapan UU KPK, telah ditafsirkan Prof Eddy sebagai bentuk percobaan ketika peristiwa tidak terjadi karena "digagalkan dengan penjebakan" oleh KPK sehingga jelas merugikan calon tersangka/terdakwa.
Penerapan analogi sejujurnya harus tidak merugikan tersangka/terdakwa. Moeljatno sependapat dengan Van Bemmelen dan Van Hattum membolehkan analogi terhadap ketentuan pidana tertulis yang tidak didasarkan pada suatu kaidah yang menentukan dapat tidak dipidananya seorang pelaku pelanggaran (Prof Eddy, halaman 112).
Penafsiran Prof Eddy perihal OTT KPK dan hasilnya merupakan delik percobaan (Pasal 53KUHP) atau merupakan perbuatan pelaksanaan yang digagalkan KPK dengan sengaja dan direncanakan terlebih dulu sehingga perbuatan permulaan pelaksanaan oleh calon tersangka jelas diarahkan (digiring) sehingga merupakan tindak pidana terlepas dari gagalnya tindak pidana tersebut karena memang sengaja digagalkan OTT KPK.
Selain itu, menurut Prof Eddy, peristiwa penangkapan dalam OTT membuktikan telah terjadi percobaan tindak pidana dan merupakan delik selesai sesuai UU Tipikor. Pendapat saya bukan pada peristiwa tindak pidana, melainkan pada alas hukum dan cara OTT KPK selama ini. Prof Eddy memasukkan OTT sebagai bagian dari penyelidikan didahului dengan pengintaian yang dia namakan pekerjaan intelijen, dan sejalan dengan asas legalitas penulis tegaskan bahwa penafsiran tersebut keliru karena UU KPK tidak membolehkan kegiatan intelijen kecuali untuk tindak pidana narkotika (BNN) dan terorisme (BNPT-Densus Antiterorisme).
Jika tafsir Prof Eddy tentang OTT dijadikan rujukan maka secara jelas dan transparan Prof Eddy berada pada golongan yang menerima analogi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekalipun posisi Prof Eddy dalam konteks analogi tidak jelas. Apakah pro atau kontra, tetapi demi untuk kepentingan, KPK "mendadak" menerima analogi untuk menjelaskan undang-undang (halaman 120 buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana)?
Fokus diskusi sampai dengan hari ini pada penerapan Undang-Undang KPK (hukum pidana formil) cc OTT yang menurut penulis tindakan KPK tidak sah dan cacat hukum. Penulis yakin dan percaya pada integritas keilmuan seorang almarhum Prof Moeljatno yang secara tegas dan jelas menempatkan dirinya -menurut Prof Eddy (murid almarhum) sendiri- berada pada posisi menolak analogi. Penulis sependapat dengan enam ahli hukum pidana termasuk pendapat almarhum Prof Moeljatno bahwa analogi dalam penegakan hukum dapat merugikan kepentingan seseorang calon tersangka. Padahal, kepentingan ini seharusnya wajib dilindungi sesuai amanat Bab XA Konstitusi UUD 1945, daripada sebaliknya mengkriminalisasi hak hidup dan kemerdekaan bergeraknya yang dilakukan tanpa ada risih, malu, dan bahkan bangga telah melanggar hak asasi seorang warga negara Indonesia, bahkan seorang pejabat tinggi negara.
Apakah enam kali pembatalan status tersangka KPK dalam perkara praperadilan oleh PN Jaksel belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa sekaliber KPK, termasuk pimpinan dan penyidik KPK yang katanya "independen segala-galanya" (tafsir keliru dan sesat), bisa berbuat salah yang mengakibatkan nasib dan kehidupan seseorang telah"dirampas" selama kurang lebih 2-5 bulan, bahkan ada yang lebih dari satu tahun berada dalam "cengkeraman kuku" KPK?
Bagaimana pertanggungjawaban publik yang wajib disampaikan KPK sesuai dengan Pasal 20 UU KPK dengan lima asas kepemimpinan KPK (Pasal 5 UUKPK) lebih khusus pertanggungjawaban KPK terhadap istri, anak-anak, dan keluarga calon tersangka/tersangka/terdakwa? Masalah ini diperparah lagi dengan temuan Pansus Angket KPK yang telah dibuka kepada publik, dan penulis percaya keterangan saksi-saksi di Pansus Angket KPK.
Penulis tidak pernah merasa dan bahkan menyebutnya analisis pars pro toto; persepsi Prof Eddy saja karena penulis memahami bahwa tafsir tersebut bukan tafsir hukum (hukum pidana), melainkan tafsir sosiologis. Terkait generalisasi, penulis menyampaikan contoh bahwa praktik penjebakan bukan hanya terjadi pada KPK Jilid IV, melainkan juga sejak KPK Jilid I alias telah dijadikan preseden yang dianggap benar, walaupun tidak benar secara hukum formal.
Soal tertangkap tangan, Prof Eddy menjelaskan sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 19, dan telah memenuhi asas lex certa dan memang seharusnya dibaca seperti apa yang dituliskan di dalam ketentuan tersebut, tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi. Prof Eddy telah menguraikan unsur-unsur dari perbuatan tertangkap tangan, dihubungkan dengan mengutip putusan MA AS 1932, dalam kalimat, "sesuatu dianggap penjebakan bila ada tindakan aktif dari penyidik untuk membuat seseorang melakukan kejahatan"; a law enforcement officer’s inducement of a person to commit a crime, for the purpose of prosecution (Black’s law dictionary, 1996, page 225).
Ternyata terdapat empat kasus terkenal di dalam praktik yurisprudensi MA AS, dan dari keempat perkara terkemuka tersebut sebagian terbesar berpihak pada pendekatan objektif (objective approach) yang melarang tindakan petugas (polisi) melakukan pembujukan yang berlebihan (overreaching inducement) terlepas dari apakah pelaku sesungguhnya terindikasi melakukan kejahatan. Pendekatan objektif mencegah seseorang warga yang baik, dengan tindakan petugas tersebut yang melakukan pembujukan berlebihan, menjadi pelaku kejahatan.
Jika calon tersangka dapat membuktikan sebaliknya dari tuduhan maka yang bersangkutan harus dibebaskan terlepas dari apakah yang bersangkutan sedang mempersiapkan atau hendak melakukan kejahatan (Encyclopedia of Criminal Justice, 1983). Penulis sependapat dengan pendekatan objektif karena penyadapan merupakan "the intrusion of the right to privacy " yang dilindungi penuh baik di dalam Konstitusi AS maupun UUD 1945.
Penulis berpendapat bahwa KPK telah mempraktikkan serangkaian proses mulai penyadapan, pengintaian (ontel, bahasa KPK), penggiringan seseorang menjadi calon tersangka, termasuk opini publik, kemudian dilakukan penangkapan termasuk penjebakan yang diharamkan. Cara tersebut telah dilakukan dalam kasus suap Probosutedjo, MWK, Wali Kota Batu ER, oknum kajari Pamekasan, dll. Apalagi UU KPK 2002 tidak mengatur secara eksplisit pengintaian (interdiction).
Dalam konteks ini, Prof Eddy mengemukakan pertanyaan apakah sesuatu yang tidak diatur secara mutatis mutandis dilarang atau ilegal? Pertanyaan Prof Eddy mengingatkan penulis pada penegakan hukum masa Orde Baru di mana seorang pejabat tinggi hukum mengajukan pertanyaan yang sama untuk membenarkan tindakan aparaturnya yang tidak berdasarkan ketentuan UU (abuse of power) semata-mata demi pemegang kekuasaan bukan demi melindungi hak asasi anggota masyarakat.
Prof Eddy dalam kaitan ini juga menyatakan antara lain, "harap diingat bahwa penegak hukum yang melakukan penyelidikan/penyidikan, pada hakikatnya juga melaksanakan fungsi intelijen dalam penanganan suatu kasus" dengan mengambil contoh, kepolisian dan kejaksaan; akan tetapi, tidak mengambil contoh UU KPK yang menjadi fokus diskusi dengan penulis. Menutup soal pengintaian, Prof Eddy menyatakan pengintaian oleh KPK dimasukkan dalam monitoring dan hal yang wajar dilakukan dalam proses penyelidikan/penyidikan. Prof Eddy lupa menyebutkan pasal dalam UU KPK yang mengaturnya jika masih berpegang pada asas legalitas.
Lagi pula, fungsi intelijen telah diatur dalam UU Intelijen yang hanya berlaku untuk kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS, BNN, dan BNPT; tidak untuk KPK. KPK lembaga penegak hukum independen bukan lembaga intelijen jelas beda besar antara kedua lembaga tersebut.
Prof Eddy menyinggung RKUHAP, hal tersebut masalah lain dan bukan fokus diskusi, dan juga belum diberlakukan sampai saat ini. Putusan MK RI sudah jelas dan tegas bahwa penyadapan harus dilakukan dengan dasar suatu UU bukan PP, perpres atau bahkan standard and operating procedure (SOP) yang diterbitkan dengan peraturan pimpinan KPK dengan pertimbangan bahwa penyadapan terkait the right to privacy yang dilindungi UUD 1945 (pasal 28 g ayat (1)).
Fokus diskusi penulis dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK dalam hubungannya UU Tipikor dan KUHAP. Sesungguhnya ada masalah besar yang belum disentuh dalam diskusi dan penting serta perlu dipahami baik oleh ahli hukum pidana dan praktisi hukum, terutama pimpinan/pegawai KPK. Bahwa UU KPK telah memberikan mandat lebih kepada pimpinan KPK berbeda dengan Polri dan kejaksaan; kelebihannya adalah tugas dan wewenang KPK selain penindakan juga koordinasi dan supervisi, pencegahan, monitoring, dan evaluasi terhadap kementerian/lembaga (K/L).
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KPK dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal aquo mempertegas dan mengingatkan KPK bahwa tugas penindakan hanya salah satu dari sekian tugas KPK berdasarkan UU KPK.
Dalam Penjelasan Umum UU KPK telah ditegaskan KPK memiliki fungsi "trigger mechanism " yang menempatkan KPK adalah counter-partner kepolisian dan kejaksaan. Namun yang terjadi adalah, KPK telah menempatkan dirinya sebagai kompetitor terhadap kepolisian dan kejaksaan di mana sering kasus dengan nilai kerugian negara jauh di bawah satu miliar rupiah. Begitu juga pihak swasta telah ditetapkan tersangka tanpa melibatkan penyelenggara negara; terjadi dalam praktik KPK.
Penjelasan umum UU KPK juga menegaskan bahwa KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pertanyaan saya adalah: pertama, mengapa KPK tidak menerapkan tugas dan wewenang (prioritas) sesuai Pasal 6 UU KPK, yaitu koordinasi dan supervisi serta pencegahan? Mengapa ditunggu sampai terjadinya suatu tindak pidana? Hal ini disebabkan di dalam UU KPK, tugas pencegahan dan penindakan berhubungan satu sama lain yang diatur dalam satu pasal saja; tidak dalam dua pasal terpisah dan tugas korsup, bukan juga alternatif penindakan.
Kedua, apakah yang menjadi dasar KPK melakukan penangkapan melalui OTT; sprint lid, sprint dik atau surat tugas pimpinan KPK; dan dapat dipastikan ketika terjadi penangkapan dalam OTT KPK, KPK belum memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan satu hari kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Bagaimana dengan tenggat waktu antara sprint lid ke sprint dik, yang memerlukan tenggat waktu tujuh hari, termasuk gelar perkara oleh pimpinan KPK sampai diterbitkan SPDP?
Ketiga, jika KPK tidak dapat menjelaskan dari aspek hukum pidana tindakan tersebut, tentu ada masalah mengenai "perampasan kemerdekaan bergerak" atas orang yang terhadapnya dilakukan penangkapan. Dalam konteks ini, KPK selalu berdalih telah ada SOP internal untuk melaksanakan tindakan tersebut. Akan tetapi dalam kasus praperadilan SN, terbukti hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim Cepi membatalkan penetapan status tersangka SN.
Dalam kasus praperadilan atas nama SN, bahkan SOP pimpinan KPK sendiri No 01/23/2008, juga telah dilanggar pimpinan KPK. Penulis berpendapat SOP internal KPK sesuai dengan kewajiban KPK bertanggung jawab kepada publik. Selama ini dalam praktik, KPK selalu "menyembunyikan" SOP tersebut dengan alasan "kerahasiaan" dan penulis berpendapat tidak dapat dibenarkan karena terkait hak asasi tersangka.
Merunut uraian penulis di atas, tampak bahwa kisah OTT KPK telah menimbulkan banyak masalah yang mendasar, (pertama) yaitu soal ketidakwenangan KPK melaksanakan "interdiction " dan "entrapment ". Kedua, dasar hukum "penangkapan disertai penetapan tersangka dan penahanan" selama dan pasca OTT. Ketiga, bukti permulaan yang cukup ketika akan, sedang, dan pascapenetapan tersangka dalam proses "OTT".
KPK sebagai lembaga penegak hukum masih terikat prinsip-prinsip hukum pidana universal, "due process of law ", "presumption of innocence ", dan "evidentiary rules " termasuk "exclusionary rules of evidence ", KPK berbeda dengan lembaga intelijen sehingga tidak ada sekecil apapun tindakan KPK yang boleh disembunyikan dari pengawasan publik, dan cara tersebut merupakan langkah pembenaran pelanggaran hukum dengan menyesatkan masyarakat.
Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI melalui Pansus Angket KPK menjadi sangat penting dan strategis. Jika UNODC mengetahui fakta KPK telah melanggar prinsip-prinsip universal tersebut di atas, penulis yakin bahwa gelar "best practices " KPK akan dicabut. Karena di dalam UNCAC 2003 yang diratifikasi UU RI Nomor 7 Tahun 2006 telah ditegaskan antara lain, "acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights ". Hal ini berarti pemberantasan korupsi harus sesuai standar internasional dan harus mematuhi standar perlakuan berdasarkan perlindungan hak asasi tersangka yang diakui universal.
Guru Besar Emeritus Hukum Pidana Universitas Padjadjaran (Unpad), Expert UNODC untuk UNCAC 2003
ARTIKEL Prof Edward OS Hiariej (Prof Eddy) sebagai respons artikel saya di KORAN SINDO 5 Oktober 2017 mencantumkan empat variabel. Pertama, tertangkap tangan dibedakan dengan penjebakan. Kedua, percobaan dalam konteks hasil dari OTT. Ketiga, analogi merupakan cara yang bersangkutan membaca peristiwa hasil OTT. Keempat, dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KUHP.
Mengenai larangan analogi, saya tidak akan kupas lebih jauh karena dalam buku Prof Eddy sendiri sudah cukup jelas terdapat tiga golongan pendapat, dan pendapat yang menolak (Moeljatno, Simons, Van Hamel, Van Bemmelen, Van Hattum, dan Remmelink) lebih banyak dari yang menerima analogi (Rolling, Pompe, dan Jonkers), dan golongan yang tidak jelas (Hazewinkel Suringa dan Vos). Intinya tentang analogi jika dalam penerapan hukum (undang-undang) dilarang, sedangkan dalam penjelasan undang-undang boleh saja.
Namun, fokus diskusi saya dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK 2002 bukan penjelasan ketentuan UU KPK terkait pelaksanaan OTT dalam konteks penyelidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 UU KPK. Prof Eddy menyatakan dalam buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (hlm 120): Pertama, dalam konteks hukum pidana nasional, penerapan analogi hanya diperbolehkan dalam rangka menjelaskan undang-undang. Kedua, masih dalam konteks hukum pidana nasional, analogi hukum tidak diperkenankan karena akan menimbulkan perbuatan pidana baru yang jelas bertentangan dengan asas legalitas. Ketiga, dalam konteks penegakan hukum, analogi untuk menjelaskan undang-undang ataupun menimbulkan perbuatan pidana, baru diperbolehkan.
Prof Eddy sendiri tidak berpendapat atau tidak mempunyai pendapat sendiri tentang analogi; apakah menerima atau menolak. OTT sebagai bagian pelaksanaan penyelidikan-jelas merupakan penerapan UU KPK, telah ditafsirkan Prof Eddy sebagai bentuk percobaan ketika peristiwa tidak terjadi karena "digagalkan dengan penjebakan" oleh KPK sehingga jelas merugikan calon tersangka/terdakwa.
Penerapan analogi sejujurnya harus tidak merugikan tersangka/terdakwa. Moeljatno sependapat dengan Van Bemmelen dan Van Hattum membolehkan analogi terhadap ketentuan pidana tertulis yang tidak didasarkan pada suatu kaidah yang menentukan dapat tidak dipidananya seorang pelaku pelanggaran (Prof Eddy, halaman 112).
Penafsiran Prof Eddy perihal OTT KPK dan hasilnya merupakan delik percobaan (Pasal 53KUHP) atau merupakan perbuatan pelaksanaan yang digagalkan KPK dengan sengaja dan direncanakan terlebih dulu sehingga perbuatan permulaan pelaksanaan oleh calon tersangka jelas diarahkan (digiring) sehingga merupakan tindak pidana terlepas dari gagalnya tindak pidana tersebut karena memang sengaja digagalkan OTT KPK.
Selain itu, menurut Prof Eddy, peristiwa penangkapan dalam OTT membuktikan telah terjadi percobaan tindak pidana dan merupakan delik selesai sesuai UU Tipikor. Pendapat saya bukan pada peristiwa tindak pidana, melainkan pada alas hukum dan cara OTT KPK selama ini. Prof Eddy memasukkan OTT sebagai bagian dari penyelidikan didahului dengan pengintaian yang dia namakan pekerjaan intelijen, dan sejalan dengan asas legalitas penulis tegaskan bahwa penafsiran tersebut keliru karena UU KPK tidak membolehkan kegiatan intelijen kecuali untuk tindak pidana narkotika (BNN) dan terorisme (BNPT-Densus Antiterorisme).
Jika tafsir Prof Eddy tentang OTT dijadikan rujukan maka secara jelas dan transparan Prof Eddy berada pada golongan yang menerima analogi dalam sistem hukum pidana Indonesia, sekalipun posisi Prof Eddy dalam konteks analogi tidak jelas. Apakah pro atau kontra, tetapi demi untuk kepentingan, KPK "mendadak" menerima analogi untuk menjelaskan undang-undang (halaman 120 buku Prinsip-Prinsip Hukum Pidana)?
Fokus diskusi sampai dengan hari ini pada penerapan Undang-Undang KPK (hukum pidana formil) cc OTT yang menurut penulis tindakan KPK tidak sah dan cacat hukum. Penulis yakin dan percaya pada integritas keilmuan seorang almarhum Prof Moeljatno yang secara tegas dan jelas menempatkan dirinya -menurut Prof Eddy (murid almarhum) sendiri- berada pada posisi menolak analogi. Penulis sependapat dengan enam ahli hukum pidana termasuk pendapat almarhum Prof Moeljatno bahwa analogi dalam penegakan hukum dapat merugikan kepentingan seseorang calon tersangka. Padahal, kepentingan ini seharusnya wajib dilindungi sesuai amanat Bab XA Konstitusi UUD 1945, daripada sebaliknya mengkriminalisasi hak hidup dan kemerdekaan bergeraknya yang dilakukan tanpa ada risih, malu, dan bahkan bangga telah melanggar hak asasi seorang warga negara Indonesia, bahkan seorang pejabat tinggi negara.
Apakah enam kali pembatalan status tersangka KPK dalam perkara praperadilan oleh PN Jaksel belum cukup bukti yang menunjukkan bahwa sekaliber KPK, termasuk pimpinan dan penyidik KPK yang katanya "independen segala-galanya" (tafsir keliru dan sesat), bisa berbuat salah yang mengakibatkan nasib dan kehidupan seseorang telah"dirampas" selama kurang lebih 2-5 bulan, bahkan ada yang lebih dari satu tahun berada dalam "cengkeraman kuku" KPK?
Bagaimana pertanggungjawaban publik yang wajib disampaikan KPK sesuai dengan Pasal 20 UU KPK dengan lima asas kepemimpinan KPK (Pasal 5 UUKPK) lebih khusus pertanggungjawaban KPK terhadap istri, anak-anak, dan keluarga calon tersangka/tersangka/terdakwa? Masalah ini diperparah lagi dengan temuan Pansus Angket KPK yang telah dibuka kepada publik, dan penulis percaya keterangan saksi-saksi di Pansus Angket KPK.
Penulis tidak pernah merasa dan bahkan menyebutnya analisis pars pro toto; persepsi Prof Eddy saja karena penulis memahami bahwa tafsir tersebut bukan tafsir hukum (hukum pidana), melainkan tafsir sosiologis. Terkait generalisasi, penulis menyampaikan contoh bahwa praktik penjebakan bukan hanya terjadi pada KPK Jilid IV, melainkan juga sejak KPK Jilid I alias telah dijadikan preseden yang dianggap benar, walaupun tidak benar secara hukum formal.
Soal tertangkap tangan, Prof Eddy menjelaskan sebagaimana telah dicantumkan dalam Pasal 1 angka 19, dan telah memenuhi asas lex certa dan memang seharusnya dibaca seperti apa yang dituliskan di dalam ketentuan tersebut, tidak boleh dilebihkan ataupun dikurangi. Prof Eddy telah menguraikan unsur-unsur dari perbuatan tertangkap tangan, dihubungkan dengan mengutip putusan MA AS 1932, dalam kalimat, "sesuatu dianggap penjebakan bila ada tindakan aktif dari penyidik untuk membuat seseorang melakukan kejahatan"; a law enforcement officer’s inducement of a person to commit a crime, for the purpose of prosecution (Black’s law dictionary, 1996, page 225).
Ternyata terdapat empat kasus terkenal di dalam praktik yurisprudensi MA AS, dan dari keempat perkara terkemuka tersebut sebagian terbesar berpihak pada pendekatan objektif (objective approach) yang melarang tindakan petugas (polisi) melakukan pembujukan yang berlebihan (overreaching inducement) terlepas dari apakah pelaku sesungguhnya terindikasi melakukan kejahatan. Pendekatan objektif mencegah seseorang warga yang baik, dengan tindakan petugas tersebut yang melakukan pembujukan berlebihan, menjadi pelaku kejahatan.
Jika calon tersangka dapat membuktikan sebaliknya dari tuduhan maka yang bersangkutan harus dibebaskan terlepas dari apakah yang bersangkutan sedang mempersiapkan atau hendak melakukan kejahatan (Encyclopedia of Criminal Justice, 1983). Penulis sependapat dengan pendekatan objektif karena penyadapan merupakan "the intrusion of the right to privacy " yang dilindungi penuh baik di dalam Konstitusi AS maupun UUD 1945.
Penulis berpendapat bahwa KPK telah mempraktikkan serangkaian proses mulai penyadapan, pengintaian (ontel, bahasa KPK), penggiringan seseorang menjadi calon tersangka, termasuk opini publik, kemudian dilakukan penangkapan termasuk penjebakan yang diharamkan. Cara tersebut telah dilakukan dalam kasus suap Probosutedjo, MWK, Wali Kota Batu ER, oknum kajari Pamekasan, dll. Apalagi UU KPK 2002 tidak mengatur secara eksplisit pengintaian (interdiction).
Dalam konteks ini, Prof Eddy mengemukakan pertanyaan apakah sesuatu yang tidak diatur secara mutatis mutandis dilarang atau ilegal? Pertanyaan Prof Eddy mengingatkan penulis pada penegakan hukum masa Orde Baru di mana seorang pejabat tinggi hukum mengajukan pertanyaan yang sama untuk membenarkan tindakan aparaturnya yang tidak berdasarkan ketentuan UU (abuse of power) semata-mata demi pemegang kekuasaan bukan demi melindungi hak asasi anggota masyarakat.
Prof Eddy dalam kaitan ini juga menyatakan antara lain, "harap diingat bahwa penegak hukum yang melakukan penyelidikan/penyidikan, pada hakikatnya juga melaksanakan fungsi intelijen dalam penanganan suatu kasus" dengan mengambil contoh, kepolisian dan kejaksaan; akan tetapi, tidak mengambil contoh UU KPK yang menjadi fokus diskusi dengan penulis. Menutup soal pengintaian, Prof Eddy menyatakan pengintaian oleh KPK dimasukkan dalam monitoring dan hal yang wajar dilakukan dalam proses penyelidikan/penyidikan. Prof Eddy lupa menyebutkan pasal dalam UU KPK yang mengaturnya jika masih berpegang pada asas legalitas.
Lagi pula, fungsi intelijen telah diatur dalam UU Intelijen yang hanya berlaku untuk kepolisian, kejaksaan, BIN, BAIS, BNN, dan BNPT; tidak untuk KPK. KPK lembaga penegak hukum independen bukan lembaga intelijen jelas beda besar antara kedua lembaga tersebut.
Prof Eddy menyinggung RKUHAP, hal tersebut masalah lain dan bukan fokus diskusi, dan juga belum diberlakukan sampai saat ini. Putusan MK RI sudah jelas dan tegas bahwa penyadapan harus dilakukan dengan dasar suatu UU bukan PP, perpres atau bahkan standard and operating procedure (SOP) yang diterbitkan dengan peraturan pimpinan KPK dengan pertimbangan bahwa penyadapan terkait the right to privacy yang dilindungi UUD 1945 (pasal 28 g ayat (1)).
Fokus diskusi penulis dan Prof Eddy tentang penerapan UU KPK dalam hubungannya UU Tipikor dan KUHAP. Sesungguhnya ada masalah besar yang belum disentuh dalam diskusi dan penting serta perlu dipahami baik oleh ahli hukum pidana dan praktisi hukum, terutama pimpinan/pegawai KPK. Bahwa UU KPK telah memberikan mandat lebih kepada pimpinan KPK berbeda dengan Polri dan kejaksaan; kelebihannya adalah tugas dan wewenang KPK selain penindakan juga koordinasi dan supervisi, pencegahan, monitoring, dan evaluasi terhadap kementerian/lembaga (K/L).
Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU KPK dinyatakan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal aquo mempertegas dan mengingatkan KPK bahwa tugas penindakan hanya salah satu dari sekian tugas KPK berdasarkan UU KPK.
Dalam Penjelasan Umum UU KPK telah ditegaskan KPK memiliki fungsi "trigger mechanism " yang menempatkan KPK adalah counter-partner kepolisian dan kejaksaan. Namun yang terjadi adalah, KPK telah menempatkan dirinya sebagai kompetitor terhadap kepolisian dan kejaksaan di mana sering kasus dengan nilai kerugian negara jauh di bawah satu miliar rupiah. Begitu juga pihak swasta telah ditetapkan tersangka tanpa melibatkan penyelenggara negara; terjadi dalam praktik KPK.
Penjelasan umum UU KPK juga menegaskan bahwa KPK tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pertanyaan saya adalah: pertama, mengapa KPK tidak menerapkan tugas dan wewenang (prioritas) sesuai Pasal 6 UU KPK, yaitu koordinasi dan supervisi serta pencegahan? Mengapa ditunggu sampai terjadinya suatu tindak pidana? Hal ini disebabkan di dalam UU KPK, tugas pencegahan dan penindakan berhubungan satu sama lain yang diatur dalam satu pasal saja; tidak dalam dua pasal terpisah dan tugas korsup, bukan juga alternatif penindakan.
Kedua, apakah yang menjadi dasar KPK melakukan penangkapan melalui OTT; sprint lid, sprint dik atau surat tugas pimpinan KPK; dan dapat dipastikan ketika terjadi penangkapan dalam OTT KPK, KPK belum memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka, dan satu hari kemudian yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Bagaimana dengan tenggat waktu antara sprint lid ke sprint dik, yang memerlukan tenggat waktu tujuh hari, termasuk gelar perkara oleh pimpinan KPK sampai diterbitkan SPDP?
Ketiga, jika KPK tidak dapat menjelaskan dari aspek hukum pidana tindakan tersebut, tentu ada masalah mengenai "perampasan kemerdekaan bergerak" atas orang yang terhadapnya dilakukan penangkapan. Dalam konteks ini, KPK selalu berdalih telah ada SOP internal untuk melaksanakan tindakan tersebut. Akan tetapi dalam kasus praperadilan SN, terbukti hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan hukum hakim Cepi membatalkan penetapan status tersangka SN.
Dalam kasus praperadilan atas nama SN, bahkan SOP pimpinan KPK sendiri No 01/23/2008, juga telah dilanggar pimpinan KPK. Penulis berpendapat SOP internal KPK sesuai dengan kewajiban KPK bertanggung jawab kepada publik. Selama ini dalam praktik, KPK selalu "menyembunyikan" SOP tersebut dengan alasan "kerahasiaan" dan penulis berpendapat tidak dapat dibenarkan karena terkait hak asasi tersangka.
Merunut uraian penulis di atas, tampak bahwa kisah OTT KPK telah menimbulkan banyak masalah yang mendasar, (pertama) yaitu soal ketidakwenangan KPK melaksanakan "interdiction " dan "entrapment ". Kedua, dasar hukum "penangkapan disertai penetapan tersangka dan penahanan" selama dan pasca OTT. Ketiga, bukti permulaan yang cukup ketika akan, sedang, dan pascapenetapan tersangka dalam proses "OTT".
KPK sebagai lembaga penegak hukum masih terikat prinsip-prinsip hukum pidana universal, "due process of law ", "presumption of innocence ", dan "evidentiary rules " termasuk "exclusionary rules of evidence ", KPK berbeda dengan lembaga intelijen sehingga tidak ada sekecil apapun tindakan KPK yang boleh disembunyikan dari pengawasan publik, dan cara tersebut merupakan langkah pembenaran pelanggaran hukum dengan menyesatkan masyarakat.
Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI melalui Pansus Angket KPK menjadi sangat penting dan strategis. Jika UNODC mengetahui fakta KPK telah melanggar prinsip-prinsip universal tersebut di atas, penulis yakin bahwa gelar "best practices " KPK akan dicabut. Karena di dalam UNCAC 2003 yang diratifikasi UU RI Nomor 7 Tahun 2006 telah ditegaskan antara lain, "acknowledging the fundamental principles of due process of law in criminal proceedings and in civil or administrative proceedings to adjudicate property rights ". Hal ini berarti pemberantasan korupsi harus sesuai standar internasional dan harus mematuhi standar perlakuan berdasarkan perlindungan hak asasi tersangka yang diakui universal.
(rhs)














