Ketimpangan dan Kemiskinan
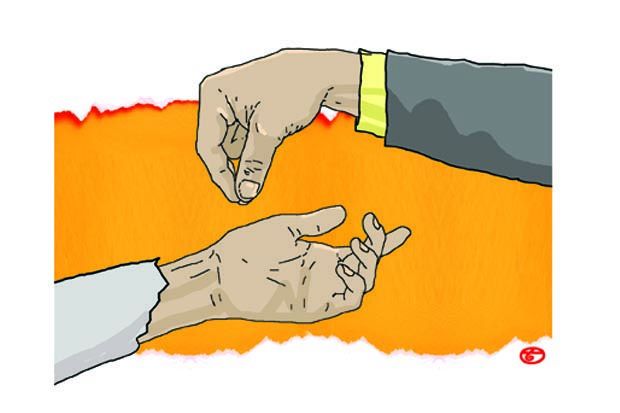
Ketimpangan dan Kemiskinan
A
A
A
Ahmad Iskandar
Dosen FE Universitas Ibnu Chaldun Jakarta
dan Universitas Atmajaya
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pendapatan Indonesia belakangan ini cenderung memburuk. Hal itu ditandai dengan indeks gini yang mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran pada 2015 sekitar 0,413 dan 2017 sedikit menurun menjadi 0,397. Sebaliknya, angka kemiskinan pada 2017 meningkat menjadi 27,77 juta orang dari 2016 yang mencapai 27,76 juta.
Terlepas dari angka-angka yang dilaporkan BPS, menurut saya ketimpangan dan kemiskinan patut menjadi catatan hitam ekonomi Indonesia dalam 50 tahun terakhir, dan sebagai refleksi saat Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Selain trennya yang cenderung statis atau jalan di tempat —dan bahkan memburuk dalam jangka panjang—, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tidak berubah, yaitu mengandalkan kebijakan neoliberal plus mekanisme trickle down effect. Kebijakan yang tidak berubah ini seolah menunjukkan kurang seriusnya the decision maker dalam memecahkan masalah tersebut.
Belum lama ini dana moneter Internasional (IMF) sebagai mbahnya neoliberal mengakui bahwa mekanisme trickle down effect atau efek menetes ke bawah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak berjalan. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan.
Hal ini telah terbukti di Indonesia, ketika pertumbuhan ekonomi 7% rata-rata tiap tahun selama tiga dasawarsa Orde Baru, namun ketimpangan pendapatan tidak menurun. Sehingga terbukti tidak ada efek menetes ke bawah, yang terjadi pertumbuhan selalu mengalir ke atas membesarkan konglomerat.
Ketimpangan
LSM Oxfam pada Februari 2017 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia. Oxfam mencatat, harta empat taipan terkaya di negara ini sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin. Harta empat orang terkaya di Indonesia mencapai USD 25 miliar atau setara Rp333,8 triliun. Sementara total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar USD24 miliar atau sekitar Rp320,3 triliun.
Saking banyaknya harta orang kaya tersebut, bu-nga yang didapat dari kekayaan orang terkaya Indonesia mencapai 1000 kali jumlah uang yang dibelanjakan penduduk miskin selama setahun. Jumlah miliarder dolarman Indonesia juga bertambah, dari 1 pada 2002 menjadi 20 orang di 2016. Tumbuhnya jumlah jutawan dan miliarder ini menjadi lawan nyata bagi kemiskinan. Hal ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi paling banyak dinikmati oleh golongan kaya.
Di industri keuangan sesuai data OJK, 50 konglomerasi keuangan menguasai 70% aset industri keuangan Indonesia atau Rp6.300 triliun dari total aset Rp9.000 triliun. Bila melihat publikasi 10 orang terkaya di Indonesia atau 50 orang terkaya di Indonesia, aset orang-orang tersebut jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Sementara kelompok masyarakat yang nyaris miskin gampang sekali terhempas ke kelompok miskin hanya gara-gara kebijakan pemerintah yang inflatoir. Nyata sekali gap antara kelompok kaya dan kelompok miskin itu.
Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. Bahkan dalam distribusi aset lebih memprihatinkan, yaitu rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat 56% aset berupa tanah, properti dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2% penduduk. Nah, kondisi ketimpangan yang semakin parah ini kalau kita bedah merupakan akibat langsung model kebijakan pemerintah yang tidak berubah sejak Orde Baru sampai sekarang yang melibatkan enam presiden (1967-2017).
Kebijakan itu adalah kebijakan neoliberal yang pro utang luar negeri, pro investor asing, pro Lembaga Internasional, pro pemodal, pro konglomerat, dan diwarnai KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga kapitalisme yang dikembangkan cenderung kapitalisme kroni.
Kisah parahnya ketimpangan ini bermula dari kebijakan pemerintah pro konglomerat yang dimulai sejak Orde Baru pada 1970-an. Pada periode awal berjalannya usaha konglomerat dimulai dengan bantuan tidak kecil dari pemerintah, bahkan dengan menugaskan langsung bank-bank pemerintah memberi kredit kepada usaha mereka.
Begitu juga saat periode membesarnya konglomerat dan mereka sudah memiliki bank sendiri karena didukung Pakto 88 (kebijakan BI mempermudah kepemilikan bank hanya dengan Rp10 miliar), pemerintah juga terus mendukung usaha konglomerat dengan kebijakan moneter, pasar modal, perbankan, kebijakan fiskal sampai kebijakan industrial.
Data ekonomi Indonesia mencatat, ketika usaha konglomerat Indonesia semakin membesar pada 1996, kesenjangan sosial semakin besar (dengan indeks gini 0,35). Ketika terjadi krisis ekonomi 1997/1998, hampir sebagian besar konglomerat melarikan uangnya ke luar negeri.
Kebijakan pemerintah Indonesia saat krisis ini kembali membantu konglomerat yang banknya mati suri dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kebijakan rekapitalisasi perbankan (injeksi modal bank dengan surat utang).
Biaya krisis 1997/1998 senilai Rp670 triliun dan membuat pemerintah jadi mandul kebijakan fiskalnya karena harus bayar utang dalam negeri (bunga rekapitalisasi) sekitar Rp70 triliun tiap tahun. Selain menimbulkan skandal BLBI, kebijakan pemerintah 1997/1998 dengan melakukan rekapitalisasi perbankan juga menciptakan skandal lain, yaitu skandal memindahkan utang swasta (konglomerat) menjadi utang publik. Rakyatlah yang membayar utang konglomerat itu melalui APBN.
Skandal itu menyebabkan APBN Indonesia tak bisa lagi membantu rakyatnya untuk program sosial. Bersamaan dengan proses liberalisasi total perekonomian Indonesia yang dilakukan IMF, konglomerat yang semaput oleh dana rekap di APBN lambat laun bangkit lagi, dan pada 2015 mereka sudah bangkit lagi sebagai konglomerat yang lebih kaya dari sebelum krisis 1997/1998. Inilah fase baru ketimpangan yang semakin parah di Indonesia.
Konglomerasi masa sekarang ditandai dengan skandal baru, yaitu skandal reklamasi dan skandal meikarta. Inilah saat jaringan konglomerat bertransformasi dari entitas bisnis ke entitas politik yang mempengaruhi kebijakan dan mengambil porsi kebijakan yang harusnya domain pemerintah.
Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi 7% rata-rata tiap tahun selama tiga dekade yang dicapai Orde Baru, terbukti bisa menurunkan tingkat kemiskinan di kota maupun di desa, dari awalnya setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia sampai hanya sekitar 11%. Ini semua bisa terjadi karena ada strategi langsung dan tidak langsung melalui program penanggulangan kemiskinan yang efisien.
Pemerintah Orde Baru juga merekrut pakar kemiskinan Mubyarto untuk terlibat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Namun, krisis ekonomi 1997/1998 membuat tingkat kemiskinan di Indonesia melejit lagi dari 11% menjadi 19.9% di akhir tahun 1998. Persentase kemiskinan ini terus berkurang menjadi di bawah 15% sejak 2009 dan pada 2016 menjadi 10,9%.
Memasuki 2017, BPS mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64%.
Terakhir, bicara soal kemiskinan dan ketimpangan ekonom senior Hartojo Wignjowijoto (kini almarhum) pernah bertanya kepada pakar kemiskinan dunia Jeffrey D Sachs dalam sebuah seminar di Jakarta, apakah pantas negara kaya seperti Indonesia penduduknya banyak yang miskin? Jeffrey yang terkejut dengan pertanyaan tadi tercenung sebentar dan menjawab: ”tidak pantas”.
Memang sangatlah tidak pantas penduduk negara ini miskin, padahal Indonesia merupakan surga di dunia. Dan sangat tidak pantas juga kalau ketimpangan pendapatan sampai sedemikian rupa sehingga 4 orang penduduk setara dengan 100 orang. Pemerintah harus berada di garda depan. Tidak boleh lagi urusan ekonomi diserahkan ke mekanisme pasar semata, maka wajib pemerintah mengoreksi kebijakan zaman IMF saat krisis 1997/1998 karena terlalu liberal.
Dan hal yang penting juga, pemerintah jangan menghilangkan subsidi untuk rakyat. Gunakan prinsip-prinsip UUD 45 dan Pancasila, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dosen FE Universitas Ibnu Chaldun Jakarta
dan Universitas Atmajaya
BADAN Pusat Statistik (BPS) mencatat ketimpangan pendapatan Indonesia belakangan ini cenderung memburuk. Hal itu ditandai dengan indeks gini yang mendekati 0,5 atau gini ratio pengeluaran pada 2015 sekitar 0,413 dan 2017 sedikit menurun menjadi 0,397. Sebaliknya, angka kemiskinan pada 2017 meningkat menjadi 27,77 juta orang dari 2016 yang mencapai 27,76 juta.
Terlepas dari angka-angka yang dilaporkan BPS, menurut saya ketimpangan dan kemiskinan patut menjadi catatan hitam ekonomi Indonesia dalam 50 tahun terakhir, dan sebagai refleksi saat Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang ke-72. Selain trennya yang cenderung statis atau jalan di tempat —dan bahkan memburuk dalam jangka panjang—, kebijakan yang digunakan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan tidak berubah, yaitu mengandalkan kebijakan neoliberal plus mekanisme trickle down effect. Kebijakan yang tidak berubah ini seolah menunjukkan kurang seriusnya the decision maker dalam memecahkan masalah tersebut.
Belum lama ini dana moneter Internasional (IMF) sebagai mbahnya neoliberal mengakui bahwa mekanisme trickle down effect atau efek menetes ke bawah dari pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara tidak berjalan. Dengan demikian, tidak bisa dijadikan kebijakan untuk mengatasi ketimpangan.
Hal ini telah terbukti di Indonesia, ketika pertumbuhan ekonomi 7% rata-rata tiap tahun selama tiga dasawarsa Orde Baru, namun ketimpangan pendapatan tidak menurun. Sehingga terbukti tidak ada efek menetes ke bawah, yang terjadi pertumbuhan selalu mengalir ke atas membesarkan konglomerat.
Ketimpangan
LSM Oxfam pada Februari 2017 menyebut Indonesia sebagai salah satu negara dengan ketimpangan paling parah di dunia. Oxfam mencatat, harta empat taipan terkaya di negara ini sama dengan harta yang dimiliki oleh 100 juta orang miskin. Harta empat orang terkaya di Indonesia mencapai USD 25 miliar atau setara Rp333,8 triliun. Sementara total kekayaan 100 juta penduduk miskin di Indonesia sebesar USD24 miliar atau sekitar Rp320,3 triliun.
Saking banyaknya harta orang kaya tersebut, bu-nga yang didapat dari kekayaan orang terkaya Indonesia mencapai 1000 kali jumlah uang yang dibelanjakan penduduk miskin selama setahun. Jumlah miliarder dolarman Indonesia juga bertambah, dari 1 pada 2002 menjadi 20 orang di 2016. Tumbuhnya jumlah jutawan dan miliarder ini menjadi lawan nyata bagi kemiskinan. Hal ini mengonfirmasi bahwa pertumbuhan ekonomi paling banyak dinikmati oleh golongan kaya.
Di industri keuangan sesuai data OJK, 50 konglomerasi keuangan menguasai 70% aset industri keuangan Indonesia atau Rp6.300 triliun dari total aset Rp9.000 triliun. Bila melihat publikasi 10 orang terkaya di Indonesia atau 50 orang terkaya di Indonesia, aset orang-orang tersebut jumlahnya terus meningkat tiap tahun. Sementara kelompok masyarakat yang nyaris miskin gampang sekali terhempas ke kelompok miskin hanya gara-gara kebijakan pemerintah yang inflatoir. Nyata sekali gap antara kelompok kaya dan kelompok miskin itu.
Secara khusus Bank Dunia pada 2015 mencatat laju peningkatan ketimpangan ekonomi di Indonesia paling tinggi di Asia Timur. Bahkan dalam distribusi aset lebih memprihatinkan, yaitu rasio gini penguasaan lahan mencapai angka 0,72. Angka ini lebih tinggi daripada rasio gini pendapatan. Badan Pertanahan Nasional bahkan mencatat 56% aset berupa tanah, properti dan perkebunan hanya dikuasai oleh sekitar 0,2% penduduk. Nah, kondisi ketimpangan yang semakin parah ini kalau kita bedah merupakan akibat langsung model kebijakan pemerintah yang tidak berubah sejak Orde Baru sampai sekarang yang melibatkan enam presiden (1967-2017).
Kebijakan itu adalah kebijakan neoliberal yang pro utang luar negeri, pro investor asing, pro Lembaga Internasional, pro pemodal, pro konglomerat, dan diwarnai KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) sehingga kapitalisme yang dikembangkan cenderung kapitalisme kroni.
Kisah parahnya ketimpangan ini bermula dari kebijakan pemerintah pro konglomerat yang dimulai sejak Orde Baru pada 1970-an. Pada periode awal berjalannya usaha konglomerat dimulai dengan bantuan tidak kecil dari pemerintah, bahkan dengan menugaskan langsung bank-bank pemerintah memberi kredit kepada usaha mereka.
Begitu juga saat periode membesarnya konglomerat dan mereka sudah memiliki bank sendiri karena didukung Pakto 88 (kebijakan BI mempermudah kepemilikan bank hanya dengan Rp10 miliar), pemerintah juga terus mendukung usaha konglomerat dengan kebijakan moneter, pasar modal, perbankan, kebijakan fiskal sampai kebijakan industrial.
Data ekonomi Indonesia mencatat, ketika usaha konglomerat Indonesia semakin membesar pada 1996, kesenjangan sosial semakin besar (dengan indeks gini 0,35). Ketika terjadi krisis ekonomi 1997/1998, hampir sebagian besar konglomerat melarikan uangnya ke luar negeri.
Kebijakan pemerintah Indonesia saat krisis ini kembali membantu konglomerat yang banknya mati suri dengan mengeluarkan kebijakan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan kebijakan rekapitalisasi perbankan (injeksi modal bank dengan surat utang).
Biaya krisis 1997/1998 senilai Rp670 triliun dan membuat pemerintah jadi mandul kebijakan fiskalnya karena harus bayar utang dalam negeri (bunga rekapitalisasi) sekitar Rp70 triliun tiap tahun. Selain menimbulkan skandal BLBI, kebijakan pemerintah 1997/1998 dengan melakukan rekapitalisasi perbankan juga menciptakan skandal lain, yaitu skandal memindahkan utang swasta (konglomerat) menjadi utang publik. Rakyatlah yang membayar utang konglomerat itu melalui APBN.
Skandal itu menyebabkan APBN Indonesia tak bisa lagi membantu rakyatnya untuk program sosial. Bersamaan dengan proses liberalisasi total perekonomian Indonesia yang dilakukan IMF, konglomerat yang semaput oleh dana rekap di APBN lambat laun bangkit lagi, dan pada 2015 mereka sudah bangkit lagi sebagai konglomerat yang lebih kaya dari sebelum krisis 1997/1998. Inilah fase baru ketimpangan yang semakin parah di Indonesia.
Konglomerasi masa sekarang ditandai dengan skandal baru, yaitu skandal reklamasi dan skandal meikarta. Inilah saat jaringan konglomerat bertransformasi dari entitas bisnis ke entitas politik yang mempengaruhi kebijakan dan mengambil porsi kebijakan yang harusnya domain pemerintah.
Kemiskinan
Pertumbuhan ekonomi 7% rata-rata tiap tahun selama tiga dekade yang dicapai Orde Baru, terbukti bisa menurunkan tingkat kemiskinan di kota maupun di desa, dari awalnya setengah dari jumlah keseluruhan populasi penduduk Indonesia sampai hanya sekitar 11%. Ini semua bisa terjadi karena ada strategi langsung dan tidak langsung melalui program penanggulangan kemiskinan yang efisien.
Pemerintah Orde Baru juga merekrut pakar kemiskinan Mubyarto untuk terlibat dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Namun, krisis ekonomi 1997/1998 membuat tingkat kemiskinan di Indonesia melejit lagi dari 11% menjadi 19.9% di akhir tahun 1998. Persentase kemiskinan ini terus berkurang menjadi di bawah 15% sejak 2009 dan pada 2016 menjadi 10,9%.
Memasuki 2017, BPS mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Indonesia meningkat masing-masing 1,83 dan 0,48 di Maret 2017 dibanding realisasi September 2016 yang sebesar 1,74 dan 0,44. Jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64%.
Terakhir, bicara soal kemiskinan dan ketimpangan ekonom senior Hartojo Wignjowijoto (kini almarhum) pernah bertanya kepada pakar kemiskinan dunia Jeffrey D Sachs dalam sebuah seminar di Jakarta, apakah pantas negara kaya seperti Indonesia penduduknya banyak yang miskin? Jeffrey yang terkejut dengan pertanyaan tadi tercenung sebentar dan menjawab: ”tidak pantas”.
Memang sangatlah tidak pantas penduduk negara ini miskin, padahal Indonesia merupakan surga di dunia. Dan sangat tidak pantas juga kalau ketimpangan pendapatan sampai sedemikian rupa sehingga 4 orang penduduk setara dengan 100 orang. Pemerintah harus berada di garda depan. Tidak boleh lagi urusan ekonomi diserahkan ke mekanisme pasar semata, maka wajib pemerintah mengoreksi kebijakan zaman IMF saat krisis 1997/1998 karena terlalu liberal.
Dan hal yang penting juga, pemerintah jangan menghilangkan subsidi untuk rakyat. Gunakan prinsip-prinsip UUD 45 dan Pancasila, yaitu keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
(thm)














