Pembangkangan Hukum ala DPD
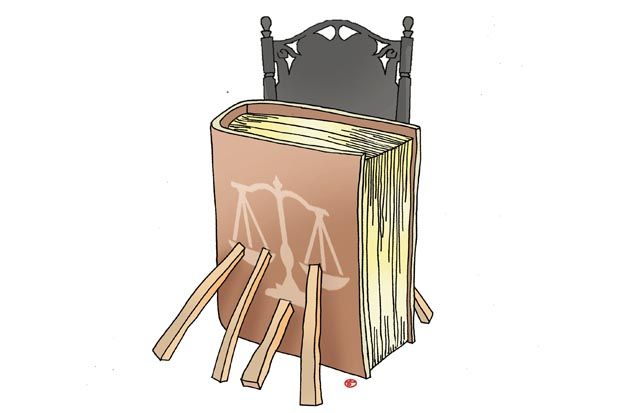
Pembangkangan Hukum ala DPD
A
A
A
Khairul Fahmi
Dosen HTN, Peneliti PUSaKO FH Universitas Andalas, dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum UGM
Jabatan dan kekuasaan itu memang memesona. Ia diperebutkan. Cara apa pun akan ditempuh, bahkan tidak pandang dengan cara 'halal' atau 'haram'. Perebutan jabatan juga tidak menimbang seberapa besar kekuasaan yang akan direngkuh. Berapa pun kecilnya, jabatan tetap menyimpan daya tarik luar biasa untuk digenggam.
Postulat itu pun berlaku di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sekalipun dengan kewenangan yang sangat terbatas, perebutan kekuasaan di sana justru terjadi dengan eskalasi politik yang sebanding dengan yang pernah terjadi di DPR, bahkan lebih. Bila disandingkan, kekuasaan DPD tidak ada apa-apanya dibandingkan DPR. Namun, sikap bar-bar dalam menghadapi dinamika politik internal justru terlihat menonjol dalam penggantian pimpinan DPD. Pengalaman yang sungguh sangat memalukan bagi seluruh anak bangsa.
Hal yang lebih menyedihkan, dinamika politik yang amat tidak sehat itu justru disertai pula dengan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Ketika Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1/2017 yang mengatur masa jabatan pimpinan selama 2,5 tahun dibatalkan melalui Putusan Nomor 20.P/HUM/2017, peraturan itu malah tetap dijadikan dasar hukum untuk memilih pimpinan baru.
Putusan MA
Sebagian anggota DPD yang kukuh melaksanakan agenda pemilihan pimpinan beralasan, Putusan MA mengandung kesalahan sehingga menyebabkan Tatib Nomor 1/2017 dianggap tetap berlaku. Alasan tersebut sesungguhnya tidak dapat dijadikan argumentasi untuk membelakangi putusan MA. Sebab, jika dibaca lebih jauh, memang terdapat kekeliruan kecil pada diktum kedua dan ketiga putusan dimaksud. Di mana, pada diktum kedua terselip frasa 'Undang-Undang' di antara frasa 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia' dan frasa 'Nomor 1/2017.. dst.' Sementara pada diktum ketiga, terselip kata 'Rakyat' di antara frasa 'Pimpinan Dewan Perwakilan' dan frasa 'Daerah untuk...dst.'
Lebih jauh kekeliruan dimaksud juga tidak menimbulkan keraguan terhadap maksud yang dikehendaki di dalamnya. Karena, pertama, pada diktum kedua, peraturan yang dituju untuk dibatalkan adalah Peraturan DPD No 1/2017, bukan Undang-Undang No 1/2017. Maksud itu dapat dipahami dengan dua penjelasan.
Pertama, dalam seluruh pertimbangan hukum, peraturan yang dipertimbangkan dan dinilai adalah Peraturan DPD Nomor 1/2017, bukan Undang Nomor 1/2017. Dalam konteks perumusan norma peraturan, sama sekali tidak dikenal frasa 'Republik Indonesia Undang-Undang Nomor ...dst.' Dengan begitu, keberadaan frasa 'Undang-Undang' dalam diktum kedua, sama sekali tidak mengubah substansi pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 tersebut.
Kedua, pada diktum ketiga, terkait perintah pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kaitannya dengan diktum kedua, peraturan yang dibatalkan adalah Peraturan Nomor 1/2017 sehingga perintah untuk membatalkannya tentu juga ditujukan kepada DPD, bukan yang lain. Dengan demikian, sekalipun terdapat kata 'Rakyat', hal itu tidaklah menyebabkan subjek yang diperintahkan dalam diktum ketiga menjadi tidak jelas.
Dengan tetap mengandung kepastian maksud serta telah pula diperbaiki oleh MA, kesalahan penulisan tersebut sama sekali tidak berakibat pada hilangnya sifat mengikat putusan pembatalan peraturan DPD. Sifat mengikat putusan pengujian peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan MA berimplikasi terhadap hilangnya daya berlaku peraturan yang dibatalkan.
Dengan tanpa daya berlaku, Peraturan DPD Nomor 1/2017 tidak lagi dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan agenda-agenda kelembagaan DPD, termasuk mengganti pimpinan. Bahkan, dalam pertimbangan hukumnya, MA menegaskan, masa jabatan pimpinan tidak bisa diubah dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun sehingga pimpinan DPD yang telah dipilih sebelumnya tidak dapat diganti, kecuali dalam hal terjadi kekosongan karena berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.
Selain itu, juga ada hal lain yang cukup menarik dalam putusan dimaksud, yaitu adanya perintah kepada DPD untuk mencabut Peraturan Nomor 1/2017. Di mana perintah itu dimaknai oleh sebagian kalangan DPD sebagai sesuatu yang memberi ruang untuk tetap memberlakukannya. Dalam arti, ketika DPD belum mencabutnya, regulasi tersebut tetap berlaku.
Penilaian demikian merupakan sebuah pandangan yang keliru. Sebab, perintah pencabutan sebuah peraturan yang sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang hanya bersifat administratif. Hal mana, tanpa adanya tindakan pencabutan sekalipun, peraturan yang sudah dinyatakan bertentangan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga ia tidak dapat lagi dijadikan dasar bertindak. Lebih jauh, menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengakali diktum pembatalan Peraturan Nomor 1/2017 justru akan bergeser menjadi pembangkangan terhadap putusan itu sendiri.
Mengkhianati Negara Hukum
Sikap menyanggah putusan MA sebagaimana dipertontonkan DPD nyata-nyata merupakan manuver mengkhianati negara hukum. Putusan lembaga kekuasaan kehakiman dalam pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 adalah hukum. Sebagai lembaga negara, DPD seharusnya memberi contoh bagaimana hukum dihormati, bukan malah sebaliknya. Jangan hanya untuk memenuhi hasrat kuasa yang tak terbendung, semua hendak diterabas, termasuk hukum.
Segala bentuk pembangkangan terhadap hukum adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, sehingga ia harus dihentikan.
Oleh karena itu, sejumlah upaya mesti dilakukan. Di antaranya, pertama, hasil pemilihan pimpinan DPD yang tetap merujuk Tatib Nomor 1/2017 harus didelegitimasi dengan cara MA menolak untuk memandu proses pengucapan sumpah pimpinan DPD terpilih. MA tentunya akan mengambil langkah itu. Sebab, pimpinan baru DPD jelas-jelas terlahir dari upaya pengangkangan terhadap putusan MA sendiri. Bila bersikap sebaliknya, MA tentu akan mendeligitimasi putusan sendiri dan pada saat yang sama akan menghancurkan prinsip negara hukum. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA tentu tidak akan bertindak demikian.
Kedua, secara internal, seluruh anggota DPD yang masih berpikir 'waras' ihwal bagaimana menyelenggarakan negara menurut hukum mesti mengonsolidasikan diri guna membenahi lembaga yang sudah terkoyak. DPD mesti ditarik kembali ke jalur yang benar, jalur di mana hukum yang menjadi panduannya.
Sekiranya dua langkah itu tidak dilaksanakan, pembangkangan hukum ala DPD akan berjalan sempurna. Prinsip-prinsip negara hukum yang dengan susah payah dijaga justru dihancurkan. Bila sampai demikian, Indonesia sebagaimana negara hukum sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentu sekadar hiasan dalam kita bernegara.
Dosen HTN, Peneliti PUSaKO FH Universitas Andalas, dan Kandidat Doktor Ilmu Hukum UGM
Jabatan dan kekuasaan itu memang memesona. Ia diperebutkan. Cara apa pun akan ditempuh, bahkan tidak pandang dengan cara 'halal' atau 'haram'. Perebutan jabatan juga tidak menimbang seberapa besar kekuasaan yang akan direngkuh. Berapa pun kecilnya, jabatan tetap menyimpan daya tarik luar biasa untuk digenggam.
Postulat itu pun berlaku di Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sekalipun dengan kewenangan yang sangat terbatas, perebutan kekuasaan di sana justru terjadi dengan eskalasi politik yang sebanding dengan yang pernah terjadi di DPR, bahkan lebih. Bila disandingkan, kekuasaan DPD tidak ada apa-apanya dibandingkan DPR. Namun, sikap bar-bar dalam menghadapi dinamika politik internal justru terlihat menonjol dalam penggantian pimpinan DPD. Pengalaman yang sungguh sangat memalukan bagi seluruh anak bangsa.
Hal yang lebih menyedihkan, dinamika politik yang amat tidak sehat itu justru disertai pula dengan pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Agung. Ketika Peraturan Tata Tertib DPD Nomor 1/2017 yang mengatur masa jabatan pimpinan selama 2,5 tahun dibatalkan melalui Putusan Nomor 20.P/HUM/2017, peraturan itu malah tetap dijadikan dasar hukum untuk memilih pimpinan baru.
Putusan MA
Sebagian anggota DPD yang kukuh melaksanakan agenda pemilihan pimpinan beralasan, Putusan MA mengandung kesalahan sehingga menyebabkan Tatib Nomor 1/2017 dianggap tetap berlaku. Alasan tersebut sesungguhnya tidak dapat dijadikan argumentasi untuk membelakangi putusan MA. Sebab, jika dibaca lebih jauh, memang terdapat kekeliruan kecil pada diktum kedua dan ketiga putusan dimaksud. Di mana, pada diktum kedua terselip frasa 'Undang-Undang' di antara frasa 'Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Indonesia' dan frasa 'Nomor 1/2017.. dst.' Sementara pada diktum ketiga, terselip kata 'Rakyat' di antara frasa 'Pimpinan Dewan Perwakilan' dan frasa 'Daerah untuk...dst.'
Lebih jauh kekeliruan dimaksud juga tidak menimbulkan keraguan terhadap maksud yang dikehendaki di dalamnya. Karena, pertama, pada diktum kedua, peraturan yang dituju untuk dibatalkan adalah Peraturan DPD No 1/2017, bukan Undang-Undang No 1/2017. Maksud itu dapat dipahami dengan dua penjelasan.
Pertama, dalam seluruh pertimbangan hukum, peraturan yang dipertimbangkan dan dinilai adalah Peraturan DPD Nomor 1/2017, bukan Undang Nomor 1/2017. Dalam konteks perumusan norma peraturan, sama sekali tidak dikenal frasa 'Republik Indonesia Undang-Undang Nomor ...dst.' Dengan begitu, keberadaan frasa 'Undang-Undang' dalam diktum kedua, sama sekali tidak mengubah substansi pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 tersebut.
Kedua, pada diktum ketiga, terkait perintah pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 yang ditujukan kepada Dewan Perwakilan Daerah. Dalam kaitannya dengan diktum kedua, peraturan yang dibatalkan adalah Peraturan Nomor 1/2017 sehingga perintah untuk membatalkannya tentu juga ditujukan kepada DPD, bukan yang lain. Dengan demikian, sekalipun terdapat kata 'Rakyat', hal itu tidaklah menyebabkan subjek yang diperintahkan dalam diktum ketiga menjadi tidak jelas.
Dengan tetap mengandung kepastian maksud serta telah pula diperbaiki oleh MA, kesalahan penulisan tersebut sama sekali tidak berakibat pada hilangnya sifat mengikat putusan pembatalan peraturan DPD. Sifat mengikat putusan pengujian peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan MA berimplikasi terhadap hilangnya daya berlaku peraturan yang dibatalkan.
Dengan tanpa daya berlaku, Peraturan DPD Nomor 1/2017 tidak lagi dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan agenda-agenda kelembagaan DPD, termasuk mengganti pimpinan. Bahkan, dalam pertimbangan hukumnya, MA menegaskan, masa jabatan pimpinan tidak bisa diubah dari 5 tahun menjadi 2,5 tahun sehingga pimpinan DPD yang telah dipilih sebelumnya tidak dapat diganti, kecuali dalam hal terjadi kekosongan karena berhenti atau diberhentikan dari jabatannya.
Selain itu, juga ada hal lain yang cukup menarik dalam putusan dimaksud, yaitu adanya perintah kepada DPD untuk mencabut Peraturan Nomor 1/2017. Di mana perintah itu dimaknai oleh sebagian kalangan DPD sebagai sesuatu yang memberi ruang untuk tetap memberlakukannya. Dalam arti, ketika DPD belum mencabutnya, regulasi tersebut tetap berlaku.
Penilaian demikian merupakan sebuah pandangan yang keliru. Sebab, perintah pencabutan sebuah peraturan yang sudah dinyatakan bertentangan dengan undang-undang hanya bersifat administratif. Hal mana, tanpa adanya tindakan pencabutan sekalipun, peraturan yang sudah dinyatakan bertentangan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga ia tidak dapat lagi dijadikan dasar bertindak. Lebih jauh, menjadikan hal itu sebagai alasan untuk mengakali diktum pembatalan Peraturan Nomor 1/2017 justru akan bergeser menjadi pembangkangan terhadap putusan itu sendiri.
Mengkhianati Negara Hukum
Sikap menyanggah putusan MA sebagaimana dipertontonkan DPD nyata-nyata merupakan manuver mengkhianati negara hukum. Putusan lembaga kekuasaan kehakiman dalam pembatalan Peraturan DPD Nomor 1/2017 adalah hukum. Sebagai lembaga negara, DPD seharusnya memberi contoh bagaimana hukum dihormati, bukan malah sebaliknya. Jangan hanya untuk memenuhi hasrat kuasa yang tak terbendung, semua hendak diterabas, termasuk hukum.
Segala bentuk pembangkangan terhadap hukum adalah sikap yang bertentangan dengan prinsip negara hukum, sehingga ia harus dihentikan.
Oleh karena itu, sejumlah upaya mesti dilakukan. Di antaranya, pertama, hasil pemilihan pimpinan DPD yang tetap merujuk Tatib Nomor 1/2017 harus didelegitimasi dengan cara MA menolak untuk memandu proses pengucapan sumpah pimpinan DPD terpilih. MA tentunya akan mengambil langkah itu. Sebab, pimpinan baru DPD jelas-jelas terlahir dari upaya pengangkangan terhadap putusan MA sendiri. Bila bersikap sebaliknya, MA tentu akan mendeligitimasi putusan sendiri dan pada saat yang sama akan menghancurkan prinsip negara hukum. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, MA tentu tidak akan bertindak demikian.
Kedua, secara internal, seluruh anggota DPD yang masih berpikir 'waras' ihwal bagaimana menyelenggarakan negara menurut hukum mesti mengonsolidasikan diri guna membenahi lembaga yang sudah terkoyak. DPD mesti ditarik kembali ke jalur yang benar, jalur di mana hukum yang menjadi panduannya.
Sekiranya dua langkah itu tidak dilaksanakan, pembangkangan hukum ala DPD akan berjalan sempurna. Prinsip-prinsip negara hukum yang dengan susah payah dijaga justru dihancurkan. Bila sampai demikian, Indonesia sebagaimana negara hukum sebagaimana dimaktubkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentu sekadar hiasan dalam kita bernegara.
(zik)














