Absennya Muhammadiyah
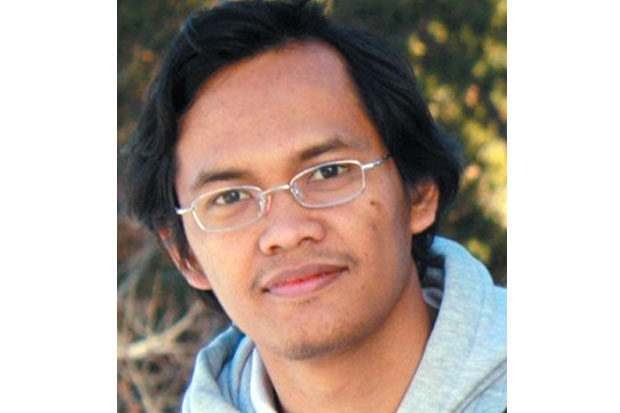
Absennya Muhammadiyah
A
A
A
AHMAD NAJIB BURHANI
Peneliti LIPI dan Maarif Institute
Mengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2015?
Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?
Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).
Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.
Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.
Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.
Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.
Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.
Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.
Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.
Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.
Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.
Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.
Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.
NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.
Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.
Peneliti LIPI dan Maarif Institute
Mengapa seolah-olah pemerintahan Jokowi-JK mengabaikan Muhammadiyah dalam menyusun Kabinet Kerja 2014- 2015?
Apakah tidak ada profesional dari organisasi yang berdiri sejak 1912 ini yang layak untuk masuk dalam kabinet, termasuk di bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial, bidang-bidang yang telah ditekuni oleh organisasi ini selama lebih dari satu abad? Apakah pengabaian ini terjadi sebagai akibat sampingan dari survei PPIM tahun 2011 lalu, yang merilis bahwa jumlah warga Muhammadiyah di Indonesia jauh lebih kecil dari klaimnya selama ini?
Ataukah ini terjadi karena pilihan sebagian anggota organisasi ini dan partai yang berbasiskan organisasi ini pada masa kampanye presiden? Banyak pertanyaan yang berkaitan dengan absennya kader inti Muhammadiyah dalam Kabinet Kerja Jokowi- JK.
Pertanyaan-pertanyaan itu semakin deras setelah melihat ada enam kader NU (Nahdlatul Ulama) yang masuk dalam kabinet, yaitu M Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan), Marwan Jafar (Menteri PDT dan Transmigrasi), Imam Nahrawi (Menteri Pemuda dan Olahraga), Khofifah Indar Parawansa (Menteri Sosial), M Nasir (Menteri Ristek dan Dikti), dan Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama).
Memang ada beberapa menteri yang memiliki latar belakang Muhammadiyah seperti Siti Nurbaja (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atau konon direkomendasikan oleh Muhammadiyah seperti Nila F Moeloek (Menteri Kesehatan). Namun, tidak ada kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri.
Maksud dari kader inti di sini adalah mereka mendapat pengaderan di Muhammadiyah dan aktif dalam organisasi ini dalam masa yang cukup panjang. Sering dikatakan, beberapa menteri dari NU itu diangkat bukan karena latar belakang ke-NU-annya, melainkan karena mereka berangkat atau diusulkan oleh PKB atau PPP. Satusatunya yang tidak berangkat dari partai atau profesional adalah Khofifah Indar Parawansa yang dalam masa kampanye presiden merupakan anggota tim inti dan juru bicara Jokowi-JK.
Pertanyaannya kemudian adalah apakah tidak ada orang Muhammadiyah dalam tim inti pemenangan Jokowi-JK? Ada beberapa nama dari Muhammadiyah yang masuk tim inti Jokowi-JK, seperti Rizal Sukma, Abdul Munir Mulkhan, dan Malik Fadjar. Bahkan berbeda dari Said Aqil Siradj, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang secara tegas memberikan dukungan kepada Prabowo-Hatta, Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin berusaha bersikap netral selama kampanye.
Konon Rizal Sukma yang merupakan direktur eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan ketua bidang hubungan luar negeri pimpinan pusat Muhammadiyah sudah masuk sebagai calon menteri luar negeri, namun namanya dicoret pada keputusan akhir.
Apakah ini karena dia dari CSIS yang dulu dikenal sebagai think tank Orde Baru, dekat dengan kalangan Kristen, dan dekat dengan konglomerat? Jawabannya tentu ada di Jokowi dan orangorang yang terlibat dalam keputusan akhir. Dugaan lain tentang absennya Muhammadiyah di kabinet Jokowi adalah karena Partai Amanat Nasional (PAN) yang dulu kelahirannya dibidani oleh Muhammadiyah memilih berkoalisi dengan Gerindra untuk mengusung Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden.
Dan dalam beberapa survei, warga Muhammadiyah lebih banyak yang mendukung Prabowo-Hatta dari pada Jokowi-JK. Ini barangkali dugaan terkuat mengapa tidak ada orang Muhammadiyah yang menjadi menteri. Pilihan politik PAN berdampak pada Muhammadiyah. Namun demikian, mengidentikkan Muhammadiyah dengan PAN tentu tak sepenuhnya tepat mengingat hubungan keduanya tak seperti dulu lagi.
Di samping itu, kini banyak pimpinan PAN yang bukan berasal dari Muhammadiyah termasuk ketua umumnya, Hatta Rajasa. Ada lagi yang menduga, meski kemungkinannya sangat kecil, bahwa tiadanya kader inti Muhammadiyah yang menjadi menteri adalah akibat sampingan dari survei yang dikembangkan oleh The Asia Foundation (TAF), Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM), dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2010.
Dari survei yang di antaranya diterbitkan oleh Robin Bush (2014) dalam artikelnya yang berjudul “A snapshot of Muhammadiyah social change and shifting markers of identity and values “ itu, disebutkan bahwa jumlah responden yang menyatakan diri berafiliasi dengan NU berjumlah 49%, sementara yang berafiliasi dengan Muhammadiyah hanya 7,9%.
Angka ini kemudian sering dipakai untuk menarik kesimpulan bahwa warga Indonesia yang berafiliasi ke NU hampir mencapai 50%, sementara warga Indonesia yang Muhammadiyah tidak ada 10%. Kesimpulan ini kemudian dipakai sebagai alat untuk merevisi pandangan sebelumnya, yang didasarkan klaim masingmasing organisasi, bahwa beda antara jumlah warga Muhammadiyah dan NU itu hanya 10 juta orang.
Jika NU memiliki 40 juta anggota, Muhammadiyah memiliki 30 juta warga. Atau, jika 40% dari umat Islam Indonesia secara tradisi adalah warga NU, 30% orang Indonesia adalah Muhammadiyah. Sisanya adalah mengikuti organisasi lain.
Apa konsekuensi dari penelitian PPIM, TAF, dan LSI itu? Ternyata jumlah warga Muhammadiyah tidak sesignifikan yang selama ini dibayangkan. Karena itu, Muhammadiyah bisa diabaikan dalam pembentukan kabinet. Tidak ada keharusan mengangkat menteri dari organisasi yang jumlah warganya kurang dari 10% warga Indonesia ini.
Asumsi di atas, yang didasarkan pada jumlah kepala, tentu tak sejalan dengan kontribusi yang diberikan oleh Muhammadiyah kepada bangsa ini. Di Jawa Timur, misalnya, meski warga Muhammadiyah jauh lebih kecil dari NU, organisasi ini telah menyumbangkepada bangsadalam bentuk pendirian sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, pusat pelayanan sosial hampir di setiap kota dari propinsi itu.
Belum lagi jumlah sekolah, rumah sakit pusat pelayanan sosial yang diberikan oleh Muhammadiyah di provinsi- provinsi lain di Indonesia. Persoalan lain yang berkaitan dengansurvei itu adalah berkaitan dengan metode, kebenaran data, dan kesimpulan. Jika diasumsikan semuanya benar, kemudian pertanyaannya adalah berkaitan dengan perbedaan karakter warga dan organisasi.
NU lebih merupakan budaya, sementara Muhammadiyah adalah organisasi. Orang yang melaksanakan tradisi NU seperti selamatan dan tahlilan akan dengan mudah mengasosiasikan dirinya dengan NU. Sementara di Muhammadiyah, orang yang tidak menjadi pengurus organisasi atau pernah sekolah di Muhammadiyah kadang enggan mengidentifikasi diri sebagai bagian dari Muhammadiyah.
Jadi, meski orang terus menduga-duga tentang absennya Muhammadiyah di kabinet, satu hal yang saya yakin adalah bahwa Muhammadiyah akan terus mengabdi kepada negeri ini meski tak ada anggotanya yang menjadi menteri. Sementara dari pihak Jokowi-JK, keputusan tak memasukkan orang Muhammadiyah adalah sikap kurang mengapresiasi kontribusi organisasi ini untuk bangsa.
(bbg)














