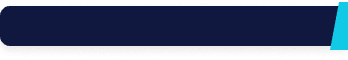Menakar Skema Final DAU 2019

Menakar Skema Final DAU 2019
A
A
A
Haryo Kuncoro
Direktur Riset SEEBI
(the Socio-Economic & Educational Business Institute ) Jakarta
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta
Baru dua tahun diberlakukan, skema pemberian dana alokasi umum (DAU) untuk tiap daerah akan diubah pada 2019. Mengikuti ketentuan sebelumnya, DAU pada tahun anggaran 2017 dan 2018 disalurkan ke daerah dengan skema dinamis mengikuti realisasi penerimaan dalam negeri.
Porsi 26% dari penerimaan dalam negeri tersebut kemudian dialokasikan ke pemerintah daerah kota/kabupaten dan provinsi. Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.
Skema dinamis dalam pembagian DAU sejatinya memiliki maksud baik. Skema ini hendak mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah bahwa penerimaan negara senantiasa memuat unsur ketidakpastian. Konsekuensinya, pemerintah daerah pun sudah sepatutnya ikut menanggung risiko ketidakpastian itu.
Skema fleksibilitas DAU niscaya juga menjadi sarana edukasi fiskal bagi pemerintah daerah. Selama ini pemerintah pusat bekerja keras untuk memastikan penerimaan negara bisa akurat sejak APBN disahkan. Karena itu, pemerintah daerah pun harus melakukan upaya yang setimpal untuk memastikan penerimaan dalam APBD-nya.
Namun, harus diakui pula, skema dinamis memberi efek yang kurang menguntungkan bagi daerah. Penerimaan pemerintah daerah menjadi tidak pasti menyesuaikan dengan capaian pendapatan dalam negeri. Sementara belanja daerah adalah hal yang pasti. Faktanya, daerah siap kalau DAU-nya naik, tapi tidak siap kalau DAU turun.
Dengan argumen kepastian penerimaan daerah, DAU pada 2019 diubah menjadi bersifat final (fixed ). Skema final ini seolah memutar kembali jarum jam ke 2001 saat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai diimplementasikan. Padahal, kondisi saat ini sudah sangat berbeda dengan kondisi keuangan pemerintah daerah pada saat itu.
DAU yang bersifat final pada saat itu lebih banyak didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah daerah tengah mengalami tekanan fiskal (fiscal distress ). Tekanan fiskal bersumber dari ketidakpastian pendapatan asli daerah (PAD) sebagai imbas panjang dari krisis ekonomi 1997/1998.
Lemahnya kondisi keuangan daerah juga diperparah oleh pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menetapkan pemerintah kota/kabupaten hanya boleh memungut enam jenis pajak daerah. Beberapa item pajak yang potensial bagi daerah menjadi hilang atau terhapus.
Sementara itu, UU Nomor 28 Tahun 2008 sebagai revisi atas UU Nomor 18 Tahun 1997 menggariskan kualifikasi pajak daerah dan retribusi daerah bagi kota/kabupaten dan provinsi. Pada gilirannya, kemandirian fiskal akan merawat kepastian belanja sehingga mengakselerasi pembangunan daerah.
Tesis di atas tampaknya tidak kesampaian. Secara rata-rata nasional, kontribusi PAD terhadap APBD hanya sekitar 12,87%. Sedangkan porsi dana transfer dari pusat dalam APBD tetap dominan mencapai 80,1%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya.
Alhasil, penerimaan final DAU yang disertai dengan stagnasi PAD dikhawatirkan membuat pemerintah daerah semakin mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini terjadi hampir pada semua pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten.
Ironisnya lagi, ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22/1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 32/2004.
Ketergantungan fiskal kemungkinan juga bersumber dari eksekusinya. Seperti diketahui, DAU untuk tiap daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiscal gap ) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan nilai gaji PNS daerah.
Di sisi lain, PAD tidak selalu merepresentasikan kapasitas fiskal akibat persaingan pajak (tax competition ) antardaerah. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik penanaman modal akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak menjadi keniscayaan sehingga PAD lebih kecil dari yang seharusnya.
Demikian pula, kebutuhan belanja fiskal daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (expenditures competition ). Belanja pemerintah daerah sangat boleh jadi meningkat tajam lantaran efek limpahan (spillover ) negatif dari daerah lain yang tidak bisa dihindari.
Tren ini semakin terlihat jelas. Untuk 2019, DAU naik dari Rp401,5 triliun pada tahun ini. Pagu DAU nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp414,87 triliun, ditambah dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun. Kenaikan DAU 2019 ini sudah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNS daerah, THR, dan gaji ke-13.
Alhasil, besaran DAU terus mengalami kenaikan dengan rata-rata 4,4% dalam tiga tahun terakhir. Angka ini nyaris sama dengan rata-rata inflasi nasional. Artinya, kenaikan penerimaan daerah dan belanja daerah yang merupakan turunan dari DAU sangat boleh jadi mengikuti kaidah incremental atas dasar laju inflasi yang jauh dari penganggaran matang.
Dengan pola semacam ini pula, kenaikan DAU senantiasa dianggap sebagai tambahan neto penerimaan daerah alih-alih tambahan kewajiban moral untuk ikut menggenjot PAD. Upaya melengkapi kenaikan DAU dengan PAD niscaya menaikkan ongkos politik yang tidak sebanding dengan benefit jika PAD dibikin status quo .
Demikian pula, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi daripada kenaikan DAU itu sendiri. Alhasil, pemerintah daerah, lagi-lagi, menggantungkan pembiayaan APBD pada transfer dari pusat.
Sayangnya, dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance ). Riset empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik dengan governansinya. Intinya, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada uang "hadiah" yang diterima dari pusat.
Berbagai skenario di atas menegaskan responsi pemerintah daerah terhadap perubahan skema pembagian DAU menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas DAU. Tanpa inisiatif perubahan yang berasal dari daerah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tahun ini sudah menginjak usia ke-18 akan semakin menjauh dari filosofi awalnya.
Direktur Riset SEEBI
(the Socio-Economic & Educational Business Institute ) Jakarta
Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta
Baru dua tahun diberlakukan, skema pemberian dana alokasi umum (DAU) untuk tiap daerah akan diubah pada 2019. Mengikuti ketentuan sebelumnya, DAU pada tahun anggaran 2017 dan 2018 disalurkan ke daerah dengan skema dinamis mengikuti realisasi penerimaan dalam negeri.
Porsi 26% dari penerimaan dalam negeri tersebut kemudian dialokasikan ke pemerintah daerah kota/kabupaten dan provinsi. Besaran alokasi DAU per daerah dihitung menggunakan formulasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005.
Skema dinamis dalam pembagian DAU sejatinya memiliki maksud baik. Skema ini hendak mengingatkan kembali kepada pemerintah daerah bahwa penerimaan negara senantiasa memuat unsur ketidakpastian. Konsekuensinya, pemerintah daerah pun sudah sepatutnya ikut menanggung risiko ketidakpastian itu.
Skema fleksibilitas DAU niscaya juga menjadi sarana edukasi fiskal bagi pemerintah daerah. Selama ini pemerintah pusat bekerja keras untuk memastikan penerimaan negara bisa akurat sejak APBN disahkan. Karena itu, pemerintah daerah pun harus melakukan upaya yang setimpal untuk memastikan penerimaan dalam APBD-nya.
Namun, harus diakui pula, skema dinamis memberi efek yang kurang menguntungkan bagi daerah. Penerimaan pemerintah daerah menjadi tidak pasti menyesuaikan dengan capaian pendapatan dalam negeri. Sementara belanja daerah adalah hal yang pasti. Faktanya, daerah siap kalau DAU-nya naik, tapi tidak siap kalau DAU turun.
Dengan argumen kepastian penerimaan daerah, DAU pada 2019 diubah menjadi bersifat final (fixed ). Skema final ini seolah memutar kembali jarum jam ke 2001 saat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal mulai diimplementasikan. Padahal, kondisi saat ini sudah sangat berbeda dengan kondisi keuangan pemerintah daerah pada saat itu.
DAU yang bersifat final pada saat itu lebih banyak didasarkan pada pertimbangan bahwa pemerintah daerah tengah mengalami tekanan fiskal (fiscal distress ). Tekanan fiskal bersumber dari ketidakpastian pendapatan asli daerah (PAD) sebagai imbas panjang dari krisis ekonomi 1997/1998.
Lemahnya kondisi keuangan daerah juga diperparah oleh pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini menetapkan pemerintah kota/kabupaten hanya boleh memungut enam jenis pajak daerah. Beberapa item pajak yang potensial bagi daerah menjadi hilang atau terhapus.
Sementara itu, UU Nomor 28 Tahun 2008 sebagai revisi atas UU Nomor 18 Tahun 1997 menggariskan kualifikasi pajak daerah dan retribusi daerah bagi kota/kabupaten dan provinsi. Pada gilirannya, kemandirian fiskal akan merawat kepastian belanja sehingga mengakselerasi pembangunan daerah.
Tesis di atas tampaknya tidak kesampaian. Secara rata-rata nasional, kontribusi PAD terhadap APBD hanya sekitar 12,87%. Sedangkan porsi dana transfer dari pusat dalam APBD tetap dominan mencapai 80,1%. Implisit, pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya.
Alhasil, penerimaan final DAU yang disertai dengan stagnasi PAD dikhawatirkan membuat pemerintah daerah semakin mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat. Hal ini terjadi hampir pada semua pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kota/kabupaten.
Ironisnya lagi, ketergantungan fiskal terhadap pusat justru lebih parah terjadi pada pemerintah daerah kota/kabupaten. Padahal, level kota/kabupaten inilah titik berat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diletakkan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 22/1999 yang telah diubah menjadi UU Nomor 32/2004.
Ketergantungan fiskal kemungkinan juga bersumber dari eksekusinya. Seperti diketahui, DAU untuk tiap daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal (fiscal gap ) dan alokasi dasar. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal. Sementara alokasi dasar dihitung berdasarkan nilai gaji PNS daerah.
Di sisi lain, PAD tidak selalu merepresentasikan kapasitas fiskal akibat persaingan pajak (tax competition ) antardaerah. Pemotongan pajak lokal secara sepihak oleh satu daerah guna menarik penanaman modal akan diikuti oleh daerah lain agar tidak kehilangan investornya masing-masing. Perang tarif pajak menjadi keniscayaan sehingga PAD lebih kecil dari yang seharusnya.
Demikian pula, kebutuhan belanja fiskal daerah tidak selalu mencerminkan kebutuhan riil masyarakatnya akibat persaingan pengeluaran (expenditures competition ). Belanja pemerintah daerah sangat boleh jadi meningkat tajam lantaran efek limpahan (spillover ) negatif dari daerah lain yang tidak bisa dihindari.
Tren ini semakin terlihat jelas. Untuk 2019, DAU naik dari Rp401,5 triliun pada tahun ini. Pagu DAU nasional yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp414,87 triliun, ditambah dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun. Kenaikan DAU 2019 ini sudah memperhitungkan kenaikan gaji 5%, formasi CPNS daerah, THR, dan gaji ke-13.
Alhasil, besaran DAU terus mengalami kenaikan dengan rata-rata 4,4% dalam tiga tahun terakhir. Angka ini nyaris sama dengan rata-rata inflasi nasional. Artinya, kenaikan penerimaan daerah dan belanja daerah yang merupakan turunan dari DAU sangat boleh jadi mengikuti kaidah incremental atas dasar laju inflasi yang jauh dari penganggaran matang.
Dengan pola semacam ini pula, kenaikan DAU senantiasa dianggap sebagai tambahan neto penerimaan daerah alih-alih tambahan kewajiban moral untuk ikut menggenjot PAD. Upaya melengkapi kenaikan DAU dengan PAD niscaya menaikkan ongkos politik yang tidak sebanding dengan benefit jika PAD dibikin status quo .
Demikian pula, kenaikan DAU dipersepsikan sebagai kenaikan tanggung jawab yang dibebankan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Karena itu, penyesuaian belanja pemerintah daerah akan lebih tinggi daripada kenaikan DAU itu sendiri. Alhasil, pemerintah daerah, lagi-lagi, menggantungkan pembiayaan APBD pada transfer dari pusat.
Sayangnya, dominasi transfer dari pusat tidak diikuti dengan perbaikan pengelolaannya (governance ). Riset empiris Bank Dunia (2001) menunjukkan tingginya ketergantungan pada transfer berbanding terbalik dengan governansinya. Intinya, pemerintah daerah akan lebih berhati-hati dalam mendayagunakan PAD daripada uang "hadiah" yang diterima dari pusat.
Berbagai skenario di atas menegaskan responsi pemerintah daerah terhadap perubahan skema pembagian DAU menjadi determinan penting dalam menunjang efektivitas DAU. Tanpa inisiatif perubahan yang berasal dari daerah, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang tahun ini sudah menginjak usia ke-18 akan semakin menjauh dari filosofi awalnya.
(nag)