Menyongsong Momentum Politik Indonesia
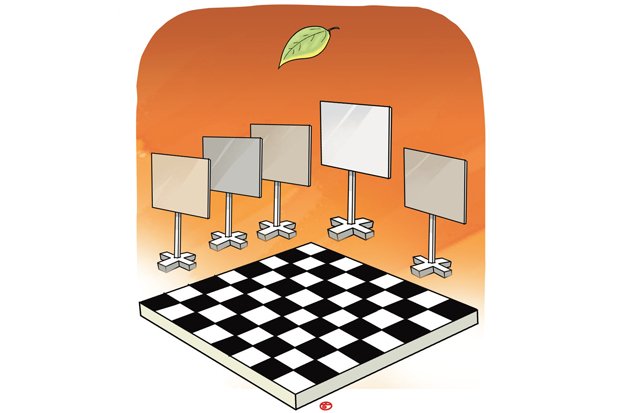
Menyongsong Momentum Politik Indonesia
A
A
A
Syaiful Bahri Ruray
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar
INDONESIA sebagai bangsa yang giat berpolitik, 2018 adalah sebuah tahun politik, dan 2019 sebagai puncaknya. Mungkin saja kita tengah bergiat mengekspresikan diri sebagai makhluk politik sebagaimana kata Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon.
Pada 2018 ini akan berlangsung pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Setelah itu, pada 2019 juga akan berlangsung pemilu legislatif dan pemilu presiden (pileg dan pilpres) secara serentak pula.
Momentum politik akbar ini tentu membutuhkan kesiapan, baik manusia maupun infrastruktur lain sebagai supporting system. Semua itu dilakukan demi sebuah alasan tunggal, yakni tercapai Indonesia sebagai sebuah negeri demokratis. Sebuah cita-cita yang digeluti sejak awal republik ini didirikan 73 tahun silam oleh para the founding fathers.
Demokrasi sendiri sebagai sebuah sistem mengalami jatuh bangun dalam pengalaman Indonesia. Herbert Feith, dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (2007), mengemukakan perjalanan demokrasi Indonesia sejak 1949 hingga 1957 di mana Pemilu 1955 yang tercatat sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia.
Pemilu 1955 ini adalah eksperimentasi demokrasi Indonesia, sayangnya kandas karena kerja Konstituante mengalami perdebatan panjang dalam perang argumentasi ideologis antara kubu Islam, komunis, dan nasionalis, serta berbuntut pada Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959.
Adapun politik Indonesia kontemporer tidak dapat lepas dari fragmentasi politik ideologis Pemilu 1955. Dengan keluarnya Dekrit Presiden Soekarno, masih menurut Herbert Feith, eksperimentasi demokrasi Indonesia saat itu mengalami titik balik menjadi neo-authoritarian style of government, Demokrasi Terpimpin.
Setelah itu tidak ada lagi tercatat pemilu sebagai mekanisme demokrasi hingga akhir kepemimpinan Soekarno yang ditandai dengan tragedi 1965. Meski demikian, situasi global era 1960-an juga turut membuat Indonesia terkooptasi dengan hebatnya pada pertarungan Perang Dingin blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Soviet) saat itu.
Bipolarisasi kekuatan global saat itu seakan tak terhindari dan turut menentukan situasi politik dalam negeri Indonesia. Implikasi domestiknya adalah terjadi pertarungan kekuatan politik dalam negeri yang tak lepas dari intervensi kekuatan besar dunia.
Keluarnya Indonesia dari PBB membuat gusar mata dunia, terutama Amerika Serikat dan blok Baratnya. Ditambah lagi dengan manuver antineokolonialisme (nekolim) sebagai reaksi atas berdirinya negara Federasi Malaya. Soekarno memprakarsai berdirinya New Emerging Forces dengan mengadakan Ganefo sebagai poros ketiga dunia.
Catatan-catatan ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pusaran politik pertarungan global di Asia Tenggara selain Perang Vietnam yang sedang berkecamuk saat itu. Hal yang tak juga luput adalah dukungan Presiden John Fitzgerald Kennedy terhadap Operasi Trikora yang dicanangkan Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Walaupun timbal baliknya Irian Barat menjadi incaran Freeport (1967) sebagai nilai tukarnya bagi Amerika Serikat. There is no free lunch .
Situasi domestik Indonesia, bagaikan takdir, senantiasa terkait dengan kepentingan mancanegara. Sejak Nusantara ini ada, bahkan pasukan Mongol (Meng Khi) yang diutus Kubilai Khan pun pernah dua kali mengirim ekspedisinya untuk menguasai Jawadwipa, namun porak-poranda menghadapi Prabu Raden Wijaya. Jika bangsa ini waspada, sejarah pengaruh mancanegara senantiasa dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia ke depan. Le histoire seLe histoire serepete, sejarah sering berulang.
Demokrasi yang menjadi cita-cita juga adalah bagian dari pergeseran kekuatan global di mana fenomena radikalisme dan sentimen identitas menguat di seantero dunia saat ini. Sesuatu yang juga patut kita waspadai pada momentum politik 2018-2019 ini.
Sebagai bangsa yang bineka tentu terbuka peluang berbagai intervensi kepentingan yang tidak menghendaki bangunan kuatnya Indonesia sebagai nation state. Ketidaksiapan elite politik akan sangat membahayakan bangunan nation state. Perang asimetrik (proxy war) seakan tidak dapat kita hindari.
Merajalelanya peredaran narkoba, radikalisme dan terorisme, juga menguatnya neolib adalah fase-fase proxy war yang tengah kita hadapi. Kepentingan pragmatisme kekuasaan akan dengan mudah dimanfaatkan dalam pertarungan politik dalam negeri.
Seakan kita tidak sadar bahwa Indonesia sedang dalam proses perang besar yang sangat menentukan kokoh dan tidak bangunan Indonesia sebagai nationstate ke depan. Dan, itu sangat ditentukan oleh dua tahun momentum politik 2018-2019.
Pertarungan politik yang tidak dilandasi bangunan etika politik yang kuat akan dengan mudah dimanfaatkan kepentingan radikalisme dan politik identitas yang justru berpotensi menghancurkan bangunan induk kita sebagai sebuah nation state.
Kennichi Ohmae dalam The End of Nation State (2010) bahkan menggambarkan dengan jelas akan berakhirnya negara bangsa karena deru globalisasi yang semakin deras dengan terjadinya arus investasi, informasi, industrialisasi, dan individu yang meningkat mobilitasnya melampaui batas-batas negara bangsa. Batas-batas teritorial negara hanyalah menjadi hal administratif belaka, bukan lagi penghalang dalam globalisasi dewasa ini.
Momentum demokrasi yang kita hadapi seyogianya bukan prosedural belaka, namun kehilangan makna substantifnya. Persoalan kesiapan berdemokrasi kita dalam banyak dimensi masihlah semrawut, terutama tata kelola institusionalnya, baik penyelenggaranya maupun institusi partainya.
Semua harus berbenah diri untuk menyongsong momentum politik ini. Komitmen etika politik institusionalnya juga perlu terbangun baik dan kuat agar kita tidak mengalami kegagalan eksperimentasi demokrasi sebagaimana masa lalu Indonesia era 1950-an.
Potensi konflik horizontal akan terbuka lebar jika isu SARA mengemuka dalam momentum politik ini. Padahal, sesungguhnya momentum ini haruslah dimanfaatkan untuk kontestasi program yang kualitatif sekaligus sebagai pendidikan dan penguatan civil society Indonesia.
Sayangnya, proses rekrutmen yang tidak transparan institusi partai politik dalam pilkada juga menjadi tanda tanya akan kesiapan kita menjemput momentum politik ini secara arif dan transparan. Rakyat sebagai konstituen seharusnya tidak dipersempit perspektifnya sehingga hanya terjebak pada kepentingan pragmatis sesaat atau jangka pendek elite politik semata.
Juga kejujuran perangkat penyelenggara sangat menentukan social trust rakyat terhadap hasil pilkada nanti. Hanyalah keledai yang terantuk pada satu batu untuk kedua kalinya, kata pepatah Arab. Semoga kita bukan bangsa keledai.
Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar
INDONESIA sebagai bangsa yang giat berpolitik, 2018 adalah sebuah tahun politik, dan 2019 sebagai puncaknya. Mungkin saja kita tengah bergiat mengekspresikan diri sebagai makhluk politik sebagaimana kata Aristoteles bahwa manusia adalah zoon politicon.
Pada 2018 ini akan berlangsung pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia. Setelah itu, pada 2019 juga akan berlangsung pemilu legislatif dan pemilu presiden (pileg dan pilpres) secara serentak pula.
Momentum politik akbar ini tentu membutuhkan kesiapan, baik manusia maupun infrastruktur lain sebagai supporting system. Semua itu dilakukan demi sebuah alasan tunggal, yakni tercapai Indonesia sebagai sebuah negeri demokratis. Sebuah cita-cita yang digeluti sejak awal republik ini didirikan 73 tahun silam oleh para the founding fathers.
Demokrasi sendiri sebagai sebuah sistem mengalami jatuh bangun dalam pengalaman Indonesia. Herbert Feith, dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (2007), mengemukakan perjalanan demokrasi Indonesia sejak 1949 hingga 1957 di mana Pemilu 1955 yang tercatat sebagai pemilu paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia.
Pemilu 1955 ini adalah eksperimentasi demokrasi Indonesia, sayangnya kandas karena kerja Konstituante mengalami perdebatan panjang dalam perang argumentasi ideologis antara kubu Islam, komunis, dan nasionalis, serta berbuntut pada Dekrit Presiden Soekarno, 5 Juli 1959.
Adapun politik Indonesia kontemporer tidak dapat lepas dari fragmentasi politik ideologis Pemilu 1955. Dengan keluarnya Dekrit Presiden Soekarno, masih menurut Herbert Feith, eksperimentasi demokrasi Indonesia saat itu mengalami titik balik menjadi neo-authoritarian style of government, Demokrasi Terpimpin.
Setelah itu tidak ada lagi tercatat pemilu sebagai mekanisme demokrasi hingga akhir kepemimpinan Soekarno yang ditandai dengan tragedi 1965. Meski demikian, situasi global era 1960-an juga turut membuat Indonesia terkooptasi dengan hebatnya pada pertarungan Perang Dingin blok Barat (Amerika Serikat) dan blok Timur (Uni Soviet) saat itu.
Bipolarisasi kekuatan global saat itu seakan tak terhindari dan turut menentukan situasi politik dalam negeri Indonesia. Implikasi domestiknya adalah terjadi pertarungan kekuatan politik dalam negeri yang tak lepas dari intervensi kekuatan besar dunia.
Keluarnya Indonesia dari PBB membuat gusar mata dunia, terutama Amerika Serikat dan blok Baratnya. Ditambah lagi dengan manuver antineokolonialisme (nekolim) sebagai reaksi atas berdirinya negara Federasi Malaya. Soekarno memprakarsai berdirinya New Emerging Forces dengan mengadakan Ganefo sebagai poros ketiga dunia.
Catatan-catatan ini menjadikan Indonesia sebagai pusat pusaran politik pertarungan global di Asia Tenggara selain Perang Vietnam yang sedang berkecamuk saat itu. Hal yang tak juga luput adalah dukungan Presiden John Fitzgerald Kennedy terhadap Operasi Trikora yang dicanangkan Soekarno untuk mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi. Walaupun timbal baliknya Irian Barat menjadi incaran Freeport (1967) sebagai nilai tukarnya bagi Amerika Serikat. There is no free lunch .
Situasi domestik Indonesia, bagaikan takdir, senantiasa terkait dengan kepentingan mancanegara. Sejak Nusantara ini ada, bahkan pasukan Mongol (Meng Khi) yang diutus Kubilai Khan pun pernah dua kali mengirim ekspedisinya untuk menguasai Jawadwipa, namun porak-poranda menghadapi Prabu Raden Wijaya. Jika bangsa ini waspada, sejarah pengaruh mancanegara senantiasa dapat dijadikan pelajaran berharga bagi Indonesia ke depan. Le histoire seLe histoire serepete, sejarah sering berulang.
Demokrasi yang menjadi cita-cita juga adalah bagian dari pergeseran kekuatan global di mana fenomena radikalisme dan sentimen identitas menguat di seantero dunia saat ini. Sesuatu yang juga patut kita waspadai pada momentum politik 2018-2019 ini.
Sebagai bangsa yang bineka tentu terbuka peluang berbagai intervensi kepentingan yang tidak menghendaki bangunan kuatnya Indonesia sebagai nation state. Ketidaksiapan elite politik akan sangat membahayakan bangunan nation state. Perang asimetrik (proxy war) seakan tidak dapat kita hindari.
Merajalelanya peredaran narkoba, radikalisme dan terorisme, juga menguatnya neolib adalah fase-fase proxy war yang tengah kita hadapi. Kepentingan pragmatisme kekuasaan akan dengan mudah dimanfaatkan dalam pertarungan politik dalam negeri.
Seakan kita tidak sadar bahwa Indonesia sedang dalam proses perang besar yang sangat menentukan kokoh dan tidak bangunan Indonesia sebagai nationstate ke depan. Dan, itu sangat ditentukan oleh dua tahun momentum politik 2018-2019.
Pertarungan politik yang tidak dilandasi bangunan etika politik yang kuat akan dengan mudah dimanfaatkan kepentingan radikalisme dan politik identitas yang justru berpotensi menghancurkan bangunan induk kita sebagai sebuah nation state.
Kennichi Ohmae dalam The End of Nation State (2010) bahkan menggambarkan dengan jelas akan berakhirnya negara bangsa karena deru globalisasi yang semakin deras dengan terjadinya arus investasi, informasi, industrialisasi, dan individu yang meningkat mobilitasnya melampaui batas-batas negara bangsa. Batas-batas teritorial negara hanyalah menjadi hal administratif belaka, bukan lagi penghalang dalam globalisasi dewasa ini.
Momentum demokrasi yang kita hadapi seyogianya bukan prosedural belaka, namun kehilangan makna substantifnya. Persoalan kesiapan berdemokrasi kita dalam banyak dimensi masihlah semrawut, terutama tata kelola institusionalnya, baik penyelenggaranya maupun institusi partainya.
Semua harus berbenah diri untuk menyongsong momentum politik ini. Komitmen etika politik institusionalnya juga perlu terbangun baik dan kuat agar kita tidak mengalami kegagalan eksperimentasi demokrasi sebagaimana masa lalu Indonesia era 1950-an.
Potensi konflik horizontal akan terbuka lebar jika isu SARA mengemuka dalam momentum politik ini. Padahal, sesungguhnya momentum ini haruslah dimanfaatkan untuk kontestasi program yang kualitatif sekaligus sebagai pendidikan dan penguatan civil society Indonesia.
Sayangnya, proses rekrutmen yang tidak transparan institusi partai politik dalam pilkada juga menjadi tanda tanya akan kesiapan kita menjemput momentum politik ini secara arif dan transparan. Rakyat sebagai konstituen seharusnya tidak dipersempit perspektifnya sehingga hanya terjebak pada kepentingan pragmatis sesaat atau jangka pendek elite politik semata.
Juga kejujuran perangkat penyelenggara sangat menentukan social trust rakyat terhadap hasil pilkada nanti. Hanyalah keledai yang terantuk pada satu batu untuk kedua kalinya, kata pepatah Arab. Semoga kita bukan bangsa keledai.
(thm)














