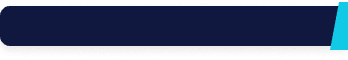Rezim Administrasi Gagal

Rezim Administrasi Gagal
A
A
A
A Alamsyah Saragih
Anggota Ombudsman RI 2016–2021, Bidang Ekonomi
PELAYANAN publik telah menjadi simpul loyalitas warga terhadap suatu institusi bernama negara. Banyak penduduk akhirnya memutuskan berpindah kewarganegaraan atau menjadi pemukim tetap di negara lain demi mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Setidaknya ada dua cara pandang dalam melihat ruang lingkup pelayanan publik. Pertama, cara pandang yang menggunakan sifat kepentingan bersama sebagai kriteria. Penyediaan produk seperti jalan, transportasi umum, dan rumah sakit adalah pelayanan publik––walaupun disediakan oleh badan swasta tanpa penugasan dari otoritas publik tertentu.
Kedua, cara pandang yang menggunakan kriteria penyediaan oleh otoritas publik. Suatu jenis pelayanan oleh badan swasta dinyatakan sebagai pelayanan publik jika badan swasta tersebut mendapat penugasan dari otoritas publik. Aliran ini kemudian dikenal sebagai rezim administrasi.
Terlepas dari perbedaan cara pandang tersebut, keduanya meyakini bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh kuat terhadap kualitas hidup warga negara. Warga kadang tak mungkin mencari penyedia lain meski kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Tak jarang mereka terpaksa membayar melebihi ketentuan untuk mendapatkan pelayanan.
Sejarah Akuntabilitas
Penelusuran akademik mengenai akuntabilitas merujuk pada masa William I yang mensyaratkan para pemilik tanah di wilayah kekuasaannya untuk menghitung luas tanah milik mereka. Nilai tanah milik warga kemudian ditaksir dan didaftar oleh para agen kerajaan dalam sesuatu buku perhitungan yang dikenal sebagai Doomesday Books (Dubnick, 2007).
Dalam perkembangan, beberapa ahli akhirnya berupaya memaknai akuntabilitas sebagai suatu hubungan antara pemegang kedaulatan dan pelaksana. Sering juga dikenal sebagai hubungan antara principle dan agent (Bovens, 2008).
Tak mudah mencarikan padanan kata yang tepat bagi kata akuntabilitas. Di Indonesia akuntabilitas kadang kala diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai tanggung-gugat.
Akuntabilitas memiliki banyak dimensi sehingga digunakan beragam istilah. Akuntabilitas administratif memastikan pelaksana pelayanan bekerja sesuai dengan regulasi dan prosedur baku yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas sosial memastikan apakah pelayanan yang diberikan pelaksana memuaskan masyarakat. Adapun akuntabilitas profesi memastikan apakah pelaksana bekerja sesuai dengan kode etik yang dianut.
Bagi penganut demokrasi, akuntabilitas sosial adalah faktor penentu agar penyelenggaraan negara tak terjebak pada demokrasi prosedural semata. Akuntabilitas sosial dalam pelayanan publik diperlukan agar negara memberikan pilihan terbaik bagi warga sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
Paradoks Akuntabilitas
Antardimensi akuntabilitas sering kali saling bertolak belakang dan saling mereduksi. Dalam taraf tertentu, upaya memacu akuntabilitas administratif dapat membunuh sikap responsif terhadap masyarakat pengguna yang justru menjadi tolok ukur utama akuntabilitas sosial.
Fenomena ini kemudian dinamakan sebagai paradoks akuntabilitas administratif. Beberapa pemikiran untuk mengatasi kecenderungan ini melahirkan gagasan lama yang dikenal sebagai reinventing government (Osborne, 1992).
Untuk memastikan pelayanan publik menjadi lebih responsif, UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) telah mengatur agar penyelenggara pelayanan menyepakati standar pelayanan bersama warga. Selain itu diatur pula mekanisme penanganan pengaduan dan kewajiban melakukan survei kepuasan masyarakat.
Ombudsman RI pada 2016 menemukan bahwa rata-rata pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur UU Pelayanan Publik masih rendah. Kementerian mencapai 44% kewajiban, lembaga pemerintah non-kementerian 66,7%, pemerintah provinsi 33,4%, pemerintah kota 29%, dan pemerintah kabupaten 18%. Semakin rendah tingkatan pemerintahan, semakin tidak patuh terhadap UU Pelayanan Publik.
Namun ditemukan juga bahwa 73,15% penyelenggara pelayanan dengan tingkat pemenuhan tinggi lebih memilih menjalankan standar pelayanan secara top down, bukan membangun kesepakatan bersama warga seperti yang diatur UU Pelayanan Publik.
Baru 53,86% penyelenggara pelayanan dengan tingkat pemenuhan tinggi yang melakukan survei kepuasan masyarakat. Dari yang melakukan, hanya 30,45% yang memublikasikan hasil survei tersebut. Dalam hal aduan masyarakat, hanya 39,4% penyelenggara dengan tingkat pemenuhan tinggi yang mencatatnya. Padahal aduan adalah salah satu umpan balik untuk memperbaiki pelayanan.
Paradoks akuntabilitas administratif tampaknya tengah terjadi di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara bahkan menyatakan bahwa situasi pelayanan publik di negeri ini sudah pada taraf mengerikan (29/10/2016). Terlalu banyak regulasi yang mengatur sehingga penyelenggara pelayanan disibukkan oleh pemenuhan kewajiban administratif daripada melayani masyarakat secara cepat dan memuaskan.
Di sektor publik sering kali penyedia layanan tak memiliki risiko merugi atau bangkrut meski pelayanan mereka tak memuaskan pengguna. Kebijakan reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar seperti terhenti sebatas remunerasi, lelang jabatan dan keterampilan menyusun standar prosedur operasi.
Insentif berbasis kinerja penting, tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana memasukkan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama kinerja, mendorong menyepakati standar pelayanan bersama warga dan menangani pengaduan tepat waktu. Peraturan yang mengekang kreativitas penyelenggara mesti dikurangi. Sungguh suatu pekerjaan rumah yang tak ringan di tengah dominasi rezim administrasi yang positivistik dan sangat mengandalkan otoritas.
Anggota Ombudsman RI 2016–2021, Bidang Ekonomi
PELAYANAN publik telah menjadi simpul loyalitas warga terhadap suatu institusi bernama negara. Banyak penduduk akhirnya memutuskan berpindah kewarganegaraan atau menjadi pemukim tetap di negara lain demi mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik.
Setidaknya ada dua cara pandang dalam melihat ruang lingkup pelayanan publik. Pertama, cara pandang yang menggunakan sifat kepentingan bersama sebagai kriteria. Penyediaan produk seperti jalan, transportasi umum, dan rumah sakit adalah pelayanan publik––walaupun disediakan oleh badan swasta tanpa penugasan dari otoritas publik tertentu.
Kedua, cara pandang yang menggunakan kriteria penyediaan oleh otoritas publik. Suatu jenis pelayanan oleh badan swasta dinyatakan sebagai pelayanan publik jika badan swasta tersebut mendapat penugasan dari otoritas publik. Aliran ini kemudian dikenal sebagai rezim administrasi.
Terlepas dari perbedaan cara pandang tersebut, keduanya meyakini bahwa akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh kuat terhadap kualitas hidup warga negara. Warga kadang tak mungkin mencari penyedia lain meski kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Tak jarang mereka terpaksa membayar melebihi ketentuan untuk mendapatkan pelayanan.
Sejarah Akuntabilitas
Penelusuran akademik mengenai akuntabilitas merujuk pada masa William I yang mensyaratkan para pemilik tanah di wilayah kekuasaannya untuk menghitung luas tanah milik mereka. Nilai tanah milik warga kemudian ditaksir dan didaftar oleh para agen kerajaan dalam sesuatu buku perhitungan yang dikenal sebagai Doomesday Books (Dubnick, 2007).
Dalam perkembangan, beberapa ahli akhirnya berupaya memaknai akuntabilitas sebagai suatu hubungan antara pemegang kedaulatan dan pelaksana. Sering juga dikenal sebagai hubungan antara principle dan agent (Bovens, 2008).
Tak mudah mencarikan padanan kata yang tepat bagi kata akuntabilitas. Di Indonesia akuntabilitas kadang kala diterjemahkan sebagai pertanggungjawaban, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai tanggung-gugat.
Akuntabilitas memiliki banyak dimensi sehingga digunakan beragam istilah. Akuntabilitas administratif memastikan pelaksana pelayanan bekerja sesuai dengan regulasi dan prosedur baku yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas sosial memastikan apakah pelayanan yang diberikan pelaksana memuaskan masyarakat. Adapun akuntabilitas profesi memastikan apakah pelaksana bekerja sesuai dengan kode etik yang dianut.
Bagi penganut demokrasi, akuntabilitas sosial adalah faktor penentu agar penyelenggaraan negara tak terjebak pada demokrasi prosedural semata. Akuntabilitas sosial dalam pelayanan publik diperlukan agar negara memberikan pilihan terbaik bagi warga sesuai dengan sumber daya yang tersedia.
Paradoks Akuntabilitas
Antardimensi akuntabilitas sering kali saling bertolak belakang dan saling mereduksi. Dalam taraf tertentu, upaya memacu akuntabilitas administratif dapat membunuh sikap responsif terhadap masyarakat pengguna yang justru menjadi tolok ukur utama akuntabilitas sosial.
Fenomena ini kemudian dinamakan sebagai paradoks akuntabilitas administratif. Beberapa pemikiran untuk mengatasi kecenderungan ini melahirkan gagasan lama yang dikenal sebagai reinventing government (Osborne, 1992).
Untuk memastikan pelayanan publik menjadi lebih responsif, UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik (UU Pelayanan Publik) telah mengatur agar penyelenggara pelayanan menyepakati standar pelayanan bersama warga. Selain itu diatur pula mekanisme penanganan pengaduan dan kewajiban melakukan survei kepuasan masyarakat.
Ombudsman RI pada 2016 menemukan bahwa rata-rata pemenuhan kewajiban sebagaimana diatur UU Pelayanan Publik masih rendah. Kementerian mencapai 44% kewajiban, lembaga pemerintah non-kementerian 66,7%, pemerintah provinsi 33,4%, pemerintah kota 29%, dan pemerintah kabupaten 18%. Semakin rendah tingkatan pemerintahan, semakin tidak patuh terhadap UU Pelayanan Publik.
Namun ditemukan juga bahwa 73,15% penyelenggara pelayanan dengan tingkat pemenuhan tinggi lebih memilih menjalankan standar pelayanan secara top down, bukan membangun kesepakatan bersama warga seperti yang diatur UU Pelayanan Publik.
Baru 53,86% penyelenggara pelayanan dengan tingkat pemenuhan tinggi yang melakukan survei kepuasan masyarakat. Dari yang melakukan, hanya 30,45% yang memublikasikan hasil survei tersebut. Dalam hal aduan masyarakat, hanya 39,4% penyelenggara dengan tingkat pemenuhan tinggi yang mencatatnya. Padahal aduan adalah salah satu umpan balik untuk memperbaiki pelayanan.
Paradoks akuntabilitas administratif tampaknya tengah terjadi di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara bahkan menyatakan bahwa situasi pelayanan publik di negeri ini sudah pada taraf mengerikan (29/10/2016). Terlalu banyak regulasi yang mengatur sehingga penyelenggara pelayanan disibukkan oleh pemenuhan kewajiban administratif daripada melayani masyarakat secara cepat dan memuaskan.
Di sektor publik sering kali penyedia layanan tak memiliki risiko merugi atau bangkrut meski pelayanan mereka tak memuaskan pengguna. Kebijakan reformasi birokrasi yang diharapkan dapat menjadi jalan keluar seperti terhenti sebatas remunerasi, lelang jabatan dan keterampilan menyusun standar prosedur operasi.
Insentif berbasis kinerja penting, tetapi tantangan ke depan adalah bagaimana memasukkan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur utama kinerja, mendorong menyepakati standar pelayanan bersama warga dan menangani pengaduan tepat waktu. Peraturan yang mengekang kreativitas penyelenggara mesti dikurangi. Sungguh suatu pekerjaan rumah yang tak ringan di tengah dominasi rezim administrasi yang positivistik dan sangat mengandalkan otoritas.
(poe)