Obesitas Regulasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia
loading...
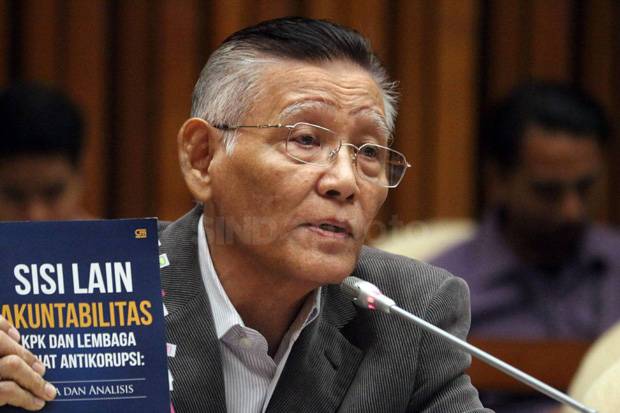
Romli Atmasasmita (Ist)
A
A
A
ROMLI ATMASASMITA
Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran
PADA 10 Desember 2021, Hari Anti Korupsi sedunia diperingati dengan
meriah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian meriahnya perayaan tidak sebanding dengan kenyataan yang tengah dialami dalam praktik memerangi korupsi. Diakui, memang terjadi keberhasilan dari sisi kuantitas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dengan jumlah koruptor yang semakin meningkat. Pada 2020, mencapai 340 (tiga ratus empat puluh) penyelenggara negara yang terjerat, mereka berasal dari pusat dan daerah.
Namun, di tengah-tengah keberhasilan tersebut, terdapat keganjilan perilaku aparat penegak hukum (APH), khusus penyidik dan penuntut yang masih belum memahami asas praduga tak bersalah. Sebagai contoh, pemberitaan kepada pers dan masyarakat terkait seseorang yang masih dalam status tersangka, seolah yang bersangkutan sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Begitu juga hakim yang masih belum memahami asas hukum ultimun remedium dalam penerapan hukum atas suatu peristiwa diduga perkara pidana padahal objek pokok perkara adalah perkara perdata atau pelanggaran yang bersifat administrasi. Misalnya, terkait undang-undang (UU) sektoral dan UU ASN atau UU Korporasi dan Ketentuan KUHPdt. Sejak di Fakultas Hukum telah diajarkan pembedaan kelompok hukum pidana dan hukum lainnya, misalnya hukum perdata dan hukum administrasi pemerintahan, begitu juga dengan hukum keuangan negara. Keadaan perlintasan hukum yang menganut hukum sektoral (yang bersifat administratif), hukum pidana dan hukum keuangan negara, serta hukum perseroan terbatas, ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi (UU PK). UU PK berbeda dengan UU lain pada umumnya yang bersifat one single regulation, seperti terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PK, yang memiliki 6 (enam ) aspek hukum di dalamnya, yaitu aspek hukum administrasi pemerintahan, 3 (tiga) kelompok undang-undang tentang keuangan negara, hukum korporasi dan hukum pidana.
Dalam keadaan multiaspek di mana peraturan tersebut tanpa petunjuk normatif, bagaimana penerapan hukum yang seharusnya dilakukan, menimbulkan kesimpang-siuran tafsir hukum dalam penerapannya, termasuk domain hukum yang mana yang harus didahulukan penerapannya.
Perdebatan di antara pakar dari keenam aspek hukum tersebut tidak menggoyahkan pendirian hakim pengadilan tipikor. Pertimbangannya adalah bahwa keterangan ahli dalam sidang pengadilan hanya merupakan keterangan saja, dan diakui hakim jika hakim menilai keterangan ahli memberikan kontribusi kepada keyakinannya dalam mempertimbangkan untuk memutus perkara yang dihadapinya.
Bahkan ada hakim yang berpendapat bahwa perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan adalah domain keyakinan hakim, bukan para pihak lainnya yakni jaksa atau penasihat hukum (PH).
Terlepas dari kelaziman praktik peradilan sidang tipikor selama ini masih juga ada hakim tipikor yang menjatuhkan putusan lepas dari penuntutan atau putusan bebas. Kelaziman praktik tersebut bukan satu jaminan perkara akan dijatuhi putusan yang sama pada pemeriksaan pada tingkat kasasi; namun 99% putusan adalah dijatuhi hukuman atau dilepas dari penuntutan. Namun yang pasti sesuai dengan KUHP dan KUHAP sebagai payung hukum beracara lebih diutamakan daripada sumber hukum di luar UU (hukum tertulis). Tidak ada yang salah dalam hal tersebut akan tetapi dalam konteks UU PK yang memiliki karakter multi-aspek diperlukan pandangan baru (new outlook) yang dapat menguraikan secara sistematis-logis sesuai dengan asas-asas umum hukum pidana yang bersifat mendasar, asas proporsionalitas dan asas subsidiaritias (J. Remmenlink).
Awal mula dari kekeliruan penerapan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) atas pengaturan UU yang bersifat multi-aspek hukum adalah bersumber pada UU P3 (UU Nomor 12 Tahun 2011) itu sendiri yang merupakan payung hukum (umbrella act). Dan, sesungguhnya ini tidak cocok bagi pembentukan suatu pengaturan yang bersifat multi-aspek hukum yang bertujuan mengharmonisasi dan mensinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Dengan harmonisasi dan sinkronisasi tersebut diharapkan tercapai kepastian hukum, keadilan dan dapat memberikan kemanfaatan sosial terbesar bagi para pemangku kepentingan. UU No 12 Tahun 2011/UU P3 tidak disiapkan untuk pembentukan suatu UU yang bersifat multi-aspect regulation karena proses pembentukannya bertujuan untuk membentuk satu objek pengaturan saja. Dibandingkan situasi pasca PD II dengan perkembangan paham tentang hukum dan pembangunan (law and development) yang terjadi pada perkembangan tahap dua, Globalisasi Dunia; UU P3 jelas gagap menghadapi pengaturan yang bersifat multidimensi dan karakter dan yang saling berhubungan satu dan lainnya. Perkembangan globalisasi tahap ketiga pasca-1990, ternyata masalah hukum dan pembangunan (law and development) yang dihadapi bersifat multidimensional, juga masalah sosial, ekonomi, politik perdagangan internasional dan arus intervensi hukum asing semakin kompleks yang memerlukan pendekatan mulitiaspek hukum terkait di dalamnya.
Penerapan UU P3 dipastikan tidak akan efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pemangku kepentingan karena akan menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran hukum oleh APH dan PH serta para Ahli, begitu juga Hakim.
Berdasarkan uraian di atas, sudah saatnya, walaupun terlambat; pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk UU segera mempertimbangkan UU Omnibus Pemberantasan Korupsi yang mengatur kelima aspek hukum yang bertujuan pada pencegahan dan penindakan represif tindak pidana korupsi. Namun sebelum hal tersebut dipersiapkan diperlukan revisi UU P3 dengan metode omnibus yang dapat menjadi payung hukum (umbrella act) untuk pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang sejenis.
Guru Besar Hukum Universitas Padjadjaran
PADA 10 Desember 2021, Hari Anti Korupsi sedunia diperingati dengan
meriah di berbagai negara, termasuk Indonesia. Namun demikian meriahnya perayaan tidak sebanding dengan kenyataan yang tengah dialami dalam praktik memerangi korupsi. Diakui, memang terjadi keberhasilan dari sisi kuantitas perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dengan jumlah koruptor yang semakin meningkat. Pada 2020, mencapai 340 (tiga ratus empat puluh) penyelenggara negara yang terjerat, mereka berasal dari pusat dan daerah.
Namun, di tengah-tengah keberhasilan tersebut, terdapat keganjilan perilaku aparat penegak hukum (APH), khusus penyidik dan penuntut yang masih belum memahami asas praduga tak bersalah. Sebagai contoh, pemberitaan kepada pers dan masyarakat terkait seseorang yang masih dalam status tersangka, seolah yang bersangkutan sudah dianggap bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Begitu juga hakim yang masih belum memahami asas hukum ultimun remedium dalam penerapan hukum atas suatu peristiwa diduga perkara pidana padahal objek pokok perkara adalah perkara perdata atau pelanggaran yang bersifat administrasi. Misalnya, terkait undang-undang (UU) sektoral dan UU ASN atau UU Korporasi dan Ketentuan KUHPdt. Sejak di Fakultas Hukum telah diajarkan pembedaan kelompok hukum pidana dan hukum lainnya, misalnya hukum perdata dan hukum administrasi pemerintahan, begitu juga dengan hukum keuangan negara. Keadaan perlintasan hukum yang menganut hukum sektoral (yang bersifat administratif), hukum pidana dan hukum keuangan negara, serta hukum perseroan terbatas, ditemukan dalam ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi (UU PK). UU PK berbeda dengan UU lain pada umumnya yang bersifat one single regulation, seperti terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PK, yang memiliki 6 (enam ) aspek hukum di dalamnya, yaitu aspek hukum administrasi pemerintahan, 3 (tiga) kelompok undang-undang tentang keuangan negara, hukum korporasi dan hukum pidana.
Dalam keadaan multiaspek di mana peraturan tersebut tanpa petunjuk normatif, bagaimana penerapan hukum yang seharusnya dilakukan, menimbulkan kesimpang-siuran tafsir hukum dalam penerapannya, termasuk domain hukum yang mana yang harus didahulukan penerapannya.
Perdebatan di antara pakar dari keenam aspek hukum tersebut tidak menggoyahkan pendirian hakim pengadilan tipikor. Pertimbangannya adalah bahwa keterangan ahli dalam sidang pengadilan hanya merupakan keterangan saja, dan diakui hakim jika hakim menilai keterangan ahli memberikan kontribusi kepada keyakinannya dalam mempertimbangkan untuk memutus perkara yang dihadapinya.
Bahkan ada hakim yang berpendapat bahwa perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan adalah domain keyakinan hakim, bukan para pihak lainnya yakni jaksa atau penasihat hukum (PH).
Terlepas dari kelaziman praktik peradilan sidang tipikor selama ini masih juga ada hakim tipikor yang menjatuhkan putusan lepas dari penuntutan atau putusan bebas. Kelaziman praktik tersebut bukan satu jaminan perkara akan dijatuhi putusan yang sama pada pemeriksaan pada tingkat kasasi; namun 99% putusan adalah dijatuhi hukuman atau dilepas dari penuntutan. Namun yang pasti sesuai dengan KUHP dan KUHAP sebagai payung hukum beracara lebih diutamakan daripada sumber hukum di luar UU (hukum tertulis). Tidak ada yang salah dalam hal tersebut akan tetapi dalam konteks UU PK yang memiliki karakter multi-aspek diperlukan pandangan baru (new outlook) yang dapat menguraikan secara sistematis-logis sesuai dengan asas-asas umum hukum pidana yang bersifat mendasar, asas proporsionalitas dan asas subsidiaritias (J. Remmenlink).
Awal mula dari kekeliruan penerapan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) atas pengaturan UU yang bersifat multi-aspek hukum adalah bersumber pada UU P3 (UU Nomor 12 Tahun 2011) itu sendiri yang merupakan payung hukum (umbrella act). Dan, sesungguhnya ini tidak cocok bagi pembentukan suatu pengaturan yang bersifat multi-aspek hukum yang bertujuan mengharmonisasi dan mensinkronisasi peraturan perundang-undangan.
Dengan harmonisasi dan sinkronisasi tersebut diharapkan tercapai kepastian hukum, keadilan dan dapat memberikan kemanfaatan sosial terbesar bagi para pemangku kepentingan. UU No 12 Tahun 2011/UU P3 tidak disiapkan untuk pembentukan suatu UU yang bersifat multi-aspect regulation karena proses pembentukannya bertujuan untuk membentuk satu objek pengaturan saja. Dibandingkan situasi pasca PD II dengan perkembangan paham tentang hukum dan pembangunan (law and development) yang terjadi pada perkembangan tahap dua, Globalisasi Dunia; UU P3 jelas gagap menghadapi pengaturan yang bersifat multidimensi dan karakter dan yang saling berhubungan satu dan lainnya. Perkembangan globalisasi tahap ketiga pasca-1990, ternyata masalah hukum dan pembangunan (law and development) yang dihadapi bersifat multidimensional, juga masalah sosial, ekonomi, politik perdagangan internasional dan arus intervensi hukum asing semakin kompleks yang memerlukan pendekatan mulitiaspek hukum terkait di dalamnya.
Penerapan UU P3 dipastikan tidak akan efektif dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pemangku kepentingan karena akan menimbulkan kesimpangsiuran penafsiran hukum oleh APH dan PH serta para Ahli, begitu juga Hakim.
Berdasarkan uraian di atas, sudah saatnya, walaupun terlambat; pemerintah dan DPR RI sebagai pembentuk UU segera mempertimbangkan UU Omnibus Pemberantasan Korupsi yang mengatur kelima aspek hukum yang bertujuan pada pencegahan dan penindakan represif tindak pidana korupsi. Namun sebelum hal tersebut dipersiapkan diperlukan revisi UU P3 dengan metode omnibus yang dapat menjadi payung hukum (umbrella act) untuk pembentukan peraturan perundang-undangan lain yang sejenis.
(bmm)
Lihat Juga :

























