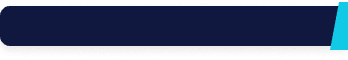Politik Normalisasi Amerika Serikat

Politik Normalisasi Amerika Serikat
A
A
A
Presiden Barack Obama mungkin adalah orang yang paling tidak populer saat ini di Amerika Serikat (AS) terkait normalisasi hubungan politik dengan Kuba dan Iran.
Politisi dari kubu Republik adalah yang terdepan menyerang kebijakan normalisasi terhadap dua negara tersebut. Alasannya, keyakinan bahwa dua negara tersebut tidak melakukan perubahan apa pun terkait demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Pernyataan itu sejalan dengan laporan HAM Amerika yang terbit pada minggu lalu.
Laporan ini biasanya menjadi rujukan bagi organisasi, baik organisasi politik atau bukan, untuk menindaklanjuti atau menghentikan hubungan kerja sama dengan negara-negara yang teridentifikasi sebagai pelanggar HAM. Ini mungkin ironis karena di sisi lain AS juga dianggap sebagai pelanggar HAM karena aksiaksi militer mereka di beberapa negara Timur Tengah dalam sepuluh tahun terakhir ini.
Terlepas dari paradoks tersebut, laporan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS telah mengecam Kuba karena tidak memberikan izin kepada tokoh-tokoh politik yang beroposisi kepada pemerintahan Kuba untuk masuk ke Kuba atau mengganggu mereka ketika kembali ke sana.
Seperti kita ketahui bahwa kemudahan untuk pergi dari dan menuju Kuba dari AS adalah produk politik yang terjadi setelah berhasilnya negosiasi untuk menormalisasi hubungan dua negara atas fasilitasi Vatikan dan Kanada sejak tahun lalu.
Senada dengan kritik atas praktik demokrasi di Kuba yang dianggap minim, Iran juga disebutkan sebagai negara totaliter yang mengekang kebebasan berpendapat, menghukum orang tanpa melalui pengadilan yang terbuka, melakukan hukuman mati, atau melakukan intimidasi kepada lawan-lawan politiknya.
Saya tidak berusaha untuk mendukung atau membantah isi laporan tersebut karena dalam urusan diplomasi segala sesuatu adalah politis; pasti terkait langsung atau tidak dengan pilihan kebijakan di dalam maupun luar negeri. Isi laporan baik atau buruknya akan bergantung pada kepentingan politik si pembuat laporan.
Ambil contoh keterlambatan laporan HAM yang baru disampaikan pada minggu lalu. Foreign Assistance Act of 1961 Section 116(d) sebetulnya telah mensyaratkan administrasi pemerintahan AS untuk mengirimkan kepada Kongres sebuah laporan penilaian praktik HAM seluruh negara di dunia setiap tanggal 25 Februari.
Obama terlambat. Keterlambatan itu mengundang kecaman dari publik di AS sekaligus sinisme bahwa laporan tersebut akan dipengaruhi oleh hasil perundingan yang sedang berlangsung, terutama dengan Iran. Bila perundingan itu gagal, apakah laporan itu akan berubah menjadi lebih kritis atau lebih moderat? Di dalam negeri sendiri, laporan itu mungkin juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat AS.
Dalam konteks hubungan dengan Kuba, survei Gallup selama 1999-2015 memperlihatkan bahwa masyarakat AS cenderung mendukung penataan kembali hubungan AS dan Kuba. Angka yang mendukung adalah ratarata di atas 50% dibandingkan mereka yang menolak. Mereka yang menyetujui embargo ekonomi dihentikan terhadap Kuba juga berada di atas 50%.
Persepsi masyarakat terhadap Iran lebih negatif ketimbang kepada Kuba. Survei dari lembaga yang sama menunjukkan bahwa sejak 1990, Iran mendapatkan persepsi yang negatif di mata masyarakat AS. Angka mereka yang positif tidak lebih dari 20%. Persepsi yang lebih positif terhadap Iran paling tinggi terjadi pada 2004 sebesar 17%.
Ini mungkin terkait pembukaan akses PBB untuk menginvestigasi fasilitas nuklir mereka, atau laporan intelijen AS yang menyebutkan Iran telah menghentikan upaya untuk membuat senjata nuklir diakhir 2003, atau mungkin juga karena AS tidak menemukan kaitan antara Iran dan serangan 9/11. Apabila kita meletakkan gambar-gambar tersebut dalam satu cerita, mungkin kita akan bingung.
Mengapa AS mau menormalisasi hubungan dengan dua negara yang di dalam laporan mereka sendiri dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang selama ini diagung-agungkan oleh politik Amerika? Banyak analis yang menganut paham idealis akan menganggap itu sebagai anomali, tetapi untuk mereka yang menganut paham rationalchoice (pilihan rasional) akan menganggapnya sebagai konsistensi.
Paham rational choice mengasumsikan bahwa individu mengambil pilihan dari ragam opsi yang ada berdasarkan ranking keuntungan yang mereka ketahui secara lengkap dan sesuai prinsip pilihan yang sifatnya transitif. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi berbasis analisa cost-benefit .
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada masyarakat, Presiden Obama dan birokrasinya selalu mengatakan bahwa normalisasi terhadap Kuba dan Iran salah satu terobosan baru dalam diplomasi AS setelah mereka sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan lama yang mengutamakan sanksi dan embargo tidak berhasil mengubah perilaku dua negara tersebut untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi liberal Barat.
AS berharap, dengan normalisasi hubungan diplomatik terhadap dua negara tersebut, demokrasi justru akan datang secara perlahanlahan. Dua negara tersebut akan terpapar oleh nilai-nilai demokrasi Barat yang datang seiring dengan investasi yang ditanam di negara tersebut. Pernyataan itu terdengar sangat demokratis dan egaliter, tetapi nyatanya itu bukan sesuatu yang baru dan mungkin juga bukan maksud sesungguhnya.
Walau dengan kata yang berbeda, cost-benefit dari normalisasi dalam politik luar negeri salah satunya untuk mendistribusikan kekuatan regional dan membuka pasar baru untuk menampung produksi ekonomi. Saya mengatakan itu bukan hal yang baru karena pada 1972, Richard Nixon, seorang presiden ke-37 dan politikus antikomunis dari kubu Republik, juga telah menormalisasikan hubungan AS dengan China yang menganut ideologi sama dengan Kuba saat ini.
China pada masa itu juga tidak lebih demokratis ketimbang Iran saat ini. Motivasi utama dari normalisasi dengan China saat itu adalah demi memecahkan kekuatan ideologi sosialis agar tidak lagi terpusat di tangan Uni- Soviet. AS bisa langsung melakukan negosiasi dengan China terkait upaya untuk menstabilisasi politik kawasan, khususnya di wilayah Asia.
AS bahkan bersedia mengakui Taiwan sebagai bagian dari China sebagai kompensasinya. Dari sisi perdagangan, China adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia yang dapat menyerap ekspor manufaktur dan investasi dari AS. Ini yang kemudian terbukti dari sejarah perdagangan antara China-Amerika sejak normalisasi pada 1972.
Pada awal normalisasi nilai perdagangan mereka hanya USD4,7 juta, namun pada 2014 telah mencapai USD536,2 miliar. China bahkan telah menjadi negara dengan nilai perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan AS saat ini (Dong Wang 2013). Saya memandang bahwa hal yang sama akan terjadi pada hubunganAS dengan Iran dan Kuba walau pengawalan atas kebijakan normalisasi akan berbeda sesuai konteks dua negara tersebut.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry misalnya mengatakan bahwa tujuan dari negosiasi dengan Iran bukanlah untuk menyelesaikan masalah HAM, melainkan bagaimana membuat negara tersebut tidak dapat memproduksi senjata nuklir. Dengan kata lain, masalah politik dalam negeri Iran tampaknya tidak menjadi prioritas bagi AS. Ini berbeda dengan Kuba yang mendapat sorotan, terutama dalam praktik penyelenggaraan HAM-nya.
Amerika mengatakan bahwa mereka akan lebih serius ”mendampingi” Kuba untuk mereformasi sistem politiknya. Pernyataan ini tidak lepas dari banyak warga Kuba dan tokoh politik yang lari ke Amerika dan menggalang dukungan politik dari dalam sana.
Dari perkembangan ini, apakah artinya faktor moral dan nilai semakin tidak lagi punya tempat dalam politik luar negeri di dunia? Atau, memang faktor moral dan nilai sekadar menjadi jembatan bagi pencapaian kepentingan ekonomi semata?
DINNA WISNU, PhD
Pengamat Hubungan Internasional, Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy @dinnawisnu
Politisi dari kubu Republik adalah yang terdepan menyerang kebijakan normalisasi terhadap dua negara tersebut. Alasannya, keyakinan bahwa dua negara tersebut tidak melakukan perubahan apa pun terkait demokrasi dan hak asasi manusia (HAM). Pernyataan itu sejalan dengan laporan HAM Amerika yang terbit pada minggu lalu.
Laporan ini biasanya menjadi rujukan bagi organisasi, baik organisasi politik atau bukan, untuk menindaklanjuti atau menghentikan hubungan kerja sama dengan negara-negara yang teridentifikasi sebagai pelanggar HAM. Ini mungkin ironis karena di sisi lain AS juga dianggap sebagai pelanggar HAM karena aksiaksi militer mereka di beberapa negara Timur Tengah dalam sepuluh tahun terakhir ini.
Terlepas dari paradoks tersebut, laporan yang dikeluarkan Departemen Luar Negeri AS telah mengecam Kuba karena tidak memberikan izin kepada tokoh-tokoh politik yang beroposisi kepada pemerintahan Kuba untuk masuk ke Kuba atau mengganggu mereka ketika kembali ke sana.
Seperti kita ketahui bahwa kemudahan untuk pergi dari dan menuju Kuba dari AS adalah produk politik yang terjadi setelah berhasilnya negosiasi untuk menormalisasi hubungan dua negara atas fasilitasi Vatikan dan Kanada sejak tahun lalu.
Senada dengan kritik atas praktik demokrasi di Kuba yang dianggap minim, Iran juga disebutkan sebagai negara totaliter yang mengekang kebebasan berpendapat, menghukum orang tanpa melalui pengadilan yang terbuka, melakukan hukuman mati, atau melakukan intimidasi kepada lawan-lawan politiknya.
Saya tidak berusaha untuk mendukung atau membantah isi laporan tersebut karena dalam urusan diplomasi segala sesuatu adalah politis; pasti terkait langsung atau tidak dengan pilihan kebijakan di dalam maupun luar negeri. Isi laporan baik atau buruknya akan bergantung pada kepentingan politik si pembuat laporan.
Ambil contoh keterlambatan laporan HAM yang baru disampaikan pada minggu lalu. Foreign Assistance Act of 1961 Section 116(d) sebetulnya telah mensyaratkan administrasi pemerintahan AS untuk mengirimkan kepada Kongres sebuah laporan penilaian praktik HAM seluruh negara di dunia setiap tanggal 25 Februari.
Obama terlambat. Keterlambatan itu mengundang kecaman dari publik di AS sekaligus sinisme bahwa laporan tersebut akan dipengaruhi oleh hasil perundingan yang sedang berlangsung, terutama dengan Iran. Bila perundingan itu gagal, apakah laporan itu akan berubah menjadi lebih kritis atau lebih moderat? Di dalam negeri sendiri, laporan itu mungkin juga tidak banyak diketahui oleh masyarakat AS.
Dalam konteks hubungan dengan Kuba, survei Gallup selama 1999-2015 memperlihatkan bahwa masyarakat AS cenderung mendukung penataan kembali hubungan AS dan Kuba. Angka yang mendukung adalah ratarata di atas 50% dibandingkan mereka yang menolak. Mereka yang menyetujui embargo ekonomi dihentikan terhadap Kuba juga berada di atas 50%.
Persepsi masyarakat terhadap Iran lebih negatif ketimbang kepada Kuba. Survei dari lembaga yang sama menunjukkan bahwa sejak 1990, Iran mendapatkan persepsi yang negatif di mata masyarakat AS. Angka mereka yang positif tidak lebih dari 20%. Persepsi yang lebih positif terhadap Iran paling tinggi terjadi pada 2004 sebesar 17%.
Ini mungkin terkait pembukaan akses PBB untuk menginvestigasi fasilitas nuklir mereka, atau laporan intelijen AS yang menyebutkan Iran telah menghentikan upaya untuk membuat senjata nuklir diakhir 2003, atau mungkin juga karena AS tidak menemukan kaitan antara Iran dan serangan 9/11. Apabila kita meletakkan gambar-gambar tersebut dalam satu cerita, mungkin kita akan bingung.
Mengapa AS mau menormalisasi hubungan dengan dua negara yang di dalam laporan mereka sendiri dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang selama ini diagung-agungkan oleh politik Amerika? Banyak analis yang menganut paham idealis akan menganggap itu sebagai anomali, tetapi untuk mereka yang menganut paham rationalchoice (pilihan rasional) akan menganggapnya sebagai konsistensi.
Paham rational choice mengasumsikan bahwa individu mengambil pilihan dari ragam opsi yang ada berdasarkan ranking keuntungan yang mereka ketahui secara lengkap dan sesuai prinsip pilihan yang sifatnya transitif. Keputusan diambil berdasarkan pertimbangan ekonomi berbasis analisa cost-benefit .
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada masyarakat, Presiden Obama dan birokrasinya selalu mengatakan bahwa normalisasi terhadap Kuba dan Iran salah satu terobosan baru dalam diplomasi AS setelah mereka sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan lama yang mengutamakan sanksi dan embargo tidak berhasil mengubah perilaku dua negara tersebut untuk mengadopsi nilai-nilai demokrasi liberal Barat.
AS berharap, dengan normalisasi hubungan diplomatik terhadap dua negara tersebut, demokrasi justru akan datang secara perlahanlahan. Dua negara tersebut akan terpapar oleh nilai-nilai demokrasi Barat yang datang seiring dengan investasi yang ditanam di negara tersebut. Pernyataan itu terdengar sangat demokratis dan egaliter, tetapi nyatanya itu bukan sesuatu yang baru dan mungkin juga bukan maksud sesungguhnya.
Walau dengan kata yang berbeda, cost-benefit dari normalisasi dalam politik luar negeri salah satunya untuk mendistribusikan kekuatan regional dan membuka pasar baru untuk menampung produksi ekonomi. Saya mengatakan itu bukan hal yang baru karena pada 1972, Richard Nixon, seorang presiden ke-37 dan politikus antikomunis dari kubu Republik, juga telah menormalisasikan hubungan AS dengan China yang menganut ideologi sama dengan Kuba saat ini.
China pada masa itu juga tidak lebih demokratis ketimbang Iran saat ini. Motivasi utama dari normalisasi dengan China saat itu adalah demi memecahkan kekuatan ideologi sosialis agar tidak lagi terpusat di tangan Uni- Soviet. AS bisa langsung melakukan negosiasi dengan China terkait upaya untuk menstabilisasi politik kawasan, khususnya di wilayah Asia.
AS bahkan bersedia mengakui Taiwan sebagai bagian dari China sebagai kompensasinya. Dari sisi perdagangan, China adalah negara dengan penduduk terbesar di dunia yang dapat menyerap ekspor manufaktur dan investasi dari AS. Ini yang kemudian terbukti dari sejarah perdagangan antara China-Amerika sejak normalisasi pada 1972.
Pada awal normalisasi nilai perdagangan mereka hanya USD4,7 juta, namun pada 2014 telah mencapai USD536,2 miliar. China bahkan telah menjadi negara dengan nilai perdagangan terbesar di dunia, mengalahkan AS saat ini (Dong Wang 2013). Saya memandang bahwa hal yang sama akan terjadi pada hubunganAS dengan Iran dan Kuba walau pengawalan atas kebijakan normalisasi akan berbeda sesuai konteks dua negara tersebut.
Menteri Luar Negeri AS John Kerry misalnya mengatakan bahwa tujuan dari negosiasi dengan Iran bukanlah untuk menyelesaikan masalah HAM, melainkan bagaimana membuat negara tersebut tidak dapat memproduksi senjata nuklir. Dengan kata lain, masalah politik dalam negeri Iran tampaknya tidak menjadi prioritas bagi AS. Ini berbeda dengan Kuba yang mendapat sorotan, terutama dalam praktik penyelenggaraan HAM-nya.
Amerika mengatakan bahwa mereka akan lebih serius ”mendampingi” Kuba untuk mereformasi sistem politiknya. Pernyataan ini tidak lepas dari banyak warga Kuba dan tokoh politik yang lari ke Amerika dan menggalang dukungan politik dari dalam sana.
Dari perkembangan ini, apakah artinya faktor moral dan nilai semakin tidak lagi punya tempat dalam politik luar negeri di dunia? Atau, memang faktor moral dan nilai sekadar menjadi jembatan bagi pencapaian kepentingan ekonomi semata?
DINNA WISNU, PhD
Pengamat Hubungan Internasional, Co-founder & Director Paramadina Graduate School of Diplomacy @dinnawisnu
(ftr)