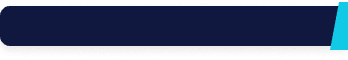Diplomasi Aksi Iklim dan Kredit Karbon Indonesia
loading...

Makarim Wibisono, Pengamat Hubungan Internasional dan Lingkungan Hidup. Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
Makarim Wibisono
Pengamat Hubungan Internasional dan Lingkungan Hidup
SEMUA negara dirasa perlu memperbaiki persepsi globalnya dan membangun soft power untuk kebijakan luar negerinya. Menurut Anholt (2015) terdapat empat atribut yang mempengaruhi posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, yaitu: moralitas, estetika, kekuatan, dan relevansi.
Moralitas berkaitan dengan nilai nilai luhur yang dianut pemimpinnya, penduduknya, dan swasta serta institusi publiknya. Posisi moral yang jelas merupakan soft power yang paling efektif bagi negara manapun. Estetika dilihat dari harmoni masyarakat, keindahan lingkungan alam dan lingkungan buatannya, kecanggihan produk dan hasil budayanya yang dipandang indah sehingga enak dipandang atau dilihat oleh indera.
Kekuatan berkaitan dengan persepsi kekuatan militer dan ekonomi negara dan juga kekuatan media yang mampu memaksakan pandangannya terhadap opini publik internasional. Relevansi adalah konsep yang lebih kompleks dibandingkan tiga konsep sebelumnya, yang melibatkan persepsi masyarakat luar negeri dan ini lebih sulit diprediksi atau dimanipulasi.
Di sinilah peran diplomasi diperlukan, yaitu untuk mempengaruhi presepsi, keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat asing. Diplomasi dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lain selain perang atau kekerasan. Diplomasi merupakan instrumen utama kebijakan luar negeri dan merupakan dasar interaksi suatu negara dengan negara-negara lain di dunia.
Pada akhir abad ke-20 muncul salah satu bentuk diplomasi yaitu diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan mengacu pada penggunaan diplomasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Saat ini, tantangan global dikenal dengan triple planetary crisis yaitu 3 krisis global berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Gagasan dari Tanah Air.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan istilah “leading by example” untuk menggambarkan bagaimana strategi diplomasi lingkungan Indonesia. Indonesia memperkuat posisinya di dunia internasional dengan selalu menjadi contoh bagi dunia dalam menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Keberhasilan Indonesia menurunkan deforestasi, mengatasi kebakaran hutan dan lahan, melakukan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove merupakan aksi nyata yang telah memperoleh pengakuan dunia sehingga memperkuat posisi (standing) Indonesia secara global.
Data deforestasi mulai periode 1996-2000 hingga periode pemantauan 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta ha. Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI tahun 2021 dan 2022 yang terekam pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia mencapai 104.032,9 ha, dengan rincian laju deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 73.130,4 ha dan di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) sebesar 30.902,6 ha.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Luas karhutla tahun 2023 adalah 1.161.192 hektar sedangkan luas karhutla pada tahun 2019 adalah 1.649.258 ha. Luasan ini jauh lebih kecil dibandingkan karhutla pada tahun 2015 yang mencapai 2,61 juta ha.
Pemulihan ekosistem gambut berhasil dilakukan pada lahan seluas 5,57 juta hektar dengan perincian 3,93 juta ha di kawasan konsesi sedangkan pemulihan pemulihan dilahan masyarakat mencapai 1.692.480 ha. Rehabilitasi mangrove juga telah dilakukan secarak marak di berbagai pelosok tanah air dan juga ditandai dengan berbagai inisiatif seperti World Mangrove Center di Bali.
Keberhasilan tersebut didukung data dan informasi yang akurat, transparan dan kredibel memenuhi kaidah Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV). Terukur (Measurable) artinya kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur dengan akurat.
Dapat dilaporkan (Reportable) berarti hasil pengukuran harus dapat dilaporkan secara transparan dan terbuka. Dapat Diverifikasi (Verifiable) berarti bahwa data yang dilaporkan harus dapat diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Ini memastikan integritas dan keandalan data.
Pada COP 28 Dubai tahun 2023 Indonesia melaporkan tingkat emisi GRK di tahun 2022 sebesar 1.220 Mton CO2e yang berasal dari berbagai sektor. Yaitu: sektor energi sebesar 715,95 Mton CO2e; proses industri dan penggunaan produk sebesar 59.15 Mton CO2e; pertanian sebesar 89,20 Mton CO2e; kehutanan dan kebakaran gambut sebesar 221,57 Mton CO2e; dan limbah sebesar 221,57 Mton CO2e.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) tingkat emisi memang mengalami kenaikan sebesar 6,9 % seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan BAU pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%.
Dengan berbagai kebijakan dan tindakan nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, posisi (standing) Indonesia di forum internasional sangat kuat. Hal ini terbukti dengan pengakuan kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia melalui REDD+ telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pembayaran berbasis kinerja/Result-Based Payment (RBP).
Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang menerima RBP paling besar, dengan total komitmen RBP sebesar USD439,8 juta. Di mana dari total komitmen tersebut Indonesia telah menerima pembayaran sebesar USD279,8 juta.
World Bank (2023) dalam laporannya Country Climate and Development Report 2023 - East Asia Indonesia juga memberikan apresiasi yang baik tentang kemajuan penanganan perubahan iklim di Indonesia. Dalam laporannya disebutkan Indonesia telah membuat komitmen penting untuk memenuhi target iklim dan pembangunannya.
Upaya yang sedang berjalan mulai membuahkan hasil dalam memperlambat emisi gas rumah kaca (GRK), mempertahankan pertumbuhan, dan memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Transisi ini melibatkan trade-off antara aksi iklim dan prioritas pembangunan jangka pendek‒terutama karena rekam jejak pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan Indonesia yang kuat sebagian disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam‒termasuk batu bara, minyak, hutan, dan lahan gambut.
Indonesia telah menetapkan jalur baru dalam Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Karbon dan Iklim Rendah (LTS-LCCR) 2050 untuk mempertahankan dan berpotensi mempercepat transformasi ekonomi dari negara berpendapatan menengah ke tinggi.
Kebijakan Ekonomi Karbon
Presiden Jokowi, dalam KTT Perubahan Iklim World Leaders’ Summit, Glasgow tahun 2021, menegaskan kembali posisi Indonesia dalam diplomasi lingkungan dengan komitmen Indonesia untuk berkontribusi lebih cepat bagi Net-Zero Emission dunia melalui sistem nilai karbon. Presiden menegaskan pasar karbon dan nilai karbon harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.
Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan. Komitmen ini disampaikan setelah pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021 menerbitkan Perpres No 98/2021 yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan NDC.
Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Permen LHK No 21/2022 mengatur tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon, yang keduanya dapat menjadi payung hukum bagi visi jangka panjang LTS-LCCR 2050 menuju Net-Zero Emission 2060 atau lebih cepat.
Perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca (offset karbon). Mekanisme perdagangan emisi berlaku diterapkan perusahaan yang memiliki batas atas emisi GRK yaitu batas tertinggi jumlah emisi GRK yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dalam suatu periode tertentu.
Sedangkan mekanisme offset karbon diterapkan untuk perusahaan yang tidak memiliki kewajiban membatasi emisi namun berkehendak untuk memberikan pernyataan pengurangan emisi atau pemenuhan target netralitas karbon dengan menggunakan hasil aksi mitigasi dari usaha dan atau kegiatan lain.
Offset karbon pada umumnya terdiri dari 4 kategori utama, pertama adalah kategori mencegah kehilangan sumber daya alam penyerap karbon (avoided nature loss) seperti mengindari terjadinya deforestasi yang mencegah kehilangan penyerapan karbon secara alami.
Kategori kedua adalah menghindari terjadinya emisi (avoidance of emissions) yakni mengganti kegiatan yang menghasilkan emisi dengan kegiatan yang lebih rendah emisi, misalnya mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan.
Ketiga adalah penyerapan berbasis alam (nature based sequestration or capture) misalnya melalui rehabilitasi hutan atau memperbaiki pengelolaan hutan. Kategori terakhir adalah penyerapan CO2 langsung dari atmosfer misalnya melalui Carbon Capture Utilization dan Storage. Sebagai tambahan dari empat kategori ini juga ada offset yang berasal dari pengurangan GRK yang belum diatur dalam regulasi seperti mengurangi kebocoran metan.
Antusiasme perdagangan offset karbon secara sukarela memang sangat tinggi. Kreibicha, N dan Hermwille, L (2021) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat di kalangan sektor swasta untuk menjadi netral karbon atau iklim: pada April 2021, 482 perusahaan dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar USD 16 triliun telah mengadopsi offset karbon untuk mendukung target netralitas (net zero carbon) mereka.
Meskipun angka-angka ini mengesankan dan mungkin mengindikasikan potensi permintaan kredit karbon yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, namun peran offset karbon sukarela dalam strategi iklim perusahaan masih harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Situasi di mana perusahaan menggunakan offset karbon dari pasar sukarela sebagai jalan keluar yang ‘mudah’ untuk menghindari tanggung jawab pengurangan emisi dari aktifitas mereka sendiri harus dihindari.
Pada tingkat internasional perdangangan offset karbon secara sukarela juga terus diperdebatkan efektitas dan akuntabilitasnya. Penelitian Kreibicha, N dan Hermwille, L (2021) mengindikasikan bahwa mekanisme pasar karbon sukarela secara keseluruhan masih belum terintegrasi dengan arsitektur sistem hukum Paris Agreement secara kredible dan legitimate terutama isu terjadinya double counting kredit karbon.
Kreibicha, N dan Hermwille, L juga mencatat paling tidak terdapat 4 wacana mekanisme perdagangan karbon sukarela sekarang diperdebatkan pada tingkat global, yaitu: on-NDC crediting, yaitu pemberian kredit pada proyek-proyek di atur dalam NDC negara penghasil kredit karbon, sehingga tidak perlu dilakukan corresponding adjustments, yaitu konsep penting dalam perdagangan karbon untuk mencegah penghitungan ganda dalam pengurangan emisi.
Ketika suatu negara mentransfer unit emisi (kredit karbon) ke negara lain, negara penjual harus mengurangi unit tersebut dari target emisinya. Pada saat yang sama, negara pembeli menambahkan unit-unit ini ke targetnya.
Pada dasarnya, penyesuaian yang sesuai memastikan bahwa pengurangan emisi yang sama tidak dihitung dua kali—sekali oleh penjual dan sekali lagi oleh pembeli. Kelemahan mekanisme on-NDC Crediting adalah cakupannya sangat terbatas dan dapat menyebabkan insentif yang merugikan bagi negara tuan rumah (tidak) untuk memperluas ruang lingkup NDCnya. Kelemahan lain adalah ruang lingkup NDC tidak selalu cukup jelas untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilingkup dalam NDC dan yang di luar NDC.
NDC support units, mekanisme ini memberikan label kepada proyek-proyek yang berkontribusi tehadap pencapaian NDC negara tuan rumah tetapi tidak dapat diklaim oleh perusahaan yang mendanai proyek tersebut. Untuk memperoleh dukungan mekanisme ini diperlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pelaku pasar.
Pendekatan ini, sering disebut yang juga disebut sebagai model pendanaan pengurangan emisi atau pendekatan klaim kontribusi, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pendanaan iklim berbasis hasil swasta. Mekanisme ini per definisi tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan yang berusaha memenuhi komitmen net zero mereka karena unit tersebut tidak boleh digunakan untuk klaim netralitas.
Namun, berdasarkan penelitian beberapa perusahaan besar, khususnya yang beroperasi di tingkat global, mungkin tertarik untuk mendukung negara tertentu dalam melaksanakan NDC-nya. Model ini mungkin juga akan menarik perhatian perusahaan dan individu yang benar-benar bertujuan untuk kontribusi terhadap penurunan emisi karbon dan perbaikan lingkungan.
Sebaliknya, pembeli yang model bisnisnya berbasis upaya untuk menghasilkan produk yang netral karbon diperkirakan akan enggan membeli offset karbon dari mekanisme ini (Kreibich & Obergassel, 2019).
Non-compliance credits, melalui mekanime ini kredit karbon digunakan perusahaan untuk klaim netralitas karbonnya, namun tidak tercatat dalam pembukuan emisi resmi di bawah UNFCCC. Mekanisme ini menghadapi permasalahan legitimasi yang serius dan menyebabkan klaim ganda yang pada gilirannya dapat mengakibatkan peningkatan emisi secara keseluruhan alih-alih menurunkan emisi karbon. Hal ini juga akan berdampak pada reputasi perusahaan yang membeli kredit karbon tersebut, dan juga dapat mendistorsi persepsi kita mengenai tindakan kolektif global untuk mengatasi perubahan iklim.
NDC crediting with corresponding adjustments menurut Kreibicha, N dan Hermwille, L (2021) adalah satu-satunya solusi yang memperkuat dan melindungi legitimasi penggunaan kredit karbon untuk mengimbangi kebutuhan perusahaan untuk klaim target netralitas karbon mereka sambil memastikan kredit karbon yang dihasilkan memiliki nilai integritas yang tinggi.
Untuk menerapkan mekanisme ini memang perlu penyesuaian karena pencapaian corresponding adjustments dapat menyebabkan pencapaian NDC negara-negara tuan rumah akan sulit, kecuali proyek-proyek yang dibiayai kredit karbon ini hasil benar-benar bersifat tambahan dan membantu negara negara tuan rumah untuk tetap berada pada jalur dekarbonisasi jangka panjang.
Mempersiapkan Diri ke Depan.
Jika menyimak penelitian Kreibicha, N dan Hermwille, L maka mekanisme perdagangan karbon yang diatur dalam Perpres No 98/2021 dan Permen LHK No 21/2022 sekali lagi menunjukkan karakter diplomasi lingkungan “lead by example” Presiden Jokowi.
Selagi masyarakat global masih memperdebatkan mekanisme perdagangan offset karbon sukarela, Indonesia sudah menggariskan kebijakan yang jelas untuk membangun ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil.
Elemen-elemen penting kebijakan ekosistem karbon Indonesia seperti : semua penyelenggaraan NDC dan NEK perlu dicatat dan dapat tertelusuri pada Sistem Registri Nasional (SRN); Upaya pengurangan emisi GRK harus dilaksanakan secara terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi (Measurable, Reportable, Verifiable); unit karbon kinerja pengurangan emisi GRK yang akan ditransaksikan dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPEI GRK); dan penyesuaian pencatatan guna menghindari adanya pencatatan ganda, maka perlu dilakukan corresponding adjustment, sudah tepat dan akan memperkuat standing Indonesia dalam diplomasi lingkungan global.
Sekali lagi mengutip Anholt (2015) terdapat empat atribut yang mempengaruhi posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, yaitu: moralitas, estetika, kekuatan, dan relevansi. Jangan sampai kepentingan jangka pendek mengalahkan martabat bangsa dan negara dengan mengalah kepada tekanan asing dan golongan tertentu yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.
Pengamat Hubungan Internasional dan Lingkungan Hidup
SEMUA negara dirasa perlu memperbaiki persepsi globalnya dan membangun soft power untuk kebijakan luar negerinya. Menurut Anholt (2015) terdapat empat atribut yang mempengaruhi posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, yaitu: moralitas, estetika, kekuatan, dan relevansi.
Moralitas berkaitan dengan nilai nilai luhur yang dianut pemimpinnya, penduduknya, dan swasta serta institusi publiknya. Posisi moral yang jelas merupakan soft power yang paling efektif bagi negara manapun. Estetika dilihat dari harmoni masyarakat, keindahan lingkungan alam dan lingkungan buatannya, kecanggihan produk dan hasil budayanya yang dipandang indah sehingga enak dipandang atau dilihat oleh indera.
Kekuatan berkaitan dengan persepsi kekuatan militer dan ekonomi negara dan juga kekuatan media yang mampu memaksakan pandangannya terhadap opini publik internasional. Relevansi adalah konsep yang lebih kompleks dibandingkan tiga konsep sebelumnya, yang melibatkan persepsi masyarakat luar negeri dan ini lebih sulit diprediksi atau dimanipulasi.
Di sinilah peran diplomasi diperlukan, yaitu untuk mempengaruhi presepsi, keputusan dan perilaku pemerintah dan masyarakat asing. Diplomasi dilakukan melalui dialog, negosiasi, dan tindakan lain selain perang atau kekerasan. Diplomasi merupakan instrumen utama kebijakan luar negeri dan merupakan dasar interaksi suatu negara dengan negara-negara lain di dunia.
Pada akhir abad ke-20 muncul salah satu bentuk diplomasi yaitu diplomasi lingkungan. Diplomasi lingkungan mengacu pada penggunaan diplomasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi tantangan lingkungan global. Saat ini, tantangan global dikenal dengan triple planetary crisis yaitu 3 krisis global berupa perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi.
Gagasan dari Tanah Air.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan istilah “leading by example” untuk menggambarkan bagaimana strategi diplomasi lingkungan Indonesia. Indonesia memperkuat posisinya di dunia internasional dengan selalu menjadi contoh bagi dunia dalam menjaga lingkungan dan mengatasi perubahan iklim. Keberhasilan Indonesia menurunkan deforestasi, mengatasi kebakaran hutan dan lahan, melakukan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove merupakan aksi nyata yang telah memperoleh pengakuan dunia sehingga memperkuat posisi (standing) Indonesia secara global.
Data deforestasi mulai periode 1996-2000 hingga periode pemantauan 2020-2021 menunjukkan bahwa deforestasi berhasil diturunkan pada titik terendah dalam 20 tahun terakhir yaitu pada angka 0,11 juta ha. Berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI tahun 2021 dan 2022 yang terekam pada tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022, laju deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia mencapai 104.032,9 ha, dengan rincian laju deforestasi di dalam kawasan hutan sebesar 73.130,4 ha dan di luar kawasan hutan/Area Penggunaan Lain (APL) sebesar 30.902,6 ha.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2023 berhasil ditekan lebih kecil dibandingkan tahun 2019 dengan pengaruh El-Nino yang hampir sama, bahkan kondisi 2023 lebih kering. Luas karhutla tahun 2023 adalah 1.161.192 hektar sedangkan luas karhutla pada tahun 2019 adalah 1.649.258 ha. Luasan ini jauh lebih kecil dibandingkan karhutla pada tahun 2015 yang mencapai 2,61 juta ha.
Pemulihan ekosistem gambut berhasil dilakukan pada lahan seluas 5,57 juta hektar dengan perincian 3,93 juta ha di kawasan konsesi sedangkan pemulihan pemulihan dilahan masyarakat mencapai 1.692.480 ha. Rehabilitasi mangrove juga telah dilakukan secarak marak di berbagai pelosok tanah air dan juga ditandai dengan berbagai inisiatif seperti World Mangrove Center di Bali.
Keberhasilan tersebut didukung data dan informasi yang akurat, transparan dan kredibel memenuhi kaidah Measurable, Reportable, and Verifiable (MRV). Terukur (Measurable) artinya kegiatan yang dilakukan harus dapat diukur dengan akurat.
Dapat dilaporkan (Reportable) berarti hasil pengukuran harus dapat dilaporkan secara transparan dan terbuka. Dapat Diverifikasi (Verifiable) berarti bahwa data yang dilaporkan harus dapat diverifikasi oleh pihak ketiga yang independen. Ini memastikan integritas dan keandalan data.
Pada COP 28 Dubai tahun 2023 Indonesia melaporkan tingkat emisi GRK di tahun 2022 sebesar 1.220 Mton CO2e yang berasal dari berbagai sektor. Yaitu: sektor energi sebesar 715,95 Mton CO2e; proses industri dan penggunaan produk sebesar 59.15 Mton CO2e; pertanian sebesar 89,20 Mton CO2e; kehutanan dan kebakaran gambut sebesar 221,57 Mton CO2e; dan limbah sebesar 221,57 Mton CO2e.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2021) tingkat emisi memang mengalami kenaikan sebesar 6,9 % seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun demikian tingkat emisi tahun 2022 apabila dibandingkan dengan BAU pada tahun yang sama menunjukkan pengurangan sebesar 42%.
Dengan berbagai kebijakan dan tindakan nyata dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, posisi (standing) Indonesia di forum internasional sangat kuat. Hal ini terbukti dengan pengakuan kinerja pengurangan emisi GRK Indonesia melalui REDD+ telah mendapatkan rekognisi internasional yang diwujudkan melalui pembayaran berbasis kinerja/Result-Based Payment (RBP).
Pada saat ini Indonesia tercatat sebagai negara yang menerima RBP paling besar, dengan total komitmen RBP sebesar USD439,8 juta. Di mana dari total komitmen tersebut Indonesia telah menerima pembayaran sebesar USD279,8 juta.
World Bank (2023) dalam laporannya Country Climate and Development Report 2023 - East Asia Indonesia juga memberikan apresiasi yang baik tentang kemajuan penanganan perubahan iklim di Indonesia. Dalam laporannya disebutkan Indonesia telah membuat komitmen penting untuk memenuhi target iklim dan pembangunannya.
Upaya yang sedang berjalan mulai membuahkan hasil dalam memperlambat emisi gas rumah kaca (GRK), mempertahankan pertumbuhan, dan memperkuat ketahanan ekonomi dan sosial. Transisi ini melibatkan trade-off antara aksi iklim dan prioritas pembangunan jangka pendek‒terutama karena rekam jejak pertumbuhan dan pengentasan kemiskinan Indonesia yang kuat sebagian disebabkan oleh kekayaan sumber daya alam‒termasuk batu bara, minyak, hutan, dan lahan gambut.
Indonesia telah menetapkan jalur baru dalam Strategi Jangka Panjang untuk Ketahanan Karbon dan Iklim Rendah (LTS-LCCR) 2050 untuk mempertahankan dan berpotensi mempercepat transformasi ekonomi dari negara berpendapatan menengah ke tinggi.
Kebijakan Ekonomi Karbon
Presiden Jokowi, dalam KTT Perubahan Iklim World Leaders’ Summit, Glasgow tahun 2021, menegaskan kembali posisi Indonesia dalam diplomasi lingkungan dengan komitmen Indonesia untuk berkontribusi lebih cepat bagi Net-Zero Emission dunia melalui sistem nilai karbon. Presiden menegaskan pasar karbon dan nilai karbon harus menjadi bagian dari upaya penanganan isu perubahan iklim.
Ekosistem ekonomi karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil harus diciptakan. Komitmen ini disampaikan setelah pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2021 menerbitkan Perpres No 98/2021 yang mengatur secara lebih rinci mengenai pelaksanaan NDC.
Kemudian ditindaklanjuti dengan menerbitkan Permen LHK No 21/2022 mengatur tata laksana penerapan nilai ekonomi karbon, yang keduanya dapat menjadi payung hukum bagi visi jangka panjang LTS-LCCR 2050 menuju Net-Zero Emission 2060 atau lebih cepat.
Perdagangan karbon dalam negeri dan luar negeri dilakukan melalui mekanisme perdagangan emisi dan offset emisi gas rumah kaca (offset karbon). Mekanisme perdagangan emisi berlaku diterapkan perusahaan yang memiliki batas atas emisi GRK yaitu batas tertinggi jumlah emisi GRK yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan dalam suatu periode tertentu.
Sedangkan mekanisme offset karbon diterapkan untuk perusahaan yang tidak memiliki kewajiban membatasi emisi namun berkehendak untuk memberikan pernyataan pengurangan emisi atau pemenuhan target netralitas karbon dengan menggunakan hasil aksi mitigasi dari usaha dan atau kegiatan lain.
Offset karbon pada umumnya terdiri dari 4 kategori utama, pertama adalah kategori mencegah kehilangan sumber daya alam penyerap karbon (avoided nature loss) seperti mengindari terjadinya deforestasi yang mencegah kehilangan penyerapan karbon secara alami.
Kategori kedua adalah menghindari terjadinya emisi (avoidance of emissions) yakni mengganti kegiatan yang menghasilkan emisi dengan kegiatan yang lebih rendah emisi, misalnya mengganti bahan bakar fosil dengan energi terbarukan.
Ketiga adalah penyerapan berbasis alam (nature based sequestration or capture) misalnya melalui rehabilitasi hutan atau memperbaiki pengelolaan hutan. Kategori terakhir adalah penyerapan CO2 langsung dari atmosfer misalnya melalui Carbon Capture Utilization dan Storage. Sebagai tambahan dari empat kategori ini juga ada offset yang berasal dari pengurangan GRK yang belum diatur dalam regulasi seperti mengurangi kebocoran metan.
Antusiasme perdagangan offset karbon secara sukarela memang sangat tinggi. Kreibicha, N dan Hermwille, L (2021) menunjukkan bahwa terdapat peningkatan minat di kalangan sektor swasta untuk menjadi netral karbon atau iklim: pada April 2021, 482 perusahaan dengan perkiraan pendapatan tahunan sebesar USD 16 triliun telah mengadopsi offset karbon untuk mendukung target netralitas (net zero carbon) mereka.
Meskipun angka-angka ini mengesankan dan mungkin mengindikasikan potensi permintaan kredit karbon yang sangat besar dan belum pernah terjadi sebelumnya, namun peran offset karbon sukarela dalam strategi iklim perusahaan masih harus dipertimbangkan dengan hati-hati. Situasi di mana perusahaan menggunakan offset karbon dari pasar sukarela sebagai jalan keluar yang ‘mudah’ untuk menghindari tanggung jawab pengurangan emisi dari aktifitas mereka sendiri harus dihindari.
Pada tingkat internasional perdangangan offset karbon secara sukarela juga terus diperdebatkan efektitas dan akuntabilitasnya. Penelitian Kreibicha, N dan Hermwille, L (2021) mengindikasikan bahwa mekanisme pasar karbon sukarela secara keseluruhan masih belum terintegrasi dengan arsitektur sistem hukum Paris Agreement secara kredible dan legitimate terutama isu terjadinya double counting kredit karbon.
Kreibicha, N dan Hermwille, L juga mencatat paling tidak terdapat 4 wacana mekanisme perdagangan karbon sukarela sekarang diperdebatkan pada tingkat global, yaitu: on-NDC crediting, yaitu pemberian kredit pada proyek-proyek di atur dalam NDC negara penghasil kredit karbon, sehingga tidak perlu dilakukan corresponding adjustments, yaitu konsep penting dalam perdagangan karbon untuk mencegah penghitungan ganda dalam pengurangan emisi.
Ketika suatu negara mentransfer unit emisi (kredit karbon) ke negara lain, negara penjual harus mengurangi unit tersebut dari target emisinya. Pada saat yang sama, negara pembeli menambahkan unit-unit ini ke targetnya.
Pada dasarnya, penyesuaian yang sesuai memastikan bahwa pengurangan emisi yang sama tidak dihitung dua kali—sekali oleh penjual dan sekali lagi oleh pembeli. Kelemahan mekanisme on-NDC Crediting adalah cakupannya sangat terbatas dan dapat menyebabkan insentif yang merugikan bagi negara tuan rumah (tidak) untuk memperluas ruang lingkup NDCnya. Kelemahan lain adalah ruang lingkup NDC tidak selalu cukup jelas untuk menetapkan kegiatan-kegiatan yang dilingkup dalam NDC dan yang di luar NDC.
NDC support units, mekanisme ini memberikan label kepada proyek-proyek yang berkontribusi tehadap pencapaian NDC negara tuan rumah tetapi tidak dapat diklaim oleh perusahaan yang mendanai proyek tersebut. Untuk memperoleh dukungan mekanisme ini diperlukan kerja keras dan kerja sama dari seluruh pelaku pasar.
Pendekatan ini, sering disebut yang juga disebut sebagai model pendanaan pengurangan emisi atau pendekatan klaim kontribusi, pada dasarnya merupakan suatu bentuk pendanaan iklim berbasis hasil swasta. Mekanisme ini per definisi tidak dapat memenuhi permintaan perusahaan yang berusaha memenuhi komitmen net zero mereka karena unit tersebut tidak boleh digunakan untuk klaim netralitas.
Namun, berdasarkan penelitian beberapa perusahaan besar, khususnya yang beroperasi di tingkat global, mungkin tertarik untuk mendukung negara tertentu dalam melaksanakan NDC-nya. Model ini mungkin juga akan menarik perhatian perusahaan dan individu yang benar-benar bertujuan untuk kontribusi terhadap penurunan emisi karbon dan perbaikan lingkungan.
Sebaliknya, pembeli yang model bisnisnya berbasis upaya untuk menghasilkan produk yang netral karbon diperkirakan akan enggan membeli offset karbon dari mekanisme ini (Kreibich & Obergassel, 2019).
Non-compliance credits, melalui mekanime ini kredit karbon digunakan perusahaan untuk klaim netralitas karbonnya, namun tidak tercatat dalam pembukuan emisi resmi di bawah UNFCCC. Mekanisme ini menghadapi permasalahan legitimasi yang serius dan menyebabkan klaim ganda yang pada gilirannya dapat mengakibatkan peningkatan emisi secara keseluruhan alih-alih menurunkan emisi karbon. Hal ini juga akan berdampak pada reputasi perusahaan yang membeli kredit karbon tersebut, dan juga dapat mendistorsi persepsi kita mengenai tindakan kolektif global untuk mengatasi perubahan iklim.
NDC crediting with corresponding adjustments menurut Kreibicha, N dan Hermwille, L (2021) adalah satu-satunya solusi yang memperkuat dan melindungi legitimasi penggunaan kredit karbon untuk mengimbangi kebutuhan perusahaan untuk klaim target netralitas karbon mereka sambil memastikan kredit karbon yang dihasilkan memiliki nilai integritas yang tinggi.
Untuk menerapkan mekanisme ini memang perlu penyesuaian karena pencapaian corresponding adjustments dapat menyebabkan pencapaian NDC negara-negara tuan rumah akan sulit, kecuali proyek-proyek yang dibiayai kredit karbon ini hasil benar-benar bersifat tambahan dan membantu negara negara tuan rumah untuk tetap berada pada jalur dekarbonisasi jangka panjang.
Mempersiapkan Diri ke Depan.
Jika menyimak penelitian Kreibicha, N dan Hermwille, L maka mekanisme perdagangan karbon yang diatur dalam Perpres No 98/2021 dan Permen LHK No 21/2022 sekali lagi menunjukkan karakter diplomasi lingkungan “lead by example” Presiden Jokowi.
Selagi masyarakat global masih memperdebatkan mekanisme perdagangan offset karbon sukarela, Indonesia sudah menggariskan kebijakan yang jelas untuk membangun ekosistem karbon yang transparan, berintegritas, inklusif dan adil.
Elemen-elemen penting kebijakan ekosistem karbon Indonesia seperti : semua penyelenggaraan NDC dan NEK perlu dicatat dan dapat tertelusuri pada Sistem Registri Nasional (SRN); Upaya pengurangan emisi GRK harus dilaksanakan secara terukur, dapat dilaporkan dan dapat diverifikasi (Measurable, Reportable, Verifiable); unit karbon kinerja pengurangan emisi GRK yang akan ditransaksikan dalam bentuk Sertifikat Pengurangan Emisi GRK (SPEI GRK); dan penyesuaian pencatatan guna menghindari adanya pencatatan ganda, maka perlu dilakukan corresponding adjustment, sudah tepat dan akan memperkuat standing Indonesia dalam diplomasi lingkungan global.
Sekali lagi mengutip Anholt (2015) terdapat empat atribut yang mempengaruhi posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain, yaitu: moralitas, estetika, kekuatan, dan relevansi. Jangan sampai kepentingan jangka pendek mengalahkan martabat bangsa dan negara dengan mengalah kepada tekanan asing dan golongan tertentu yang ingin mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia.
(poe)