50% Setuju Skripsi Dihapus
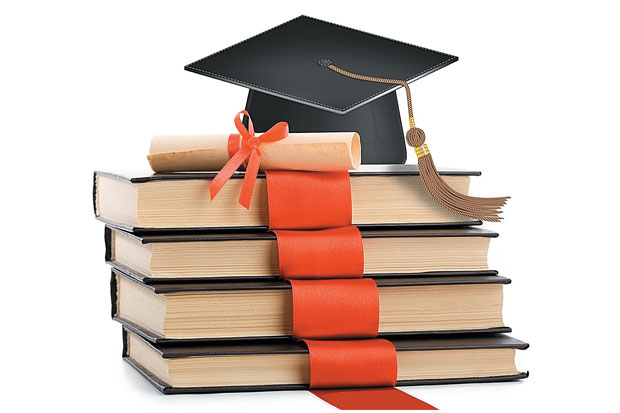
50% Setuju Skripsi Dihapus
A
A
A
Survei Litbang KORAN SINDO terhadap 100 mahasiswa dan SMA di lima kota besar yang berbeda menunjukkan 50% dari mereka setuju skripsi menjadi tidak diwajibkan sebagai prasyarat kelulusan.
Alasannya? Sebanyak 22% dari mereka mengakui keribetansaat mengerjakan skripsi menjadi penghambat kelulusan. Selain itu, 9% berpendapat bahwa saat ini banyak sekali kecurangan dan jiplakan dalam membuat skripsi. Jumlah yang sama juga berpendapat bahwa skripsi juga tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur dan menjamin kredibilitas.
Namun, 7% di antara mereka setuju dengan syarat tertentu, yakni ada pengganti yang relevan ke arah pengabdian seperti kuliah kerja nyata (KKN). Wacana mengenai tidak wajib lagi mengerjakan skripsi memang disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir belum lama ini. Praktik jualbeli skripsi yang masih marak menjadi salah satu alasan utama penghapusan skripsi.
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Ilah Sailah menilai kecurangan mahasiswa itu sebagai bentuk perilaku tidak bermoral. “Yang bekerja orang lain, yang dapat nilai dia. Tidak fair, tidak adil, dan tidak etis,” katanya kepada GEN SINDO. Karena itu, Ilah menegaskan bahwa mahasiswa harus memerangi keinginan untuk menempuh jalan pintas tanpa mempertimbangkan akibatnya.
Untuk mencapai apa yang dicitacitakan, mahasiswa harus tetap persisten dengan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran demi kemudahan untuk mendapatkan selembar kertas bernama ijazah. Ilah menilai skripsi merupakan salah satu cara latihan untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Karena belum terputusnya mata rantai kejahatan itu, Ilah memperingatkan juga bagi para dosen supaya lebih mengawasi dan tidak malas dalam membimbing mahasiswanya.
Dimulai dari bagaimana berdiskusi tentang penentuan masalah yang akan diteliti, menentukan metode, bahkan harus rela berdebat dengan mahasiswa. “Jangan hanya terima beres. Terima tulisan, lalu ujian. Kalau dosen tidak cermat membuat pertanyaan, itu berarti hanya normatif, tidak akan ketahuan kalau yang menulis itu bukan yang sedang diuji,” katanya.
Problem lain yang jadi alasan penghapusan skripsi adalah masih merebaknya budaya menyalin (copy paste). Untuk menangani hal ini, Ilah mengambil langkah kompetensi. Menurut dia, kalau sudah fokus ke arah kompetensi, kemampuan-kemampuan itu dapat juga dicapai melalui jalan nonskripsi.
Saat ini otonomi akademik sudah diberikan kepada kampus. Karena itu dengan program studi yang beragam, tiap-tiap kampus dapat leluasa menentukan bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan menuangkan ide lewat tulisan, berpikir logis, kritis, analitis, dan komprehensif, serta cakap menggunakan metode untuk memformulasikan keputusan. “Seperti tugas akhir dari hasil magang, pembuatan produk, melukis dan membuat suatu pertunjukan,” paparnya.
Pengamat pendidikan Dirgantara Wicaksono merupakan orang yang tidak sepakat jika skripsi diganti dengan opsi lain. Dosen yang mengajar di tiga kampus berbeda ini menilai ketiadaan skripsi akan menghambat sikap analisis kritis dan inovatif mahasiswa. “Penelitian di skripsi mengembangkan paradigma berpikir, juga sikap mahasiswa dalam memecahkan masalah,” ujar Bombom—sapaan akrabnya—yang pernah dinobatkan sebagai kepala sekolah termuda di DKI Jakarta ini.
Budaya Riset dan Menulis Masih Rendah
Alasan Bombom tersebut serupa dengan alasan dari responden yang menolak skripsi dihapus (sebesar 13%). Jika skripsi dihilangkan, menurut mereka, dampak langsung terhadap mahasiswa adalah tidak memiliki karya ilmiah sehingga tidak akan ada lagi yang bisa diapresiasikan. Sebab, karya ilmiah memang terlahir dari penelitian sebagai upaya pemecahan suatu masalah.
Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Ferly Ferdyant juga tak menampik alasan tersebut. Dia mempertanyakan ulang bahwa apabila rencana kebijakan itu diterapkan, kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya riset mahasiswa yang notabene masih rendah?
Menurut mantan mahasiswa jurusan akuntansi itu, kebijakan opsional skripsi sejatinya masih terlalu dini untuk disamaratakan di seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Mengingat kualitas PT yang berbeda, mulai dari tenaga pengajar (dosen), hingga sarana dan prasarana pendukung.
Kepedulian terhadap rendahnya budaya juga kualitas riset oleh mahasiswa begitu dirasakan Ferly yang pernah menjabat sebagai Kepala Departemen BEM UNJ pada periode 2014-2015. Sarannya, seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas dan pemerataan perguruan tinggi daripada membuat kebijakan opsional skripsi yang justru kontraproduktif dengan budaya riset penelitian oleh mahasiswa yang masih rendah.
Untuk itu, Ferly mengharapkan adanya pembenahan dalam budaya riset dari berbagai sisi. Misalnya dari internal kampus, seperti birokratnya (rektorat dan dekanat), bisa membuat program wajib sejak masa pengenalan mahasiswa baru sebagai bentuk upaya peningkatan budaya meneliti.
Rahmat mustakim
Alasannya? Sebanyak 22% dari mereka mengakui keribetansaat mengerjakan skripsi menjadi penghambat kelulusan. Selain itu, 9% berpendapat bahwa saat ini banyak sekali kecurangan dan jiplakan dalam membuat skripsi. Jumlah yang sama juga berpendapat bahwa skripsi juga tidak bisa dijadikan sebagai tolok ukur dan menjamin kredibilitas.
Namun, 7% di antara mereka setuju dengan syarat tertentu, yakni ada pengganti yang relevan ke arah pengabdian seperti kuliah kerja nyata (KKN). Wacana mengenai tidak wajib lagi mengerjakan skripsi memang disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir belum lama ini. Praktik jualbeli skripsi yang masih marak menjadi salah satu alasan utama penghapusan skripsi.
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Ilah Sailah menilai kecurangan mahasiswa itu sebagai bentuk perilaku tidak bermoral. “Yang bekerja orang lain, yang dapat nilai dia. Tidak fair, tidak adil, dan tidak etis,” katanya kepada GEN SINDO. Karena itu, Ilah menegaskan bahwa mahasiswa harus memerangi keinginan untuk menempuh jalan pintas tanpa mempertimbangkan akibatnya.
Untuk mencapai apa yang dicitacitakan, mahasiswa harus tetap persisten dengan tidak tergiur oleh tawaran-tawaran demi kemudahan untuk mendapatkan selembar kertas bernama ijazah. Ilah menilai skripsi merupakan salah satu cara latihan untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Karena belum terputusnya mata rantai kejahatan itu, Ilah memperingatkan juga bagi para dosen supaya lebih mengawasi dan tidak malas dalam membimbing mahasiswanya.
Dimulai dari bagaimana berdiskusi tentang penentuan masalah yang akan diteliti, menentukan metode, bahkan harus rela berdebat dengan mahasiswa. “Jangan hanya terima beres. Terima tulisan, lalu ujian. Kalau dosen tidak cermat membuat pertanyaan, itu berarti hanya normatif, tidak akan ketahuan kalau yang menulis itu bukan yang sedang diuji,” katanya.
Problem lain yang jadi alasan penghapusan skripsi adalah masih merebaknya budaya menyalin (copy paste). Untuk menangani hal ini, Ilah mengambil langkah kompetensi. Menurut dia, kalau sudah fokus ke arah kompetensi, kemampuan-kemampuan itu dapat juga dicapai melalui jalan nonskripsi.
Saat ini otonomi akademik sudah diberikan kepada kampus. Karena itu dengan program studi yang beragam, tiap-tiap kampus dapat leluasa menentukan bagaimana mahasiswa memiliki kemampuan menuangkan ide lewat tulisan, berpikir logis, kritis, analitis, dan komprehensif, serta cakap menggunakan metode untuk memformulasikan keputusan. “Seperti tugas akhir dari hasil magang, pembuatan produk, melukis dan membuat suatu pertunjukan,” paparnya.
Pengamat pendidikan Dirgantara Wicaksono merupakan orang yang tidak sepakat jika skripsi diganti dengan opsi lain. Dosen yang mengajar di tiga kampus berbeda ini menilai ketiadaan skripsi akan menghambat sikap analisis kritis dan inovatif mahasiswa. “Penelitian di skripsi mengembangkan paradigma berpikir, juga sikap mahasiswa dalam memecahkan masalah,” ujar Bombom—sapaan akrabnya—yang pernah dinobatkan sebagai kepala sekolah termuda di DKI Jakarta ini.
Budaya Riset dan Menulis Masih Rendah
Alasan Bombom tersebut serupa dengan alasan dari responden yang menolak skripsi dihapus (sebesar 13%). Jika skripsi dihilangkan, menurut mereka, dampak langsung terhadap mahasiswa adalah tidak memiliki karya ilmiah sehingga tidak akan ada lagi yang bisa diapresiasikan. Sebab, karya ilmiah memang terlahir dari penelitian sebagai upaya pemecahan suatu masalah.
Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Ferly Ferdyant juga tak menampik alasan tersebut. Dia mempertanyakan ulang bahwa apabila rencana kebijakan itu diterapkan, kemudian bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan budaya riset mahasiswa yang notabene masih rendah?
Menurut mantan mahasiswa jurusan akuntansi itu, kebijakan opsional skripsi sejatinya masih terlalu dini untuk disamaratakan di seluruh perguruan tinggi (PT) di Indonesia. Mengingat kualitas PT yang berbeda, mulai dari tenaga pengajar (dosen), hingga sarana dan prasarana pendukung.
Kepedulian terhadap rendahnya budaya juga kualitas riset oleh mahasiswa begitu dirasakan Ferly yang pernah menjabat sebagai Kepala Departemen BEM UNJ pada periode 2014-2015. Sarannya, seharusnya pemerintah meningkatkan kualitas dan pemerataan perguruan tinggi daripada membuat kebijakan opsional skripsi yang justru kontraproduktif dengan budaya riset penelitian oleh mahasiswa yang masih rendah.
Untuk itu, Ferly mengharapkan adanya pembenahan dalam budaya riset dari berbagai sisi. Misalnya dari internal kampus, seperti birokratnya (rektorat dan dekanat), bisa membuat program wajib sejak masa pengenalan mahasiswa baru sebagai bentuk upaya peningkatan budaya meneliti.
Rahmat mustakim
(ftr)














