Menjaga Integritas Hakim Konstitusi dan Lembaga Peradilan
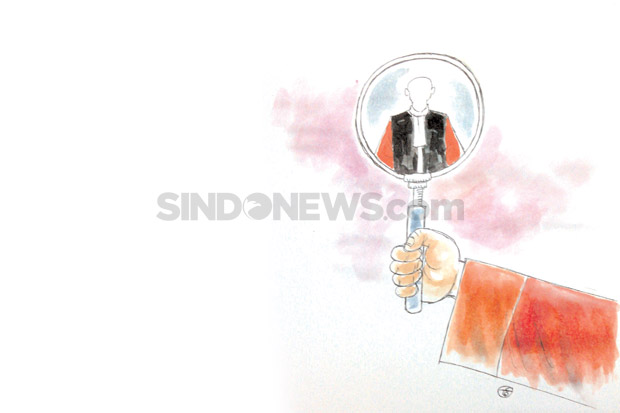
Menjaga Integritas Hakim Konstitusi dan Lembaga Peradilan
A
A
A
Arief Hidayat
Ketua Mahkamah Konstitusi
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
PADA Kamis, 26 Januari 2017 pagi, tidak hanya jagat dunia hukum, tetapi publik kembali dikagetkan dengan berita tertangkap tangannya seorang hakim konstitusi berinisial PAK oleh KPK. Penangkapan dilakukan pada Rabu 25 Januari 2017 malam di sebuah pusat perbelanjaan. Namun, aromanya mulai tercium jelas melalui pemberitaan di berbagai media pada Kamis 26 Januari 2017 pagi.
Pada Kamis malam, KPK menyelenggarakan konferensi pers guna mengumumkan secara resmi pemberitaan ihwal kasus yang membelit hakim konstitusi PAK. Wajah MK pun kembali tercoreng untuk kedua kalinya pascatertangkapnya AM yang kala itu menjabat sebagai ketua MK.
Berbeda dengan AM yang tersandung transaksi suap pilkada, PAK diduga tersandung kasus suap perkara pengujian UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun hal itu merupakan tindakan individual, lembaga MK tetap memikul beban berat dan sangat mencederai nama baik MK.
Terlebih sebentar lagi MK akan mengadili kasus sengketa hasil pilkada serentak. Oleh karena itu, diharapkan Presiden segera melakukan seleksi untuk memilih hakim konstitusi pengganti PAK.
Seiring dengan itu, ada permasalahan klasik ihwal “pengawasan hakim konstitusi” yang acap kali muncul dan menguat manakala terkait dengan hakim konstitusi yang tersandung kasus hukum, terutama kasus tindak pidana korupsi. Saat ini publik juga menilai adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengawasi MK melalui pintu KY.
Akan tetapi, upaya untuk “mengawasi” MK melalui pintu KY hampir dipastikan selalu kandas di tengah jalan. Oleh karena MK selalu saja membatalkan norma yang memuat pengawasan MK oleh KY. Walhasil hingga saat ini KY tak memiliki kewenangan untuk mengawasi MK.
Sikap MK ini didasari oleh Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, di mana MK telah memutuskan bahwa Hakim MK tidak terkait dengan KY yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945.
Berdasarkan kedua putusan ini, setidaknya terdapat dua alasan mengapa KY tidak didesain untuk “mengawasi” MK. Pertama, berdasarkan penafsiran sistematis atas pasal-pasal dalam konstitusi.
Posisi KY berada pada Pasal 24B UUD 1945, sedangkan MA berada pada Pasal 24A UUD 1945 dan posisi MK berada pada Pasal 24C UUD 1945 yang letak pengaturan pasalnya satu tingkat berada di bawah KY. Keberadaan pengaturan posisi pasal-pasal ini menyirat makna bahwa KY didesain untuk “mengawasi” hakim di lingkungan MA dan KY tidak didesain untuk “mengawasi” MK.
Akan tetapi, tidaklah berarti “pengawasan” terhadap MK diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjadi “pengawas” MK adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat ad hoc yang akan bekerja tatkala ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Namun, dalam perkembangannya, terutama pascatragedi konstitusional yang melibatkan AM sebagai ketua MK dalam skandal suap perkara pilkada, dipandang perlu dilakukan rekonstruksi untuk mendesain ulang mekanisme “pengawasan” terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saat ini telah terbentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai lembaga permanen dan independen yang bertugas menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi yang bekerja day to day selain Majelis Kehormatan yang sifatnya ad hoc.
Kedua, menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). Apabila KY diberikan kewenangan mengawasi MK, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan manakala KY berkedudukan sebagai pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi domain kewenangan MK. Dalam kondisi ini, MK akan “tersandera” karena lembaga pengawasnya turut menjadi pihak dalam sengketa yang harus diputus olehnya.
Hal ini jelas berpotensi mereduksi independensi dan imparsialitas MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan Pasal 24 UUD 1945. Selain dijaga oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK juga telah bersinergi membangun sistem pengawasan eksternal.
Hal ini dibuktikan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara MK dengan KPK sehingga peristiwa “OTT” hakim konstitusi PAK merupakan satu keberhasilan dari sistem ini. Oleh sebab itu, instrumen untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi telah terbangun dengan baik sehingga hal ini menafikan pendapat bahwa MK alergi terhadap “pengawasan” eksternal. Hal yang perlu dipahami bersama adalah pola “pengawasan” yang berbeda antara MA dengan MK.
Dalam konteks ini, MK tidak dapat dipaksa “diawasi” oleh KY, karena jika demikian, maka yang terjadi adalah sebuah bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.
Jika memang “pengawasan” eksternal sebagaimana yang berlaku saat ini belum mencukupi, maka terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh, yaitu: (i) menjadikan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai lembaga independen dan mandiri yang berwenang menjaga integritas hakim konstitusi seperti halnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU); (ii) melakukan perubahan UUD 1945 dengan meletakkan posisi kewenangan KY setelah kewenangan MA dan MK.
Artinya, posisi KY harus diletakkan pada Pasal 24C setelah Pasal 24A yang mengatur tentang MA dan Pasal 24B yang mengatur tentang MK. Selain itu, perlu dinyatakan secara tegas pada perubahan Pasal 24 UUD 1945 bahwa objek kewenangan KY meliputi pula hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, terdapat salah kaprah mengenai kata “pengawasan” yang sering kali digunakan terhadap lembaga peradilan. Dalam Pasal 24B UUD 1945 yang mengatur tentang Komisi Yudisial, menyatakan, ”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan “menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dan bukan “mengawasi”. Perbedaan kata “menjaga” dan “mengawasi” membawa implikasi hukum yang berbeda.
Secara gramatikal sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menjaga” memuat makna, yakni: (1) menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan); (2) mengiringi untuk melindungi dari bahaya; mengawal; (3) mengasuh (mengawasi anak kecil); (4) “mengawasi” sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian); (5) mempertahankan keselamatan (orang, barang, dan sebagainya); (6) mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya);(7) memeliharakan; merawat. Sementara kata “mengawasi” memuat makna, yakni: (1) melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang); (2) mengamat-amati dan menjaga baik-baik; mengontrol.
Dalam perspektif bahasa, kata “menjaga” dipandang lebih elegan dan komprehensif ketimbang kata “mengawasi”. Selain itu secara filosofis, terdapat dua faktor yang menyebabkan penggunaan kata “menjaga” lebih baik daripada kata “mengawasi, yaitu: (1) Kata “menjaga” memuat persepsi pencegahan, sedangkan kata “mengawasi” memuat persepsi penindakan; (2) Kata “menjaga” memuat persepsi “koordinatif”, sedangkan kata “mengawasi” memuat persepsi “subordinasi”.
Oleh karena itu dalam konteks peradilan, para pengubah UUD 1945 menentukan bahwa dalam Pasal 24B UUD 1945 yang dipilih adalah kata “menjaga” sebagai pilihan nomenklatur daripada kata “mengawasi”. Dalam struktur peraturan perundang-undangan, konstitusi merupakan produk hukum tertinggi (the supreme law of the land) sehingga semua produk hukum yang berada di bawahnya wajib mengikuti ketentuan yang secara tegas ditentukan dalam UUD 1945. Begitu pula terhadap kata “menjaga” yang mesti digunakan daripada kata “mengawasi” karena UUD 1945 menentukan demikian.
Dalam perkembangannya, kata “menjaga” ini kemudian pernah ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang menjadi kata “mengawasi” sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan, ”Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
Pasal inilah yang kemudian dibatalkan oleh MK karena ternyata dalam praktik, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui penilaian terhadap putusannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, asas res judicata pro veritate habetur, dan asas universal yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak dapat diubah kecuali melalui putusan pengadilan itu sendiri.
Dengan demikian kata “menjaga” kini mesti digunakan dan dipopulerkan dalam dunia peradilan ketimbang kata “mengawasi” karena hakim sebagai “vicegerent" di muka bumi harus kita jaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya dan bukan diawasi.
Ketua Mahkamah Konstitusi
Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang
PADA Kamis, 26 Januari 2017 pagi, tidak hanya jagat dunia hukum, tetapi publik kembali dikagetkan dengan berita tertangkap tangannya seorang hakim konstitusi berinisial PAK oleh KPK. Penangkapan dilakukan pada Rabu 25 Januari 2017 malam di sebuah pusat perbelanjaan. Namun, aromanya mulai tercium jelas melalui pemberitaan di berbagai media pada Kamis 26 Januari 2017 pagi.
Pada Kamis malam, KPK menyelenggarakan konferensi pers guna mengumumkan secara resmi pemberitaan ihwal kasus yang membelit hakim konstitusi PAK. Wajah MK pun kembali tercoreng untuk kedua kalinya pascatertangkapnya AM yang kala itu menjabat sebagai ketua MK.
Berbeda dengan AM yang tersandung transaksi suap pilkada, PAK diduga tersandung kasus suap perkara pengujian UU Nomor 41/2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Meskipun hal itu merupakan tindakan individual, lembaga MK tetap memikul beban berat dan sangat mencederai nama baik MK.
Terlebih sebentar lagi MK akan mengadili kasus sengketa hasil pilkada serentak. Oleh karena itu, diharapkan Presiden segera melakukan seleksi untuk memilih hakim konstitusi pengganti PAK.
Seiring dengan itu, ada permasalahan klasik ihwal “pengawasan hakim konstitusi” yang acap kali muncul dan menguat manakala terkait dengan hakim konstitusi yang tersandung kasus hukum, terutama kasus tindak pidana korupsi. Saat ini publik juga menilai adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengawasi MK melalui pintu KY.
Akan tetapi, upaya untuk “mengawasi” MK melalui pintu KY hampir dipastikan selalu kandas di tengah jalan. Oleh karena MK selalu saja membatalkan norma yang memuat pengawasan MK oleh KY. Walhasil hingga saat ini KY tak memiliki kewenangan untuk mengawasi MK.
Sikap MK ini didasari oleh Putusan Nomor 005/PUU-IV/2006, tanggal 23 Agustus 2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, di mana MK telah memutuskan bahwa Hakim MK tidak terkait dengan KY yang mendapatkan kewenangan berdasarkan Pasal 24B UUD 1945.
Berdasarkan kedua putusan ini, setidaknya terdapat dua alasan mengapa KY tidak didesain untuk “mengawasi” MK. Pertama, berdasarkan penafsiran sistematis atas pasal-pasal dalam konstitusi.
Posisi KY berada pada Pasal 24B UUD 1945, sedangkan MA berada pada Pasal 24A UUD 1945 dan posisi MK berada pada Pasal 24C UUD 1945 yang letak pengaturan pasalnya satu tingkat berada di bawah KY. Keberadaan pengaturan posisi pasal-pasal ini menyirat makna bahwa KY didesain untuk “mengawasi” hakim di lingkungan MA dan KY tidak didesain untuk “mengawasi” MK.
Akan tetapi, tidaklah berarti “pengawasan” terhadap MK diabaikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 27A ayat (2) UU Nomor 8/2011 tentang Perubahan UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi juncto UU Nomor 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi, lembaga yang diberikan kewenangan untuk menjadi “pengawas” MK adalah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang bersifat ad hoc yang akan bekerja tatkala ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Namun, dalam perkembangannya, terutama pascatragedi konstitusional yang melibatkan AM sebagai ketua MK dalam skandal suap perkara pilkada, dipandang perlu dilakukan rekonstruksi untuk mendesain ulang mekanisme “pengawasan” terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, saat ini telah terbentuk Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai lembaga permanen dan independen yang bertugas menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi yang bekerja day to day selain Majelis Kehormatan yang sifatnya ad hoc.
Kedua, menghindari konflik kepentingan (conflict of interest). Apabila KY diberikan kewenangan mengawasi MK, hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan manakala KY berkedudukan sebagai pihak dalam sengketa kewenangan lembaga negara yang menjadi domain kewenangan MK. Dalam kondisi ini, MK akan “tersandera” karena lembaga pengawasnya turut menjadi pihak dalam sengketa yang harus diputus olehnya.
Hal ini jelas berpotensi mereduksi independensi dan imparsialitas MK sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka berdasarkan Pasal 24 UUD 1945. Selain dijaga oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK juga telah bersinergi membangun sistem pengawasan eksternal.
Hal ini dibuktikan dengan adanya Memorandum of Understanding (MoU) antara MK dengan KPK sehingga peristiwa “OTT” hakim konstitusi PAK merupakan satu keberhasilan dari sistem ini. Oleh sebab itu, instrumen untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi telah terbangun dengan baik sehingga hal ini menafikan pendapat bahwa MK alergi terhadap “pengawasan” eksternal. Hal yang perlu dipahami bersama adalah pola “pengawasan” yang berbeda antara MA dengan MK.
Dalam konteks ini, MK tidak dapat dipaksa “diawasi” oleh KY, karena jika demikian, maka yang terjadi adalah sebuah bentuk penyelundupan hukum karena hal tersebut secara jelas bertentangan dengan Putusan Mahkamah Nomor 005/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014.
Jika memang “pengawasan” eksternal sebagaimana yang berlaku saat ini belum mencukupi, maka terdapat beberapa langkah yang dapat ditempuh, yaitu: (i) menjadikan Dewan Etik Hakim Konstitusi sebagai lembaga independen dan mandiri yang berwenang menjaga integritas hakim konstitusi seperti halnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU); (ii) melakukan perubahan UUD 1945 dengan meletakkan posisi kewenangan KY setelah kewenangan MA dan MK.
Artinya, posisi KY harus diletakkan pada Pasal 24C setelah Pasal 24A yang mengatur tentang MA dan Pasal 24B yang mengatur tentang MK. Selain itu, perlu dinyatakan secara tegas pada perubahan Pasal 24 UUD 1945 bahwa objek kewenangan KY meliputi pula hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, terdapat salah kaprah mengenai kata “pengawasan” yang sering kali digunakan terhadap lembaga peradilan. Dalam Pasal 24B UUD 1945 yang mengatur tentang Komisi Yudisial, menyatakan, ”Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim”.
Dalam pasal ini ditegaskan bahwa Komisi Yudisial memiliki kewenangan “menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim” dan bukan “mengawasi”. Perbedaan kata “menjaga” dan “mengawasi” membawa implikasi hukum yang berbeda.
Secara gramatikal sebagaimana termuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “menjaga” memuat makna, yakni: (1) menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan); (2) mengiringi untuk melindungi dari bahaya; mengawal; (3) mengasuh (mengawasi anak kecil); (4) “mengawasi” sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian); (5) mempertahankan keselamatan (orang, barang, dan sebagainya); (6) mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya);(7) memeliharakan; merawat. Sementara kata “mengawasi” memuat makna, yakni: (1) melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang); (2) mengamat-amati dan menjaga baik-baik; mengontrol.
Dalam perspektif bahasa, kata “menjaga” dipandang lebih elegan dan komprehensif ketimbang kata “mengawasi”. Selain itu secara filosofis, terdapat dua faktor yang menyebabkan penggunaan kata “menjaga” lebih baik daripada kata “mengawasi, yaitu: (1) Kata “menjaga” memuat persepsi pencegahan, sedangkan kata “mengawasi” memuat persepsi penindakan; (2) Kata “menjaga” memuat persepsi “koordinatif”, sedangkan kata “mengawasi” memuat persepsi “subordinasi”.
Oleh karena itu dalam konteks peradilan, para pengubah UUD 1945 menentukan bahwa dalam Pasal 24B UUD 1945 yang dipilih adalah kata “menjaga” sebagai pilihan nomenklatur daripada kata “mengawasi”. Dalam struktur peraturan perundang-undangan, konstitusi merupakan produk hukum tertinggi (the supreme law of the land) sehingga semua produk hukum yang berada di bawahnya wajib mengikuti ketentuan yang secara tegas ditentukan dalam UUD 1945. Begitu pula terhadap kata “menjaga” yang mesti digunakan daripada kata “mengawasi” karena UUD 1945 menentukan demikian.
Dalam perkembangannya, kata “menjaga” ini kemudian pernah ditafsirkan oleh pembentuk undang-undang menjadi kata “mengawasi” sebagaimana tertuang dalam Pasal 20 UU 22/2004 tentang Komisi Yudisial, yang menyatakan, ”Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.
Pasal inilah yang kemudian dibatalkan oleh MK karena ternyata dalam praktik, Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim melalui penilaian terhadap putusannya. Hal ini jelas bertentangan dengan Pasal 24B UUD 1945, asas res judicata pro veritate habetur, dan asas universal yang menyatakan bahwa putusan pengadilan tidak dapat diubah kecuali melalui putusan pengadilan itu sendiri.
Dengan demikian kata “menjaga” kini mesti digunakan dan dipopulerkan dalam dunia peradilan ketimbang kata “mengawasi” karena hakim sebagai “vicegerent" di muka bumi harus kita jaga kehormatan, keluhuran martabat, serta perilakunya dan bukan diawasi.
(maf)














